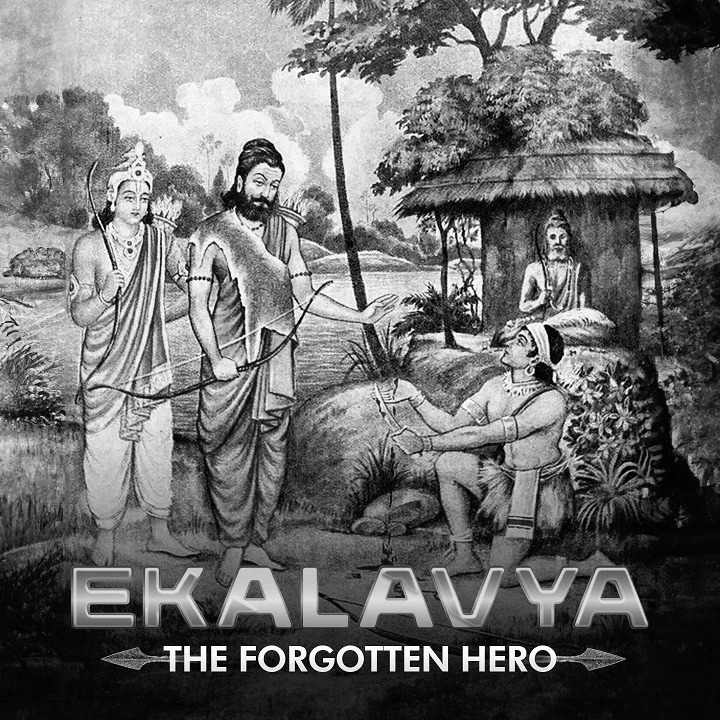Benarkah jurnalisme memperkuat demokrasi?
Hari-hari ini, ketika kebenaran dan kebohongan bercampur-aduk serta berita benar dan hoax sulit dibedakan, pertanyaan itu layak diajukan kembali.
Berita bohong memang telah jadi omongan. Tak cuma diproduksi oleh akun media sosial abal-abal, tapi dalam beberapa kasus juga oleh media yang pada umumnya kita kenal.
Alih-alih menjadi “clearing house of information”, media menyebarkan rumor dan membibitkan wasangka. Saya teringat pada Presiden Joko Widodo di depan para pemimpin redaksi media massa pada awal Januari 2017. Katanya mengkritik, alih-alih menjernihkan, media mainstream malah ikut menyebarkan hoax.
Mereka yang tak sependapat dengan kritik ini tentu bisa menangkis: media adalah medium, narasumberlah yang paling bertanggung jawab atas produksi kebohongan. Bukankah pemerintah sendiri pernah menjadi bagian dari produksi itu, baik sebagai korban maupun pelaku? Koran Tempo 23 Januari 2017 memuat cerita hoax dari rezim ke rezim: harta karun di bawah Istana Batu Tulis pada era Megawati, blue energy di zaman Susilo Bambang Yudhoyono, minyak murah Sonangol pada pemerintahan Jokowi.
Saya menikmati artikel itu, meski tak sepakat pada mereka yang menggunakannya untuk menangkis Presiden. Bagi saya, jurnalisme bukan sekadar persoalan medium. Jurnalisme adalah laku--ikhtiar dengan segala kekuatan dan kelemahannya.
Satu yang terpenting dalam laku itu adalah kesadaran bahwa fakta yang dikumpulkan wartawan sesungguhnya berpotensi menyimpan kekeliruan, kelemahan, sesuatu yang lancung--secermat apa pun fakta itu dikumpulkan. Kesalahan ini tidak terhindarkan karena jurnalis menyimpan daifnya sendiri. Wartawan bukan penegak hukum yang bisa memaksa narasumber berbicara.
Dalam jurnalisme investigasi, misalnya, jurnalis tidak dapat menyadap percakapan telepon atau memeriksa rekening bank. Yang bisa dilakukan wartawan adalah membujuk dan mempengaruhi, dua kata kerja yang berlaku dua arah--dari wartawan kepada narasumber dan sebaliknya.
Dengan kata lain, ada proses saling mempengaruhi di antara keduanya--sesuatu yang efek buruknya hanya bisa diatasi lewat proses kerja newsroom yang egaliter dan terbuka sehingga ada kontrol di antara awak redaksi.
Lewat proses di ruang berita itulah setiap fakta yang berpotensi lancung diuji. Cek-ricek dan verifikasi adalah dua hal yang wajib dilakukan betapapun kini terdengar klise. Setiap jurnalis sepatutnya terus-menerus berada dalam ketegangan antara meyakini dan meragukan; membela publik atau menjerumuskannya; mengungkapkan kebenaran atau justru kebohongan. Setiap jurnalis seyogianya menyimpan rasa cemas bahwa di tengah kerja jurnalistik yang terkesan heroik, boleh jadi mereka sedang memproduksi hoax.
Kewajiban wartawan meminta konfirmasi kepada narasumber muncul karena prinsip ini. Bahwa narasumber boleh jadi memiliki versi lain atas cerita yang diberitakan. Kedua cerita harus secara proporsional disajikan agar orang ramai memiliki kesempatan menentukan versi siapa yang benar.
Tentu saja pada prakteknya “yang lancung” itu bisa dilakukan kedua pihak: wartawan dan narasumber. Ada wartawan yang tidak sungguh-sungguh mengejar dan mewawancarai narasumber. Sebaliknya ada narasumber yang dengan sengaja menghindari wawancara agar kerja jurnalistik itu menyimpan “cacat” untuk dipersoalkan di kemudian hari.
Jurnalisme dengan demikian berdiri di antara kehendak untuk mengungkap “kebenaran” dan keinginan untuk tidak memonopoli “kebenaran” itu. Pada titik ini, menurut hemat saya, jurnalisme perlu kembali kepada fakta dan temuan.
Jurnalis yang mengutamakan fakta akan mengulik cerita sampai tekstur yang paling halus. Ia tak akan berhenti pada statemen narasumber, tetapi mencari tahu sesuatu di balik statemen tersebut. Ia tidak stop pada peristiwa tetapi menelisik cerita di balik kejadian. Pencarian terhadap tekstur itu dilakukan wartawan dengan terus-menerus mempertanyakan hipotesisnya sendiri.
Si wartawan akan mengurangi--jika bukan menabukan sama sekali--masuknya opini dalam karya jurnalistiknya. Ia menyadari bahwa opini dan subyektivitas sesungguhnya sudah diserap ketika ia menentukan angle, menetapkan narasumber, atau menyusun daftar pertanyaan.
Jurnalis mengungkap bukti dan tidak berpretensi menafsirkannya. Ia percaya bahwa tafsir adalah milik publik. Semakin detail dan lengkap fakta disajikan, semakin kecil ruang tafsir yang tersedia. Dengan mengungkap bukti sampai tekstur yang paling dalam--lewat reportase, pemanfaatan data, wawancara kritis, dan verifikasi yang berlapis--tafsir nyaris tak dibutuhkan lagi.
Abstraksi tentu saja bukan sesuatu yang buruk--ia diperlukan untuk merangkai gejala. Tapi tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mencapai kedalaman fakta, abstraksi akan mentah atau bahkan salah arah. Jurnalis yang kembali kepada fakta menyadari bahwa ia tak boleh menjadikan abstraksi sebagai bunker--tempat berlindung dari kemalasan atau risiko kerja kewartawanan.
Seluruh proses kerja itu membutuhkan ruang bernama indepedensi. Semakin sedikit kepentingan merecoki jurnalis, semakin leluasa ia menelusuri tekstur fakta. Ini tentu bukan perkara yang mudah.
Hari-hari ini kita saksikan bagaimana kemandirian media terus-menerus dipertanyakan. Kebebasan pasca-reformasi 1998 membuat siapa pun dapat membuat perusahaan pers, tak terkecuali politikus, pebisnis, organisasi masyarakat radikal atau setengah radikal. Semakin banyak kepentingan melilit media, semakin kecil ruang kemandirian itu.
Betapapun begitu selalu ada kesempatan untuk melihat "gelas setengah penuh" ketimbang "setengah kosong". Bagi saya, ketidakmandirian media bisa diatasi salah satunya dengan memelihara pluralisme media. Semakin banyak media didirikan, dengan segala variasinya, semakin besar kesempatan publik untuk memilih. Sampai di sini mestinya berlaku seleksi alam: yang tidak independen pelan-pelan akan ditinggalkan orang ramai. Hipotesis ini tentu tak boleh mengabaikan kematangan konsumen media. Semakin matang mereka, semakin tinggi kebutuhan mereka pada media yang independen.
Di era media sosial seperti sekarang, kebutuhan pada kemandirian itu semakin besar, terutama karena adanya respons cepat dari publik--lewat comment, like, dan dislike. Di satu sisi, ini dapat dibaca sebagai kesempatan bagi jurnalis untuk becermin. Di sisi yang lain, ia dapat pula menjadi tekanan bahkan intervensi. Kondisi ini mengharuskan jurnalis kembali pada posisi awal: ia harus pandai-pandai meniti buih.
Jikapun ia bisa lepas dari kepentingan bisnis media, tekanan pemilik, atau pengaruh narasumber dan khalayak, ia patut independen dari dirinya sendiri. Jurnalis selayaknya kritis bahkan kepada dirinya sendiri.
Pada hari-hari ketika jurnalisme didiskusikan kembali--peringatan Hari Pers Nasional 2017 dipusatkan di Ambon, Maluku, Kamis pekan ini--persoalan-persoalan ini layak dibicarakan.
Pembicaraan yang dapat membuat pers bertahan dari pelbagai gerus dan jurnalisme bisa mempertahankan perannya dalam demokrasi.
***
*Pemimpin Redaksi Majalah Tempo
Ikuti tulisan menarik Redaksi lainnya di sini.