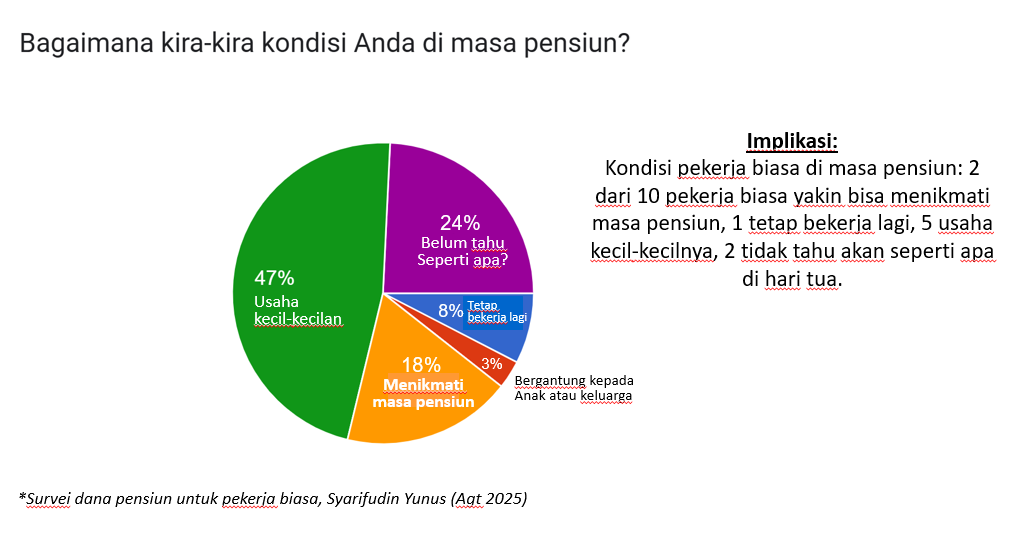Bahaya Banalitas Politik Elite Agama
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Potret laku politik yang banalis demikian merupakan 'warisan leluhur' ala Indonesia
Wacana sertifikasi para mubaligh dan ulama yang berprofesi sebagai penceramah agama yang kini sedang digodok Kementrian Agama bukan tanpa alasan. Pemerintah melalui Kemenag merespon berbagai tuntutan publik terkait terus meningkatnya isu-isu agama sempit yang berkelindan dengan aktor-aktor politik, para elite politik di negeri ini.
Apalagi diketahui, di era Pilkada langsung dimana eskalasi dukung-mendukung terhadap salah satu pasangan calon selalu saja menyertakan para tokoh agama, para alim-ulama, para dai hingga kelompok-kelompok organisasi sosial-keagamaan yang terus dihadap-hadapkan untuk berkonfrontasi. Dukungan para kyai, alim ulama dan tokoh agama terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah berdasarkan data Badan Intelijen Negara (BIN) ternyata bukanlah 'gratisan' apalagi tanpa bayaran. Mirip politik dagang, 'tak ada makan siang gratis', sudah menjadi rahasia umum bahwa dukung-mendukung butuh logistik dan biaya 'ubo rampe' untuk kepentingan menggalang massa akar rumput.
Dalam konteks demikian, pidato, ceramah atau kultum-kultum yang banyak digelar oleh berbagai komponen masyarakat, ormas atau organisasi keagamaan hingga para alim ualam faktanya tidaklah semata-mata sebagai upaya 'santapan rohani' guna mencerahkan jiwa religiusitas umat, tetapi banyak sudah menjadi 'forum politik berkedok' agama tertentu untuk satu tujuan: menggalang dukungan pada salah satu calon dengan menu agama yang kental karena diyakini menjadi bumbu penyedap politik yang paling joss!
Di sisi lain, pemahaman agama dan keberagamaan sebagian besar pemeluk agama di Indonesia, seperti hasil kajian peneliti Strategic Politics Institute Australia, Dr. Carl Ungerer, dalam "Beyond Religious Politics", (2010) 80% adalah pemeluk pasif yakni cenderung menjadikan keyakinan agama dan penerapan interprestasi ayat-ayat agama hanya dari satu sumber: para alim ulama atau yang dianggap 'ditokohkan' dalam hal agama tertentu. Beragama dan keberagamaan model demikian dikenal bak buih yang amat mudah mengalami turbuensi kadar religiusitas ketika 'cuaca politik' tak menguntungkan diri dan kelompoknya, atau terlalu bersemangat dengan respon berlebihan atas segala ucapan, dan ekspresi narasi linguistik yang dilontarkan sosok yang disebut 'ulama'.
Atmosfir politik di Indonesia akhir-akhir ini turut menopang perubahan gaya dan model 'berdemokrasi politik' dengan melibatkan para alim ulama dengan sistem 'saling mengutungkan' 'sama-sama tahu butuh biaya operasional yang tidak sedikit. Dalam kehausan materialisme di kalangan elite agama tersebut, di luar sana, yakni para aktor politik butuh 'penyambung lidah' sesuai target politiknya, perebutan jabatan publik tertentu, butuh legitimasi instan dan sesaat yakni dukungan massa akar rumput yang selama ini kian sulit 'dikadali' jika tidak menggunakan 'lidah para eite agama' tersebut. Maka media dan forum penggalangan massa rakyat untuk urusan kepentingan dan target politik adalah 'banalisasi politik ulama': dengan dalih menebar ajaran dan nilai agama tertentu tetapi sejatinya hanyalah upaya untuk mengeruk target politik sesaat!
Bahaya Besar
Potret laku politik yang banalis demikian merupakan 'warisan leluhur' ala Indonesia, dimana agama sudah menjadi bagian politik yang kental. Padahal diantara keduanya sejatinya bersebrangan: agama adalah roh penggerak religiusitas yang autentik atas pesan-pesan keilahian yang ditanamkan dalam bumi jiwa manusia beradab, sementara politik adalah 'upaya pertaruang perebutan kuasa duniawiah' sebagai media seleksi elite negara/pemerintahan (John Durrant dalam The Distinguish Between Religious and Politics, 2011).
Atas dasar hal tersebut, melibatkan para elite agama (baca: ulama), dalam konteks dukung-mendukung pada para aktor politik yang sedang berjibaku memperebutkan jabatan publik, sejatinya merefleksikan 'kekalahan substantif' dari para elite agama tersebut. Pakar Sosiologi Pembangunan UI, Imam B Prasojo (2017) menyebutkan setidaknya ada tiga bahaya besar yang bakal dialami elite agama atas 'pilihan politik' mereka yang cenderung jauh dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan, jauh dari spirit keberagaman, toleransi dan kerukunan antar umat.
Pertama, degradasi moral dan wibawa elite agama secara massif. Seperti yang sudah tergambar dalam data Barometer Komunikasi Indonesia (2017), dengan terjun dan pelibatan tokoh agama, para ulama, habib dan eite agama dalam forum-forum perdebatan politik dan demokrasi, ternyata bukan memperkuat wibawa dan derajat elite agama tersebut, tetapi justru meningkatkan antipati dan sinisme publik pada elite agama tertentu. Satir dan sarkasme cuitan meme di berbagai media sosial yang kini menjadi media komunikasi antar warga akar rumput pada sosok sepak terjang elite agama yang dengan gencar dengan dalih agama membela mati-matian pada aktor politik tertentu, sebagian besar direspon negatif oleh para nietizens lantaran ucapan, tindakan, dan lakunya jauh dari pesan-pesan religius sesuai keyakinan agamanya selama ini. Sarkasme cuitan nietizens yang menilai ucapan dan perilaku 'brutal' elite agama pun mudah menjadi 'provokator' baru yang terus mencipatakan kegaduhan di ruang politik publik.
Kedua, merusak citra agama dan umat. Harus diakui, dengan menampilkan ucapan dan tindakan/laku berkedok 'agama' tetapi sarat dengan muatan politik, ternyata menjadi hotbed perusakan citra agama dan umat secara keseluruhan. Agama dalam konteks demikian akan menerima dampak buruknya dan akan dikenang sejarah dunia sebagai agama sarkasme yang tempramental , padahal sejatinya seseorang yang dinilai 'beragama' sesuai dengan makna sintaksisnya dari bahasa Sansekerta, 'a' berarti ' tidak', dan 'gama' berarti 'kacau-balau' (beragama berarti: hidupnya tidak kacau balau seperti dikutip dari budayawan MH Ainun Nadjib, 2009-red), maka ketika seseorang mengaku beragama daya filtrasi religiusnya mampu mendorong laku dan kalbunya menghindari laku yang menyebabkan kekacau balauan, apalagi mengajak dan menebar kebencian hanya lantaran beda keyakinan agama. Laku demikian tak hanya merefleksikan kepandiran beragama, tetapi sekaligus merusak sumsum citra agama itu sendiri di mata umat lain.
Ketiga, membusukkan spirit persatuan dan kebhinekaan. Nilai-nilai persatuan baik antar umat seagama (ukhuwah Islamiah), persatuan antar umat (ukhuwah basariah) dan persatuan antar bangsa-warga (ukhuwah wathoniah) yang menjadi 'idiologi standar' keyakinan di Indonesia akan mudah membusuk apabila ucapan, sikap dan laku-tindak-tanduk elite agama tidak seperti yang diharapkan publik/umat. Apalagi ditambah dengan banalisasi politik elite agama yang begitu kuat menyeruak turut memperebutkan 'materialisme' politik kian menciptakan kehancuran moral agama itu sendiri.
Atas dasar bahaya besar diatas, maka layak untuk dikembangkan upaya-upaya 'mendidik' dan 'mengarahkan kembali' agar para elite agama, tokoh agama atau sebutan lainnya kembali ke khittah yakni menjalankan tugas-peran sebagai 'pencerah religiusitas' menuju oase hidup umat yang lebih beradab, jujur, toleran dan bertanggungjawab dalam setiap ucapan, laku dan tindak-tanduknya tak hanya kepada sang khaliq, tetapi kepada keadaban umat, berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya Kemenag RI untuk melakukan sertifikasi terhadap profesi dai atau ustadz atau penceramah agama bukan dimaknai sebagai pembatasan kebebasan berekspresi seorang warga negara di negara hukum dan demokrasi, tetapi semata-mata untuk melindungi wibawa agama dan umat serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas agar para martabat dan citra eite agama di Indonesia pulih dan normal kembali. Dalam konteks demikian, model pembinaan dan pengawasan tuntas terhadap laku dan tindakan provokatif, agitatif dan fitnah harus terus digalakkan hingga ke massa akar rumput agar banalitas politik elite agama segera dihentikan sebelum merusak tata nilai keberagaan di tanah air. Penegakkan hukum yang tegas, lugas dan tuntas juga mendesak digalang negara pada para pelaku banalist tersebut guna menyadarkan mereka untuk kembali ke tugas (suci) pokoknya: menjaga nilai religiusitas tanpa kekerasan, dan sarkasme untuk mencerahkan hidup umat!** (Tasroh, S.S.,MPA,.MSc: Pegiat Banyumas Policy Watch dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan)
Oleh Tasroh
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Strategi Antikorupsi Proyek Strategis
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Bahaya Banalitas Politik Elite Agama
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0







 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 98
98 0
0