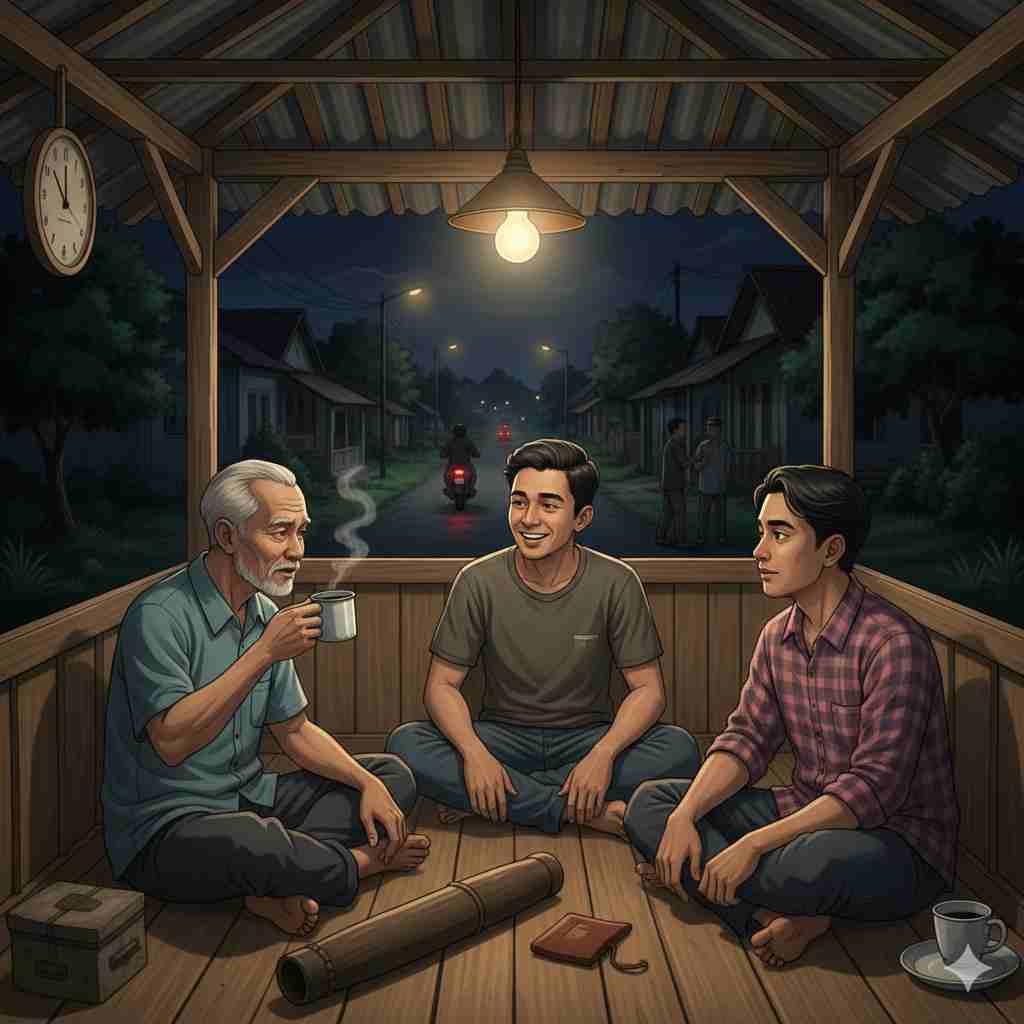Surga yang Tak Terjamah, Gudang Sains Tanpa Penjaga
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
minusnya peneliti di negeri ini, kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat
Belum lama ini, dari ANU atau The Australian National University, yang diwakili oleh Dr. Debbie Argue, mengumumkan hasil penelitian tentang teka teki, darimana asalnya Homo Floresiensis, yang ditemukan pertama kali di Liang Bua pada tahun 1965. Banyak teori yang bermunculan setelah ditemukannya manusia purba asal Flores ini. Mengingat penemuan ini jauh lebih baru dibandingkan beberapa penemuan manusia purba di negeri ini, sementara penemuan ini justru mengemukakan fakta mengejutkan, bahwa, Homo Floresiensis ini mempunyai jenis yang jauh berbeda dengan jenis manusia purba yang lebih awal ditemukan di Sangiran dan sekitarnya. Perbedaan ini bukan sekedar tentang bentuk tubuh, tapi juga rentang usia hidup keduanya yang amat sangat jauh.
Pada awalnya, manusia Flores ini diperkirakan terkait juga dengan jenis Homo Erectus dan Homo Sapiens yang ditemukan lebih awal di seputaran tanah Jawa, sebut saja Pithecantropus Erectus, Homo Wajakensis, Meganthropus Paleojavanicus, Homo Erectus, Pithecantropus Mojokertensis. Tapi, ternyata, setelah diteliti lebih lanjut, bukan hanya dari bentuk tulang, juga kebudayaan yang ditinggalkan, terungkap fakta baru bahwa keberadaan Homo Floresiensis ini jauh lebih tua dari Homo Erectus maupun Homo Sapiens. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Debbie Argue dari ANU beberapa waktu lalu, bahwa, pada kenyataannya, Homo Floresiensis ini justru mempunyai kemiripan dengan Homo Habilis yang ditemukan di Benua Afrika, diperkirakan, mereka mempunya leluhur yang sama. Dan dalam pernyataannya, Dr. Debbie Argue bahkan berkata bahwa, bisa terjadi kemungkinan ditemukan fakta baru bahwa usia Homo Floresiensis lebih tua dari usia Homo Habilis. Karena pada kenyataannya, dalam diagram pohon evolusi saat ini, posisi Homo Floresiensis, berada sebagai jenis manusia purba yang paling primitive.
Sebetulnya agak terkejut dengan pengumuman dari ANU tersebut. Mengingat ‘geger-geger’ Hobbit asal Flores ini mungkin sudah dilupakan orang. Padahal di tahun 2003, publik bukan hanya dikejutkan oleh pengumuman penemuan manusia Hobbit asal Flores, tapi juga merasa kecolongan karena yang mengumumkan justru peneliti dari Australia, sementara penelitian atas Homo Floresiensis tersebut bukan hanya karena situsnya ada di Indonesia, yaitu di Liang Bua, Flores, tapi juga ada sejumlah nama arkeolog dari Indonesia, yang dipimpin oleh R.P. Soejono dari Arkanas yang ikut meneliti, dan penelitian itu, bersifat sebuah kerjasama. Tapi yah, posisi peneliti kita pada waktu itu memang boleh dibilang amat sangat lemah, mengingat biaya penelitian yang tersedia amat sangat terbatas, belum lagi, untuk masalah penelitian semacam ini, pada tahun tersebut, belum ada Protokol Kyoto yang melindungi kepentingan sebuah penelitian.
Indonesia, pada dasarnya memang surga bagi dunia penelitian. Bukan hanya karena kemajemukan geografis, budaya, suku tapi juga ragam hayati. Meskipun sayang sekali, pemerintah kurang memperhitungkan hal tersebut. Sebutlah data terakhir bahwa total periset atau peneliti untuk segala bidang penelitian di negara ini hanya berjumlah 89 peneliti untuk per 1 juta penduduk. Ya, dalam satu tahun, Indonesia hanya mampu menghasilkan 6.250 periset. Itulah , mungkin, kenapa, data per tanggal 31 Desember 2016, hanya ada 10.054 riset di Indonesia. Bandingkan dengan Malaysia yang menghasilkan 25.000 periset tiap tahunnya, atau Singapura yang menghasilkan 18.000 periset tiap tahunnya, belum lagi Thailand yang menghasilkan 12.000-13.000 periset tiap tahun. Padahal, jika dilihat dari segi luas wilayah, serta banyaknya penduduk, ketiga negara tersebut, kalah jauh dengan Indonesia. Mungkin bisa dibayangkan, ada berapa banyak riset yang ada jika saja peneliti yang ada berjumlah kurang lebih sama dengan Singapura, yaitu 6.658 periset per 1juta jiwa.
Padahal, jika dikaji ulang, banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang terbit dari hasil meneliti keanekaragaman hayati nusantara. Sebut saja misalnya nama Alfred Russel Wallace, yang pernah menerbitkan jurnal ilmiah yang berjudul The Malay Archipelago. Dalam jurnal tersebut, Wallace menulis tentang keanekaragaman hayati yang ada di nusantara. Yang kemudian, sempat menjadi polemik. Karena konon kabarnya, atas surat Wallace kepada Darwin lah, yang membuat Darwin menyempurnakan teori evolusinya. Surat Wallace saat itu kurang lebih berisi bahwa pada akhirnya, proses perbaikan ras ini tidak kurang tidak lebih dari individu yang inferior akan mati lebih dulu, sedangkan yang superior bertahan, atau dengan kata lain, the fittest would surfive. Hal ini bahkan sempat menjadi perdebatan panjang antar ilmuwan hingga sempat beberapa ilmuwan menerbitkan buku yang membahas hal ini. Sebut saja buku A Delicate Arrangement, The Strange Case Of Charles Darwin and Alfred Russel Wallace karya Arnold C. Brackman. Buku tersebut mengungkap banyak polemik tentang siapakan yang seharusnya menjadi penemu teori evolusi.
Mungkin memang bakal jadi pekerjaan rumah yang lumayan panjang bagi pemerintah, mengingat, memang butuh biaya yang tidak sedikit, tapi jika melihat ‘surga’ ilmu yang ada, yang siap dipanen kapan saja oleh tangan kita sendiri, kenapa tidak? Walau ada fakta miris yaitu, Kemenbudpar, hanya diberi jatah 12-15 peneliti tiap tahun. Padahal, kita tahu, budaya di negara ini amat sangat majemuk, juga sudah sekian tahun menjadi incaran para peneliti Internasional. Tapi apa mau dikata, jika kita bicara jumlah peneliti, memang kadangkala, tidak semua lulusan universitas ternama sekalipun, sanggup untuk menjdi peneliti. Dan, kecuali untuk jurusan Arkeologi, pemerintah benar-benar butuh usaha ekstra, karena hanya ada sedikit sekali universitas di negara ini yang membuka jurusan tersebut. Tercatat hanya ada 4 universitas negeri yang membuka jurusan Arkeologi, yaitu UI, UGM, Udayana dan Universitas Hassanudin Makasar, dengan jumlah lulusan hanya 80 orang per tahun. Belum lagi fakta bahwa, UI pun membatasi jumlah mahasiswa pengampu jurusan ini. Pihak UI hanya mau menerima 15-20 siswa Arkeologi tiap tahunnya, dengan alasan menjaga kualitas kelulusan. Sementara fakta di lapangan adalah, Indonesia, juga surganya arkeologi.
Begitulah, amat sangat disayangkan, jika hal ini terus menerus didiamkan. Tidak lucu rasanya, bahwa untuk tahu segala sesuatu secara lengkap tentang science dan sejarah kita sendiri, justru kita harus membuka jurnal-jurnal ilmiah di negara lain. Apakah separah itu literature kita, hingga saat kita bicara spesies hayati kita, kita mesti berkiblat kepada Leiden, Australia dan yang lainnya?
" Books are carriers of civilization, without books, history is silent, literature is dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill."
Mungkin kita memang mulai harus berbenah, bukan hanya perlu banyaknya peneliti, tapi juga mulai belajar berbenah masalah literatur. Seperti apa kata sejarawan Barbara Tuchman tadi, tanpa buku, tanpa catatan, segala sesuatu hanya menjadi sekedar spekulasi, alias omong kosong.
Tapi, sampai kapan negeri ini akan mulai berbenah, sedang "surga-surga' yang ada, kian tak dijamah...
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Siapa Sebenarnya yang Masih Butuh Pendidikan?
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Menilik Hasil Rumusan Para Tokoh Lintas Agama
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
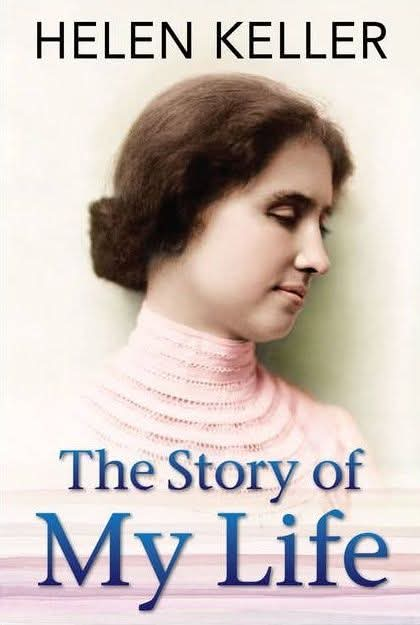
 Berita Pilihan
Berita Pilihan





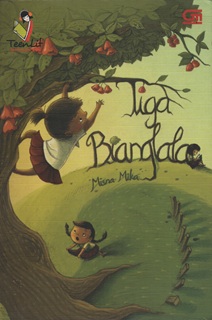

 99
99 0
0