Perang Aceh: Antara Strategi Militer dan Alasan Etis
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB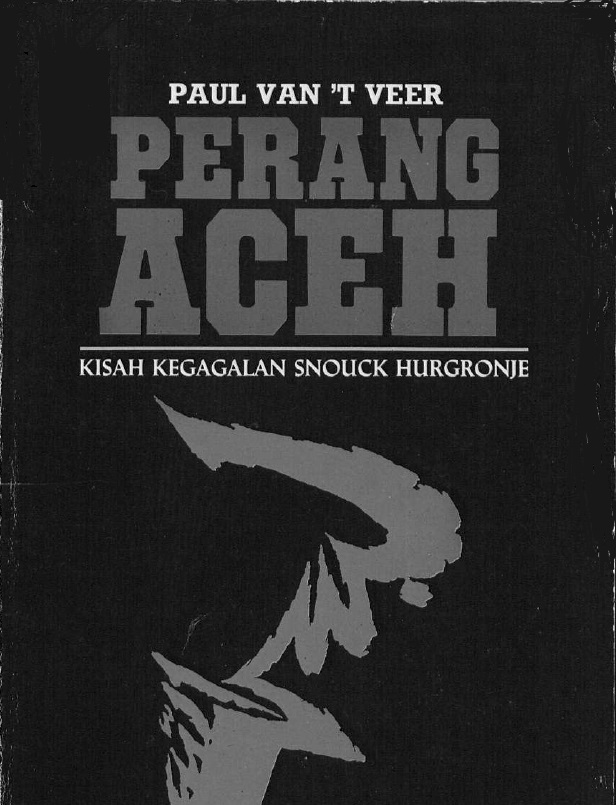
Pandangan sejarahwan Belanda terhadap Perang Aceh
Judul: Perang Aceh
Judul Asli: De Atjeh Oorlog
Penulis: Paul van ’t Veer
Penterjemah: Grafitipers
Tahun Terbit: 1985
Penerbit: Grafitipers
Tebal: ix + 270
ISBN:
Perang Aceh adalah perang terlama yang dihadapi oleh Belanda, yaitu dari tahun 1873 sampai 1942. Korban di kedua belah pihak sangat banyak. Buku ini mencoba mencari jawab dua pertanyaan, yaitu (1) Apakah perang ini dilakukan dengan cara yang tepat (secara militer)? (2) Apakah perang ini bisa dibenarkan (secara sosial dan etika)? Dua pertanyaan dari dua aspek peperangan dicoba untuk dijawab oleh Veer. Dua pertanyaan ini memang sangat relevan untuk diajukan dalam membahas perang Aceh. Sebab perang berjalan sangat lama dengan korban yang begitu banyak, dan perang ini tak bisa dilihat dari sisi hitam-putih siapa benar-siapa salah. Buku ini ditulis dengan cara pandang Eropa. Itulah sebabnya alasan-alasan yang berhubungan dengan kondisi Belanda/Eropa menjadi tumpuan dalam menjawab dua pertanyaan di atas. Veer membahas sangat banyak tokoh Belanda, khususnya dari kalangan militer yang terlibat dalam perang Aceh secara mendetail.
Pada tahun 1870 terjadilah sebuah perubahan radikal. Keberhasilan perkebunan tembakau J. Nienhuys (1864) dan dibukanya terusan Suez membuat peran orang-orang swasta menjadi lebih besar. Perjalanan antara Eropa dan Asia Tenggara yang lebih singkat membuat banyak orang swasta yang pergi ke Asia Tenggara untuk berbisnis dalam jangka panjang, bukan lagi sekedar datang untuk mengumpulkan uang dan kemudian pensiun di Eropa. Mereka-mereka ini datang ke Asia Tenggara untuk melakukan kolonisasi dalam bentuk perkebunan-perkebunan dan usaha-usaha dagang.
Terbukanya Terusan Suez membuat Selat Malaka menjadi lebih penting dalam jalur pelayaran. Kebanyakan pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Sumatra telah dikuasai Belanda. Namun di ujung Sumatra, yaitu Aceh masih belum. Akibatnya banyak terjadi perompakan di Selat Malaka. Delam perundingan antara Inggris dan Belanda disepakati bahwa Belanda harus segera menguasai Aceh, sehingga pelayaran, termasuk kapal-kapal dagang Inggris bisa berlalu dengan aman (hal. 19). Kesepakatan ini juga ditunjang dengan pertukaran keleluasaan Belanda di Sumatra sementara Pantai Emas di Afrika diserahkan kepada Inggris.
Namun implementasi dari persepakatan Inggris-Belanda tentang Aceh ini tidaklah mulus. Beberapa persoalan dimunculkan oleh Veer dalam buku ini. Beberapa persoalan tersebut diantaranya adalah kritik dari Multatuli. Multatuli tidak setuju perjanjian penguasaan Aceh (hal. 23) karena menurut dia, orang Aceh telah siap untuk berperang. Artinya tindakan Belanda untuk menguasai Aceh ini akan berakibat peperangan yang sangat dalam. Persoalan kedua adalah adanya pihak-pihak seperti Kesultanan Otoman di Turki, perwakilan Italia dan Amerika di Singapura yang juga memiliki kepentingan di Aceh. Kesultanan Otoman jelas berkewajiban untuk melindungi masyarakat Islam di manapun, karena posisinya sebagai kekhalifahan. Sedangkan Italia dan Amerika Serikat berkepentingan dalam perdagangan.
Dalam hal membahas awal peperangan di Aceh, Veer menggunakan dua alasan yang sangat Eropa sentris. Alasan pertama adalah perjanjian antara Inggris dan Belanda berdasarkan Traktat London yang ditanda-tangani pada tahun 1824 (hal. 2), dimana Belanda tidak boleh mengusik kemerdekaan Aceh tetapi harus menjaga ketertiban supaya Aceh bisa melindungi pelayaran di selat Malaka; dan perekrutan tentara untuk ditugaskan di Hindia Belanda yang tidak profesional (hal. 3). Tentara-tentara yang direkrut adalah berasal dari orang-orang gunung di Swiss dan para pengangguran di Belanda. Para rekrutan ini pun sebenarnya tidak siap perang, karena yang dibayangkan adalah menikmati hidup dalam romantisme timur.
Veer juga menyinggung tentang kebijakan lokal Inggris dan Belanda dalam menyikapi traktat London. Meski secara pemerintahan kedua negara ini bersepakat untuk tidak mengusik kemerdekaan kesultanan-kesultanan setempat, namun di lapangan, karena keuntungan dagang yang sangat tinggi, mereka sering “melanggar” traktat London. Serawak telah jatuh ke tangan Inggris dan Siak masuk dalam rengkuhan Belanda. Masuknya Serawak ke dalam “kedaulatan” Inggris dan Siak ke rengkuhan Belanda semata-mata untuk mencari keuntungan dagang. Namun hal ini menyebabkan kesultanan lain, seperti Aceh menjadi lebih waspada.
Pada serangan pertama, yaitu serangan pada tahun 1873, Belanda mengalami kegagalan yang parah. Kekalahan ini disebabkan karena Belanda tidak memiliki informasi yang akurat tentang Aceh. Panglima Perang yang diutus untuk menggerakkan pasukan ke Aceh pada tahun 1873, yaitu Kohler, hanya berbekal informasi dari para pedagang dan musafir saja (hal. 32). Kapal pengangkut tentara pun adalah kapal yang tidak layak. Akibatnya pendaratan tentara Belanda di Aceh disambut dengan pertempuran yang hebat (hal. 35). Informasi yang seadanya tersebut membawa malapetaka bagi Kohler. Sebab serangan yang dikiranya dilakukan kepada keraton, ternyata adalah sebuah masjid. Akibatnya peperangan ini bukan lagi sebuah pekerjaan menaklukkan kekuasaan (keraton) tetapi sudah mengarah kepada perang agama. Kohler sendiri tewas dalam pengepungan masjid ini (hal. 36).
Tak berbeda, serangan kedua yang dipimpin oleh Van Sweiten pada tahun 1874, rombongan tentara ini juga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Aceh. Demikian pun dengan pengiriman tentara dari daratan Eropa yang dilakukan secara sembrono. Banyak tentara yang didatangkan dari Eropa ini mati karena kolera di atas kapal.
Penyerahan diri seorang hulubalang Mukim bernama Teuku Nek dianggap sebagai sebuah keberhasilan dalam penaklukan kesultanan Aceh (hal. 73). Serangan utama yang pertama diarahkan kepada Masjid Agung. Hal ini mengulangi kesalahan Jenderal Kohler. Serangan ke Masjid Agung ini telah mengurangi kekuatan tentara Van Sweiten, sebab sepertujuh pasukannya telah tak berdaya. Van Sweiten selanjutnya mengikuti nasihat Teuku Nek untuk mengitari keraton. Saat keraton diserang, ternyata keraton sudah kosong karena ditinggalkan oleh penghuninya. Namun jatuhnya keraton ini tidak berarti menyerahnya rakyat Aceh. Serangan kepada tentara Belanda terus berlangsung siang dan malam. Serangan dilakukan oleh rakyat dan bukan oleh tentara keraton (hal. 75). Sebab ternyata Aceh bukan Jawa atau Siak, dimana kekuasaan terpusat pada seorang sultan. Aceh terbagi dalam daerah-daerah kecil yang dikuasai oleh hulubalang. Peperangan antar daerah-daerah kecil yang berlangsung bertahun-tahun telah membuat mereka terbiasa dengan perang. Apalagi sekarang peperangan dengan Belanda dianggap perang dengan kafir.
Setelah menguasai keraton, Van Sweiten segera mengubah pemerintahan Aceh. Ia menyatakan bahwa para hulubalang tak bisa memerintah sendiri. Pemerintahan berada di tangan Belanda dan hulubalang bisa memerintah atas nama pemerintah Belanda apabila mereka menyatakan takluk. Keputusan ini untuk sementara seakan-akan memberi kemenangan kepada Belanda. Namun tak lama setelah Sweiten balik ke Batavia, Kolonel Pel, sang pengganti sudah meminta bala bantuan untuk mempertahankan Aceh (hal. 78).
Pemerintahan Belanda ini kemudian hancur dan dikalahkan pada tahun 1876. Abdurrahman, sang mangkubumi yang menghilang dari Aceh dan menggalang dukungan internasional telah kembali. Ia bersama-sama dengan Teuku di Tiro melakukan perlawanan kepada Belanda. Kolonen Pel gugur dalam peperangan dan banyak tentara Belanda yang tewas. Teuku di Tiro adalah seorang ulama. Ia membekali rakyat Aceh dengan ajaran agama untuk melawan Belanda. Peperangan segera berkobar kembali. Serangan yang dilakukan oleh Jenderal Van der Heijden berhasil mempertahankan Kutaraja, mengalahkan Montasik (Pidie) dan memaksa Abdurrahman untuk meninggalkan Aceh pada tahun 1878. Abdurrahman kemudian tinggal di Mekkah dan menasihati para ulama dan hulubalang untuk menyerah kepada Belanda. Namun nasihatnya tersebut tidak diikuti oleh para pejuang Aceh.
Meski peperangan belum padam sepenuhnya, tetapi Jenderal Van der Heijden telah membawa ketertiban, setidaknya di sekitar Kutaraja pada tahun 1880. Perdamaian tersebut sesungguhnya semu belaka. Sebab di luar Kutaraja peperangan masih terus berlangsung. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya ada beberapa tentara NIL yang desersi dan menggabungkan diri dengan Panglima Polim.
Pada tahun 1883, Deijkerhoff tampil dengan kebijakan berbeda. Ia mengajak Teuku Umar untuk memerangi para gerilyawan. Teuku Umar sangat berhasil memerangi para gerilyawan dengan bantuan persenjataan dari Belanda. Keberhasilannya ini membuat Teuku Umar mengambil gelar Teuku Johan Pahlawan. Hadirnya pasukan Teuku Johan Pahlawan ini menyebabkan para gerilyawan bingung. Mereka tidak bisa lagi berperang sebagai pihak yang membunuh orang kafir (hal. 150).
Adalah Snouck Hurgronje yang mengawali sebuah penelitian antropologi tentang Aceh. Informasi hasil penelitian Snouck Hurgronje inilah yang kemudian mengubah pandangan Belanda tentang perang Aceh. Dialah yang memperingatkan bahaya bekerja sama dengan Teuku Umar (hal. 156). Dan benar saja pada tahun 1896 Teuku Umar membelot, setelah mendapatkan banyak senjata baru (hal. 164).
Snouck Hurgronje memberi saran sebagai beriku: "Hanyalah orang yang menunjukkan memiliki kekuasaan untuk memaksakan keinginannya yang dihormati, di mana pun juga dan dalam keadaan bagaimanapun juga, dan di mana perlu, dengan menggunakan tangan besi yang berdaya guna, dialah yang akan menaklukkan Aceh sepenuhnya, yang akan membuat rakyat Aceh yang berani dan cinta damai bertekuk lutut” (hal. 157). Menurutnya, orang Aceh yang Islam hanya akan tunduk kepada kekuasaan yang tidak terkalahkan. Selain dari menggunakan kekuatan tangan besi, Snouck juga menyarankan program kesejahteraan kepada penduduk Aceh. Pandangan Snouck Hurgronje ini mengubah pandangan Belanda tentang orang Aceh. Orang Aceh tidak lagi dipandang sebagai orang-orang licik, penipu dan pembunuh yang tak berperi kemanusiaan, tetapi sebagai orang-orang yang berjuang untuk tanah airnya. Namun penilaian Snouck Hurgronje ini salah besar. Sebab orang Aceh tak pernah menyerah terhadap kekuasaan Belanda yang seakan tak terkalahkan itu. Snouck Hurgronje juga salah menilai bahwa peperangan di Aceh hanya dilandasi masalah agama. Ia tidak memperhitungkan keadaan pranasionalisme yang sedang tumbuh di Hindia Belanda, dimana rakyat Aceh juga menginginkan kemerdekaan penuh dari Belanda (hal. 209).
Pemberontakan Teuku Umar menyebabkan serangan besar-besaran ke Aceh. Politik bumi hangus dilakukan untuk mengejar Teuku Umar. Pembumi-hangusan Aceh Besar ini dilakukan secara brutal. Seorang pemimpin gerilya bernama Teuku Nyak Makam yang sedang sakit parah dan diusung dalam tandu, dibunuh di depan anak istrinya. Kepalanya dipenggal dan diawetkan serta disimpan di Rumah Sakit Tentara di Kutaraja sebagai peringatan. Alih-alih membuat orang Aceh mereda pemberontakannya, cara-cara biadab seperti ini justru meningkatkan jumlah rakyat Aceh yang memberontak (hal. 194).
Di sisi lain, kebijakan yang menekan ulama dan mendukung para ningrat ini membuat banyak hulubalang menyerahkan diri dan mengikat perjanjian dengan Belanda (hal. 199). Termasuk sang Sultan Teuku Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Penyerahan Sultan ini dengan jaminan bahwa Sultan tidak akan diasingkan keluar Aceh. Namun keputusan Van Heutsz ini bertentangan dengan strategi besar Snouck Hurgronje. Snouck Hurgronje menganggap bahwa Van Heutsz bermain-main dengan kesultanan Aceh. Tidak seharusnya Sultan diberi kesempatan untuk kembali ke Kutaraja. Meski banyak hulubalang yang telah mengikat perjanjian dengan Belanda, dan kekuatan Belanda terlihat semakin kokoh, namun perlawanan sporadik kelompok-kelompok “muslimin” masih terus berlangsung (hal. 218).
Seriring dengan pergantian gubernur dari Van Heutsz ke Van Daalen (tahun 1904), kebijakan sapu bersih mulai dikurangi. Beberapa kompi tentara dikembalikan ke Jawa. Pada saat yang sama terjadi kemenangan Jepang atas Rusia. Ini adalah kemenangan bangsa luar terhadap Eropa. Kemenangan Jepang terhadap Rusia (Eropa) ini membuktikan bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Kejadian-kejadian ini mengobarkan kembali peperangan di Aceh. Beberapa hulubalang kembali memberontak. Sultan Teuku Muhammad Daud yang sudah tidak memiliki kekuasaan di Kutaraja menjalin hubungan dengan Jepang (hal. 236). Akibatnya Sultan dibuang ke Jawa karena ketahuan telah menjalin hubungan dengan Jepang. Menjelang kedatangan Jepang, pemberontakan di Aceh semakin besar, sampai akhirnya Belanda meninggalkan Aceh saat Jepang masuk ke wilayah ini pada tahun 1942.
Dari sisi militer terlihat sekali bahwa Perang Aceh dilakukan secara sembrono. Belanda tidak memiliki cukup informasi tentang siapa sebenarnya Aceh, bagaimana sistem pemerintahannya, intrik di dalam kesultanan dan diperparah dengan tidak paham tentang kondisi geografisnya. Kurangnya informasi tersebut menjadi penyebab kekalahan Belanda dan berlarut-larutnya peperangan.
Dari sisi pemerintahan Hindia Belanda, perang Aceh (dan ekspansi ke luar Jawa lainnya) telah menyedot laba yang didapat dari Tanam Paksa di Jawa. Akibat dari perang Aceh dan ekspansi ke tempat-tempat lain di luar Jawa berakibat kurangnya perhatian terhadap pertahanan Jawa. Ekspansi ke luar Jawa ini adalah sebuah keputusan yang kurang bijak. Selain itu polemik tentang perang Aceh terus terjadi sejalan dengan pelasakaan perang itu sendiri. Para pelaku perang Aceh di satu pihak dijuluki sebagai seorang pahlawan, tetapi di pihak lain dianggap sebagai “bajingan” (hal. 98).
Perang Aceh juga telah menggunakan narapidana untuk keperluan perang. Mereka dipaksa untuk menjadi pengangkut meriam, mendorong kereta baja untuk menghindari ranjau yang dipasang oleh gerilyawan Aceh. Jumlah narapidana yang dipekerjakan secara semena-mena, dan banyak yang tewas tersebut ditaksir ada 2000 jiwa (hal. 135).
Di sisi lain, ada kecurigaan bahwa perang dipelihara (dalam waktu yang sangat lama) adalah untuk mengeruk keuntungan saja (hal. 176). Para perwira muda mendapatkan promosi dari perang Aceh dan kemudian menikmati masa pensiun di Negeri Belanda dengan nyaman. Sementara itu kerugian di pihak Belanda dan juga di pihak rakyat Aceh telah sedemikian besarnya. Biaya perang Belanda dibayar sebagian besar dari penghasilan di Jawa. Akibatnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa menjadi tertunda (hal. 190). Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidak-puasan masyarakat Jawa. Apakah itu etis?
Buku ini juga menyinggung serba sedikit tentang para petualang Belanda, Eropa dan Amerika yang memanfaatkan persaingan kerabat kesultanan/kerajaan dalam proses suksesi. Informasi tentang Lange (orang Denmark) dan King (orang Inggris) yang memecah belah Bali dan orang Amerika di Jambi (hal. 7) dan James Brooke (hal. 8) disajikan serba sedikit dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Dari kisah-kisah para petualang ini jelaslah bahwa sejarah Hindia Belanda/Indonesia tidak hanya kisah hubungan antar negara saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh para petualang-petualang kecil di tingkat lokal.
Sub judul versi Bahasa Indonesia yang tercantum dalam buku ini adalah “Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje”. Menurut saya sub judul ini sama sekali tidak tepat. Sub judul tidak tercantum dalam judul buku aslinya. Saya menyatakan sub judul ini tidak tepat, karena nama Snouck Hurgronje baru muncul pada periode ketiga peperangan, yaitu tahun 1884-1890. Artinya dua periode perang Aceh sebelumnya, yang sudah mulai pada tahun 1873 tidak melibatkan Snouck Hurgronje. Nasihat Snouck Hurgronje juga tidak diikuti secara penuh oleh perwira yang menjalankan kegiatan militer di Aceh. Serangan bumi hangus, misalnya tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. Demikian pun politik tidak memberi kesempatan kepada kekuasaan-kekuasaan ternyata diabaikan saat Sultan Teuku Muhammad Daud dibolehkan tinggal di Kutaraja. Kalaupun ada salah analisis yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje adalah landasan perang. Snouck menganggap bahwa perang di Aceh sangat dilandasi oleh agama. Namun pada kenyataannya, peperangan ini juga dilandasi keinginan rakyat Aceh untuk merdeka dari Belanda. Satu hal lagi yang membuat saya tidak setuju dengan sub judul versi Bahasa Indonesia, adalah bahwa pada kenyataannya buku ini membahas sangat detail para pelaku perang Aceh dari pihak Belanda yang penuh intrik dan memanfaatkan perang Aceh untuk kenaikan pangkat, bukan hanya membahas kebijakan Snouck Hurgronje.
Penulis Indonesiana
2 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler

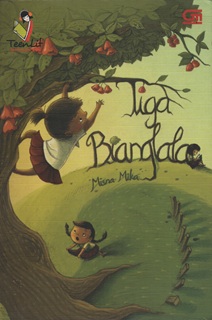
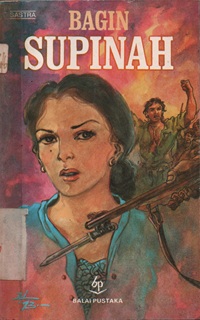
 0
0


 Berita Pilihan
Berita Pilihan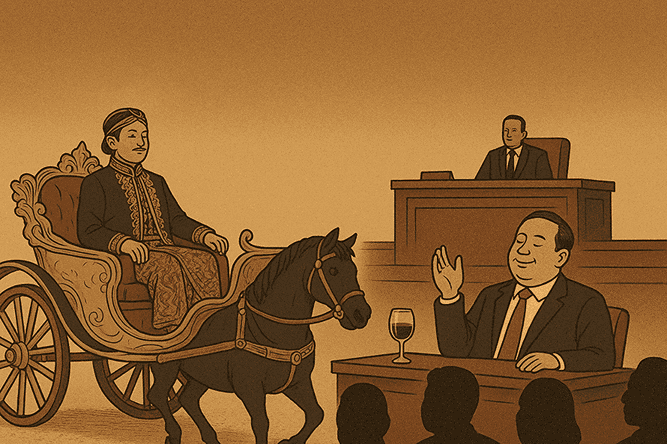






 98
98 0
0














