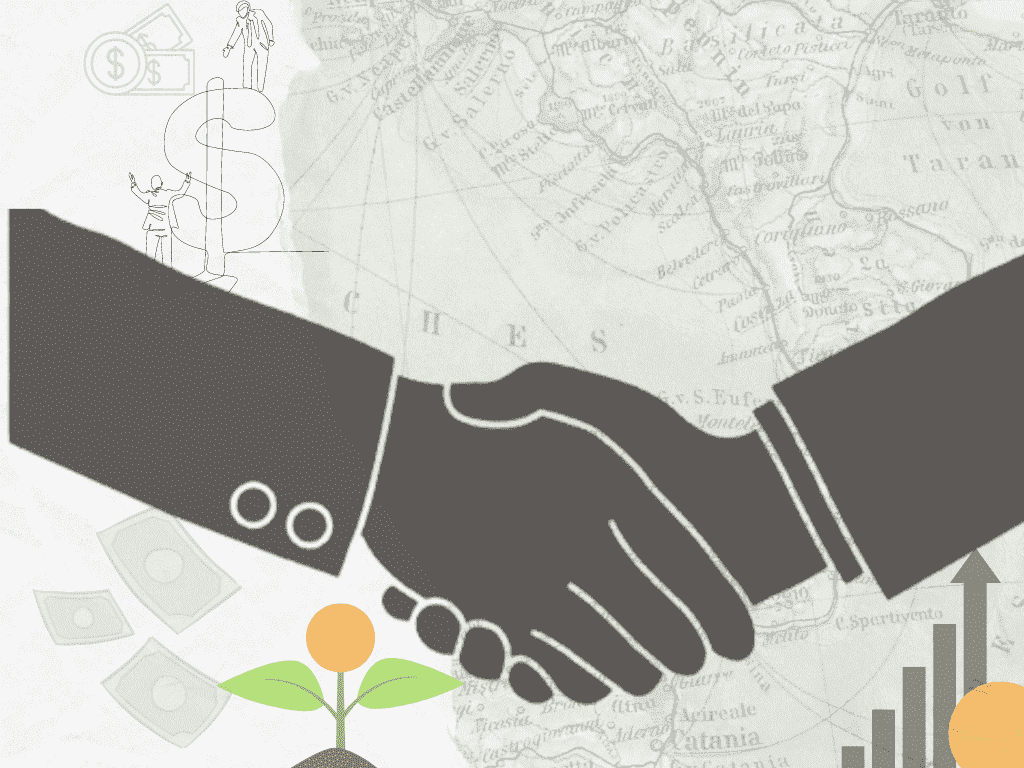Dunia saat ini sedang menyoroti kasus minoritas etnis Rohingya di Myanmar yang sedang “dihabisi” oleh junta militer di negeri Tanah Emas tersebut. Etnis yang kurang lebih berjumlah 1,1 juta orang ini telah sekian lama menjadi warga negara kelas dua di Myanmar, terus menerus mendapat tekanan, bahkan mereka termasuk warga negara yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Myanmar—yang sebelum 1989 dikenal sebagai Burma—telah lebih dari 46 tahun dipimpin oleh pemerintahan junta militer yang dikenal “rasis”. Bagaimana tidak, istilah “Burma” yang didominasi oleh etnis Bama di Myanmar seakan menunjukkan superioritasnya sebagai etnis terbesar dan menjadikan etnis lain inferior, seperti yang dialami etnis Rohingya yang hidup di wilayah negara bagian Rakhine.
Keberpihakan otoritas junta militer Myanmar terhadap etnis tertentu sudah sangat dirasakan bahkan sebelum Burma berubah menjadi Myanmar. Pemerintahan Myanmar misalnya telah memberikan otoritas kepada etnis tertentu, seperti Mon, Chin, Kahcin, Kayah dan Shan untuk mendirikan sebuah negara tersendiri di wilayah Myanmar. Namun, otoritas tidak berlaku untuk etnis Rohingya, walaupun etnis ini mayoritas di wilayah Rakhine. Pemerintah lebih memilih etnis Rakhin yang beragama Budha yang hanya sekitar 10 persen menduduki wilayah tersebut untuk diberikan hak istimewa. Dengan demikian, mayoritas etnis Rohingya yang beragama Islam justru semakin dipinggirkan oleh penguasa bahkan dikebiri hak-haknya sebagai warga negara, sehingga kehidupan muslim Rohingya di Myanmar jauh dari rasa kemanusiaan apalagi kesejahteraan.
Adalah Aung San Suu Kyi, salah seorang pejuang demokrasi yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan perdamaian yang selama kurang lebih 28 tahun berjuang melawan kesewenang-wenangan junta militer Myanmar. Suu Kyi yang kemudian sukses membawa perubahan, didapuk menjadi pemimpin Myanmar dengan jabatan State Counsellor (setara perdana menteri) yang tentu saja “hadiah terindah” junta militer kepadanya. Suu Kyi dianggap sebagai ikon demokrasi negeri ini karena berhasil merubah tatanan pemerintahan yang dulunya sangat berkesan militeristik dan tertutup menjadi tampak lebih demokratis, mengedepankan nilai-nilai HAM, terbuka dan transparan. Atas jasanya bagi perjuangan demokrasi dan HAM, Suu Kyi kemudian dianugerahi Nobel Perdamaian pada 1991 dan Havel Price pada 2012.
Penggagas demokrasi dan perdamaian yang melekat pada Suu Kyi, belakangan mulai dipertanyakan banyak pihak, bahkan ada sementara kalangan yang memprakarsai sebuah petisi agar Nobel Perdamaian yang disematkan kepada dirinya dicabut. Nobel Perdamaian yang seharusnya melekat pada diri seseorang sepanjang hidupnya, justru ternodai oleh beberapa sikap dan pernyataan Suu Kyi sendiri yang terkesan rasis. Dia misalnya, pada 2013 lalu pernah mengutarakan kekesalannya karena telah diwawancarai seorang jurnalis dari BBC Today, bernama Mishal Husain. Mishal yang seorang muslim justru diketahui belakangan oleh Suu Kyi, sehingga di acara off air selepas wawancara, dirinya justru menggerutu dengan kalimat bernada rasis yang tidak pantas.
Pernyataan Suu Kyi yang kontroversial ini jelas bertolakbelakang dengan label pejuang demokrasi dan perdamaian yang disematkan kepadanya. Suu Kyi justru semakin mengukuhkan dirinya sebagai seorang rasis, antiperdamaian, dan bahkan anti-islam. Sikap diam dirinya terhadap pembantaian etnis Rohingya yang mayoritas muslim, membuat seluruh dunia kecewa dan muncul berbagai kecaman yang dialamatkan pada peraih Nobel Perdamaian ini. Sejauh ini memang sulit dimengerti, kenapa pemimpin Myanmar itu diam terhadap tragedi kemanusiaan yang jelas-jelas adalah bangsanya sendiri. Fenomena ini seakan mengingatkan kembali pada pembersihan etnis Yahudi oleh tentara Nazi Jerman pada 1940-an dengan alasan rasisme atas ras Arya yang superior.
Kita tentu dibuat miris oleh sebuah kenyataan bahwa selama 3 tahun terakhir, lebih dari 140.000 minoritas muslim etnis Rohingya di Myanmar terusir dari negerinya sendiri karena mengalami berbagai macam kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat militer dibawah pemerintahan Aung San Suu Kyi. Pemberitaan diberbagai media bahkan menggambarkan, bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang harus diterima mereka yang sama sekali jauh dari nilai-nilai HAM dan kemanusiaan. Suu Kyi tetap bungkam tak memberikan reaksi apapun terhadap serangkaian upaya kekerasan yang terjadi ini. Dia seakan membenarkan, bahwa etnis Rohingya mayoritas muslim tidak boleh hidup di negeri yang mayoritas beragama Budha. Lalu, masih pantaskah gelar Nobel Perdamaian disematkan pada Suu Kyi setelah dirinya mendiamkan tragedi kemanusiaan ini?
Banyak yang beranggapan, bahwa diamnya Suu Kyi justru terkait dengan isu politik, dimana partainya justru disokong penuh oleh kekuatan junta militer. Melawan militer sama dengan memberangus kekuasaannya sendiri. Perjuangan Suu Kyi sejauh ini, justru hanya sekedar “alat” hegemoni politik atas militer yang sampai saat ini masih berbulan madu dengan dirinya. Diakui atau tidak, Suu Kyi seakan bersimbiosis mutualisma dengan militer, dimana pihak militer hanya menjadikan Suu Kyi sebagai alat legitimasi pemerintahan Myanmar yang “demokratis” dimata negara-negara lain. Namun yang pasti, sentimen antimuslim tampaknya cenderung lebih kuat sehingga berdampak serius terhadap tragedi kemanusiaan atas minoritas muslim di Rohingya.
Saya kira, Suu Kyi sebagai seorang pejuang demokrasi sekaligus corong penggagas perdamaian di Myanmar seharusnya mampu menjadi sosok terdepan untuk mengecam dan bersuara lantang ketika ada pelanggaran HAM di negerinya sendiri. Posisinya yang strategis sebagai orang nomor dua di Myanmar justru akan dapat lebih didengar suaranya oleh penguasa. Yang dilakukan Suu Kyi justru lebih nyaman bersembunyi dibalik kursi kekuasaannya dan enggan melakukan langkah “bunuh diri” melawan tirani kekuasaan yang saat ini dikuasai junta militer. Yang lebih mengherankan lagi, bahwa Myanmar justru menolak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya, padahal sudah lebih dari 15 abad mereka ada disana. Bahkan, yang lebih menyakitkan, etnis mayoritas disana menyebut minoritas Rohingya sebagai “imigran ilegal” asal Bangladesh yang sampai detik ini tak pernah diakui keberadaannya.
Bagi saya, kesewenang-wenangan tirani manusia atas manusia harus dilawan, melalui suara bersama “memanusiakan manusia”. Terlebih melekat pada diri seorang pemimpinnya “tokoh perdamaian dan kemanusiaan”. Penilaian terhadap sesorang yang layak mendapatkan nobel perdamaian, bukanlah hal mudah dan bukan juga berdasarkan dorongan “kepentingan” pihak-pihak tertentu. Tentunya, pejuang nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan penggagas demokratisasi yang melekat pada diri Aung San Suu Kyi yang dilihat oleh lembaga pemberi nobel bergengsi itu. Lalu, jika kemudian kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan dan pengusiran masih terjadi di wilayah dimana dirinya berkuasa justru tetap ada dan bahkan dibiarkan, masihkah pantas dia disebut sebagai penerima Nobel Perdamaian?
Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.