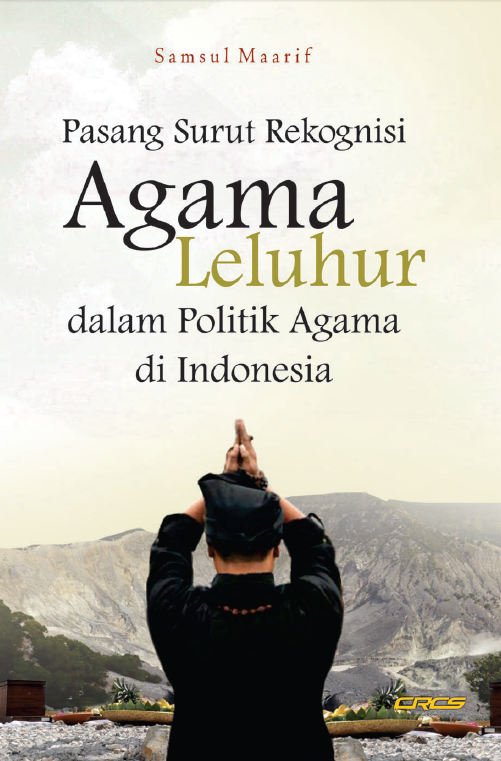Judul: Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur
Penulis: Samsum Maarif
Tahun Terbit: 2017
Penerbit: Center for Religious and Cros-cultural Studies
Tebal: xx + 130
ISBN: 978-602-50445-0-2
Penghayat Agama Leluhur di Indonesia mengalami fase-fase yang dinamis. Di era Hindia Belanda para penganut kebatinan mendapatkan tempat yang luas sebagai pihak yang dianggap mendukung Belanda dari pemberontakan yang pada umumnya diprakarsai oleh tokoh-tokoh Islam Di akhir orde lama dan selama orde baru mereka dituduh komunis, kepercayaannya ditetapkan sebagai budaya, dan penganutnya dipaksa berafiliasi ke agama resmi. Namun di era reformasi mereka mendapatkan kesempatan untuk memulihkan jatidirinya.
Pembedaan antara agama dan adat dimulai di akhir abad 19, ketika Pemerintah Hindia Belanda membedakan antara Islam politik dan Islam kesalehan serta adat. Kebijakan ini didasarkan kepada nasihat Snouch Hurgronje untuk menekan perkembangan Islam yang dipakai untuk melawan Belanda. Sejak itu agama resmi mulai terpolarisasi dengan adat/agama leluhur. Kebijakan ini memposisikan Islam sebagai musuh dan adat sebagai aliansi untuk melawan para pemberontak. Di sisi lain, adat dianggap primitif dan harus dimodernkan. Agama Kristen dengan sistem pendidikannya dipakai oleh negara untuk memodernkan adat. Untuk menjadi modern harus konversi menjadi Kristen. Kebijakan ini memposisikan adat/agama leluhur bukan sebagai agama.
Pada masa berikutnya, saat kesadaran orang Indonesia berorganisasi sudah mulai marak, sekali lagi adat diasosiasikan dengan perkumpulan atau partai politik sehingga pengelompokan masyarakat berdasarkan perkumpulan/partai selaras dengan kecenderungan partai politiknya. Budi Uotmo atau PNI berarti para priyayi-aristokrat, abangan berarti PKI, Islam berarti Masyumi, Muhamadiyah atau NU. Polarisasi yang dilihat oleh Clifford Geertz ini berlanjut sampai saat persiapan pembentukan negara Indonesia di era Jepang. Bahkan saat perumusan Pasal 29 UUD 1945.
Meletusnya pemberontakan PKI 1948 membuat polarisasi antara Islam dan abangan menjadi semakin hebat. Kelompok adat (dan kebatinan) yang belum tentu komunis, secara simplisistik – tanpa perlu dibuktikan dianggap sebagai pihak yang bukan Islam dan dengan demikian komunis.
Hegemoni agama-agama besar terjadi terhadap agama-agama leluhur saat Departemen Agama mengusulkan tiga ciri agama, yaitu adanya nabi, adanya kitab suci dan pengakuan internasional. Tiga syarat ini tentu saja sulit dipenuhi oleh agama leluhur. Definisi ini membuat kepercayaan tidak bisa digolongkan sebagai agama.
Karena merasa tak terwadahi dalam kelompok agama, para pemeluk kebatinan kemudian mengkonsolidasikan diri dengan membentuk organisasi-organisasi. Organisasi kebatinan ini, di awal 1950-an kemudian membentuk Badan Konggres Kebatinan Indonesia (BKKI) (hal. 26). Sebagai respon, karena khawatir aliran kepercayaan akan membentuk agama baru, Departemen Agama membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada tahun 1953.
Ketika di pemilu 1955 kelompok abangan memenagkannya dengan angka 59%, maka kelompok kebatinan ini segera mengkonsolidasi diri dengan membentuk BKKI. Kelompok ini menyatakan bahwa manusia Indonesia hendaknya mengutamakan kebatinan dan bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain, kemanusiaan dan dunia. Di Konggres II yang dilaksanakan di Solo yang dihadiri lebih dari 2 juta orang, kelompok abangan mengklaim bahwa kebatinan adalah bentuk implementasi dari sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Meski menyatakan bahwa kebatinan bukan agama, tetapi kelompok kebatinan mengirim surat kepada Sukarno yang meminta kebatinan disetarakan dengan agama dan mengusulkan 5 wakil di Dewan Nasional.
Meski kelompok kebatinan berhasil melakukan lobi-lobi politik, tetapi tekanan dari Departemen Agama dan Pemuda Islam terus berlanjut. Pemuda Islam menyuarakan bahaya klenik. Sedangkan Departemen Agama memasukkan Pendidikan Agama di satuan pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi. Bukan saja dari Departemen Agama dan Pemuda Islam, dalam Undang-Undang Kejaksaan tahun 1961, Kejaksaan diberi wewenang untuk mengawasi aliran kebatinan yang bisa membahayakan negara (hal. 33). Akhirnya melalui UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, delegitimasi kebatinan sebagai bukan agama menjadi nyata (hal. 34). Aliran kebatinan bisa dituduh melakukan penodaan agama.
Peristiwa G 30 S tahun 1965 membuat penganut kepercayaan tidak berani melakukan ritualnya secara terbuka. Sebagai kelompok yang dianggap belum beragama, banayk dari mereka yang dianjurkan untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh negara. Pemilihan salah satu agama juga mebuat mereka terhindar dari tuduhan sebagai anggota PKI. Karena kelompok abangan ini sebelumnya berseberangan dengan Islam, maka mereka banyak yang memilih Kristen, Katholik dan Hindu sebagai agama mereka. World Council of Church (WCC) melaporkan bahwa ada 2,5 juta yang memilih Kristen (hal. 39). Sebagai reaksi, Islam memprogramkan pengislaman orang Islam dan membawa kembali isu Piagam Jakarta. Namun upaya mengembalikan Piagam Jakarta mendapat penolakan dari kalangan militer.
Ketika Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik, Golkar secara aktif mengajak pemuka-pemuka aliran kebatinan untuk bergabung dengan mereka. Golkar menyarankan supaya “kebatinan” diganti dengan “kepercayaan.” Kata “kepercayaan” dipakai dalam rumusan Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian aliran kepercayaan seharusnya posisinya sejajar dengan agama. Oleh karenanya pemeluk kepercayaan berhak mendapatkan pelayanan di bidang hukum, organisasi, perkawinan pendidikan dan subsidi dari negara sama dengan pemeluk agama. Pemerintah Suharto menyambut baik usulan ini. Keputusan Pemerintahan Suharto ini tentu saja ditentang oleh kalangan Islam. Pada tanggal 15 Februari 1971 Senat Fakultas Usuludin IAIN Sunan Kalijaga mengeluarkan dklarasi yang menyatakan bahwa ketuhanan tanpa agama bertentangan dengan UUD 1945. HAMKA membuat brosur yang menentang kesejajaran kebatinan dengan agama. Namun Pemerintah tetap bergeming dengan keputusannya. Bahkan di tahun 1973, hal ini masuk dalam TAP MPR Nomor IV tentang GBHN yang menyatakan bahwa menegaskan bahwa kepercayaan dan agama adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sama-sama sah (hal. 45). Keputusan ini ditindak-lanjuti dengan UU Perkawinan pada tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara.
Kebijakan menyetarakan kepercayaan dengan agama ini mendapatkan reaksi yang sangat keras. Bahkan wakil Partai Persatuan Pembangunan melakukan walk out. Akhirnya pemerintah mengalah dan menyatakan bahwa aliran kepercayaan adalah budaya (hal. 52). Dengan mengkategorikan kepercayaan sebagai budaya dan bukan agama, maka pengelolaannya dipindahkan dari Departemen Agama ke Departemen Kebudayaan (Direktorat Bina Hayat yang kemudian menjadi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Melalui TAP MPR No IV/ 1978, disebutkan bahwa negara hanya mengakui 5 agama. Dengan demikian penghayat kepercayaan harus berafiliasi atau memilih salah satu agama dari kelima agama tersebut supaya mendapatkan pelayanan dari negara. Di KTP ada kolom agama yang wajib diisi.
Di penghujung era Orde Baru, tekanan terhadap aliran kepercayaan semakin besar. Kelompok Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) mentntut supaya aliran kepercayaan dikeluarkan dari GBHN. TAP MPR No II/1998 lebih jauh menyatakan bahwa kepercayaan harus memeluk salah satu agama (dunia) yang diakui oleh negara (hal. 62). Dengan demikian, seorang penganut kepercayaan mau tidak mau akhirnya harus memilih salah satu agama yang harus dipeluknya. Bahkan di TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001, kepercayaan telah dihilangkan.
Masuknya Bab tentang Hak Asasi Manusia dalam amandemen UUD 1945 membuat posisi agama-agama leluhur menjadi kuat kembali. Pasal 28E menyebutkan:
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal ini secara eksplisit membebaskan warga negara Indonesia untuk memilih caranya sendiri dalam mengekpresikan religiositasnya. Namun sayangnya di Pasal 28J ayat 2, kebebasan tersebut masih dibatasi dengan nilai-nilai agama. Selain itu revitalisasi UU PNPS tentang penodaan agama digunakan oleh banyak pihak untuk mengerdilkan kembali aliran kepercayaan. Kejaksaan dan Kementerian Dalam Negeri pun masih mengekang pelayanan kepada agama leluhur. Dalam pencatatan perkawinan misalnya, penghayat kepercayaan tetap tidak bisa mencatatkan perkawinannya kecuali mengikuti cara perkawinan salah satu agama. Untunglah dalam UU Administrasi Kependudukan nomor 23/2006 disebutkan bahwa bagi penganut kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh pemerintah bisa dikosongkan (hal. 84). Selanjutnya dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan dari penghayat kepercayaan tetap harus dilayani.
Akhirnya Negara mengakui kepercayaan sebagai sesuatu yang berarti dan menjadi bagian dari Indonesia. Dalam PP nomor 37/2007, pada Ketentuan Umum Pasal 1 No. 18-19 dituliskan:
(18) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
(19) Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Meski negara sudah mengakui hak-hak penganut kepercayaan, tetapi dalam implementasinya masih belum rapi. Masih banyak peraturan yang tumpeng tindih, sehingga para pemeluk agama leluhur ini mengalami kesulitan. Misalnya dalam hal pembuatan KTP. Instruksi Mendagri untuk mengosongkan kolom Agama di KTP bagi yang tidak menganut agama yang diakui secara sah oleh negara, telah menimbulkan kerancuan. Sebab ada beberapa pihak yang menuduh bahwa pengosongan kolom agama akan mendorong dihilangkannya kolom agama dari KTP. Atau ada juga yang menuduh bahwa pengosongan kolom agama berarti ia seorang tidak beragama, tidak bertuhan, ateis. Ganjalan-ganjalan semacam ini masih perlu terus diperjuangkan supaya semua warga negara mendapatkan haknya untuk memilih agama/kepercayaan yang dianutnya dan mendapatkan pelayanan yang sama oleh negara.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.