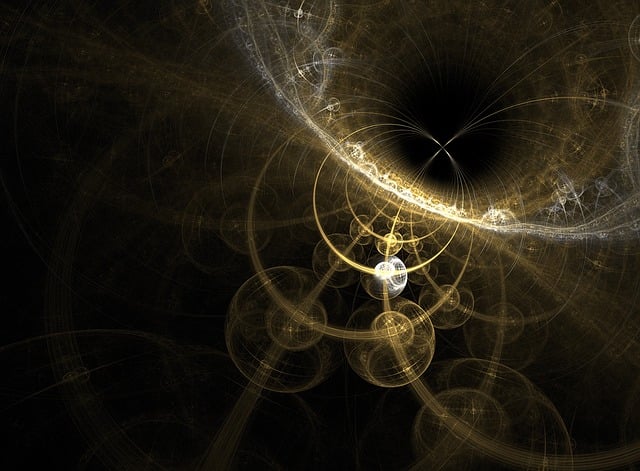Kutengok lagi jam tangan yang baru kubeli dua hari lalu. Setengah tujuh kurang lima menit. Seharusnya mobil itu datang menjemputku di mulut gang sempit sebelah stasiun KRL.
Sudah kutunggu sekitar lima belas menit. Gabut. Tanpa hape, sungguh bete. Tapi email dari majikan baruku tegas memerintahkan: “Anda diterima kerja, tetapi tidak boleh membawa ponsel ke kantor.”
Ada lagi syarat-syarat ganjil untuk bekerja di situ. Aku tidak boleh datang sendiri ke kantor yang alamatnya dirahasiakan. Juga dilarang memberitahu siapa pun tentang urusan kantor.
Tetiba mobil hitam muncul di depan hidungku. “Selamat pagi, Bang. Saya mau beli apel,” kata sopirnya sembari menurunkan kaca film pekat.
“Saya jual duku,” jawabku. Sesuai petunjuk di email kemarin.
Si sopir mengangguk. Pintu aku buka. Di dalam mobil ada seorang pria lain. Berjas rapi. Badannya lumayan tegap. Perut sedikit buncit. Beberapa helai uban menyembul.
“Wahyu, namamu jadi Wiro mulai hari ini. Dalam email, nama saya Teguh. Tapi panggil saja saya Dewa.”
“Baik, Pak Dewa. Senang sekali bisa diterima di kantor Bapak. Sudah enam bulan cari kerja, akhirnya dapat juga.”
“Kamu harus bersyukur. Kamu bekerja nanti untuk kantor yang melayani kepentingan negara.”
“Siap, Pak Dewa.”
**
Tibalah kami di sebuah bangunan bergerbang tinggi. Tanpa papan nama. Aku dan bos baruku masuk ke sebuah ruangan besar.
Ada sepuluh bilik bersekat. Mirip laboratorium bahasa. Beberapa pegawai sedang asyik mendengarkan sesuatu lewat headset. Sebagian lainnya sibuk memelototi layar laptop.
Satu hal yang mencolok: semua pegawai laki-laki. Katanya kantor untuk urusan negara, tapi tiada satu pun pegawai berseragam. Ah, entahlah. Bodo amat.
“Wiro, ini tempat kerjamu. Sehari satu sif saja. Tugasmu sederhana. Mendengarkan orang yang bicara di telepon. Mengetik isi obrolan. Tidak usah banyak bicara,” perintah si Bos.
“Baik, Pak Dewa,” jawabku.
Pria itu mengantarku ke bilik di barisan paling depan sebelah ujung. Ditunjukkannya password komputer dengan menunjukkan layar hapenya.
“Kamu harus ingat password ini,” tegasnya. “Lihat selalu layar. Jika muncul tanda gagang telepon hijau dan bunyi dering, tandanya ada obrolan yang harus kamu catat intinya. Paham?”
“Paham, Pak.”
“Jangan khawatir. Kamu bisa dengar lagu-lagu dangdut koplo di radio,” lanjutnya.
“Wah, saya memang suka dangdut koplo. Kok Bapak tahu?”
Pria itu tersenyum. “Hehehe. Aku tahu dua rekening tempat kau simpan hasil penggelapan di tempat kerjamu dulu, Wiro. Juga nomor telepon bandar pemasok pil koplo untukmu. Kau tahu berapa tahun penjara menantimu jika aku bongkar semua?”
Aku terdiam. Sialan. Aku pikir hanya aku yang tahu semua yang kusimpan di hapeku. Bukankah aplikasi-aplikasi jahanam itu juga dilindungi enskripsi?
“Tidak usah takut, Wiro. Bekerjalah untuk kantor ini. Menebus borok-borokmu,” hibur si Bos sambil menyeringai.
“Semua yang kamu kerjakan di bilik ini bisa saya pantau dari ruangan saya. Mengerti?”
Aku mengangguk. Pria itu menepuk-nepuk punggungku. “Selamat bekerja.”
Tak berselang lama, layar di depanku memunculkan tanda gagang telepon hijau. Aku sambar headset. Kupakai sambil tergesa-gesa memencet tetikus.
“Halo, Dik Nisa. Akhir bulan ini akan kita buat demo di depan pengadilan negeri. Biar hakim tahu, mahasiswa mengawal para buruh yang ditindas. Kamu bisa ajak teman-teman jurusanmu?” suara pemuda di ujung telepon.
“Bisa, Kak Bram. Nanti kami sewa tiga bus. Teman-teman sudah iuran. Ditambah hasil jualan barang bekas, cukuplah,” sahut gadis itu.
“Kamu hebat, Dik Nisa. Ini Kakak sedang bingung atur konsumsi untuk demo nanti. Warung makan Bu Tari yang biasa sumbang nasi baru saja terbakar. Untung ketahuan sehingga tidak ludes semua. Keparat betul orang-orang itu!”
“Hah, masak sih, Kak? Kakak yakin orang-orang itu pelakunya?”
“Ah, sudahlah, Dik Nisa. Kalau bukan mereka, siapa lagi. Kali lalu ada satu orang buntuti aku sampai ke warung Bu Tari. Seharusnya aku lebih hati-hati. Tak usah datang langsung ke sana. Kasihan orang-orang kecil jadi korban gara-gara aksi kita.”
“Kakak hati-hati juga. Jaga diri. I love you, Kak.”
“Iya, Dik. I love you too. Nanti aku kirim puisi untuk dibaca pada hari H. Tolong cari dua orang teman cowok untuk jadi pembaca, ya. Yang suaranya paling keras. Tak usah cari yang ganteng. Nanti aku cemburu, hahaha…”
“Oke, Kak,” pungkas gadis bersuara renyah itu.
Tiba-tiba muncul pesan di layar komputerku. “Hei, jangan melongo. Ketik sekarang juga!”
Aduh, si Bos benar-benar mengamatiku. Buru-buru aku ketik isi pembicaraan Bram dan Nisa.
Setelah mengetik, aku tepekur. Teringat pada gadis berlesung pipi itu. Sekretaris cantik yang nyaris jadi milikku. Sayang, dia sudah diembat bos di kantorku yang dulu. Aku patah hati dan jadi liar. Akhirnya kecanduan narkoba. Ah, dasar koplo!
**
Waktu bergulir cepat. Sudah dua minggu aku bekerja di kantor ganjil itu. Aku sudah mulai terbiasa mendengar obrolan seru orang-orang dari segala kalangan. Sesekali aku menguping pembicaraan oknum pejabat bejat.
“Rina, durian sudah dikirim sopir bosmu. Bilang terima kasih, ya pada bosmu. Nanti izin proyek sawitnya akan keluar dalam tiga hari,” ujar suara lelaki dari gedung kementerian.
“Iya. Makasih juga ya Mas. Kiriman parfum sudah aku terima. Makin sayang deh Rina sama Mas.”
“Malam Minggu ini aku ada waktu. Istriku pulkam dengan anak-anak. Gimana, kita ngamar lagi, ya?”
“Oke. Tapi belikan dulu lingerie yang sempat aku kirim fotonya kemarin”
“Ha…ha…untukmu apa yang tak kuberi, sayang?”
Mendengar obrolan semacam itu membuat fantasiku melayang. Enak betul jadi pejabat. Sungguh nikmat. Tak sengsara seperti jomlo yang hanya rebahan di akhir pekan.
“Kring…kring…” bunyi dering itu membuyarkan lamunanku.
“Halo Kak Bram. Aku sudah hubungi teman-teman jurusanku. Separuh lebih akan ikut demo nanti. Aku sudah baca dua puisimu. Yang satu mungkin terlalu keras, Kak. Nanti ada yang kupingnya panas. Di negeri ini, dilarang salah tulis puisi.”
“Ah, tak usah takut, Dik. Kita berjalan di jalan kebenaran. Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan!”
“Emm…baiklah, Kak. Oh, iya. Aku sudah kirim puisi rindu untukmu di chat IG. Jangan lupa dibaca sebelum tidur. Doaku untukmu, Kak. Sampai jumpa besok.”
Aku selalu bersemangat mengetik isi pembicaraan dua kekasih yang selalu bikin aku baper. Betapa beruntungnya si Bram punya cewek seperti Nisa. Satu hati membela orang-orang kecil.
**
Pagi yang mendung. Entah mengapa, hari ini aku merasa tak enak badan. Tapi tetap kupaksakan ngantor. Siapa tahu dengar obrolan seru lain yang tak terduga. Ah, pekerjaan ini lama-lama bikin aku kecanduan.
Jelang tengah hari, kudengarkan radio. Kupilih saluran radio dangdut koplo yang biasa aku dengar kala senggang.
Aneh, Jam segini siaran musik diganti berita.
“Dari kawasan seputar pengadilan kami melaporkan. Aparat menangkap sejumlah demonstran. Para mahasiswa melawan aparat yang merangsek dengan melempari batu. Aparat membalas dengan gas air mata,” kata reporter itu.
“Kring…kring…” Kulihat di layar, ada panggilan dari Nisa ke Bram. Tak ditanggapi. Panggilan kedua dan ketiga Nisa juga tak diangkat Bram.
“Kembali dari kawasan depan pengadilan. Saya harus lari ke daerah yang lebih aman. Aparat makin beringas. Memukuli demonstran secara membabi buta. Beberapa demonstran diseret dan dimasukkan truk aparat. Laporan kami lanjutkan setelah situasi lebih mendukung,” seru reporter dengan suara yang agak terputus-putus.
Aku menghela nafas panjang. Membayangkan apa yang terjadi pada Bram saat ini. Sementara itu radio kesayanganku kembali memutar dangdut koplo.
Kupejamkan mataku. Kugeleng-geleng kepalaku mengikuti irama koplo. Mencoba melupakan Bram dan Nisa.
Tetiba sebuah kain basah mendarat di wajahku. Perut buncit pria yang membekapku itu terasa di punggungku.
Aku berusaha melawan, namun cairan di kain itu membuatku lemas. Sayup-sayup terdengar lagu koplo di radio: “Tarik, Sis. Semongko...!”
***
Selesai.
Ria Gita
Praktisi psikologi yang suka merangkai aksara
Ikuti tulisan menarik ari gita lainnya di sini.