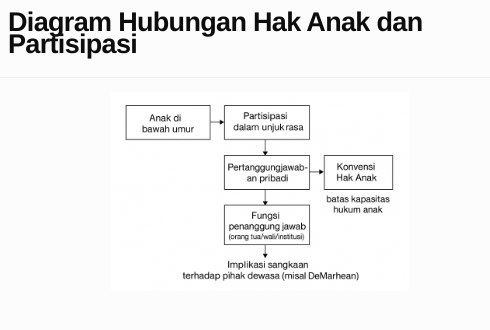Undang-undang Buatan Ayah
Kamis, 25 November 2021 08:51 WIB
Ia ingin secepat mungkin mengakhiri kunjungan, lalu pulang ke rumah. Tapi sial, perkataan sang ayah kembali terdengar jelas seperti saat pertama kali ia mendengarnya di kamp penyiksaan.
“Malam merupakan waktu favorit bagi para kriminal untuk berkeliaran mencari tempat-tempat sonder keramaian. Karena itu lah kalian ada disini, Badebah!” Ujar Rigi kepada anak buahnya yang mendapat tugas menjaga keamanan malam kota Barbiton.
Memberi wejangan memang sudah menjadi rutinitas Rigi sehari-hari. Mereka—anak buah Rigi—takkan pernah terbebas dari celotehan Rigi. Dari shift pagi hingga shift malam, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi anak-anak buahnya yang akan pergi bertugas.
Sebagai pemimpin tertinggi di Departemen Kepolisian Sektor Barbiton (DKSB), selain tegas, Rigi juga dikenal arogan oleh bawahannya. Mulutnya lebih tajam ketimbang belati yang ada di saku celana belakangnya. Tangannya pun tak segan-segan menjotos wajah mereka yang lalai dalam tugas, apalagi jika ada yang berani membantah segala perintahnya.
Di luar institusi, nama Rigi menjadi momok menakutkan bagi kebanyakan orang. Dikalangan bramacorah hingga aktivis, dirinya dijuluki seorang algojo yang siap menyiksa siapapun orang—berstatus tersangka atau belum—yang kedapatan olehnya melanggar Undang-undang Republik Omnipotensia. Tiada satu pun bandit yang bakal luput dari penglihatannya. Dimanapun dan kapanpun itu, uniform kebesarannya seolah telah menyatu dengan tubuh dan jiwanya.
Perangai kejam Rigi sengaja dibentuk oleh kedua orangtuanya sedari ia kecil; melalui cara-cara represif yang mereka (orangtua Rigi) anggap pantas dilalukan dalam proses sosialisasi primer. Ayahnya, Sirato merupakan tiran yang sangat bengis, korup, dan gila kekuasaan. Sedangkan ibunya, Malia adalah isteri yang terlatih untuk manut kepada sang suami.
Rigi kecil yang seharusnya berada di taman bermain bersama anak seumurannya, dialihkan oleh ibunya untuk turut menyaksikan—sesuai perintah Sirato—proses penyiksaan para bandit dan semua musuh politik ayahnya. Kala tragedi itu berlangsung, Rigi kecil merekam sebuah kalimat yang diucapkan ayahnya kepada ajudan presiden, dan masih tersimpan dalam memori otaknya sampai ia dewasa. Sirato mengingatkan kepada Nubus: “Pelaku kriminal tak kenal istirahat, termasuk para pengkhianat negara. Jangan mudah mempercayai orang di sekelilingmu!”
Berkat ingatan masa kecil tadi, Rigi dewasa bertekad kuat menumpas seluruh tindak tanduk kejahatan yang dapat mengancam negara, tak peduli dengan jadwal libur mingguannya sebagai polisi. Baginya, diam di rumah atau berlibur hanya akan merugikan negara.
*******
Pernah sesekali Rigi mencoba menjalani hidup seperti kebanyakan orang normal; menikmati waktu libur menyusuri tempat-tempat indah. Itu pun bukan berangkat dari keinginannya. Seorang wanita cantik berambut ikal, dan sangat disegani di lingkungan DKSB lah, orang dibalik patuhnya Rigi terhadap satu hari agung yang sering dinanti-nanti oleh setiap pegawai pemerintahan seperti mereka. Wanita itu bernama Elish, asistennya sendiri, sekaligus orang ketiga yang sangat Rigi percayai, setelah kedua orangtuanya.
Waktu itu, tepat ketika mentari baru merekah di hari Kamis, Elish sengaja mengusirnya dari kantor agar ia tidak bertugas di hari libur mingguan yang sudah terjadwal.
“Tuan, apakah Tuan tidak pernah merindukan masa-masa di mana Tuan menikmati libur panjang sekolah?” tanya Elish dengan raut wajah penasaran.
“Emm…ya, libur kenaikan kelas. Tentu saja aku rindu. Mengapa anda berusaha mengembalikan memori masa lalu itu, Nyonya Elish?” sembari mengenyernyitkan dahi.
“Kalau begitu, ada baiknya saya lancang demi mengobati rasa rindu Tuan.”
“Apa maksud anda, Nyonya Elish?”
“Silahkan tinggalkan kantor, arahkan pandangan Tuan ke Tanton! Di sana, Tuan akan mendapatkan keindahan Omnipotensia yang sesungguhnya.” pinta sekertarisnya.
Petunjuk Elisha membuat kelu lidahnya. Permintaan sang asisten tak dapat dielaknya. Elisha menghendakinya untuk menjamah jaket kulit impor yang tergantung di kapstok belakang pintu, lalu lekas pergi meninggalkan ruangan yang dipenuhi tumpukan berkas catatan kejahatan.
Udara pagi saat itu masih layak dihirup oleh warga yang rakus akan oksigen. Situasi masih sangat sepi; belum dipenuhi kendaraan, jejak kaki, hingga suara celotehan manusia. Hanya tampak jejeran gedung, burung lalu lalang di langit, dan ranting-ranting pohon berserakan di sepanjang jalan.
Rigi yang awalnya menolak mengisi waktu libur, anehnya malah larut dalam suasana hatinya sendiri. Ia menyunggingkan senyum saat melihat situasi Barbiton yang kondusif, sonder kriminil. Rasa senang, bangga, dan jumawa melebur menjadi satu. Seketika itu, ia lantas berpikir untuk membusungkan dada di hadapan para pimimpinan kepolisian kota pada rapat tahunan, begitu pula di hadapan sang ayah yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. Baginya, tiada lagi hal yang menarik selama di perjalanan, selain pencapaiannya menjaga keamanan Barbiton.
*******
Setelah hampir memakan dua jam dengan berjalan kaki, Rigi akhirnya tiba di kota—yang kata warga Barbiton—paling artistik di Omnipotensia. Ia mendapati deretan gedung-gedung mewah menoleransi keberadaan tembok-tembok kota Tanton yang dipenuhi mural. Karya seni jalanan yang tak pernah Rigi mengerti; arti dari setiap lukisan yang terpampang.
Tidak ketinggalan, anak-anak muda Tanton kedapatan tengah asyik berkumpul dalam sebuah arena diskusi di sekitar taman yang tidak jauh dari Tugu Selamat Datang. Kondisi mereka terlampau khusyuk; seluruhnya tenggelam pada pembahasan masa depan demokrasi Omnipotensia. Tanton jelas jauh berbeda dengan kondisi Barbiton yang serba kaku.
Berbeda dari kebanyakan orang yang pernah mengunjungi Tanton, kesan pertama Rigi saat menginjakkan kaki di kota itu malah tertegun, bukan kagum. Kota yang sering digembar-gemborkan paling artistik tersebut, nyatanya berhasil membuat orang nomor wahid di DKSB itu dongkol. Baginya, kebanyakan orang telah sejak lama bersekutu dengan pandangan yang keliru, salah satunya Elisha.
“Apa-apaan ini, bagaimana bisa pemerintah dan petugas kepolisian begitu kompak membiarkan warganya mengotori tembok dengan lukisan-lukisan tak bermoral.”
Muak melihat kondisi kota yang semrawut, Rigi memutuskan untuk bertemu Virgil, rekan sederajatnya di kepolisian Omnipotensia. Sesama pemimpin, ia tidak mau tinggal diam melihat rekannya membelot, sebab membiarkan kota Tanton menjadi sarang kriminil. Orang-orang seperti Virgil tak dapat diampuni olehnya, rekannya itu sudah membahayakan negara dengan mengacuhkan Undang-undang, demi merawat kebobrokan warga.
Gawai jadul merk Noknia buatan Jepun pun segera diraihnya dari saku kiri jaket. Tangan besarnya tampak gemetar saat menggenggam sembari menekan-nekan tombol karet sesuai kode alamat telepon rekannya itu. Ia tak sabar ingin mencemooh Virgil, kalau perlu mengakhiri karir Virgil, lalu menyeretnya kedalam jeruji besi.
“Hallo, Virgil, kau tak ubahnya seorang pengkhianat yang berlindung dalam balutan seragam.”
“Rigi sahabatku, apa maksudmu menuduhku di pagi yang cerah ini?” dengan nada lirih.
“Berhentilah berkata seperti pewarta ramalan cuaca, Virgil! Saat ini, aku berada di kota mu yang tampak menjijikkan.” sergahnya.
“Aku harap engkau berhenti menggerutu, lekas tanyakan saja dimana alamat kantorku!”
“Kebetulan, aku baru saja membeli kopi Brazil kualitas terbaik.” bujuk Virgil.
“Keparat kau, Virgil. Berani-beraninya kau menyumpal mulutku dengan secangkir kopi. Berikan alamatmu sekarang!”
“Siapapun tak dapat menolak nikmat tuhan yang satu ini, Rigi. Kantor Departemen Kepolisian Tanton ada di Jalan Basaw, nomor 101.” sahut Virgil.
Percakapan terputus sepihak, Rigi tak ingin lagi membuang banyak waktu yang dimilikinya.
Jarak antara Tugu Selamat Datang dengan kantor pusat kepolisian Tanton begitu dekat; hanya membutuhkan waktu lima menit dengan berjalan kaki. Namun, sedekat-dekatnya jarak, tetap saja amarah kadung menyusahkan jiwa pelancong amatiran sepertinya.
Gerak jarum jam yang tampak normal bagi warga Tanton, baginya terasa lambat. Ia ingin secepat mungkin mengakhiri kunjungan, lalu pulang ke rumah. Tapi sial, perkataan sang ayah kembali terdengar jelas seperti saat pertama kali ia mendengarnya di kamp penyiksaan. Tak ada pilihan, baginya, melanjutkan sisa-sisa liburan di Tanton yang banyak menguras emosi itu, sama saja dengan menjalankan tugas—memberantas musuh negara.
Bak prajurit militer di medan perang, suara derap langkah yang berasal dari sepatu bot Rigi menebar ancaman. Setiap burung yang sedang menginjakkan kaki di bumi yang Rigi tapaki, harus kembali terbang ke udara atau singgah sebentar di pepohonan terdekat. Cotok para unggas bersayap yang tadinya sibuk memungut remah roti sisa konsumsi warga dan wisatawan pun terpaksa terhenti.
Di sepanjang perjalanan menuju kantor DKST, matanya hanya terfokus kedepan, kiri-kanan jalan sengaja luput dari pandangan. Ia menolak mengotori martabatnya, sebab memperhatikan tembok kota Tanton—dari ujung ke ujung—yang dihiasi serba-serbi jenis mural. Jika ia menoleh pada salah satu mural, sama saja ia rela terjerat kedalam perangkap sang pelukis yang sengaja melukis di tempat umum (tembok pinggir jalan) agar terlihat oleh setiap orang.
Pantangan buatannya sendiri itu seketika terganggu, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Godaan untuk melirik menghantui segenap pikiran, juga perasaannya. Tak ingin terus merasa terancam, lantas ia hanya menjeling ke arah kanan jalan. Walhasil, tak ada satupun orang di sana, hanya terdapat gambar wajah mantan presiden ke-3, Sirato, yang terlukis sedang membakar bendera Omnipotensia menggunakan tangannya sendiri.
Melihat ayahnya di hina, Rigi meradang; masa lalunya terusik. Benda di sekelilingnya pun menjadi sasaran amarahnya yang kadung meluap.
*******
Setibanya di kantor Departemen Kepolisian Sektor Tanton (DKST), seorang lelaki muda menghampiri Rigi dan melayaninya dengan penuh takzim ala budaya hierarki; beruluk salam; memberi sapaan hormat; membantu melepas jaket; sampai mengantar tamunya itu kedepan ruangan pimpinannya, Virgil, yang berada di lantai empat.
Beruntung, berkat teknologi, lantai demi lantai terlewati dalam hitungan detik. Elevator sangat membantu meringankan langkah Rigi untuk bertemu Virgil di lantai paling atas gedung.
Setelah mereka berdua terkurung selama 20 detik, pintu lemari besi itu pun kembali terbuka. Posisi elevator persis menghadap pada satu ruangan besar. Tak ingin membuat tamunya kehilangan banyak waktu, lelaki dengan misai rapih itu pun mengajak Rigi bergegas keluar dari elevator menuju ruangan tersebut—tidak lain adalah ruangan Virgil.
Dari kejauhan, lelaki yang memandu Rigi kebingungan saat mengetahui derit pintu berbahan kayu jati tidak akan didengarnya. Pimpinannya seolah-olah sengaja membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut kedatangan tamunya itu. Namun, seperti biasa, budaya hierarki tetap berlaku meski pintu sudah terbuka.
“Lapor, Pak, Tuan Rigi yang terhormat sudah tiba!”
“Persilahkan orang itu masuk, jangan biarkan ia menunggu terlalu lama, Brob!
“Siap, laksanakan!”
“Terima kasih sudah memandu tamu ku, lekas kembali ke posisimu semula!”
Mengetahui lelaki pemilik misai rapih dengan bentuk tubuh atletis yang menemaninya itu terlalu banyak berbasa-basi, tak syak, membuat geram Rigi. Kepergian Brob amat sangat ditunggu-tunggu oleh pemimpin kepolisian Barbiton itu.
“Silahkan, Tuan Rigi, pimpinan kami menunggu Tuan!”
“Aku bukan Tuanmu, Jongos, enyahlah kau dari hadapanku!” memperlihatkan sorot mata tajam.
Suasana hening menyelimuti ruangan yang baru saja dilanda kisruh—pro-kontra adegan formalitas antara bawahan ke atasan. Virgil bertingkah layaknya barista yang tengah asyik meracik kopi pesanan pelanggan. Melihat rekannya sibuk berkutat dengan alat pembuat kopi, mau tidak mau, Rigi harus menahan emosi sembari menyeka peluh yang keluar dari pori-pori kulit wajahnya.
“Silahkan, Rigi, nikmatilah kopi buatanku!” Virgil memasang wajah senyum saat menyuguhi secangkir kopi kepada Rigi.
Rigi perlahan menyesap air yang sudah terkontaminasi serbuk Brazilian Coffee. Kerongkongannya yang lama kering semenjak berada di Tanton, kini mulai dibasahi.
“Eummm….lumayan. Sejumput kenikmatan ternyata hadir di secangkir kopi, bukan di kota yang kau diami, Brader!” tutur Rigi merendahkan profesionalisme Virgil sebagai kepala polisi.
“Oh ya, ngomong-nongomong, angin apa yang bisa membawamu sampai ke Tanton, Rigi?” tanya Virgil.
“Berhentilah berkata yang tidak penting, sekarang jawab saja pertanyaanku. Kenapa kau membiarkan kota ini dipenuhi para kriminal?” tukasnya.
“Hah, apa maksudmu?”
“Jangan berpura-pura bodoh, Virgil. Coretan di tembok menjadi bukti ketidak becusan kau memimpin kepolisian Tanton!” dengan nada ketus.
“Apakah yang kau maksud kriminal itu adalah mural, Rigi?” sahut Virgil.
“Apalagi kalau bukan itu, Jadah!”
“Oke, tolong tunjukan padaku peraturan yang menyebut seni lukis di ruang publik dilarang oleh negara?” tanya Virgil.
“Undang-undang Republik Omnipotensia, nomor 666 ayat 999. Tak usah kau menguji kredibilitas ku sebagai pemimpin.”
“UU peninggalan Sirato, ayahmu, berisi tentang larangan mengotori fasilitas umum. Aku pun sepakat tentang itu, akan tetapi, menurutku hanya sebatas limbah, sampah, dan coretan nir-makna, mural tidak termasuk.” tandasnya.
“Ya, benar, UU buatan ayahku. Dan, takkan ku biarkan orang-orang seperti mu secara serampangan menafsirkan UU warisan ayahku dengan seenak jidat.”
“Buka matamu, Rigi! Tanton dikenal sebagai gudangnya penyair, pelukis, pemahat, dan penulis ternama dunia. Lagi pula, sejauh ini belum ada masyarakat atau wisatawan yang memperkarakan mural, entah itu mural yang bermuatan kritik sosial hingga politik, justru mereka lah yang paling gencar mendukung keberadaan lukisan di tembok. Baru kau seorang yang bertindak berlawanan.”
“Tanton maju sebab demokrasi, dan kau harus ingat, negara kita sekarang menganut sistem itu. UU dibuat sesuai dengan keinginan rakyat, bukan keinginan tiran seperti 33 tahun lalu.” sambung Virgil.
“Dasar kau liberal tengik, pengkhianat negara. Jangan harap hidupmu bakal tenang, camkan itu!” timpal Rigi penuh kesal.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Sarjana Tua yang Tak Kunjung Kerja
Rabu, 8 Desember 2021 23:16 WIB
Undang-undang Buatan Ayah
Kamis, 25 November 2021 08:51 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 99
99 0
0