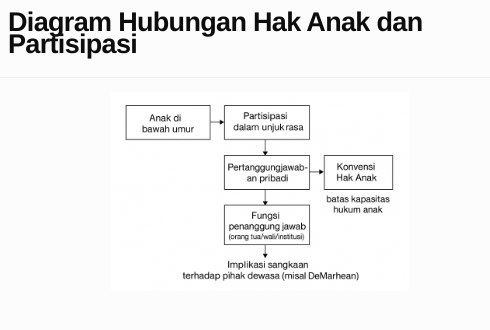Sarjana Tua yang Tak Kunjung Kerja
Rabu, 8 Desember 2021 23:16 WIB
Tidak dapat ku pungkiri, perusahaan-perusahaan bonafide yang aku incar, kebanyakan membutuhkan lulusan ilmu terapan, ketimbang ilmu murni. Sarjana Sosiologi sepertiku begitu terpuruk dalam dunia kerja. Beda urusan, jika aku mengandalkan jasa “Orang Dalem”.
Apa untungnya aku memikirkan hari libur datangnya kapan? Toh, aku hanya seorang penganggur; sonder penghasilan. Mau angka berwarna merah itu jatuh di hari Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya, aku tetap masa bodoh terhadap perhitungan Masehi.
Ketidakpedulianku pada hari libur kadung mandarah daging. Ingin rasanya aku menghilangkan kata “libur” dan membiarkan kata “hari”. Kata “hari” masih dapat ku tolerir, akan tetapi kata “libur” sudah semestinya tidak digunakan oleh para pengangguran, kalau perlu dilupakan saja. Namun, apalah daya, dua kata itu tidak mungkin dipisah; tergabung menjadi satu kalimat, syahdan merugikan satu pihak. Tentunya pihak ku, kaum penganggur.
Mendapati diri semakin terlecehkan, sisi radikal ku menggelora, menuntut agar aku tidak memajang almanak di dinding kamar. Sejujurnya aku ingin. Itu pun karena aku tergoda dengan gambar-gambar wanita bohay yang terdapat di almanak. Tubuh mereka (model wanita) singset, bak gitar Spanyol, sembari berpose layaknya Brand Ambassador sebuah produk pakaian high class. Meski, yah, kenyataannya, aku dapati wanita seksi itu di lembar almanak sebuah produk krupuk, terasi, hingga toko emas langganan Ibuku.
Pikirku, mungkin mereka sengaja menempatkan gambar wanita seksi berdampingan dengan jadwal Masehi. Pasalnya, wanita mampu membuat lelaki lupa akan segalanya. Sedangkan tanggalan, berfungsi untuk menjadwalkan banyak hari-hari penting, seperti: gajian, liburan, dan kelahiran.
Dari ketiga contoh tadi, hanya yang terakhir yang aku anggap patut untuk mendapat tempat didalam memori otak. Pasalnya, dengan mengingat tanggal lahir, aku tidak perlu mengeluarkan KTP saat mengisi kolom kelahiran di formulir pendaftaran kerja yang HRD berikan. Juga, memudahkanku mengalkulasi perkembangan umur setiap tahunnya.
*******
Purworejo, 12 Juli 1997. Tanggal dan tempat di mana aku terlahir, sekaligus diberi nama berbau-bau jantan, Vivaldi Erzak. Orang-orang biasa menyapaku “Valdi”, ada juga yang memilih “N’jak”. Terserah, aku tidak ingin ambil pusing, asalkan, jangan memenggal 3 huruf akhir nama depanku. Ya, jangan sekali-kali menyapaku “Viva”, sebab, jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti “Hidup”.
Bagaimana mungkin pengangguran sepertiku dapat hidup, terkecuali ada individu/kelompok yang sudi menghidupiku—orangtua, saudara, pemerintah, dan teman. Ah, sebenarnya aku ragu mencantumkan “teman”.
Jika dihitung-hitung, per 1 Desember 2021 lalu, umurku sudah 24 tahun lebih lima bulan. Secara kuantitatif, umurku masih terbilang sangat muda, namun, secara kualitatif diriku dianggap tidak produktif karena masih menganggur. Wajahku pun tampak 10 tahun lebih tua; kulit kencang perlahan mengendur dan rona wajah berseri ku memudar. Penyebabnya, apalagi kalau bukan memikirkan nasibku yang sudah setahun menganggur.
Status pengangguran seakan menolak lepas dari diriku. Orang di sekelilingku pun lama-kelamaan menjadi gemas. Semula, mereka bisa memaklumi kondisi ku yang lulus kuliah di tengah terjangan wabah Covid-19. Namun, setelah usia menganggur ku menyentuh 9 bulan, terjadi perubahan persepsi pada diri mereka. Antagonisme mulai menyeruak, orangtua, teman, dan saudaraku yang tadinya satu suara, seketika terpecah. Sialnya, kebanyakan dari mereka malah berbalik menyerangku. Anggap saja delapan dari sepuluh orang menuduhku ngedul.
Padahal, selepas menuntaskan agenda kelulusan, aku mampu menahan diri dari berleha-leha sebab larut dalam euforia. Aku bergegas mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sembari melakoni ikhtiar lainnya; mengedarkan Curicullum Vitae beserta dokumen penunjang ke banyak perusahaan. Mirisnya, kegigihanku untuk bekerja tidak membuahkan hasil. Aku gagal lolos tes CPNS, begitupula puluhan berkas lamaran kerja ku tidak kunjung mendapat balasan—undangan wawancara.
Tidak dapat ku pungkiri, perusahaan-perusahaan bonafide yang aku incar, kebanyakan membutuhkan lulusan ilmu terapan, ketimbang ilmu murni. Sarjana Sosiologi sepertiku begitu terpuruk dalam dunia kerja. Beda urusan, jika aku mengandalkan jasa “Orang Dalem”.
“Oh Tuhan, mengapa kau begitu tega memberiku nasib rumit—serumit saat aku memohon tipsen kepada temanku yang memegang teguh norma kesusilaan.” diriku bersenandika.
Aku yang tidak ingin memikul malu sendirian, lantas memilih menghabiskan waktu menganggur di rumah, daripada keluyuran; nongkrong atau berdarmawisata. Di bangunan megah milik orangtua ku itu, aku dapat molor berjam-jam, bila bosan melanda, aku tinggal menghibur diri dengan bermain PES 2020 di Playstation 3 milikku. Selain nyaman, aku juga terlindung dari terpaan angin, panas mentari, hujan, Covid-19, dan tidak ketinggalan hujatan yang datang dari teman seperkuliahan ku, dulu.
Satu-satunya kegiatan yang aku anggap produktif, yaitu; berkamuflase menjadi peternak burung Lovebird. Syukur Alhamdulilah, burung yang kubeli secara terpisah dari media sosial ternyata masih tokcer. Ibarat manusia, burung betina belum mencapai fase menopause, pejantannya pun belum impoten. Harapku pada si betina kelak, tidak lain agar selamat dalam proses perteluran dan sanggup mengerami telur sampai tiba waktu menetas. Piyik yang sehat adalah investasi ku di hari esok.
Inisiatif itu tumbuh berkat stimulus yang sering Ibu berikan padaku. Sekiranya, semua orangtua pasti akan melakukan hal yang sama seperti Ibuku, yakni: gemar membanding-bandingkan anak kandungnya dengan anak tetangga yang sudah meniti karir. Begitulah, orangtua seringkali tutup mata atas kondisi anaknya yang kerap terbentur hingga babak belur.
Sesekali, aku mencoba menerka-nerka jalan pikiran Ibu. Menurutku, Ibu merupakan salah satu dari sekain banyak anak-anak ideologis sistem Orba. Konon, mereka yang masih hidup akan tetap melazimkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kecurigaanku ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, Ibu pernah mengaku kepadaku bahwa dirinya telah dibantu oleh saudaranya untuk menjadi abdi negara. Dugaanku juga didukung oleh petuah dari Kakekku. Saban tahun aku mengunjunginya, Kakek selalu memberi wejangan yang sama kepadaku.
“Apalah artinya sebuah proses panjang, jika hasilnya nanti tetap saja nihil. Bayar saja, semua pasti beres kok!”
*******
Kondisi menganggur ini mencapai titik kulminasi. Tepatnya di penghujung hari Minggu, 20 November 2021. Senja di hari itu tampak sempurna; warna kuning kemerahannya berdampingan mesra dengan pendahulunya, langit biru. Alam seolah-olah tidak pernah bosan memanjakan mata setiap orang. Khususnya, bagi mereka yang di keesokan hari akan kembali kepada pelukan sang pengupah.
Kala senja berusaha menggodakuku untuk molor, tiba-tiba saja terdengar suara lagu berjudul “Nightmare” milik grup musik asal Amerika, Avanged Sevenfold. Meski tubuhku letih sehabis membersihkan kandang burung di kebun belakang rumah, namun, konsentrasiku tetap terjaga. Aku menyadari suara itu berasal dari ponselku sendiri.
Jantungku berdegup kencang ketika kudapati pemberitahuan di layar ponsel. Seorang sahabat sekaligus musuhku dalam arena perjudian, mencoba menghubungiku semenit yang lalu.
1 Panggilan masuk dari Amar pada 17:50 WIB.
Amar, seorang lelaki berperawakan kekar, berambut klimis, bermisai ala-ala pemuda English—orang di negaraku mengenalnya sebagai gaya Wak Doyok—tidak pernah menganggap kawan main terdekatnya sebagai sahabat. Baginya, tidak adil jika memilih sesuai ideal masing-masing, lantas menyingkirkan lainnya.
“Semua orang adalah saudara. Siapapun orang yang sudah aku anggap saudara, harus mau memberiku uang, kudapan, dan apapun yang aku butuhkan ketika fase menganggurku tiba”. Amar bersabda.
Ucapannya 3 tahun lalu itu masih dapat aku hapal sampai sekarang. Aku tidak sanggup menyingkirkan wejangan itu dari benakku.
Ponselku kembali berbunyi. Nada dering panggilan masuk masih tetap sama, begitupun orang yang mencoba menghubungiku.
Kali ini, aku berusaha tenang sebelum menjawab panggilan. Tujuan Amar menelponku, jelas bukan untuk bertanya kabar, apalagi sekedar menagih novel The Dante Club karya Matthew Pearl yang aku janjikan kepadanya. Kemungkinan besar, ini tentang kekalahan Manchester United atas Arsenal di Old Trafford, pekan kemarin. Pasalnya, bukan cuma Setan Merah yang merugi, tetapi semua orang yang bertaruh untuknya. Kehilangan Rp500.000, bukan perkara kecil bagi seorang pengangguran.
“Halo, dimana kau berada?” Amar mengawali.
“Rumah, seperti sediakala. Sore-sore begini, ada perlu apa kau menelponku?” penuh cemas jika benar Amar ingin mengungkit haknya.
“Sebentar, jangan bilang kalau kau masih menganggur, Valdi?” kelakarnya.
“Bagaimana bisa dakwaan seseorang dinyatakan benar, jika tanpa dibarengi bukti?” cemas bercampur kesal.
“Lho, belum pernah kutemukan, seorang pekerja berusia muda betah meringkuk di waktu libur yang terbatas ini.” Amar berdalih.
“Sudah-sudah, temui aku di Wakrop Mang Atep. Bergabunglah bersama kawan serevisian mu, dulu!” sambung Amar.
“Haha…baiklah, perkumpulan tengik itu memang membutuhkan figur sepertiku.” aku mengakhiri percakapan dengan perasaan lega.
Jarak antara kedai kopi yang amat tersohor di seantero Pejaten dengan tempat tinggalku di Citayam, kira-kira sekitar 22 kilometer. Untuk sampai ketujuan, aku biasa mengandalkan sepeda motor buatan India pemberian Ayah. Dengan kuda besi itu, perjalananku hanya membutuhkan waktu 1 jam.
Di waktu malam, sepanjang jalan Citayam-Margonda begitu lengang. Tersisa debu jalan yang beterbangan dengan bebas, mengotori wajah-wajah pengendara sepeda motor yang berhelm sonder visor dan masker. Aspal-aspal yang mengelupas pun terlihat samar-samar, berkat cahaya lampu jalan yang kian meredup, seakan memaksa setiap pengendara yang melintas malam itu—termasuk aku—untuk menyerahkan diri ke pihak asuransi.
Tidak ada yang menarik, kondisi ruas utama antar kota itu belum mengalami perubahan. Kecuali, kehadiran cahaya kelap-kelip lampu yang dililit pada dahan pohon yang tertanam di tengah jalan.
Setibanya di tapal batas Depok-Jakarta, aku sengaja mengurangi kecepatan sepeda motorku. Selain menghemat bahan bakar, aku juga dapat mengenang jalan-jalan yang sering aku lalui semasa kuliah. Aku terkejut, saat disuguhkan pemandangan teranyar, mulai jalan layang sampai warna-warni lampu Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Lagi-lagi, lampu menjadi aksesoris andalan penghias malam.
Durasi perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 1 jam itu, bertambah menjadi 20 menit sebab ulahku yang larut dalam nostalgia. Tidak ingin membuat Amar menunggu, aku langsung memacu sepeda motorku. Suara bising yang keluar dari knalpot sepeda motorku, bersahut-sahutan dengan suara gemuruh kereta api listrik. Jalur kereta yang berada persis disamping jalan protokol, merupakan kesempatan emas untuk menjajal kecepatan. Kapan lagi aku bisa balapan dengan ular besi buatan negeri Sakura.
Adu cepat antara aku dengan Masinis, berakhir di Stasiun Pasar Minggu. Kami pun berpisah. Pengemudi kereta itu melanjutkan jalannya kereta listrik menuju stasiun berikutnya—Stasiun Pasar Minggu Baru, sedangkan aku menuju kedai kopi yang letaknya tidak jauh dari gedung kampus swasta tertua di Jakarta, tempatku dulu berkutat dengan teori.
Di kedai milik Mamang Atep, orang-orang dapat bebas bergunjing ria; berdebat tentang sepakbola maupun keadaan bangsa. Di tempat itu pula, sejarah perjuangan kami, 5 mahasiswa jurusan Sosiologi dalam merebut gelar S.Sos terekam. Aku, Amar, Dorif, Herun, dan Mima sering mencurahkan isi hati sampai membahas teori, sembari menyesap kopi saset buatan Mamang Atep. Biasanya, kami di sana setelah menyelesaikan konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. Namun, setelah berhasil lulus di tahun 2020, aku jarang berkunjung ke sana, tapi tidak dengan ke-4 temanku yang mengaku sering mampir sejenak.
Sekian lama tidak menginjakkan kaki, kedatanganku di kedai milik Mamang Atep disambut meriah oleh tingkah nyeleneh Amar, dan disusul ke-3 teman ku.
“Dajal datang, Dajal datang, cepat selamatkan diri kalian!” teriak Amar membuat pelanggan Mamang Atep melirik ke arahku.
“Kiamat telah tiba, kiamat telah tiba, hatiku gembira.” Dorif, Herun, dan Mima begitu kompak merespon Amar. Mereka berhasil memancing tawa orang sekitar berkat memparodikan lagu “Libur Telah Tiba”.
Gelak tawa tidak terbendung. Aku biarkan mereka menghabiskan sisa tawa yang masih mengendap. Hitung-hitung, amal jariah untukku.
Satu menit berselang, suasana menjadi tenang. Karbon dioksida yang keluar dari mulut-mulut mereka ketika tertawa, membuat sesak seisi ruangan. 2 ventilasi yang terdapat di kedai berukuran 3x4 itu, tidak mampu mengeluarkan udara yang tidak layak hirup. Bukannya menunggu sampai udara di ruangan kembali segar, Mima malah membuka obrolan.
“Valdi, apakah gelar S.Sos dapat membantu kita meraih pekerjaan?” tanya Mima kepadaku.
“Entahlah, bagaimana menurutmu?” jawabku.
“Jelas tidak, kerja kita tidak perlu mengandalkan gelar sarjana.” kata Mima menjawab pertanyaannya sendiri.
“Tapi Mima, bukannya gelar sarjana merupakan modal penting agar kita dapat diterima kerja di perusahaan bagus?” tanyaku pada Mima sembari memasang wajah lugu.
“Maksudmu, kau akan bahagia bersama perusahaan yang menerimamu itu?” sela Dorif penuh rasa penasaran.
“Bukan, bukan. Menurutku, Valdi menganggap jerih payah kita selama duduk di perguruan tinggi akan terbayarkan ketika kita bekerja.” Herun menanggapi pertanyaan Dorif.
“Benar, gelar memang membantu kita saat melamar kerja. Tapi, kau juga harus ingat, Valdi. Kata “Kerja” sendiri tidak dikhususkan untuk mereka yang bekerja pada suatu perusahaan saja.” Amar menimpali pertanyaanku.
“Maksudmu?” tanyaku pada Amar.
“Amar, biarkan aku yang menutup perdebatan ini!” seru Dorif agar Amar berhenti berkata.
“Kegaiatan apapun yang kau lakukan setiap hari itu adalah kerja. Hanya saja, kerja yang tidak menghasilkan upah.” sambung Dorif.
“Ya, aku setuju denganmu, Dorif. Sekarang, tolong dengarkan aku, Valdi!” pinta Amar agar aku memperhatikannya secara saksama.
“Meskipun sepanjang hayatku nanti belum juga menjadi pegawai kantoran, tetapi aku menolak mati sebagai pengangguran. Aku mengisi waktu menganggurku dengan terus mencoba melamar kerja. Selepas itu, aku tidak membiarkan pikiranku dipenuhi hayalan-hayalan kontra produktif. Aku mencoba menulis apapun yang ingin ku tulis. Aku ingin seperti Pramoedya Ananta Toer, abadi.” sambung Amar.
Catatan:
Bohay akronim Body Aduhay.
Tipsen akronim Titip Absen.
Ngedul adalah kata yang berasal dari Bahasa Sunda. Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, berarti: Ogah-ogahan; Menggigit.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Sarjana Tua yang Tak Kunjung Kerja
Rabu, 8 Desember 2021 23:16 WIB
Undang-undang Buatan Ayah
Kamis, 25 November 2021 08:51 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 99
99 0
0