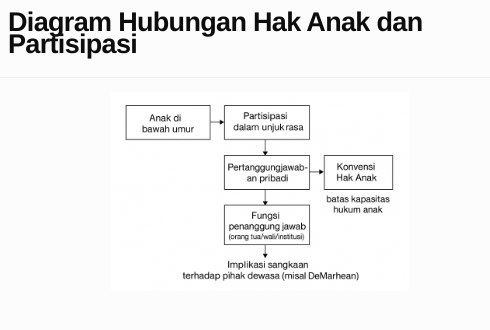Cerita yang Tertinggal di Bawah Langit New York
Rabu, 8 Desember 2021 20:45 WIB
Cerita yang tertinggal di bawah langit New York
New Yor, 2019
“Mar.”
Ia menatapku, matanya bergetar. Bersamaan dengan itu, senja yang menjatuhi Washington Square Park berubah menjadi api yang membakar seluruh tubuhku. Aku menggeliat, dalam geming yang tak bisa kupecahkan. New York, membiru dalam pandanganku.
#
New York, 1993
Wajah Nat selalu lebih cerah saat musim panas, musim panas adalah musim milik Nat, musim dimana ia bisa menghabiskan sepanjang malam di kelab malam di Manhattan tanpa disibukkan dengan tumpukan tugas kuliah. Dan musim panas adalah musim dimana menjadi agenda wajib Nat untuk merayuku untuk pergi bersamanya ke kelab malam.
“sudah berapa lama kau di New York?”
“tiga tahun…hampir.”
Si blonde menggelengkan kepalanya, “tiga tahun? Tapi kau masih saja kolot dengan budaya timurmu itu! Boleh ku tanya satu hal?”
Aku mengangguk tanpa mengalihkan mataku dari salah satu fiksi milik Woody Allen berbau usang yang kutemukan di himpitan fiksi perpustakaan NYU.
“apakah kau masih perawan?”
Kali ini aku mendelik, sedikit kesal dengan pertanyaan konyolnya, “Nat, bagi New Yorker sepertimu, mungkin terlalu kolot mempertahankan keperawanan diusia yang sudah sedewasa ini, tetapi bagi orang – orang timur seperti kami, keperawanan adalah harga mati bagi seorang perempuan.”
“tapi bersenang – senang di kelab malam bukan sebuah dosa kan menurut budayamu itu?”
Aku membalasnya dengan sebuah senyum singkat, tanda aku menyerah dengan sifat keras kepalanya. Dan akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah hidupku dan sepertinya, Nat menganggap ini adalah keberhasilan paling besar dalam hidupnya. Ia berhasil menyeretku untuk ikut bersamanya pergi ke kelab malam di Manhattan.
#
Sudah dua kali aku memuntahkan isi perutku, kepalaku seperti ditumpuki sekarung kerikil berujung lancip. Sakit dan menusuk – nusuk. Namun Nat melarangku untuk pulang. Dia membiarkanku tersiksa dengan aroma alkohol, asap rokok, serta orang – orang yang meliuk diantara dentingan musik yang bagiku sama sekali tidak manusiawi untuk telinga.
“dia Mariam, my best friend.” Kali ini Nat mengenalkanku kepada seorang lelaki yang berada di balik meja bar sekembalinya aku dari toilet. Laki – laki yang tampak acuh.
“can i have some water, please?”
Aku langsung meneguk habis sebotol mineral yang disodorkannya kepadaku.
“dia juga dari timur, indonesia. Sama sepertimu.”
“kau pasti lebih sering kesini dari dugaanku, sampai – sampai kau mengenal bartender-nya.” Bisikku, tanpa menyembunyikan rasa kesalku. Aku bersumpah, setelah hari ini, aku tidak akan membantunya menyelesaikan tugas literasi Mr. Freud yang menjadi momok menakutkan bagi si blonde.
“dia ganteng dan…hot.” Bisik Nat sebelum meninggalkanku dengan si bartender, “bersenang – senanglah.”
Aku meminta sebotol lagi mineral, kemudian menyisakannya setengah.
“kenapa tidak bergabung dengan Nat?”
“aku tidak cocok dengan tempat ini.”
Seperti kata Nat, laki – laki ini memang ganteng. Hidungnya, bibirnya, serta tatapannya seperti kumpulan medan magnet yang terus menarik pandangku. Manusiawi bukan ketika seseorang mengagumi keindahan, aku berusaha membenarkan kenyataan mataku yang tak lepas darinya.
“lalu kenapa kemari?”
“Nat memaksaku, dia tidak akan berhenti jika tidak berhasil.”
Aku menghabiskan sisa isi botolku, anehnya, malam ini aku sangat kehausan. Aku menoleh kepadanya sekilas setelah mencari keberadaan Nat yang sudah tidak tampak oleh mataku, laki – laki bartender itu membersihkan tangannya dengan sebuah lap, kemudian mengambil mantel tipisnya.
“mau keluar dari sini? Saya traktir kopi.”
Kami keluar dari kelab malam. Berjalan beriringan, membelah udara hangat New York di musim panas bersama puluhan lampu neon berisi slogan iklan disisi – sisi jalan. Suhu udara yang menyenangkan untuk manusia bertubuh tropis seperti kami. Ia meninggalkanku sebentar, lalu kembali dengan janjinya untuk mentraktirku, segelas kopi.
“nama saya Pram. Saya dari Surabaya, sebelum ke sini, saya tinggal cukup lama di Jakarta.” Ia melepaskan mantel tipisnya, aku pun merasakannya, udara New York menghangat seiring malam yang semakin larut.
“lalu bagaimana kau bisa ada disini.”
“panjang ceritanya, yang jelas tujuan saya kesini adalah melarikan diri.”
“kenapa?”
Ia mengangkat bahunya, lalu mengalihkanku dengan pertanyaan lain, “bagaimana orang – orang memanggilmu?”
“oh sorry, nama saya Maria. Maria Kemala.”
“nama yang bagus.”
“jadi disini hanya menjadi Bartender yang digila – gilai oleh para gadis New York?” Aku yakin aku tidak salah dengan pertanyaanku. Aku cukup percaya diri, jika banyak sekali gadis New York –mungkin termasuk Nat- yang mengajaknya berkencan.
"saya punya kerjaan sampingan lain.”
“apa?”
“menjadi mahasiswa.”
“jurusan apa?”
“jurusan membosankan.”
“kuliahnya dimana?”
“NYU.”
“sama, tapi kita tidak pernah bertemu sebelumnya.”
“mungkin belum waktunya.”
Aku tertawa mendengar jawabannya. Dia lebih dari ganteng dan seksi seperti yang dikatakan Nat, ia menarik dan menyenangkan, sebagai lawan bicara juga sebagai seorang laki – laki.
Kopi di dalam gelasku hampir kosong, namun jalanan Manhattan tidak juga tampak kelelahan, sepertinya ia juga ingin kami terus terjaga sepanjang malam hanya dengan menggiringnya dengan langkah – langkah kami.
“bagaimana denganmu? Menyenangkan berada di negeri orang?”
“dunia ini lebih luas dari yang kubayangkan. Tempat ini lebih sesak dari Jakarta, tetapi juga jauh lebih menenangkan. Aku suka kebebasannya, maksudku kebebasan berpikir orang – orang disini.”
“orang – orang yang berideologi liberal memang cocok tinggal di negeri ini.”
Langkah kami berhenti di halte bus. Kami terdiam, cukup lama. Bus yang berhenti, kami biarkan berlalu begitu saja. Aku tidak ingin mengakhiri malam ini begitu saja, aku ingin lebih mengenal laki – laki ini. Laki – laki yang tiba – tiba saja membuat dadaku seakan selalu kehilangan udaranya, namun rasanya menyenangkan.
“mau bermalam bersamaku?”
“apa?”
Ia tersenyum, tapi aku mengangguk tanpa memahami arti ucapannya yang sebenarnya. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya erat, dan malam itu, kami terjaga sampai pagi di sebuah sudut perpustakaan di Bleecker St, Greenwich Village sambil membicarakan banyak hal seolah kami didesak oleh waktu untuk saling mengetahui satu sama lain, tanpa melakukan hal lain.
“siapa penulis yang kau sukai?” Tanyaku sebelum kami berpisah.
“akan kukatakan nanti.”
Nanti yang dimaksudnya adalah hari dimana aku melihat banyak sekali tumpukan buku dari para penulis klasik saat mengunjungi apartemennya.
#
New York, 1997
“maafkan aku Pram.”
Desember mencapai puncaknya. Punggung Pram tampak kelelahan. Kekecewaan juga terlihat jelas disana. Keduanya berlomba di bawah rempetan sinar matahari yang tercium basah diantara celah jendela yang dibiarkan Pram terbuka sedikit. Jelas sekali kekecewaannya bukan karena kegagalan kami yang akan menghabiskan pergantian tahun di Praha.
Hal lain. Karena hal lain.
“Pram…”
Akhirnya ia berbalik setelah mengemas beberapa buku terakhir ke dalam tasku.
“aku akan pulang Mar. Tunggu aku.”
Aku terdiam. Suaranya membuat debar dadaku meluap. Kami beradu mata dan aku selalu kalah oleh kecoklatan di dalam matanya.
Sudut bibirku sedikit terangkat. Kesungguhannya membuatku begitu ingin menggodanya.
“kau yakin?”
“apa maksudmu?”
Ia mudah terpancing dengan nada meragukan yang sengaja kukeluarkan.
“seperti kata Nat, semua gadis di kelab malam menginginkanmu, aku…”
Ciuman halus dan singkatnya membuat aku berhenti berbicara.
Ia duduk disampingku, di bibir jendela yang berhadapan dengan langit New York yang perlahan dijatuhi matahari senja. Seperti biasa, orang – orang New York yang selalu menjadi pemandangan yang kami nikmati bersama. Hari ini, bersama butiran salju yang terlihat lebih putih dari hari sebelumnya.
“tunggu aku Mar, setelah studi-ku selesai, aku akan pulang dan melamarmu.”
Aku merebahkan kepalaku didadanya, membalas genggaman tangannya tanpa bicara. Hari itu, adalah hari terakhir kami menyaksikan orang – orang serta langit New York bersama. Ibu memintaku pulang, usaha keluargaku diambang kehancuran dan Papa mengalami depresi karena hal itu.
#
New York, 2019
“mengapa lama sekali Mar?”
Waktu, bagi kami adalah rentetan hari yang kami lalui dengan saling menunggu.
Aku tidak menjawab, meskipun begitu banyak yang ingin kukatakan. Semuanya tercekat didalam tenggorokkanku. Aku punya semua alasannya, hanya saja aku tidak bisa mengatakan kepadanya. Setidaknya bukan hari ini.
Nat, seperti biasanya, ia selalu melakukan semuanya tanpa seijinku.
“bagaimana kabarmu Mar?”
Aku masih tidak sanggup menjawabnya. Mataku nanar. Menahan desakan air yang memaksa keluar dari mataku.
Siluet senja hampir tidak bersisa, jendela kaca coffee shop di persimpangan bleecker st milik Nat tampak muram ditinggal senja. Matahari telah menyelesaikan tugasnya, membagikan cahaya di belahan dunia barat, tempat kami sekarang berada. New York, tiba – tiba menjadi sepi dan kehilangan suaranya. Sementara ombak di dasar hatiku mulai bergelung tak karuan.
“maafkan aku Pram.”
“apakah kau menerima surat – surat saya Mar?”
“…”
“kenapa kau tidak membalasnya? Saya mencarimu kemana – mana, saya ke Jakarta, kealamat yang kamu berikan, saya bertanya kepada semua orang. Nat dan teman – temanmu yang lain.”
Suaranya tenang dan dalam, namun getar sedih dan kecewanya menyentuh sampai ke palung hatiku.
“saya menunggumu Mar.”
Ia mengambil tanganku yang memeluk cangkir kopi didepanku. Tidak ada yang berubah, masih sama, disana masih ada sepasang mata yang mampu membawaku kedalamnya. Ketampanannya masih tersisa, namun tidak kupungkiri jika kelelahan juga jelas ada disana.
“maafkan aku Pram.”
“jelaskan kepada saya Mar, tell me everything, apa yang terjadi?”
Aku menggeleng, menarik tanganku dari genggaman tangannya. Aku belum bisa Pram.
“Mar, ada apa?” Desaknya.
“aku…”
Ombak di dalam hatiku semakin menggunung dan bergelung mendesak dadaku. Aku tau, aku tidak bisa menahannya lagi.
Bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya kepada Pram jika aku adalah bukti peristiwa porak poranda negeri kami di tahun 1998.
Katakan! Katakan padaku bagaimana caranya?!
Nat! dimana dia?
###
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Cerita yang Tertinggal di Bawah Langit New York
Rabu, 8 Desember 2021 20:45 WIB
Burung-Burung Pemberi Kabar
Rabu, 8 Desember 2021 20:40 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 99
99 0
0