Kaleng Kecil di Tepi Jalan
Jumat, 11 Februari 2022 09:37 WIB
Hal yang mengusik hatiku ialah tubuh anak itu kurus. Kering sekali. Sementara perutnya yang buncit, tampak menyembul dari balik kaos dekil compang-camping berwarna hijau pudar.
Tampak seorang anak kecil duduk bersila di pinggir trotoar tepi jalan raya besar Ibu Kota ini. Aku sedari minggu lalu selalu memperhatikannya.
Menengadah tangan bersama dengan tatapan mata kosong yang cekung, kepada setiap orang yang lewat. Di depannya tergeletak kaleng susu yang terbuka. Kaleng itu memerah, kosong dan berkarat.
Kulit anak itu menggelap, terbalut paparan debu dan asap kendaraan yang senantiasa terhirup ke dalam paru-paru. Satu-satunya pohon palem yang menaungi tubuh ringkih itu pun, seolah tak kuasa memberikan ia udara bersih serta tempat sejuk untuk bersadah.
Hal yang mengusik hatiku ialah tubuh anak itu kurus, kering sekali. Sementara perutnya yang buncit, tampak menyembul dari balik kaos dekil compang-camping berwarna hijau pudar.
Aku adalah seorang mahasiswi jurusan ahli gizi. Kampusku terletak tak jauh dari daerah ini. Melihat perutnya yang buncit dengan badan bak hanya belulang saja, aku bisa menebak bahwa dia menderita kwashiorkor. Suatu kondisi busung lapar kronis akibat gizi buruk dalam jangka waktu lama.
Sebagaimana hal yang sama yang terjadi pada anak-anak di benua Afrika nun jauh di seberang sana. Di benua tandus itu, begitu banyak kasus balita kekurangan gizi. Sehingga sering digembar-gemborkan oleh media massa.
Hingga seolah kami menutup mata, bahwa masih banyak pula anak-anak yang bernasib seperti itu, bertebaran di negeri ini. Mereka bersembunyi di kolong-kolong tergelap Ibu Kota. Seolah kami juga lupa, bahwa sebenarnya negeri ini adalah negeri yang subur. Gemah Ripah Loh Jinawi.
Libur semester kali ini, aku tak berencana pulang ke kampung halaman. Ongkos tiket pesawat yang mahal membuatku enggan pergi. Orang tua di tanah kelahiran, pasti memaklumi hal itu.
Bukankah jaman sekarang, rindu tak harus bertatap langsung? Ada berbagai media sosial yang menghubungkan kami yang sedang terpisah berjauhan. Dengan media sosial juga, kami menemukan orang-orang di masa lalu, yang nyaris terlupakan. Di abad ini, jarak memang bukan lagi suatu masalah.
Maka untuk mengisi liburan semester yang panjang, aku berencana bergabung sebagai relawan di sebuah LSM. Kantornya berada tepat di depan kampus.
Banyak mahasiswa yang bergabung di LSM tersebut untuk mencukupi sertifikat Tri Dharma Perguruan Tinggi mereka. Salah satunya mengharuskan setiap mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Aku tergerak hati bergabung bulan ini. Aku dengar dari salah seorang petugas kenalanku disana, bahwa LSM tersebut akan mengadakan pemantauan dan pengobatan. Sasarannya ialah anak-anak penderita gizi buruk yang tersebar di sepanjang jalan besar di sekitar wilayah ini.
Termasuk juga anak dengan kaleng kecil di tepi jalan yang senantiasa menarik perhatianku.
***********
Siang menjelang, aku menelusuri lorong sempit bersama tiga orang rekan relawan yang lain. Ya, aku menuju rumah anak kecil itu. Kami mengikuti petunjuk yang di dapat rekan kami, Putri dan Felix.
Mereka mendapatkan alamat rumah anak tersebut dari seorang pedagang bakso yang biasa mangkal di dekat anak kecil itu menadahkan tangannya.
Dari kejauhan, rumah itu tampak kumuh dan pengap, tak jauh berbeda dengan kondisi rumah-rumah tetangga sekitar sana. Perkampungan padat itu dikitari oleh got-got kotor yang bau. Tempat tikus-tikus besar berlarian.
Tali-tali jemuran yang kusut tak beraturan, menggantungkan pakaian-pakaian usang yang baru saja dicuci. Tumpukan sampah tersebar di mana-mana. Seakan menyuruh kami untuk segera pergi dari sana.
“Permisi, selamat siang…” Aku menyapa pemilik rumah sambil mengetok pintu. “Ya, sebentar...” Terdengar sapaan bersambut. Seorang ibu dengan mengenakan daster membuka pintu yang terbuat dari sehelai tripleks tipis.
Raut wajah ibu tersebut menyerukan tanda tanya perihal kedatangan kami.
“Perkenalku Bu, saya Nur dari Lembaga Sosial Masyarakat Tali Kasih, dan ini rekan saya: Mega, Putri, dan Felix.” Aku memperkenalkan diri beserta rekan-rekanku yang lain kepadanya.
“Kami sedang dalam pendataan terhadap anak-anak gizi buruk di wilayah sekitar sini. Boleh kami wawancara sebentar, Bu?” Lanjut Mega, sambil memperlihatkan selebaran data dan brosur yang kami peroleh dari LSM.
Wanita paruh baya yang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Darmo itu, mempersilahkan kami masuk, dan duduk di lantai ruang tamu Aku dan rekan yang lain tercengang, melihat isi perabot dalam ruang sempit itu.
Tampak televisi 21inch terpampang di dinding yang telah pudar mengelupas. Terdapat kulkas besar, dan beberapa alat elektronik yang menurut kami cukup mewah untuk berada di sebuah rumah kumuh seperti ini. Kami hanya saling pandang, keheranan.
Tak lama Bu Darmo datang dengan menggendong anaknya. Anak yang saban hari aku lihat duduk meminta-minta di pinggir jalan di bawah pohon palem. Anak itu bahkan hampir tidak bisa berdiri lagi. Badannya lemah dan rapuh, seperti tangkai kayu kering yang sedang berjuang agar tak patah.
Anak perempuan malang itu bernama Sari. Ia bungsu dari enam bersaudara. Saudara-saudaranya yang lain ada yang mengamen, dan ada juga mengemis. Pak Darmo hanyalah seorang kuli bangunan lepas, yang hanya akan dipanggil bekerja jika sedang ada proyek.
Sementara Bu Darmo sehari-hari memilah sampah plastik dan botol minuman. Dari satu tong sampah ke tong sampah yang lain. Untuk dijual kepada pengepul. Pun hasilnya tak seberapa.
Diantara keenam anaknya, hanya Sari yang mempunyai kondisi busung lapar. Saudara-saudaranya yang lain tak ada yang separah dirinya. Melihat kondisi tersebut, kami memutuskan bahwa anak ini harus dirawat di rumah sakit.
Kami meminta izin membawa Sari untuk diajak berobat. Di rumah sakit dia akan diberikan penanganan berupa terapi gizi buruk yang dapat membantu mencukupi nutrisi serta merangsang tumbuh kembangnya.
Kami harus mengejar perkembangannya agar sesuai dengan anak usia 9 tahun, usianya sekarang. Seluruh biaya nanti akan ditanggung oleh LSM kami.
Bu Darmo tampak menimang-nimang penuh keraguan, seperti ada yang dia sembunyikan. “Saya harus diskusi dulu dengan bapak.” Begitu ujarnya singkat sambil menutup pintu, mempersilahkan kami pergi.
Esok harinya kami datang lagi, dan yang membuat kami semakin heran, mereka menolak pengobatan tersebut. Namun kami tidak menyerah, sehinga esok hari dan esok harinya lagi, kami terus datang. Membujuk Pak dan Bu Darmo agar menyetujui pengobatan untuk Sari.
Setelah kami berusaha dengan gigih berkali-kali, akhirnya Pak dan Bu Darmo menyerah. Mereka izinkan kami membawa Sari ke rumah sakit. Kata dokter, kondisi anak itu sudah terlalu kronis. Butuh waktu dan kesabaran agar kondisinya dapat membaik.
Kami serahkan sepenuhnya kepada tim rumah sakit untuk melakukan yang terbaik bagi kesembuhan Sari. Kami bergantian menemani masa-masa Sari dirawat. Dari matanya yang cekung itu, terbesit ratapan terimakasih berulang kali kepada kami.
Senyumnya sedikit mengembang. Meski terlihat untuk melakukannya, dia harus mengeluarkan banyak tenaga, dengan susah payah.
Pagi hari tepat dihari kelima, saat giliranku menjaga Sari, Pak dan Bu Darmo datang. Mereka bersikeras membawa Sari kembali pulang ke rumah.
“Tapi Pak, Pengobatan Sari masih harus dilanjutkan sampai kondisinya benar-benar pulih. Lagi pula kami tidak meminta uang sepeser pun dari Bapak. Pengobatan ini gratis sepenuhnya.” Aku mencoba memberi pengertian.
“Maaf nak, Sari harus segera kembali bekerja. Sudah empat hari ini penghasilan keluarga kami menurun drastis setelah Sari berhenti mengemis. Diantara anak-anak kami yang lain, hanya Sari yang bisa memberikan kami uang paling banyak. Karena tak sedikit para pejalan kaki yang iba melihat kondisinya,” ucap Pak Darmo.
Tiada rasa penyesalan atau kasihan sedikit pun dari kata yang terlontar dari bibir pria paruh baya itu.
Bu Darmo mengangguk mengiyakan. “Saya juga takut kalau nanti Sari sembuh, penghasilan keluarga kami akan berkurang. Karena dia takkan bisa lagi mengemis belas kasihan dari orang-orang.”
“Ya Tuhan...” Aku terkejut bukan main. Pantas saja mereka bisa membeli barang-barang elektronik mewah yang menghiasi rumah itu. Tentu barang-barang tersebut bisa mereka beli dari hasil Sari mengemis dengan kondisinya yang seperti ini.
Mereka seolah menjual dengan keji, rasa iba orang-orang yang melihat tubuh rapuh anaknya dengan mata cekung yang layu itu.
Keputusan dari pihak orang tua begitu bulat. Mereka tetap bersikeras membawa Sari pulang saat itu juga. Bahkan infus yang menancap di kulit punggung tangan Sari, hendak mereka cabut dengan paksa.
Tak ada yang bisa aku lakukan, selain hanya memandang sosok tubuh Sari pergi menjauh dalam gendongan Pak Darmo. Keluar ruang rawat. Dari balik punggung Pak Darmo, mata Sari menyeruak menatapku. Tatapan itu memelas, seolah memohon meminta tolong.
Aku menggigit bibir. Tak ada hukum yang memayungi kami jika memaksa Sari untuk tetap berbaring di ranjang rumah sakit. Sementara kedua orang tuanya sebagai wali pasien, meminta pengobatan harus diakhiri.
Kami bukanlah siapa-siapa bagi Sari. Juga bukan siapa-siapa bagi keluarga mereka.
Kami hanya sekedar orang asing yang kebetulan lewat dan bertemu Sari di pinggir jalan. Sebagaimana aku yang sering bertemu sekian banyak pengemis dan pengamen. Mereka bertebaran menghiasi jalanan.
Semakin hari jumlah anak-anak itu semakin banyak. Menjadikan Ibu Kota yang sudah sesak, semakin semrawut wajahnya. Aku menghela nafas panjang. Berkali-kali menenangkan diri.
***********
Sore itu aku berjalan menapaki trotoar. Kulihat seorang anak telah kembali duduk bersandar di bawah pohon palem.
Tangannya bergetar menengadah dengan mata yang cekung. Memancarkan sorot panggilan mengiba pada orang-orang yang berlalu-lalang di hadapannya.
Tubuh itu kurus bagai belulang kering. Dari balik kaos lusuh yang telah koyak, tampak perut buncit tersembul. Seolah hendak membuncah.
Dia sendirian, hanya bertemankan kaleng kecil di tepi jalan. Kemudian tanpa sengaja, mata kami tiba-tiba bertemu.
-Ni Wayan Wijayanti-
Bali, 6 Februari 2022
Penulis Indonesiana
4 Pengikut

Seonggok Bayi Usang
Minggu, 5 Januari 2025 14:25 WIB
Sudra
Senin, 27 Mei 2024 13:31 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0



 Berita Pilihan
Berita Pilihan



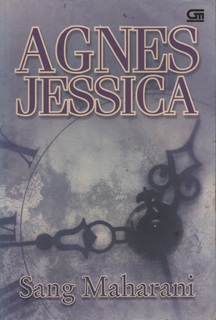

 98
98 0
0

















