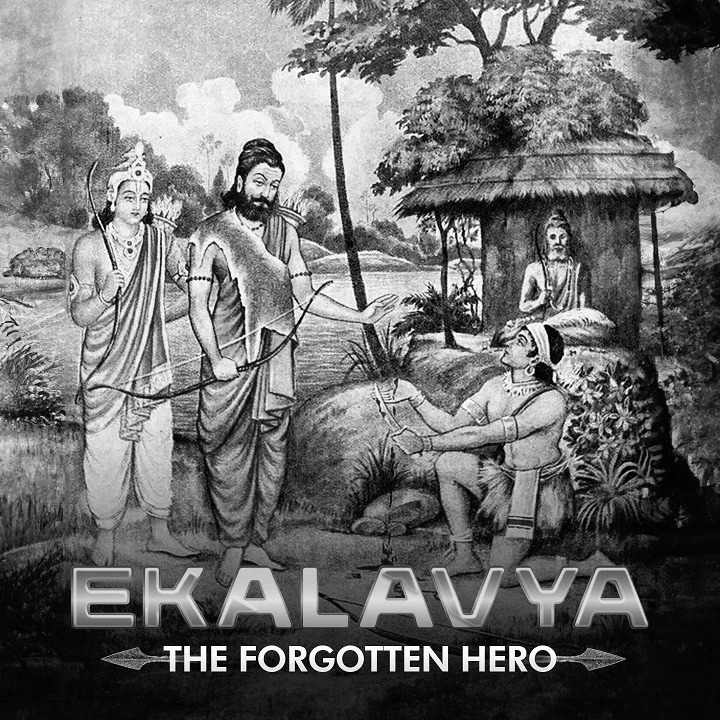Jenis Semiotik Dalam Kajian Fiksi
Dalam pandangan semiotik yang berasal dari teori Saussure bahasa merupakan sebuah sistem tanda, dan sebagai suatu tanda bahasa mewakili sesuatu yang lain yang disebut makna. Bahasa sebagai suatu sistem tanda dalam teks kesastraan, tidak hanya menyaran pada sistem (tataran) makna tingkat pertama (first-order semiotic system). Melainkan terlebih pada sistem makna tingkat kedua (second-order semiotic system) (Culler, 1977: 114). Hal itu sejalan dengan proses pembacaan teks kesastraan yang bersifat heuristik dan hermeneutik di atas.
Peletak dasar teori semiotik ada dua orang, yaitu Ferdinand Je Saussure dan Charles Sanders Peirce. Saussure-yang dikenal sebagai bapak ilmu bahasa modern-mempergunakan istilah semiologi, sedang Peirce yang seorang ahli filsafat itu memakai istilah semiotik. Kedua tokoh yang berasal dari dua benua yang berjauhan itu, Eropa dan Amerika, dan tidak saling mengenal, sama-sama mengemukakan sebuah teori yang secara prinsipial tidak berbeda. Dalam perkembangan semiotik yang kemudian, terlihat adanya kubu Saussure yang berkembang di Eropa dengan tokoh-tokoh seperti Barthes, Genette, Todorov, dan Kristeva-dan kubu Peirce yang berkembang di Amerika. Jika semiotik model Saussure bersifat semiotik struktural, model Peirce bersifat semiotik analitis. Adanya ketidaksamaan antara keduanya, tampaknya lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Peirce memusatkan perhatian pada berfungsinya tanda pada umumnya dengan menempatkan tanda-tanda linguistik pada tempat yang penting. namun bukan yang utama. Hal yang berlaku bagi tanda pada umumnya, berlaku pula bagi linguistik, namun tak sebaliknya. Saussure, di pihak lain, mengembangkan dasar-dasar teori linguistik umum. Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan bahwa ia menganggap bahasa sebagai sebuah sistem tanda (van Zoest, dalam Sudjiman & van Zoest, 1992. 2).
Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda (Hoed, 1992: 2). Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini meski harus diakui bahwa bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap dan sempurna. Tanda-tanda itu dapat berupa gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, bentuk tulisan, warna, bendera, bentuk dan potongan rumah, pakaian, karya seni: sastra, lukis, patung, film, tari, musik, dan lain-lain yang berada di sekitar kehidupan kita. Dengan demikian, teori semiotik bersifat multidisiplin sebagaimana diharap kan oleh Peirce agar teorinya bersifat umum dan dapat diterapkan pada segala macam tanda. Semiotik dapat diterapkan pada (atau: menjadi bidang garapan) linguistik, seni (dengan berbagai subdisiplinnya). sastra, film, filsafat, antropologi, arkeologi, arsitektur, dan lain-lain.
Perkembangan teori semiotik hingga dewasa ini dapat dibedakan ke dalam dua jenis semiotik, yaitu semiotik komunikasi dan semiotik signifikasi. Semiotik komunikasi menekankan din pada teori produksi tanda, sedangkan semiotik signifikasi menekankan pemahaman, dan atau pemberian makna, suatu tanda. Produksi tanda dalam semiotik komunikasi, menurut Eco (lewat Segers, 1978: 24) mensyaratkan adanya pengirim informasi, penerima informasi, sumber, tanda-tanda, saluran, proses pembacaan, dan kode. Semiotik signifikasi, di pihak lain, tidak mempersoalkan produksi dan tujuan komunikasi, melainkan menekankan bidang kajiannya pada segi pemahaman tanda-tanda serta bagaimana proses kognisi atau (interpretasi)-nya.
- Teori Semiotik Peirce
Teori Peirce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai tanda jika ia mewakili sesuatu yang lain. Sebuah tanda yang disebutnya sebagai representamen haruslah mengacu (atau: mewakili) sesuatu yang disebutnya sebagai objek (acuan, ia juga menyebutnya sebagai designatum, denotatum, dan dewasa ini orang menyebutnya dengan istilah referent). Jadi, jika sebuah tanda mewakili acuannya, hal itu adalah fungsi utama tanda itu. Misalnya, anggukan kepala mewakili persetujuan, gelengan kepala mewakili ketidaksetujuan. Agar berfungsi, tanda harus ditangkap, dipahami, misalnya dengan bantuan suatu kode (kode adalah suatu sistem peraturan, dan bersifat transindividual). "Sesuatu" yang dipergunakan agar sebuah tanda dapat berfungsi disebutnya sebagai ground. Proses pewakilan tanda terhadap acuannya terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan dalam hubungannya dengan yang diwakili. Hal itulah yang disebutnya sebagai interpretant, yaitu pemahaman makna yang timbul dalam kognisi (penerima tanda) lewat interpretasi.
Proses pewakilan itu disebut semiosis. Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai tanda, yaitu mewakili sesuatu yang ditandainya (Hoed, 1992: 3). Sesuatu tak akan pernah menjadi tanda jika tidak (pernah) ditafsirkan sebagai tanda. Jadi, proses kognisi merupakan dasar semiosis, karena tanpa hal itu semiosis tak akan terjadi. Proses semiosis yang menuntut kehadiran bersama antara tanda, objek, dan interpretant itu oleh Peirce disebut sebagai triadik. Proses semiosis dapat terjadi secara terus-menerus sehingga sebuah interpretant menghasilkan tanda baru yang mewakili objek yang baru pula dan akan menghasilkan interpretant yang lain lagi.
Peirce membedakan hubungan antara tanda dengan acuannya ke dalam tiga jenis hubungan, yaitu (1) ikon, jika ia berupa hubungan kemiripan. (2) indeks, jika ia berupa hubungan kedekatan eksistensi, dan (3) simbol, jika ia berupa hubungan yang sudah terbentuk secara konvensi (Abrams, 1981: 172; van Zoest, 1992: 8-9). Tanda berupa ikon misalnya foto, peta geografis, penyebutan atau penempatan di bagian awal atau depan (sebagai tanda sesuatu yang dipentingkan). Tanda yang berupa indeks misalnya, asap hitam tebal membubung menandai kebakaran, wajah yang terlihat muram menandai hati yang sedih, sudah berkali-kali ditegur namun tak mau gantian menegur menandakan sifat sombong, dan sebagainya. Tanda yang berupa simbol mencakup berbagai hal yang telah mengkonvensi di masyarakat. Antara tanda dengan objek tak memiliki hubungan kemiripan ataupun kedekatan, melainkan terbentuk karena kesepakatan. Misalnya, berba gai gerakan (anggota) badan menandakan maksud-maksud tertentu, warna tertentu (misalnya putih, hitam, merah, kuning, hijau) menandai (melambangkan) sesuatu yang tertentu pula, dan bahasa. Bahasa merupakan simbol terlengkap (dan terpenting) karena amat berfungsi sebagai sarana untuk berpikir dan berasa.
Dalam teks kesastraan ketiga jenis tanda tersebut sering hadir bersama dan sulit dipisahkan. Jika sebuah tanda itu dikatakan sebagai ikon, ia haruslah dipahami bahwa tanda tersebut mengandung penonjolan ikon, menunjukkan banyaknya ciri ikon dibanding dengan kedua jenis tanda yang lain. Ketiganya sulit dikatakan mana yang lebih penting. Simbol jelas merupakan tanda yang paling canggih karena berfungsi untuk penalaran, pemikiran, dan pemerasaan. Namun, indeks pun-yang dapat dipakai untuk memahami perwatakan tokoh dalam teks fiksi-mempunyai jangkauan eksistensial yang dapat melebihi simbol. Misalnya, belaian kasih dapat lebih berarti daripada kata-kata rayuan. Ikon, di pihak lain, adalah tanda yang mempunyai kekuatan "perayu" yang melebihi tanda yang lain. Itulah sebabnya, teks-teks kesastraan-juga teks-teks persuasif yang lain seperti iklan dan teks teks politik-banyak memanfaatkan tanda-tanda ikon (van Zoest, 1992: 10-11).
Dalam kajian semiotik kesastraan, pemahaman dan penerapan konsep ikonisitas kiranya memberikan sumbangan yang berarti. Peirce membedakan ikon ke dalam tiga macam, yaitu ikon topologis, diagramatik, dan metaforis (van Zoest, 1992: 11-23). Ketiganya dapat muncul bersama dalam satu teks, namun tak dapat dibedakan secara pilah karena yang ada hanya masalah penonjol..n saja. Untuk membuat pembedaan ketiganya, hal itu dapat dilakukan dengan mem buat deskripsi tentang berbagai hal yang menunjukkan kemunculannya. Jika dalam deskripsi terdapat istilah-istilah yang tergolong ke dalam wilayah makna spasialitas, hal itu berarti terdapat ikon topologis. Sebaliknya, jika termasuk wilayah makna relasional, hal itu berarti terdapat ikon diagramatik (dapat pula disebut: ikon relasional atau struktural). Jika dalam pembuatan deskripsi mengharuskan dipakainya metafora sebagai istilah-yang mirip bukan tanda dengan objek. melainkan antara dua objek (acuan) yang diwakili oleh sebuah tanda hal itu berarti ikon metafora.
- Teori Semiotik Saussure
Teori Saussure sebenarnya berkaitan dengan pengembangan teori linguistik secara umum, maka istilah-istilah yang dipakai (oleh para penganutnya pun) untuk bidang kajian semiotik meminjam dari istilah istilah dan model linguistik. Hal itu bukan saja karena Saussure yang mengilhami mereka, melainkan juga sewaktu mereka mengembangkan teori semiotik, linguistik (struktural) telah berkembang pesat. Bahasa sebagai sebuah sistem tanda, menurut Saussure, memiliki dua unsur yang tak terpisahkan: signifier dan signified, signifiant dan signifie, atau penanda dan petanda. Wujud signifiant (penanda) dapat berupa bunyi-bunyi ujaran atau huruf-huruf tulisan, sedang signifie (petanda) adalah unsur konseptual, gagasan, atau makna yang terkandung dalam penanda tersebut (Abrams. 1981: 171).
Misalnya, bunyi 'buku', yang jika dituliskan berupa rangkaian huruf (atau: lambang fonem): b-u-k-u, dapat menyaran pada benda tertentu pada bayangan pendengar atau pembaca, (yaitu: buku), yang ada secara nyata. Bunyi atau tulisan 'buku' itulah yang disebut penanda, sedang sesuatu yang diacu itulah petanda. Dalam teori Saussure, walau keduanya dapat disebut sebagai dwitunggal, hubungan antara penanda dengan petanda bersifat arbitrer. Artinya, hubungan antara wujud formal bahasa dengan konsep atau acuannya, bersifat "semaunya" berdasarkan kesepakatan sosial. Antara keduanya tidak bersifat identik. Kita tak dapat menjelaskan mengapa benda yang berwujud buku itu disebut 'buku' dalam suatu bahasa, bukan 'bulan' misalnya, dan itu akan disebut secara berbeda-beda dalam berbagai bahasa yang lain. Bahwa bunyi 'buku' itu mengacu pada benda tertentu, hal itu terjadi hanya karena masyarakat pemakai tanda (bahasa) itu menyepakatinya demikian. Kesepakatan itu dapat saja tidak berlaku dalam masyarakat (bahasa) yang lain yang telah memiliki kesepakatan sendiri.
Kanyataan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem, mengan dung arti bahwa ia terdiri dari sejumlah unsur, dan tiap unsur itu saling berhubungan secara teratur dan berfungsi sesuai dengan kaidah, sehingga ia dapat dipakai untuk berkomunikasi. Teori tersebut melan dasi teori linguistik modern (yaitu: strukturalisme), dan pada giliran selanjutnya teori itu dijadikan landasan dalam kajian kesastraan (Zaimar, 1991: 11). Dalam studi linguistik, misalnya, dikenal adanya tataran fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dalam kajian karya sastra juga dikenal adanya kajian dari aspek sintaksis semantik, dan pragmatik. Atau, menurut Todorov (1985: 12), kajian dikelompokkan berdasarkan aspek verbal, sintaksis, dan semantik, sedang menurut kaum Formalis Rusia dibedakan ke dalam wilayah kajian stilistika, komposisi, dan tematik. Kajian semiotik karya sastra, dengan demikian, dapat dimulai dengan mengkaji kebahasaannya dengan menggunakan tataran-tataran seperti dalam studi linguistik.
Bahasa sebagai aspek material, atau alat, dalam karya sastra, lain halnya dengan, misalnya, cat dalam seni lukis, telah memiliki konsep makna tertentu sesuai dengan konvensi masyarakat pemakainya di atas. Oleh karena itu, unsur bahasa tersebut sudah tidak bersifat netral walau tak tertutup kemungkinan untuk dikreasikan. Di pihak lain, sastra mempunyai konvensi antara lain untuk tidak menuturkan sesuatu secara langsung, sehingga makna yang disarankan pun lebih menunjuk pada tataran sistem makna tingkat kedua. Misalnya, hal itu terlihat pada penggunaan pelambangan-pelambangan dan atau perbandingan perbandingan. Dengan demikian, dalam sastra tidak saja signifiant menyaran pada signifie, melainkan juga signifie menyaran pada signifie-signifie yang lain. Hal itu mirip dengan proses semiosis (Peirce) yang terjadi secara berkelanjutan sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga sebuah signifie (interpretant) menghasilkan penanda baru yang mewakili sesuatu yang lain (baru) lagi.
Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik. Salah satu teori Saussure yang dipergunakan secara luas di bidang kajian kesastraan adalah konsep sintagmatik dan paradigmatik. Hal itu misalnya, dilakukan oleh Roland Barthes dan Tzvetan Todorov yang mengelompokkan kedua konsep itu ke dalam aspek sintaksis dan semantik. Dalam sebuah wacana, kata-kata saling berhubungan dan berkesinambungan sesuai dengan sifat linearitas bahasa, dan tidak mungkin orang melafalkan dua unsur sekaligus. Di pihak lain, di luar wacana, kata-kata yang mempunyai kesamaan berasosiasi dalam ingat an dan menjadi bagian kekayaan tiap individu dalam bentuk langue. Hubungan yang bersifat linear itu disebut hubungan sintagmatik, sedang hubungan asosiatif itu disebut hubungan paradigmatik. Hubungan sintagmatik dan paradigmatik dapat atau sering diterapkan pada kajian fiksi ataupun puisi.
Berhadapan dengan sebuah karya fiksi, kita akan melihat adanya hubungan antara penanda dengan petanda yang jumlahnya amat banyak. Pertama, kita akan melihat aspek formal karya itu yang berupa deretan (baca: hubungan) kata, kalimat, alinea, dan seterusnya sampai akhirnya membentuk sebuah teks yang utuh. Hubungan tersebut adalah hubungan antara penanda dengan petanda, hubungan antara unsur unsur yang hadir secara bersama. Karena baik kata, kalimat, alinea maupun yang lain dapat dilihat kehadirannya dalam teks itu, hubungan itu juga sering disebut sebagai: hubungan in praesentia.
Tiap aspek formal, kata dan kalimat, tersebut pasti berhubungan dengan aspek makna sebab tidak mungkin kehadiran aspek formal (bahasa) itu tanpa didahului oleh kehadiran konsep makna. Hubungan antara aspek formal dengan aspek makna tersebut merupakan hubungan asosiatif, hubungan antara unsur yang hadir dengan unsur yang tidak hadir. Kata dan kalimat dapat dilihat kehadirannya dalam teks itu, sedang makna hanya dapat diasosiasikan (yang notabene tidak d dilihat), maka hubungan ini sering disebut sebagai: hubungan in absentia (Todorov, 1985: 11). Hubungan pertentangan tersebut dikembangkan dari teori linguistik Saussure, yaitu yang berupa hubungan sintagmatik (diidentikkan dengan hubungan in praesentia) dan hubungan paradigmatik (diidentikkan dengan hubungan in absentia) di atas.
Hubungan sintagmatik dipergunakan untuk menelaah struktur karya dengan menekankan urutan satuan-satuan makna karya yang dianalisis. Hubungan sintagmatik adalah hubungan yang bersifat linear, hubungan konfigurasi, hubungan konstruksi (Todorov, 1985: 12), bentuk atau susunan. Dalam karya fiksi wujud hubungan itu dapat berupa hubungan kata, peristiwa, atau tokoh. Jadi, bagaimana peristiwa yang satu diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang lain yang bersebab akibat, kata-kata saling berhubungan dengan makna penuh, dan tokoh tokoh membentuk antitese dan gradasi. Untuk menelaah linearitas struktur (lengkapnya: struktur teks), yang pertama harus dilakukan adalah menentukan satuan-satuan cerita (dan fungsinya) dengan mendasarkan diri pada kriteria makna (Barthes, lewat Zaimar, 1991; 14-5).
Tiap satuan cerita, juga disebut sekuen, dapat terdiri dari sejumlah motif (satuan makna, biasanya berisi satu peristiwa)-dalam kajian karya fiksi tiap satuan cerita dan motif diberi simbol-simbol atau notasi-notasi tertentu. Menurut Barthes (Zaimar, 1991: 16) satuan cerita mempunyai dua fungsi: fungsi utama dan fungsi katalisator. Satuan cerita yang sebagai fungsi utama adalah berfungsi menentukan jalan cerita (plot!), sedang yang sebagai katalisator berfungsi meng hubungkan fungsi-fungsi utama itu. Pengurutan satuan cerita mungkin dilakukan berdasarkan urutan temporal atau urutan logis, secara kronologis atau kausalitas (Todorov, 1985: 41).
Namun, sejak zaman Yunani klasik, Aristoteles telah menge mukakan bahwa urutan kausalitas lebih penting daripada kronologis, dan berkat kausalitas peristiwa-peristiwa saling berkaitan dan bergerak. Dalam sebuah teks fiksi, keduanya dapat ditemui yang menurut Farster urutan kausalitas membentuk plot, sedang urutan temporal membentuk cerita. Contoh karya yang berisi urutan kronologis murni adalah kronik atau catatan harian, sedang yang kausalitas murni adalah wacana aksiomatis atau argumentatif. Jadi, kajian sintagmatik dalam suatu karya fiksi dipergunakan untuk mendeskripsikan urutan motif motif (peristiwa-peristiwa) dan urutan satuan-satuan cerita; satuan cerita mana yang berfungsi utama dan mana yang sebagai katalisator, serta bagaimana sifat hubungan antarsatuan cerita itu, apakah bersifat kronologis, kausal, atau kronologis-kausal.
Hubungan paradigmatik, di pihak lain, merupakan hubungan makna dan pelambangan, hubungan asosiatif, pertautan makna, antara unsur yang hadir dengan yang tidak hadir. Ia dipakai untuk mengkaji, misalnya, signifiant tertentu mengacu pada signifie tertentu, baris-baris kata dan kalimat tertentu mengungkapkan makna tertentu, peristiwa (-peristiwa) tertentu mengingatkan peristiwa(-peristiwa) yang lain, melambangkan gagasan tertentu, atau menggambarkan suasana kejiwa an tokoh (Todorov, 1985: 11-12). Dengan demikian, kajian paradig matik dalam sebuah karya fiksi berupa kajian tentang tokoh, per watakan tokoh, hubungan antartokoh, suasana, gagasan, hubung annya dengan latar, dan lain-lain Dasar kajian ini adalah konotasi, asosiasi-asosiasi yang muncul dalam pikiran pembaca.
Peristiwa-peristiwa yang berhubungan secara makna mungkin melambangkan suasana kejiwaan tokoh, gagasan tertentu, atau karena berkausalitas secara linear (sintagmatik) tempatnya mungkin berjauh an, sehingga hubungan yang demikian pun dapat disebut sebagai hubungan in absentia (paradigmatik). Misalnya, sejumlah peristiwa (atau: satuan cerita) tempatnya dalam teks ada di bagian awal, namun ia berhubungan secara logis (atau paling tidak dapat diasosiasikan) dengan peristiwa-peristiwa di bagian belakang. Misalnya, Bab pertama dalam novel Atheis tak mempunyai hubungan langsung dengan bab-bab berikutnya yang terdekat melainkan berkaitan langsung secara logika (kausalitas) justru dengan bab terakhir.
Dengan demikian, hubungan sintagmatik dan paradigmatik dapat juga dikaitkan dengan kajian dari aspek waktu yang menurut Todorov masalah waktu menjadi bagian aspek verbal yang berupa kala. Ada dua tataran waktu dalam teks fiksi: waktu dari dunia yang digam. barkan, tataran peristiwa (bersifat logis, asosiatif) dan waktu dari wacana yang menggambarkan, tataran penceritaan (bersifat linear). Masalah pertentangan antara dua tataran waktu tersebu menjadi bahan perhatian yang serius dari kaum Formalis Rusia. Mereka menamakan kedua masalah itu dengan istilah fable untuk tataran peristiwa, dan sujet untuk tataran penceritaan (Todorov, 1985:27).
Dalam karya fiksi, hubungan antara dua tataran waktu tersebut jarang untuk tidak dikatakan tidak pernah terjadi adanya kesejajaran Adanya manipulasi waktu penceritaan merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Justru karena adanya manipulasi waktu yang bervariasi itu sebuah karya fiksi menjadi lebih menarik, baru, dan lain dari yang lain, khususnya dalam hal penstrukturan. Karena adanya manipulasi waktu itu tataran peristiwa (yang logis) dipermainkan. Ia dapat dimunculkan d manapun dalam urutan penyajian penceritaan (di awal, tengah, atau akhir), sehingga mungkin terjadi unsur "anakroni": sesuatu yang terjadi lebih dahulu dikemudiankan, atau sebaliknya sesuatu yang terjadi belakangan didahulukan, penceritaannya. Dengan demikian, hal itu memungkinkan adanya unsur retrospeksi, kembali ke masa lalu, atau prospeksi (atau: antisipasi), menceritakan lebih dahulu hal-hal yang terjadi belakangan.
Salah satu kajian karya fiksi dapat berupa kajian kesejajaran atau ketidaksejajaran antara dua tataran waktu tersebut. Hal itu pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk kajian sintagmatik di paradigmatik. Namun, kajian itu haruslah dilakukan lewat (pemahan an) satuan-satuan cerita, sekuen-sekuen makna. Deskripsi kajian itu yang dapat juga berupa notasi simbol-simbol kemudian dicobajelas kan apa fungsi dan maknanya (jadi: kajian ini sebenarnya bersifat struktural-semiotik) (Nurgiyantoro, 1994: 64).
Kajian sintagmatik dan paradigmatik dapat juga diterapkan dalam kajian teks puisi, terutama yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kebahasaannya. Kajian itu biasanya dikaitkan dengan teori fungsi puità (poetic function)-nya Roman Jakobson. Jakobson (1968, lewat Teeuw 1984: 73-6), menjelaskan fungsi puitik sebagai berikut: "fungsi puit memproyeksikan prinsip ekuivalensi dari poros seleksi parataks (boleh juga disebut paradigmatik) ke poros kombinasi (sintaksis)". Menurut Jakobson, penilaian apakah bahasa sebuah puisi mengandung sifat (unsur) puitik atau tidaknya, ditentukan berdasarkan prinsip konstitutif yang berupa bentuk-bentuk kesejajarannya. Artinya, di antara sekian banyak bentuk kesejajaran yang tersedia dalam bahasa yang bersangkutan, misalnya bahasa Indonesia, baik yang berupa kesejajaran kata-kata-jadi: kata-kata yang mengandung unsur kesino niman (hubungan paradigmatik)-maupun kesejajaran sintaksis hubungan linear, hubungan sintagmatik-bentuk yang dipilih dalam puisi tersebut adalah bentuk yang paling tepat (baca: puitis, atau mengandung unsur estetis).
Pilihan bahasa yang berunsur puitik yang berupa kata-kata (paradigmatik), biasanya berkaitan dengan ketepatan unsur-unsur bunyi (sebagai pembangkit asosiasi tertentu), alitrasi, asonansi, rima, ketepatan bentuk (aspek morfologis), dan juga makna. Pilihan sintaksis (sintagmatik), di pihak lain, dapat berkaitan dengan "penemuan" konstruksi yang baru-orisinal, di samping juga ada kaitannya dengan penekanan gagasan yang pada umumnya ditempatkan di bagian awal larik (hal ini sebenarnya berupa prinsip ikonisitas, menurut Peirce). Misalnya, sebuah larik puisi yang berbunyi: Bukan kematian benar yang menusuk kalbu ("Nisan", Chairil Anwar); baik kata-kata maupun konstruksi sintaksis yang dipilih dalam larik ini dipertimbangkan sebagai yang paling tepat jika dibanding dengan kemungkinan bentuk bentuk lain yang tersedia dalam bahasa Indonesia, misalnya: yang mengiris-iris hati itu bukan masalah kematiannya itu sendiri, atau bentuk lain yang searti. Oleh karena itu, larik puisi tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat fungsi puitik, dan bahasanya pun menjadi puitis (Nurgiyantoro, 1994: 65).
Akhirnya perlu dikemukakan bahwa kajian semiotik pada dekade terakhir ini tampak sedang mendapat "pasaran". Kajian struktural, di pihak lain, seolah-olah menjadi ketinggalan zaman, atau kurang mem berikan sumbangan yang berarti. Namun, sebenarnya, seperti dikatakan Wahl (dalam kata pengantar untuk buku Todorov, 1985), perbedaan antara strukturalisme dengan semiotik kabur. Yang jelas, semiotik merupakan perkembangan yang lebih kemudian (juga: reaksi) dari strukturalisme. Selain itu, dalam praktik kajian teks kesastraan, kedua pendekatan tersebut akan sama-sama muncul, dan yang membedakan nya barangkali "hanya" masalah penekanan atau niat peneliti. Oleh karena itu, kajian yang lebih "aman" dapat berupa penggabungan keduanya: struktural-semiotik, baik hanya terhadap satu teks maupun antarteks (kesastraan), seperti yang berupa kajian intertekstual.
Tinjauan Pustaka:
Nurgiyantoro, Burhan. 2012. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ikuti tulisan menarik Siti Mutmainnah lainnya di sini.