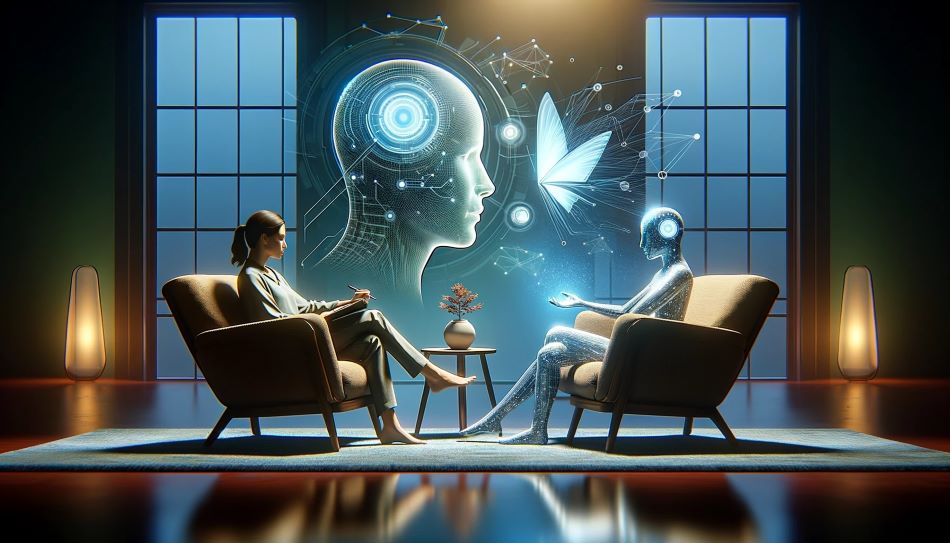Penulis lepas yang ingin terus menyuarakan isu kemanusiaan, kesetaraan gender, dan lingkungan. Seorang penikmat karya sastra dan film pendek. \xd \xd linktr.ee/jayalahaspidistra
Makna Keluarga
Kamis, 6 Juli 2023 06:35 WIB
Seharusnya dia cukup berterima kasih karena di lebaran haji ini ia masih bisa memasak rendang daging untuk suaminya yang tidak berguna itu. Ia juga bisa membelikan pakaian baru buat para keponakanku yang mungil.
“Dari mana Abang bisa mendapatkan uang buat membeli ini?” selidik Sila, adik perempuanku. Ia memang selalu ingin tahu semua hal, tapi perkara ini dia tak akan kuberi tahu secara jelas dan rinci. Seharusnya dia cukup berterima kasih karena di lebaran haji tahun ini ia masih bisa memasak rendang daging untuk suaminya yang tidak berguna itu, dan membelikan pakaian baru buat para keponakanku yang mungil. Sebenarnya aku kasihan sekali pada mereka. Sungguh malang nasib bocah-bocah itu menderita karena kemalasan ayahnya. Adik iparku tidak punya pekerjaan selain menghabiskan umurnya hanya duduk-duduk bermain kartu dengan kawan-kawan penganggurannya itu. Inilah kenapa aku melarang Sila menikah tiga tahun yang lalu. Aku tahu betul tabiat Sodik. Dia bukan laki-laki baik, tetapi Sila nekat kabur dari rumah bersama lelaki jalang itu. Dan hasilnya seperti hari ini ia hidup melarat.
“Ini anggap saja pemberian menyambut lebaran. Istriku baru sore ini sempat ke pasar,” kataku seadanya. Tidak ada rahasia besar, apalagi kebohongan yang hendak kututup-tutupi. Tetapi sorot mata perempuan itu menunjukkan ketidakpercayaan, ketidakyakinan. Dia mencoba membaca mataku, seakan-akan dia mampu mengintip isi kepalaku lewat dua bola matanya yang tajam itu. Kuguncangkan kantong plastik yang sejak tadi kusodorkan padanya. Sejak tadi aku menunggu dia meraihnya dengan tidak sabar. Andai kata dia tak segera mengambil kantong plastik itu, tentu aku tidak akan repot-repot menjelaskan atau meyakinkannya lagi. Kukira ada banyak orang yang kekurangan di luar sana. Jangankan bermimpi memasak daging, bahkan mereka tidak mampu membeli beras.
Dia mengambil kantong kresek hitam itu dengan ogah-ogahan. Setelah berterima kasih, dia berbasa-basi soal rumah besar peninggalan orang tua kami yang kini aku tempati. Mula-mula ia memuji usahaku merawat rumah tua milik keluarga kami itu, bahkan rela memboyong istriku dari kota pulang ke desa agar bisa bersama-sama menempatinya. Kemudian ia mulai menyindir tentang tanah yang sebelumnya sempat dijual oleh kakak laki-laki kami. Tanah yang membuat aku jadi bermusuhan dengan abang tertua kami itu. Sila mengungkit kembali bahwa ia tak ikhlas karena di hari itu ia mendapat bagian terkecil di antara kami empat beradik. Lalu ia berandai-andai suatu saat nanti kalau rumah tua orang tua kami itu dijual, ia ingin mendapatkan hak sepadan. Harus dibagi merata. Lagi pula, katanya, sebagai satu-satunya anak perempuan, dia selama ini tak banyak menuntut.
Aku mengiyakan saja kalimat-kalimatnya yang terdengar menguji kesabaranku itu. Dasar maruk! Padahal, semasa hidup Emak banyak memberinya tanah. Bahkan rumah yang ia tempati sekarang didapatkan dari menjual tanah warisan Emak. Sekarang ia ingin menjual harta terakhir yang diwariskan padaku itu. Aku sendiri sama sekali tidak terbesit niat ingin
menggadaikan rumah orang tua kami itu. Betapa tak ada malunya ia membahas hal ini di depanku. Bahkan sampai mati pun aku tak mau melepaskan rumah orang tuaku itu.
"Dia kelihatan tidak senang, Bang," curhat Nina beberapa hari yang lalu. Nina terlihat murung sepulang dari acara hajatan di rumah tetangga. Nina berkali-kali bercerita padaku kalau ia malu sekali lantaran diabaikan Sila. Sekarang aku mengerti mengapa saudariku ini sejak seminggu yang lalu merengut dan membisu saja setiap kali istriku menegurnya di jalan. Ternyata Sila tak begitu senang dengan kepindahan kami ke rumah Abah dan Emak selama tiga bulan terakhir.
"Lihat kelakuan binimu, Bang. Di acara Wak Eva kemarin dia tidak berbaur dengan ibu-ibu dusun ini. Aku tahu Mbak Nina orang kota, tapi harusnya dia belajar menyesuaikan diri di mana pun berada. Apa kata orang-orang kalau tingkahnya angkuh begitu?" oceh Sila. Menit-menit pembicaraan kami hanya diisi aduan demi aduan yang diutarakan saudariku itu tanpa jeda. Ia tak sedikit pun menghargai perasaanku. Ia tega menyebut istriku sebagai kakak ipar yang kurang beradat, tinggi hati, dan tidak ramah padanya. Ia meragukan karakter istriku di depan wajahku sendiri. Aku tak menyela satu kata pun tuduhannya itu. Kubiarkan dia berkata-kata sesukanya. Meskipun kupingku serasa terbakar mendengar ocehan bibirnya itu. Sila memang sangat mewarisi sifat ibu kami.
Setelah kudengar suaminya memanggil dari dalam rumah, aku langsung pamit pulang. Meninggalkan gubuk papannya yang kumuh itu. Sendirian aku melintasi jalan tanah. Memandang teras-teras rumah sepanjang jalan yang mulai terang dinyalakan lampu-lampunya. Langit petang demikian kelabu. Burung layang-layang berputar-putar bebas di bawah langit yang buram. Sekawanan kambing mengembik seolah meratap-ratap karena ditarik paksa oleh bocah kurus kering di jalan tanah. Dia Roni, anak bungsunya Bang Januar. Kelihatannya ia baru saja pulang dari mengaji. Aku membantunya menarik dua kambing itu sampai ke muka kandang bambu miliknya. Kotoran bulat-bulat berhamburan di depan kandang tanpa sadar telah ikut menempel di sandalku. Baru saja Roni hendak mengucapkan terima kasih, Bang Januar seketika memanggilnya dari teras rumah panggungnya. Meminta anaknya masuk ke dalam. Roni langsung mengikuti perintah ayahnya. Dari jauh Bang Januar menatap diriku tidak senang. Ia bergegas mengatupkan pintu dengan keras. Aku tidak mengerti mengapa saudaraku itu masih terus memusuhiku. Padahal, perdebatan kami perkara tanah itu sudah lama berlalu. Dan aku juga sudah merelakannya.
<--more-->
Sewaktu aku tiba di rumah, putriku datang memeluk kakiku erat-erat, seakan-akan kami sudah sekian lama tidak berjumpa. Kuelus rambut gelapnya. Lalu aku menggendong tubuh mungilnya itu. Aku tetap berusaha tersenyum meskipun perasaanku sedang tidak baik-baik saja. Aku terlalu mencintai putriku sehingga aku tidak bisa memperlihatkan kekalutan di kepalaku padanya. Istriku yang muncul dari ambang pintu dapur tampak begitu khawatir memandangiku. Dia bertanya bimbang, apakah kali ini adikku itu tak menjelek-jelekan dirinya padaku? Aku terpaksa berbohong. Kukatakan saja tak ada yang kami bicarakan selain membahas tentang daging kurban itu. Istriku mengangguk saja. Kini ia tak ambil pusing jika hanya itu yang ingin diketahui iparnya. Ia tak bertanya kembali mengenai kerisauan hatinya. Tetapi, aku dapat memahami perasaan Nina. Ia gelisah karena dimusuhi iparnya tanpa sebab.
“Akan kuganti kalungmu nanti, Adinda,” kataku menghiburnya. Ia mengangguk dengan senyum dan anggukan yang tulus. Namun kurasakan cahaya terang nan lembut yang biasanya menawan di matanya, kini seakan meredup. Aku mengerti betapa berharganya kalung emas itu baginya. Kalung itu adalah pemberianku di ulang tahun pertama pernikahan kami. Tapi mau bagaimana lagi, keuanganku bulan ini sedang memburuk. Kontrak kerjaku di perusahaan tidak lagi diperpanjang sejak dua bulan lalu, sementara gaji Nina sebagai PNS tak cukup karena separuhnya harus dipotong bank tempat kami meminjam. Istriku menggadaikan SK-nya demi merenovasi rumah baru ini.
Sebenarnya, Ninalah yang mendesak diriku agar mau menyenangkan Sila. Walau kupikir bahwa semua usaha ini sia-sia belaka. Sayangnya, tak bisa kujabarkan secara gamblang alasanku itu pada Nina demi mengurungkan niatnya itu. Sebab alangkah jahat bagi seorang kakak mengakui sifat jelek saudari kandungnya kepada istrinya. Tapi dalam hati kecilku, aku merasa berdosa karena tega menutupi laku buruk adiknya dari istri yang amat ia sayangi. Akan tetapi, aku terpaksa mengambil jalan tega daripada jahat. Karena aku harus bisa memaklumi segala tingkah laku adikku seberapa mengesalkan dirinya. Aku terikat pada hubungan darah ini. Aku dikutuk karena ikatan yang tak kuharapkan itu.
“Ingat Umar! Kalau kau buat adikmu menangis, Emak bersumpah kau tidak akan selamat! Kau tidak akan pernah bahagia!” Suara itu selalu datang berbisik ke telingaku setiap kali aku ingin membalas segala perbuatan buruk Sila. Kutukan yang tidak bisa kulangkahi walau sedikit pun. Emak selalu memanjakan Sila sedari kecil sehingga aku kerap dipaksa mengalah, bahkan jika itu kesalahan yang diperbuat Sila.
Keesokkan harinya seluruh keluarga bertandang ke rumah kami. Keluarga Paman Basuki dan Bibi Retno juga mudik dari kota. Mereka adalah adik-adiknya Emak yang masih hidup. Bang Januar juga datang, tapi ia hanya mengobrol dengan istriku atau tamu-tamu lain di luar teras. Sementara Sila duduk di kursi di pojok dinding berkumpul dengan sepupu-sepupu kami sambil sesekali melihat ke arah Nina yang sedang sibuk melayani hidangan buat menjamu tamu.
"Sila, kau belum cicip kue dua belas jam buatan Mbak. Sini cobalah sedikit," ajak Nina dengan ramah. Ia memberikan piring berisi kue pada Sila.
"Tidak. Gula darahku tinggi," sahut Sila dengan malas. Ia tak menyentuh sama sekali pemberian Nina.
"Apa yang sedang kau lihat, Bang Rudi?" tanya Fadil, adik laki-lakiku, anak nomor tiga. Ia rupanya memperhatikanku yang tak fokus mendengarkannya bicara.
"Ah, tidak, Dil. Abang cuma tak habis pikir dengan Sila."
"Kenapa dia? Berulah lagikah perempuan itu?"
"Dia memusuhi Nina semenjak kami pindah ke rumah ini."
"Aish, perkara itu rupanya. Abang abaikan saja dia. Rumah ini hak milik Abang Umar. Selama ini Abang dan Mbak Nina-lah yang menjaga Emak selama dirawat di rumah sakit. Bahkan Bang Juniar dan istrinya jarang membantu."
"Tidak, Dil. Kau dan istrimu pun banyak menolong Abang saat itu."
"Benar, tapi kalau tidak ada Abang mungkin hidupku pun luntang-lantung. Abang bersusah payah menyekolahkanku dan Sila. Abang rela menunda menikah agar kami berpendidikan. Walau akhirnya hanya aku yang tamat sarjana. Itu bukan salah Abang, tapi itu kehendak Sila. Ia lebih memilih Sodik begundal itu daripada nasibnya sendiri."
Aku terhibur mendengar ucapan Fadil. Aku bangga karena usahaku masih dihargainya selama ini. Di dunia ini orang mudah lupa dengan jasa dan kebaikan kita apabila mereka sudah merasa merdeka. Bang Januar tak ingat demi agar bisa menikahkannya dengan Mbak Murni, aku rela memberikan semua tabungan yang kukumpulkan selama lima tahun. Yang sampai hari ini tiada pernah kutagih sepeser pun. Sedangkan Sila, setelah menikah, ia sudah meminjam dua puluh juta lebih untuk uang jaminan setelah suaminya menabrak lari anak orang hingga nyaris celaka.
"Kapan kalian mau menambah momongan lagi?" tanya Bibi Retno pada Nina yang masih membereskan gelas-gelas berisi ampas kopi di meja.
"Insya allah, Bi. Sekarang belum. Kami mau fokus membesarkan Laras dulu," sahut Nina dengan hangat.
"Jangan kelamaan lho, Nin. Lagian kenapa mau menunggu Laras. Dia kan sudah besar juga. Kasihan suamimu," Mbak Murni ikut menimbrung.
"Maksud kami tunggu sampai Laras mengerti, Mbak."
"Iya, Mbak tahu. Cuma kan kau tidak ada beban lagi. Menurut Mbak sudah pantas Laras punya adik. Aku hanya kasihan saja dengan Umar."
"Paling-paling karena tidak mau repot, Mbak," sindir Sila memotong pembicaraan. "Dia mana peduli dengan suaminya."
"Bukan begitu, Sila. Mbak dan abangmu memang sudah ada rencana di tahun depan. Cuma untuk sekarang kami fokus dengan Laras dulu. Kami pasti tambah kok. Tapi kami berkomitmen tak perlu banyak-banyak yang penting kami bisa memberikan yang terbaik buat anak kami."
Sila merengut. Ia mendadak bicara dengan ketus dan dengan suara yang tinggi, "Ya, aku tahu, Mbak! Maksudmu tidak mau seperti kami yang punya banyak anak ini, kan? Banyak anak, tapi tidak terurus. Mbak enak, sudah pegawai negeri, punya suami kerja, dapat rumah warisan. Tidak macam kami yang harus memulai apa-apa dari nol! Hidup kami susah!"
Nina sontak terkejut dengan reaksi Sila yang tersinggung. "Jangan salah paham. Mbak tidak berpikir begitu. Kau saja yang merasa."
"Hush! Sudah, sudah, Sila," tegur Bi Retno
"Alah, Mbak. Kau itu munafik. Bicara depan bagus. Di belakang kami kau mengejek. Aku tahu tabiat orang kota."
"Kau ini kenapa Sila? Aku tak pernah membicarakanmu di mana-mana."
"Kenapa? Aku yang pantas bertanya pada Mbak Nina kenapa? Kenapa Mbak suka sekali menyindiriku? Aku kalau bukan karena suamimu mana mungkin datang ke sini. Lagi pula ini rumah orang tuaku, makanya aku sanggup melangkah ke rumah ini."
Aku yang murka hampir tak dapat menahan diri ingin memperingatkan sikap Sila yang kurang ajar terhadap kakak iparnya. Namun, Fadil lebih dahulu bangkit melerai mereka.
"Hentikan Sila! Jangan dilanjutkan. Kau ini tidak punya tata krama. Minta maaflah sama Mbak Nina!" bentak Fadil.
"Bang Fadil harusnya suruh dia yang minta maaf. Aku tidak bersalah! Aku cuma membela harga diriku!"
"Kau tidak berubah Sila. Ini yang dari dulu takutkan. Karena dahulu kau dimanja kau jadi makin tak punya adab. Mbak Nina itu istri abangmu. Kau mau memecah belah keluarga abangmu?"
Sila menangis. Ia kemudian meracau di hadapan kami. "Inilah kalau kita miskin. Saudara pun enggan mengakui! Apa-apa kita disalahkan!"
"Ayo Sila. Pulang!" bentak Sodik yang dari tadi ikut menonton. Lelaki itu menjegil. Bukannya melerai dan mendamaikan, dia sok bersikap heroik. Betapa memuakkannya keluargaku ini!
Darahku sudah mendidih naik ke ubun-ubun. Makian berbongkah-bongkah di mulutku minta dimuntahkan. Aku sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah pola kakak-adikkku yang kian lama tak menghargaiku. Mereka seolah menganggapku tidak ada. Tak peduli sebesar apa pun pengorbananku pada mereka.
"Ya! Pergilah! Pergi kalian dari rumahku! Kami ini jahat, kau saja yang baik, Sila! Ayo! Ayo adikku pergilah! Enyahlah dari sini sebelum aku membunuh orang! Jangan anggap aku lagi saudaramu! Aku bukan siapa-siapa bagi kau."
"Jaga bicaramu Umar! Kau tak seharusnya mengatakan itu pada adikmu sendiri," hardik Bang Januar yang tahu-tahu sudah ada di belakangku. Bicaranya menyerupai Emak yang dahulu sering membela Sila.
"Lalu yang dikatakan Sila itu menurutmu benar, Bang? Dia tak menghargai istriku sama sekali, padahal aku di sini masih hidup!"
"Tapi Sila itu adikmu. Kalian kakak-adik. Kalian keluarga. Janganlah dibesar-besarkan perkara kecil macam ini."
"Keluarga? Perkara kecil?" ujarku. Aku terbahak-bahak bagaikan orang sinting. Tidak ada yang berani buka mulut selagi aku menertawakan mereka. "Kau masih ingat ternyata kita keluarga? Ingat kau kalau aku ini adikmu. Lalu kenapa baru tahun ini kau menemuiku? Itu pun kau tak bicara denganku. Kemudian Sila! Dia sudah lama memusuhi istriku. Begitukah keluarga yang kau maksud? Inikah keluarga?"
"Istrimu bohong Bang! Dia mengadu domba kita," Sila menuduh.
"Diam kau! Aku tahu biniku daripada kau! Orang yang kau salah-salahkan ini justru orang yang paling perhatian pada kau. Apa yang kuberikan pada kau selama ini atas kemauan dia! Tapi mana kau tahu kebaikan orang, kau hanya suka membenarkan dirimu saja!"
"Aku ini lebih tua daripada kau, Umar. Memang kaulah yang wajar meminta maaf padaku, bukan aku. Aku menunggu kau datang menemuiku dari lama, tapi kau tidak pernah datang," Bang Januar membela diri seperti kebiasaannya. Ia menggunakan umur untuk menutupi kesalahannya.
"Benar sekali! Orang tidak peduli siapa yang salah dan yang benar. Mereka cuma percaya yang tua selalu benar. Hanya aku yang sial. Sebagai kakak maupun adik aku tetap bersalah. Aku salah di mata kalian! Aku buruk pada kalian! Nah, karena aku ini saudara yang buruk maka tidak perlu anggap aku lagi saudara kalian. Anggap saja aku sudah mati! Besok aku dan keluargaku akan meninggalkan rumah ini."
Nina terisak-isak melihatku mengamuk. Ia mungkin tak menyangka perkara mencicip makanan menjadi lari ke mana-mana. Ia memegangi lenganku sembari menenangkanku.
"Bang, tolong jangan ambil keputusan saat sedang marah," ucap Nina mencegahku.
"Abang masih ada aku dan Alisa, " kata Fadil yang tak mau diikut-ikutkan.
"Tidak! Aku sadar saat mengatakan ini. Sebetulnya dari awal Nina tak menyetujui keinginanku tinggal di rumah ini meskipun aku memang berhak. Tapi aku membujuknya, memaksanya mau pindah ke sini. Sekarang aku mengerti kenapa istriku melarangku. Aku tak punya keluarga di kampung ini. Kami akan pergi hari ini juga!"
Kini semua orang tak berani bersuara lagi di hadapan amarahku. Selama ini aku menyimpan beban amarahku yang membara dan membakarku dari dalam. Aku menabahkan hatiku, mengontrol diri agar tak kehilangan kendali. Berdoa agar mereka sedikit saja mengubah sikap mereka pada kami. Tapi makin lama mereka makin menginjak-injak harga diriku. Makin tak ada yang menghargai aku dan istriku. Aku tahu mereka tak suka lantaran aku pindah ke rumah bekas orang tuaku, tetapi mereka tidak tahu, selama ini aku membayarnya pada Emak dan bukan mendapat sepenuhnya sebagai warisan keluarga. Tanah yang digadaikan Bang Januar itu--yang membuat aku berang setahun yang lalu--sebaliknya adalah satu-satunya warisan untukku dan Fadil. Bang Januar sudah mendapat lima hektar kebun karet sebelum kami, tetapi sampai hati masih merebut hak milik adik-adiknya. Ia menjual kebun itu untuk membayar uang suap agar anaknya lolos jadi polisi. Sedangkan Sila, tak terhitung besarnya bantuanku, semua biaya pernikahannya hingga resepsi akulah yang membiayai. Ia bersalin anak pertama dan kedua, aku juga yang membayari. Maka kurang apalagi aku dengan kerabatku. Aku memilih mengalah agar keluarga kami ini tetap harmonis. Aku bungkam setiap kali kekurangajaran itu diperlihatkan di depan mataku semata-mata mengikuti petuah orang tuaku. Tapi sungai yang panjang pun ada ujungnya. Batu yang keras bakal remuk juga bila dijatuhkan berulang-ulang. Dan inilah batas kesabaranku. Inilah akhir dari semua penderitaan yang kubiarkan.
Siang hari itu juga kami berkemas. Aku menyewa mobil box untuk mengangkut barang-barang kami. Kami pun pulang ke rumah mertuaku. Nina anak semata wayang orang tuanya. Sebab itu dari dulu orang tuanya memang tak mengizinkan kami mengungsi dari rumah mereka. Maka sesuai dugaanku, kepindahan kami menjadi berita baik bagi mereka.
"Kalian tak usah tinggal di sana kalau saudara-saudarimu tak mengizinkan," ucap Papa sekali lagi menenangkanku.
"Aku malu, Pa. Aku malu karena harus membawa Nina kembali ke sini. Sebagai suami sekaligus ayah aku merasa gagal memberikan yang terbaik buat keluargaku."
"Tidak benar sama sekali, Umar. Kau sangat penyayang dengan keluargamu. Papa bangga karena kau selalu mementingkan anak-istrimu meski kau harus berselisih paham dengan kerabatmu yang lain. Padahal, Laras bukan anak kandungmu."
"Jangan katakan itu, Pa. Laras sudah kuanggap sebagai putriku sendiri. Aku menyayanginya sejak Nina mengakui bahwa ia pernah menikah dan sudah memiliki anak. Aku tidak peduli dia darah dagingku atau bukan."
"Inilah kenapa Papa menyetujuimu. Kau benar-benar mencintai Nina dan Laras sepenuh hati. Waktu kau melamar Nina, Papa akui waktu itu sempat ragu. Papa bukan tak percaya padamu, hanya saja melihat bagaimana sikap sebagian keluargamu yang nampak keberatan setelah tahu masa lalu Nina, timbul sedikit ketidakpercayaan padamu."
"Ah, jadi Papa sudah lama sadar akan hal itu? Mengenai keluargaku?" tanyaku dengan perasaan canggung sekaligus malu.
Ia mengangguk. "Sebab itu Papa melarang kalian pindah ke rumah orang tuamu. Bara yang ditimbun abu kalau disiram minyak masih terbakar juga. Kepindahanmu ke sana akan menghidupkan api yang sudah nyaris padam."
"Andai saja kemarin aku membicarakan dengan Papa terlebih dahulu."
"Tidak apa. Berkat kejadian ini Papa kian yakin padamu. Nina rupanya tak salah memilih pria. Kau layak menjadi suaminya. Semoga hubungan kalian selalu diberkati."
(Ditulis pertama kali pada 29 Juli 2020.)
Aktivis lingkungan dan penulis lepas. Seorang penikmat karya sastra dan film pendek.
0 Pengikut

Gadis Beranting Mara di Kota Kudus
Minggu, 15 Juni 2025 21:04 WIB
Perjanjian dengan Peri
Jumat, 1 Desember 2023 12:33 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 99
99 0
0