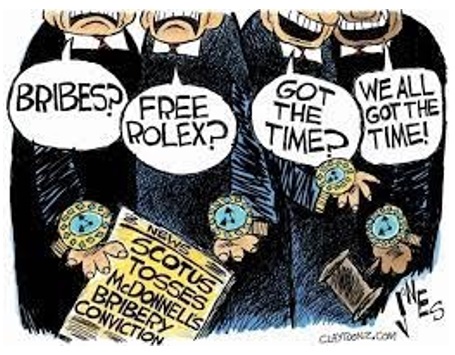Penulis lepas yang ingin terus menyuarakan isu kemanusiaan, kesetaraan gender, dan lingkungan. Seorang penikmat karya sastra dan film pendek. \xd \xd linktr.ee/jayalahaspidistra
Perjanjian dengan Peri
Jumat, 1 Desember 2023 12:33 WIB
Dengan jubah hitam, rambut terurai melebihi mata kaki, dan paruh tajam yang mirip burung elang bergerak naik-turun, makhluk itu menatap dalam-dalam mata Amnusul. Jarak mereka hanya kelang beberapa depa. Amnusul seketika bergidik ngeri saat bola mata jahat makhluk itu bertatapan dengannya. Jadi inikah maut? Mata yang hitam dan kosong itu mungkin sebentar lagi akan menyedot kehidupanku, pikirnya pasrah.
Amnusul hampir mati berdiri ketika selembar kertas ia temukan tergeletak di depan pagar rumahnya. Kertas tipis yang dicetak dengan tinta seadanya, dilipat tiga, dan distaples dua kali itu tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba saja terbang ke arah Amnusul saat ia baru saja hendak membuka pintu pagar. Berkali-kali pemuda itu menggosok-gosok matanya seakan tidak percaya sewaktu membaca nama yang tertulis di sana:
Desti & Amran
Apa-apaan ini! Apa maksudnya semua ini? batin Amnusul yang belum siap menerima mentah-mentah isi dalam undangan itu. Kepalanya serasa akan meledak. Tidakkah ini keterlaluan? Jika benar, sungguh mereka semua pengkhianat! Musuh dalam selimut, babi sialan, batinnya lagi. Gusar. Kacau. Kepalanya pening. Maka tas punggung yang belum lepas dari gendongan langsung ia lemparkan saja ke lantai teras. Tangan kirinya terus-terusan mengacak-acak rambutnya sembari mengulang-ulang membaca isi kertas itu.
Tidak salah lagi. Ini nama asli Desti dan Amran yang dia kenal. Muka Amnusul meremuk bagaikan daun kering sehabis diremas-remas. Matanya yang sipit sontak memerah, begitu terpaku erat ke tiap aksara yang tercetak di undangan itu, bahkan ia mengabaikan keponakannya yang keluar dari rumah memeluk dan membelit kakinya, mencari-cari perhatian.
“Mang, ayo!” ajak gadis kecil itu bersemangat. Ia menarik sebelah tangan pamannya yang bergayut lemas di bahu.
Amnusul membisu pada awalnya, tapi kemudian dia berlutut lalu menghadap keponakannya itu. Ia mencium kening si anak sebentar, lalu berkata dengan berbisik, “Kau masuklah duluan. Bilang Nenek kalau Mamang pergi ke rumah kawan.”
Si bocah menggeleng. "Nenek tak ada di rumah."
"Kalau begitu rahasiakan," Amnusul merogoh saku celana jinsnya dan menyerahkan selembar uang kertas kucel kepada keponakannya itu. "Ambil ini dan jangan ceritakan kalau Mamang tadi sudah pulang."
Si bocah mengangguk dan mengambil uang yang disodorkan padanya.
"Nah, sekarang masuklah," ujar Amnusul. Ia menggigit bibir seperti menyesali telah mengajari bocah polos itu berbohong.
Setelah memastikan bocah itu menghilang masuk ke dalam rumah, ia menarik kembali tali tasnya, memanggulnya, dan berjalan tergopoh menuju jalan setapak. Kertas undangan tadi masih ia genggam kuat-kuat di tangan kanan. Kini, pikirannya yang tersumbat telah pecah dan melebur ke mana-mana. Sungguh sesak dadanya tatkala ia membayangkan sepupunya kelak duduk di atas pelaminan dengan pacarnya. Alangkah sial nasibku, baru kemarin dipecat dari pabrik, sekarang malah kekasihku pula yang direbut. Bukankah aku yang sudah dulu mengenal Desti? Kenapa Amran yang malah akan kawin dengannya? Ini tidak adil! Tuhan, kau tidak adil, ia membatin sepanjang melintasi jalan tanah itu.
Pria itu tanpa sadar telah berjalan kian jauh, memasuki kerimbunan kebun dan hutan, menembus sekat resam, lalang, dan belidang, melewati deretan putat, pulai, dan rumpun bambu yang renggang sebab separuh batangnya kebanyakan telah ranggas dan rebah ditiup badai semalam. Langkah Amnusul terhenti tatkala ia telah sampai di ujung jalan yang berada tepat di atas tebing sungai. Air sungai yang setengah tebing itu mengalir tenang, hanya sesekali beriak-riak lantaran ikan timbul di seberang dan ular air yang berenang lincah ke sana ke mari tampak asyik mencari-cari mangsa.
Amnusul duduk nelangsa sembari termangu memandangi pantulan langit yang biru bersih serta dahan lebat terjulur yang berayun-ayun di atas permukaan sungai. Ia bersandar di pohon rengas kokoh berakar besar yang menaunginya dari panas tengah hari itu. Keheningan di tempat itu makin menggemakan isi kepalanya yang gaduh. Sebenarnya tempat itu tak benar-benar hening, kicau burung samar-samar terdengar entah dari mana, juga agas terus menggonggong dan merongrong di kupingnya seolah minta ditepak tanpa ampun. Tetapi nyaris semua itu tak lagi mengganggunya. Sebab, sekarang kerisauan hatinyalah yang paling keras menggebuk di dada, membuat detak jantungnya begitu kacau-balau.
Dia tidak ikhlas melepaskan gadisnya itu. Akulah yang paling berhak, bukan sepupuku itu, batinnya terus-terusan menyangkal. Desti adalah pacarnya. Semua orang di dusun ini tahu bahwa ia lebih dahulu kenal Desti dibandingkan Amran. Pun semua orang di desa ini tahu betul bahwa ialah satu-satunya lelaki yang dekat dengan gadis itu. Ini baginya tak adil.
“Andai saja bisa kugagalkan,” bisik Amnusul. "Aku rela membayarnya dengan apa pun."
***
Amnusul terbangun tatkala tetesan air menjatuhi pipinya. Ketika ia membuka mata, di hadapannya tak ada lagi langit sebiru dan sebersih sebelumnya, sekarang berganti menjadi suram dan temaram seakan sebagian lampu baru saja dipadamkan. Pohon rengas yang semula tempat ia bersandar masih ada, tapi berubah gundul dan mati meranggas, dan sungai di bawah kakinya tidak berpindah, tapi berubah surut dan kotor. Dengan kata lain, ia masih tetap di tempat terakhir ia duduk. Tetapi mengapa suasana di sini berubah menjadi mendung dan mencekam? Daun-daun kehilangan hijaunya, sungai berhenti mengalir, dan angin tidak bertiup sama sekali di sini. Tempat ini begitu sunyi dan hambar. Begitu heningnya hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Ini aneh, liyan. Apakah aku sudah mati? Amnusul bertanya-tanya dalam hati.
Belum sempat ia beranjak dari tempat duduknya, sesosok bersayap legam nampak berkitar-kitar di atas langit. Sayap itu merentang melebihi nyiur kelapa dan mengepak-ngepak gagah sebelum akhirnya jatuh dan mendarat. Bau anyir dan telur busuk seketika menyengat di mana-mana. Amnusul menggosok-gosok matanya tidak percaya melihat makhluk tinggi besar yang mengerikan telah berdiri tepat di hadapannya, siap memangsa tubuhnya. Dengan jubah hitam, rambut terurai melebihi mata kaki, dan paruh tajam yang mirip burung elang bergerak naik-turun, makhluk itu menatap dalam-dalam mata Amnusul. Jarak mereka hanya kelang beberapa depa. Amnusul seketika bergidik ngeri saat bola mata jahat makhluk itu bertatapan dengannya. Jadi inikah maut? Mata yang hitam dan kosong itu mungkin sebentar lagi akan menyedot kehidupanku, pikirnya pasrah.
Namun, sekejap kemudian makhluk menyeramkan itu berselimut kabut. Saat muncul kembali, ia telah menyaru menjadi pria berjanggut ubanan dan tebal seperti sarang tupai. Amnusul seolah tidak asing dengan lelaki tua itu. Begitu mirip dengan kakeknya.
"Wahai anak malang!" sapa si lelaki tua dengan takzim. Dia berjalan mendekati Amnusul yang gelisah. Sekujur tubuh Amnusul gemetar hebat.
"Kaukah maut? Apakah aku sudah mati?" ujar Amnusul terkaget-kaget dengan segala pemandangan ganjil yang ada di hadapannya. Ia tak bisa memberontak tatkala lelaki tua itu kini duduk bersila di depannya, mengamatinya lekat-lekat. "Tuan Maut aku belum ingin mati!"
"Mati? Kau serius? Apakah aku ini tampak jahat? Adakah maut yang mau duduk manis menunda pekerjaannya dulu?" Pria itu menjawab dengan suara lembut dan berwibawa.
Amnusul hampir mengiyakan, tetapi dia mengurungkan niatnya sesudah sadar bahwa makhluk itu ada benarnya. Maka ia memutuskan tidak menjawab.
"Kau Amnusul bin Sadiman Umar, kan? Aku kenal kau," ujar lelaki tua itu santai.
"Siapakah Tuan ini? Mengapa bisa kenal aku? Mengapa aku tiba-tiba berada di tempat ini?"
"Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, kenapa kau datang ke tempat ini? Di sini bukan tempat manusia. Ini adalah jauhar rimba, rumah kaum kami."
"Kalian hidup? Artinya di sini adalah kehidupan? Aku tidak mengerti. Di kehidupanku tidak ada manusia jadi-jadian seperti Tuan dan tempat persis seperti ini."
"Kau belum benar-benar masuk. Ini baru gerbang menuju dunia kami. Namaku Ham, aku salah satu warga yang mengurus wilayah perbatasan. Akhir-akhir ini banyak manusia sepertimu yang mencoba menyeberangi dunia kami. Saat melintas kulihat kau tengah membuka pintu masuk ke sini."
"Masuk? Tidak! Aku sama sekali tidak datang ke sini. Justru aku bingung di mana ini?"
Ham tersenyum. "Klise sekali. Alasan itu sudah sering kudengar. Tapi tenang saja. Aku tidak seperti penduduk di daerah sini yang suka melaporkan imigran ke kantor polisi atau kantor keimigrasian. Di sana kau bakal diproses lama dan bertele-tele. Dan bukan tidak mungkin mendapat hukuman sangat berat," katanya dengan nada datar.
"Tapi bagaimana mungkin?" sahut Amnusul putus asa. Ia bahkan tidak melakukan apa-apa. "Aku tidak tahu sekarang di mana dan bagaimana mungkin aku berniat mendatangi tempat yang tidak kuketahui."
"Kau putus asa dan mendendam, sebab itulah kau tiba di tempat ini. Di sini adalah tempat manusia fana yang putus asa tersesat. Sudah banyak manusia datang ke tempat kami. Nah, tenanglah, sebenarnya aku ini datang hendak menolongmu."
"Menolongku?"
"Ya, ya, tapi sebelum itu aku punya prasyarat. Kalau kau setuju nanti akan kutunjukkan jalan keluar dari tempat ini dan akan kubantu kau mengubah masa depan."
"Masa depanku?" tanya Amnusul kaget. Rupanya makhluk ini bisa membaca keinginannya.
Ham mengeluarkan sebuah buku setebal batu bata bersampul hitam dan keras. "Meski aku bukan yang paling hebat di sini, tapi aku bisa membantumu menemukan solusi atas masalahmu. Kau boleh meminta satu hal berkaitan dengan masa depanmu. Maka akan akan kukabulkan segera."
"Jadi kau bisa ubah masa depanku?"
"Ya! Satu masa depan. Pertama-tama, kau boleh menulis dahulu keinginan apa yang ingin kau capai hari ini, nanti kitab ini akan menjadi jembatanmu untuk mendapatkan hasilnya."
"Itu saja? Ya, ya, kalau begitu aku setuju dengan prasyaratmu," kata Amnusul bersemangat. Dia akan menulis rencananya menggagalkan pernikahan Desti dan Amran.
"Dengarkan dulu, aku belum bilang prasyarat apa yang kuinginkan darimu"
"Katakan saja Tuan! Aku pasti setuju!"
"Aku ingin ambil ingatan baikmu. Semua kenanganmu yang bagus. Bisa?"
Amnusul menelan ludah. Syarat yang sangat berat. Namun karena dirasuki dendam ia tanpa berpikir lagi langsung mengatakan iya.
Ham yang gembira sontak menyeringai jahat dan mencengkeram bahu Amnusul. "Sepakat!"
Aktivis lingkungan dan penulis lepas. Seorang penikmat karya sastra dan film pendek.
0 Pengikut

Gadis Beranting Mara di Kota Kudus
Minggu, 15 Juni 2025 21:04 WIB
Perjanjian dengan Peri
Jumat, 1 Desember 2023 12:33 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 97
97 0
0