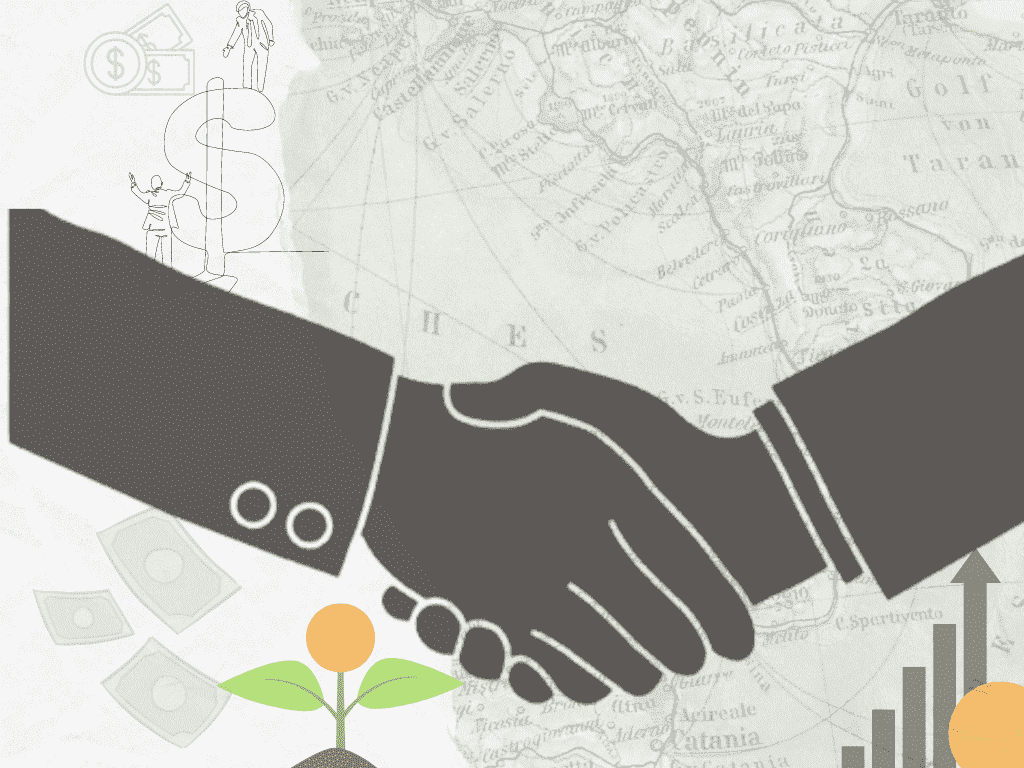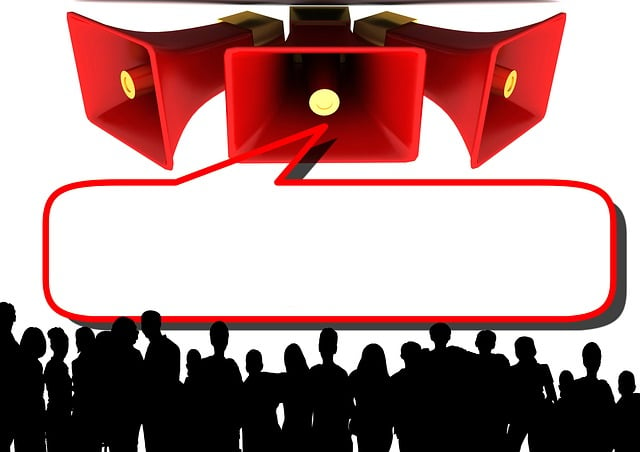Oleh Mpu Jaya Prema, pemerhati budaya
Selama ini slogan populer dalam kaitan dengan makan adalah “tak ada makan siang yang gratis”. Slogan ini tak usah diperjelas lagi. Intinya adalah ada maksud-maksud tertentu jika ada orang mengajak kita untuk makan siang. Entah itu bermuatan politik atau bisnis, tergantung bagaimana hubungan persahabatan kita.
Yang ramai sekarang diperbincangkan adalah makan bersama Presiden Joko Widodo dengan tiga calon presiden di Istana Merdeka Jakarta, Senin yang lalu. Kebetulan ini makan siang. Juga pastilah gratis. Tak mungkin Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan disuruh membayar. Adakah muatan politiknya? Woo sudah pasti. Ini tahun politik. Jangankan soal makan siangnya, posisi duduk, motif batik yang dikenakan presiden dan tamunya, semuanya dibahas dari sisi politik. Padahal inti bagian yang “tidak gratis” adalah harapan agar Presiden Jokowi netral dalam pemilu dan pilpres tahun 2024. Jokowi pun setuju hal ini, terbukti makan bersama ini adalah rentetan dari dipanggilnya kepala daerah se Indonesia, dari bupati sampai gubernur. Jokowi minta agar kepala daerah itu netral.
Bupati dan gubernur akan netral? Anda boleh percaya. Namun izinkan saya untuk tertawa. Bagaimana mungkin bupati dan gubernur bisa netral, kalau mereka adalah kader dari partai politik. Mereka naik ke jabatan itu karena diusung partai politik, meski pun untuk kepala daerah sebenarnya diperbolehkan ada calon independen, tapi tak laku. Lagi pula koalisi partai politik yang sudah mengusung capres-cawapres sudah menempatkan para bupati dan gubernur sebagai juru kampanye untuk pemilu presiden. Lihat pula di lapangan, baliho para caleg fotonya ada latar belakang para bupati dan gubernur yang menduduki jabatan ketua partai di daerah.
Begitu pula para menteri, saya yakin tak bisa netral. Bahwa mereka mengambil izin cuti saat berkampanye, itu sudah bagus. Sudah mulai ada tanda=tanda mereka memanfaatkan fasilitas jabatannya untuk kampanye. Jadi netral itu masih jauh, ibarat punguk merindukan bulan. Termasuk – disertai permohonan maaf saya – Jokowi pun saya ragukan kenetralannya. Siapa sih yang tidak menjagokan anaknya menduduki jabatan RI 2?
Saya mengajak pembaca untuk melupakan hal itu. Saya pun sesungguhnya tak tertarik membahas makan bersama ini dikaitkan dengan politik, lebih-lebih dikaitkan dengan kenetralan. Itu ibarat ungkapan dalam sastra lama: menggantang asap. Namun, saya ingin berbagi bagaimana makan bersama itu dalam khasanah budaya Nusantara kita.
Di Bali ada istilah megibung, makan bersama dengan cara khas. Tradisi lama ini sebenarnya ada di berbagai daerah, namun saya tak ingat lagi namanya. Makanan ditaruh berjejer di sebuah tempat memanjang, tergantung berapa peserta megibung. Peserta megibung duduk berjejer pula menghadap makanan itu, tentu dalam posisi duduk bersila. Peserta langsung makan di tempat tanpa mengambil nasi dan lauk dalam piring, karena memang tak disediakan piring. Secara tradisi makan pakai tangan, karena itu disediakan air cuci tangan yang disebut kwacikan. Tapi di era modern ini, sudah mulai ada sendok.
Apa maknanya? Kebersamaan. Orang bisa mengambil nasi dan lauk di tempat yang sama berkali-kali. Tak ada orang yang status sosialnya lebih tinggi dan rendah. Orang kaya dan miskin duduk dan makan bersama. Para pejabat dan para petani juga duduk bersama. Saya pernah menduga, cara makan begibung ini barangkali untuk melawan sistem kasta – yang dulu pernah memecah masyarakat Bali seolah ada yang lahir istimewa sebagai “berdarah biru”. Tradisi megibung masih umum diadakan di Bali wilayah timur.
Ada lagi makan bersama namun jatah nasi dan lauknya sudah ditentukan. Duduknya juga berjejer, bukan melingkar seperti Presiden Jokowi menjamu para calon presiden. Ini juga menandakan kebersamaan tanpa ada “orang istimewa” di hadapan seseorang. Semua orang setara. Namanya, makan nasi pangkoan. Budaya ini banyak dilakukan sebagai perjamuan jika ada upacara potong gigi.
Di masa lalu ada istilah melimbur. Ini adalah makan bersama yang lahir dari tradisi agraris. Para petani yang sawahnya bertetangga makan melimbur, duduk bersama di pematang sawah dan makan nasi yang dibawa masing-masing dari rumah. Ketika melimbur itu para petani saling menawarkan lauk yang dibawanya. Sekarang tradisi ini sudah hilang di kalangan petani karena sawah sudah menyempit. Lagi pula apa asyiknya makan di pematang sawah? Namun, anak-anak remaja di pedesaan, masih suka melimbur. Mereka membawa makanan dari rumah lalu mencari tempat untuk melimbur. Tempat makanan dan lauk pun sudah modern dan mereka senang sekali. Sambil membawa handphone untuk tiktokan… Cara melimbur yang modern.
Dalam ephos Mahabharata (tapi bukan versi wayang Jawa), Pandawa dan Korawa saat remaja sering makan bersama. Mereka sangat guyub. Suatu kali Rsi Bisma, pengasuh Bangsa Kuru, memberikan pendidikan tentang kebersamaan lewat makan bersama ini. Semuanya duduk melingkar dan masing-masing sudah punya jatah makan. Rsi Bisma berkata: “Coba kalian makan dengan tangan tak boleh menekuk, tangan harus tetap lurus”.
Semuanya mencoba, tak ada yang bisa. Makanan tak ada yang bisa masuk ke mulut jika tangan tak ditekuk. Bima, misalnya, mengambil makanan, lalu tangannya menjulur ke atas dan makanannya dijatuhkan. Mulutnya sulit bisa menangkap makanan itu, lebih banyak tercecer. Semuanya ketawa dan semuanya menyerah tak bisa melakukannya.
Lalu Yudistira berkata; “Aku bisa.” Dia mengambil makanan, tentu dengan tangan kanan. Makanan itu disodorkan ke mulut Bima yang ada di kirinya. Bima bisa melahap makanan itu. Kemudian Bima mengambil makanan dan disodorkan ke mulut Duryadana yang ada di kirinya. Duryadana pun bisa melahap makanan yang disodorkan Bima. Begitu seterusnya sampai seratus Korawa dan lima Pandawa bisa menikmati makanan dengan teknik tangan tak tertekuk di siku. “Itulah kebersamaan, kesetaraan dan keadilan. Ini harus dipegang dengan teguh,” kata Rsi Bisma.
Sayang sekali, setelah Korawa dan Pandawa dewasa dan masing-masing punya jabatan, akhirnya tak bisa mempertahankan kebersamaan dan kesetaraan itu, apalagi menciptakan keadilan. Situasi dan politik dinasti yang disiapkan Drestarasta membuat kerajaan kacau dan mereka pun berseteru dengan sengit. Rsi Bisma yang agung tidak netral, berdiri di dua kali. Badannya ada di Korawa dan pikirannya ada di Pandawa.
Kita tak tahu, apakah Presiden Jokowi dengan tiga calon presiden setelah makan bersama itu, bisa menciptakan kenetralan? Semoga terwujud dan izinkan saya meragukannya. ***
Ikuti tulisan menarik Mpu Jaya Prema lainnya di sini.