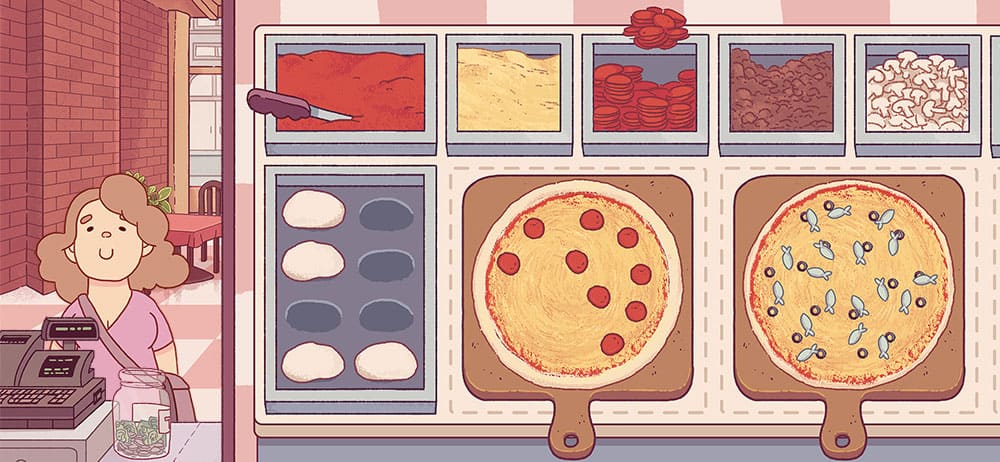Ruang-ruang Ikonik dalam Film Pengepungan di Bukit Duri
Jumat, 25 April 2025 10:35 WIB
Sutradara Joko Anwar tak asing dalam memperbincangkan isu politik dan sosial di setiap filmnya. Juga di karyanya terbatu ini.
***
Joko Anwar hampir selalu meninggalkan ruang-ruang ikonik dalam setiap karyanya. Setelah bioskop, rumah tua reot, hingga rumah susun padat penduduk, kini ia ingin bermain-main di sekolah dengan imajinya yang liar itu. Apakah dia berhasil?
Joko tak asing dalam memperbincangkan isu politik dan sosial di setiap filmnya. Jauh sebelum Pengepungan di Bukit Duri, ia sudah meninggalkan jejak dalam A Copy of My Mind, film yang diklaimnya berbudget murah dan berkru kecil. Film peraih Piala Citra tahun 2015 ini mengangkat wajah Indonesia yang "lain". Sebuah Indonesia yang tidak baik-baik saja. Ketika kekuasaan berkomplot dengan kejahatan.
Formula yang sama saat itu pula yang ia angkat dalam Gundala (2019), dengan nuansa yang lebih komikal. Jika kita menyaksikan karya-karya Joko, mestinya kita akan akrab dengan wajah Jakarta yang disajikan Joko dalam film terbarunya ini: lorong-lorong gelap, temaram cahaya, kerumunan, hingga bus kota kusam.
Indonesia imajinasi Joko adalah wajah yang identik dengan realitas: satu sisi, banal, muram, dan jahat, namun, sisi lainnya, ia berusaha menghadirkan harapan di tengah realitas itu. Pada 2017, ia memunculkan Gundala sebagai harapan di tengah kecemasan akan rusaknya generasi masa depan. Harapan yang sama ia munculkan melalui sosok Budiman Syailendra, wartawan tua, dalam Pengabdi Setan 2 (2022).
Terinspirasi dari kerusuhan Mei 1998, Indonesia versi Joko dalam film terbarunya ini dimulai dari pecahnya kerusuhan bernuansa etnis pada 2009. Adegan pilu kejahatan kemanusiaan dimunculkan Joko dengan cara yang dramatis.
Dari sinilah, akar cerita bermula. Sisa trauma meninggalkan luka sekaligus awal cerita melalui tokoh utama, Edwin. Berprofesi sebagai guru seni, Edwin (Morgan Oey, yang penampilannya gemilang) mengambil risiko dengan mendaftar ke SMA Duri, sekolah anak-anak bermasalah. Ia memiliki motif pribadi yang akan disibak perlahan.
SMA Duri mengingatkan kita pada Woodrow Wilson Classical High School, di mana Erin Gruwell mengajar. Sekolah Erin diisi dengan murid-murid bermasalah yang terjerat narkotika hingga konflik antargeng. Kisah yang kemudian tertuang dalam buku The Freedom Writers pada 1999.
Film Joko bukan bercerita tentang kisah sukses seorang guru yang berhasil meredam amarah di ruang kelas dengan terapi tulisannya seperti kisah Erin Gruwell. Penyerangan di Bukit Duri tidak menjadi solusi, melainkan atraksi. Ya, atraksi tentang betapa rentannya kita di tengah perbedaan. Premisnya pun sangat akrab dengan kita tentang bagaimana minoritas menjadi korban
Jakarta 2027 versi Joko adalah kota yang menyisakan luka dan tidak pernah sepenuhnya pulih. Polarisasi terjadi dan semua bagai bara dalam sekam. Kebencian terjadi di semua tingkatan usia, bahkan menyusup ke ruang-ruang kelas, tempat ideal membentuk budi pekerti.
Karakter Jefri (Omara Esteghlal), siswa kelas 3F, seolah menjadi fokus antagonis sejak awal. Ia adalah alfa. Ia memiliki geng yang menyasar remaja pelajar keturunan Tionghoa/China sebagai objek kekerasan. Jefri adalah pelaku sekaligus korban. Karakternya hadir untuk mengaduk-aduk perasaan kita, seperti kisah siswa nakal yang nyatanya berlatar keluarga yang pincang.
Joko memang sudah lama mengangkat isu sosial dan politik dalam film-filmnya, sekalipun bertema horor. Kali ini, tema itu terasa dekat, bahkan mudah ditemukan di kanan-kiri kita. Sang sutradara (mungkin) hendak mengingatkan kita, "Jika tidak mawas diri, bukan tak mungkin kebencian yang sama menjadi kenyataan di kemudian hari."
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Ruang-ruang Ikonik dalam Film Pengepungan di Bukit Duri
Jumat, 25 April 2025 10:35 WIB
Kekuasaan: Pelajaran (Daripada) Sejarah Pendahulu
Selasa, 5 April 2022 06:41 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




 Berita Pilihan
Berita Pilihan




 98
98 0
0