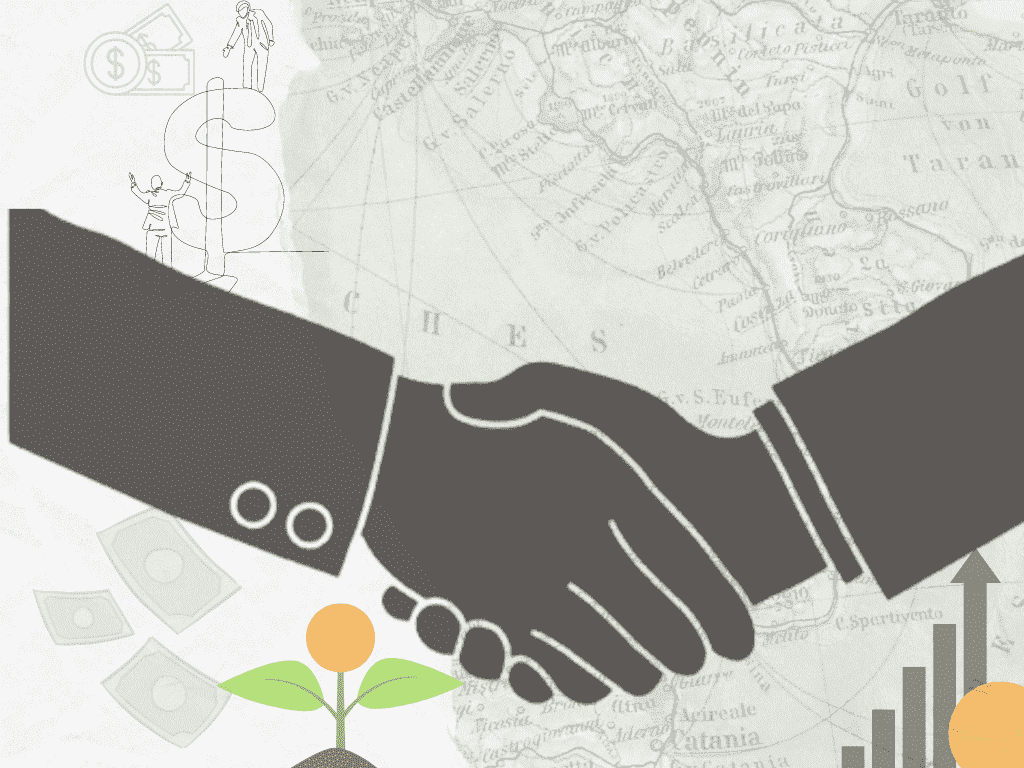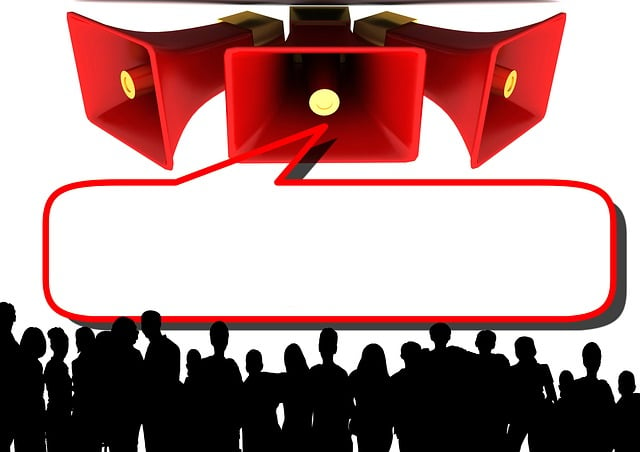Setiap perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei (May Day), biasanya kaum buruh berunjuk rasa ke istana untuk menyuarakan kepentingannya kepada sang presiden. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi titik persoalan dalam persoalan perburuhan?
Marx puluhan tahun yang lalu, menguliti persoalan buruh yang sewaktu itu dianggap persoalan yang biasa dan alamiah. Orang tak ada yang mempersoalkan, mengapa buruh bekerja dari pagi hingga malam. Namun hidupnya justru miskin dan kekurangan. Bagi pandangan umum, sudah sewajarnya buruh itu hidup miskin. Karena ia bukan majikan dan juga bukan Tuan tanah. Seorang majikan memiliki banyak tanah, peralatan dan pabrik yang besar. Namun buruh tak memiliki apapun selain tenaga dari tubuhnya sendiri. Lantas kemudian kemiskinan yang dialami sang buruh dianggap suatu yang alamiah. Kemiskinan dalam diri si buruh dianggap sebagai sebuah kodrat hukum alam, bahwa orang yang tak berpunya pastilah hidup miskin.
Akan tetapi Marx membantahnya. Bagi Marx, buruh menghasilkan kerja. Dan kerja adalah sumber keuntungan bahkan sumber kehidupan, dimana sebuah benda yang dulunya tak memiliki nilai, menjadi bernilai akibat dari kerja si buruh. Seperti sebatang kayu bisa menjadi sebuah kursi yang bernilai jual tinggi akibat dari adanya aktivitas kerja si buruh. Dengan kata lain, perubahan dari kayu yang dulu tak memiliki nilai apapun menjadi sebuah kursi yang bernilai jual tinggi adalah hasil dari kerja si buruh. Bukan dari keringat kerja majikan. Namun si buruh tak berdaulat atas objek atau barang yang diproduksinya sendiri.
Seorang buruh roti, apabila ia lapar dan ingin memakan roti. Maka ia pun harus membeli roti di toko roti. Walaupun roti itu adalah hasil kerja tangannya sendiri. Bahkan bisa saja si buruh itu tak mengerti bahwa roti yang ia makan adalah roti hasil kerja tangannya itu. Roti hasil kerja si buruh berada di luar kendali si buruh. Benda berada di luar kendali sang pencipta. Setelah buruh mencipta sebuah benda, benda itu berada di luar dirinya. Di luar kendali dirinya. Artinya si buruh itu terasing dari hasil kerjanya.
Benda atau barang hasil kerja si buruh itu tampil berhadap-hadapan dengannya sebagai sesuatu yang asing, sebagai kuasa yang mandiri dari si buruh yang menghasilkan benda atau barang itu sendiri. Bahkan buruh bukan hanya terasing dari hasil kerjanya. Si buruh pun terasing dari laku produksi, dari aktivitas produksinya sendiri. Dengan kata lain, kerja yang seharusnya menjadi aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup justru menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan diluarnya. Roti yang dihasilkan dari kerja si buruh bukanlah untuk memenuhi kebutuhan si buruh itu sendiri. Namun roti itu dihasilkan untuk memenuhi tuntutan pasar kapitalis. Begitu pula dengan kerja membuat roti. Kerja membuat roti bukanlah kerja menurut kehendak si buruh itu sendiri melainkan untuk memupuk keuntungan dan laba bagi si kapitalis. Artinya laku produksi yang dilakukan oleh si buruh bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri akan tetapi hanya menjadi sarana memenuhi kebutuhan, yakni memperoleh upah.
Kerja itu sendiri akhirnya menjadi kerja karena terpaksa; kerja paksa. Bahkan kerja sudah bukan lagi menjadi bagian dari upaya manusia guna mencipta syarat-syarat hidupnya. Melainkan kerja sudah menjadi komoditas. Si kapitalis membeli kerja si buruh dalam waktu yang sudah ditentukan dan dengan harga yang sudah ditentukan pula dalam bentuk upah. Yang harganya tak sebanding dengan hasil kerjanya. Sehingga semakin banyak buruh bekerja maka ia pun tetap saja hidup miskin. Bahkan semakin banyak ia bekerja, ia semakin terasing dari hidupnya.
Menurut Marx permasalahannya ada dalam ranah hubungan produksi. Yakni pada “kepemilikan alat produksi dan penguasaan atas sumber ekonomi”, yang kemudian berimbas pada distribusi kekayaan yang tak adil. Akibat distribusi kekayaan yang tak adil inilah kemudian muncul masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas sosial, masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Sehingga bagi Marx, pusat persoalan ketidakadilan adalah kerja yang tak lagi berada pada hakikatnya. Dan buruh sebagai manifestasi kerja yang terpasung adalah penghasil keadilan sosial.
Namun apa daya, buruh sebagai penanda etis dari ketidakadilan sosial, kini posisi politiknya kian lemah. Ia terkadang mirip dewa-dewa yang malang: suara mereka perlu disimak, tapi sering kali dunia mendengarnya melalui perantara. Banyak mereka baik aktivis, NGO hingga LSM merasa dirinya mewakili kaum buruh. Namun posisi politik buruh dihadapan kapital tetap saja tak berdaya. Yang menjadi pertanyaan, benarkah mereka mewakili buruh?
Mungkin kita perlu melihat lebih jauh makna yang terkandung dalam kata "representasi". Dalam kata "representasi", memang tersirat ada sesuatu yang tak hadir namun beroleh penggantinya yang seakan-akan menghadirkan dia. Sebagaimana para aktivis, NGO dan LSM. Mereka seolah berbicara atas nama si miskin. Mereka merasa diri sebagai "pahlawan" dan “jurubicara” yang lazimnya tampil lebih besar, berteriak lebih seru, ketimbang si miskin itu sendiri. Namun akhirnya si buruh ini tetap tak punya akses ke percakapan yang lebih luas dan tetap diabaikan dalam percaturan kekuasaan para elite. Mungkin yang terjadi justru seperti apa kata Jacques Ranciere bahwa asas perwakilan yang dipraktekan tetap terintegrasi dengan mekanisme oligarki.
Akhirnya kaum miskin pun cenderung ditampilkan seperti satu set keadaan yang biasa dipertontonkan oleh stasiun televisi yang dimiliki bisnis besar, diperdebatkan berulang-ulang oleh aktivis kiri yang dibiayai oleh founding internasional, bahkan seakan dibela mati-matian namun suaranya hanya terdengar dalam gema. Posisi politiknya masih saja tetap lemah.
Maka satu-satunya jalan yang bisa membuatnya bangkit ialah kaum buruh perlu disiapkan, dididik, buat mengartikulasikan hasrat dan kepentingan mereka sendiri. Bukan selamanya kaum buruh dibuat bergantung kepada mereka yang merasa diri mewakili si buruh. Dibiarkan hidup dalam pusaran ketergantungan kepada mereka yang selalu mengaku sebagai “representasi” dari kaum buruh.
Arjuna Putra Aldino
Ikuti tulisan menarik Arjuna Putra Aldino Aldino lainnya di sini.