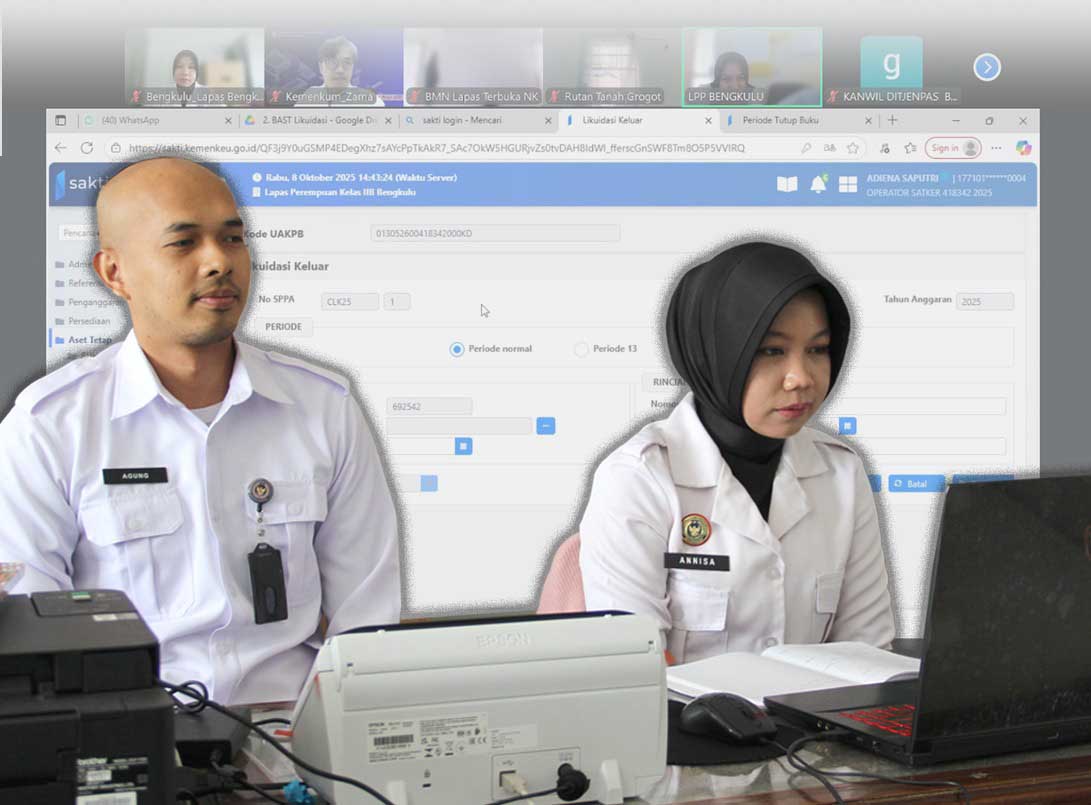Guyonan 'Lingkaran Dalam' Ala Wartawan
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Wartawan juga punya guyonannya sendiri. Seperti apa guyonan-guyonan mereka? Simak saja di sini.
Hujan rintik-rintik sementara rasa lapar di udara dingin ini makin menggelitik. Saya sebenarnya sudah memesan agak awal, atau di tengah. Entahlah, saya tak tahu pasti. Tapi yang saya tahu saya tidak memesan paling akhir. Sialnya, pesanan saya datang paling akhir. "Nasi goreng vegetables," begitu sebut si pramusaji di hadapan saya. Ia mengeja "vejetabels" untuk memastikan setelah saya melafalkan "vejteblz". Tiba-tiba saya merasa agak snobbish. Kenapa pula saya lafalkan kata itu dengan benar di hadapan pramusaji itu? Toh ini bukan kelas Pronunciation atau Speaking di perkuliahan yang pernah saya akrabi bertahun-tahun lalu.
Lalu sembari saya menunggu nasi goreng bernama aneh itu, saya teguk minuman yang sudah datang lebih dulu. Saya pesan minuman lemon grass ginger, atau sederhananya jahe dicampur dengan serai. Si pembuat menu juga sama snobbish-nya dengan saya ternyata. Sok pakai bahasa Inggris tanpa alasan jelas. Rasanya hangat dan segar di mulut. Saya sudah bilang tanpa gula tetapi saya lihat di dasar gelas masih ada butiran putih laknat itu. Saya tak izinkan perkara sepele itu membuat saya masygul. Saya hanya ingin menikmati malam ini, bersantap sampai kenyang dan tidur nyenyak agar kembali bisa bekerja besok. Saya hanya berkeluh sebentar lalu saya teguk dan menyisakan gula yang tak saya aduk di bawah.
Untuk menghibur diri karena nasi goreng sayur mayur itu tak kunjung datang, saya baca-baca e-book dalam ponsel. Saya gagal berkonsentrasi membaca. Saya rasa karena otak menderita sebab lapar masih mendera.
Mereka yang semeja sudah menelan semua hidangan yang ada. Sementara saya masih termangu seperti nenek yang kehabisan benang untuk merajut. Tidak ada yang dikerjakan. Membosankan.
Suasana bosan mulai luntur begitu pertukaran kata mulai terjalin. Mereka berbicara perkara laptop, lalu seorang di antaranya mengatakan ada anak magang yang gagal memenuhi tenggat waktu peliputannya karena harus kembali ke kantor hanya untuk mengetik beritanya.
"Ya kalau kamu begitu nanti beritamu tidak akan dimuat kalau telat," kata si wartawan pembimbing yang kesal karena tidak habis pikir. "Kamu kan bisa mengetiknya di ponsel?"
Kata di wartawan pembimbing itu, si anak magang beralasan,"Ponsel saya hang, pak. Mohon maklum."
Padahal masih anak muda tapi disuruh memakai ponsel sebagai pengirim berita saja masih tidak terbiasa. Begitu mengetik dalam percakapan di WhatsApp dan Line, terampilnya bukan main dia. Begitu mungkin pikir si wartawan pembimbing dalam benaknya.
Pikir saya, mungkin anak magang itu ingin perusahaan membelikannya ponsel baru yang khusus untuk bekerja. Bukankah begitu logikanya? Kau membudakkan diri pada korporasi dan pada gilirannya kau mengharapkan timbal balik yang sama setelah memberikan kerelaan bergaji ala kadarnya sebagai wartawan magang. Wartawan saja sudah gajinya kecil, apalagi magang. Ah, saya tak boleh berkeluh kesah terlalu banyak dalam tulisan. Nanti pembaca berpikir saya terlalu cengeng dan suka mengeluh, begitu nasihat mentor penulisan saya tempo hari. Sesekali bolehlah, saya tetap bersikukuh.
Keterampilan mengetik cepat tanpa typo di ponsel memang sudah makin penting bagi pewarta modern. Omong-omong soal keahlian mengetik secepat kilat di gawai, mereka teringat dengan seorang jurnalis sepantaran mereka yang kebetulan bertugas dalam liputan peristiwa muncratnya lumpur dari perut bumi di ujung timur pulau ini bertahun-tahun lalu, yang kau juga pasti tahu.
"Sepertinya di ujung jempolnya sudah ada matanya," tukas seseorang dari kerumunan pewarta senior itu. Saya tak tahu yang mana persisnya. Otak saya menolak bekerja keras sebelum nasi goreng sayuran itu terhidang. Saya lirik jam tangan dan kembali merutuk lambatnya juru masak bekerja untuk mencampur nasi dan sayuran di sebuah wajan.
Seorang lainnya berseloroh dengan berpura-pura memegang sebuah gawai di tangan,"Pak, nanti ngomong ini ya... Cocok nggak?!"
"Hahaha....," mereka tergelak seraya menahan makanan yang sudah masuk agar tak keluar dari kerongkongan. Sementara itu, saya juga menahan kata-kata makian pada pemilik dan manajer rumah makan agar tidak terlontar dari lidah. Orang lapar bisa sangat agresif, tetapi saya untungnya tidak.
"Send nih, pak. Send ya...!"
Tertawa mereka makin menjadi-jadi.
Saya teguk lagi serai dan jahe tadi untuk menghibur diri.
Habis satu lelucon, mereka temukan satu lagi yang baru dan tak kalah menggelikan. Asalnya dari media sebelah. Portal berita mereka pernah membuat kesalahan memalukan. Dan kesalahan itu sudah terpantau orang banyak.
"Masak ada berita judulnya dalam kurung 'HOLD, NUNGGU UPDATE'?!?!"
Tawa mereka kembali pecah. Menunggu nasi goreng ini saya mulai lelah. Saya mulai menggosok-gosok mata, berharap jika mata saya terbuka, nasi goreng itu sudah ada. Tapi sia-sia.
"Itu yang upload siapa? Haha. Kok bisa?"
Wartawan di ujung meja itu menimpali,"Memang saya dulu juga begitu pas kerja di kantor berita X. Kalau ada pertandingan olahraga, saya ketik dulu judulnya 'MENANG -KALAH' lalu saya kirim saja. Redakturnya juga memble. Nggak dibaca kali ya. Begitu tayang, pembaca protes,'Woy, itu sebenernya menang atau kalah sih??!!"
"Pilih salah satu!!!" tukasnya dilanjutkan dengan meledaknya tawa.
Dulu, ceritanya, berita tidak dibuat dalam ponsel cerdas seperti sekarang tetapi harus pakai modem telepon yang sama sekali tidak praktis dan lamban. Mulai tahun 1990-an, para wartawan kantor berita X itu menerapkan teknologi satu ini untuk berkirim berita dari lapangan. Modemnya ditancapkan di gagang telepon lalu dimasukkan kartu dan baru dipencet nomor teleponnya.
"Berita baru masuk separuh, putus! Ulang lagi deh," kenangnya.
Sungguh masa yang penuh penderitaan bagi wartawan, batin saya. Untuk saat itu saya masih duduk di sekolah dasar. Tidak perlu berpikir pusingnya mengirim berita dengan teknologi yang canggihnya belum seberapa.
Untuk mengetik dan mengirimkan berita, ada laptop yang tertancap ke modem. Di negeri ini konon alat semacam itu baru ada satu. Itupun juga bantuan dari 'saudara tua' yang pernah menjajah negeri ini 3,5 tahun. Tapi karena susah digunakan, akhirnya jarang yang pakai juga, ucap wartawan itu.
Ia memuji surat kabar lain yang sudah mendahului media lain di indonesia dengan menggunakan laptop plus modem dan meninggalkan faksimile untuk mengirimkan beritanya.
Saya terseret terus ke pemaparan tentang masa lalunya yang saya tak pernah bayangkan sebelumnya.
"Kalau kirim gambar pakai kamera Canon dengan ukuran wadah mirip kopor besar dari bahan aluminium. Kirimnya pakai modem dan kalau kirim foto warna, kirimnya harus tiga kali. Baru dua kali kirim kalau putus koneksinya harus ulangi lagi dari awal," ucap wartawan itu lagi sementara yang lain termangu mendengarkan pengalamannya. Biayanya tak terkira. Mahal bukan main. Tagihan telepon di hotel cuma untuk mengirim gambar bisa membuat bokek perusahaan. Karena sekali kirim satu file saja bisa butuh waktu 15 menit sambungan internasional. Sungguh tidak terbayang. Sekarang bisa memakai laptop murah dan wifi gratis, mau kirim foto sebesar apapun juga bisa.
Saat wartawan indonesia masih berjuang mengirim file foto sedemikian rupa (cuci film dulu baru dikirim), wartawan Reuters sudah lincah memakai ponsel dan mengirim file lewat gawai itu. "Kita hanya bisa melihat saja. Iri...," kata wartawan itu menggambarkan perasaannya.
Saat liputan, mantan wartawan kantor berita X itu kerap memikul sebuah mesin ketik portabel, benda yang mulai langka dan hanya bisa saya temui di kantor-kantor kelurahan. Suatu saat ia bertugas di luar pulau dan lebih memilih naik bus daripada naik pesawat terbang. Di sebuah rute berkelok, mesin ketik berat itu terlempar dari penyimpanan di atas kepala penumpang bus dan jatuh tepat di pangkuan seorang turis manca. Ia bersyukur benda logam itu tidak menghantam kepala turis tadi. Kalau terjadi, bisa sial ia dituntut karena sudah lalai menjaga barang sendiri dan mencederai orang lain.
Seorang lainnya membahas bagaimana konyolnya para jurnalis radio dari sebuah stasiun radio yang mewajibkan pegawainya ke mana-mana berpakaian necis dan berkaos seragam, dengan alat perekam suara di pinggang. Lalu saat liputan banjir di sebuah daerah di Jakarta Barat, dilihatnya sebuah adegan lucu si pewarta radio. "Saya lihat itu mereka tenggelam tapi urutannya kaki, badan dan tangan yang menggenggam erat alat perekam mereka. haha!" Apa lacur, karena memang dalamnya melebihi tinggi badan dan rentangan tangan, alat itu juga terendam air bah pula. Tetapi yang patut diacungi jempol, alat itu terendam paling akhir daripada orangnya yang naas karena perahunya terbalik.
"Antara kasihan dan lucu! Haha...," komentarnya pada kenangan masa lalu itu.
Percuma berpakaian rapi, toh juga tidak kelihatan gambarnya, imbuh yang lain. Tawa membahana. Saya menggaruk kepala, masih menunggu nasi goreng keparat itu muncul.
Seorang yang lain di tepi meja sana menyumbang lelucon. Juga tentang pewarta radio yang dinaungi pemerintah. "Kalau saya dulu pernah tahu ada teman wartawan radio. Jika dia ingin melaporkan secara langsung (live), sebelumnya ia sudah rekam dulu suara sirine, suara kesibukan orang, lalu begitu masuk kamar hotel yang kebetulan saya ada di dalamnya, ia meminta saya diam dulu saat akan melapor ke Jakarta. Di telepon, ia berpura-pura sedang di lokasi kejadian dan untuk meyakinkan pendengar ia putar lagi suara-suara sirine dan keriuhan yang sudah disimpan di perekam."
Teman-temannya tertegun siap menyambut punch line. Saya juga.
"Dia bilang,'Saudara, saya berada di garis finish,'" katanya. "Saya mau teriakin,'Boong!!!'"
Lain lagi dengan pengalaman wartawan di depan saya yang juga tentang wartawan radio. "Ini wartawan dari (masukkan nama kantor berita pemerintah di sini), saat itu dia harus meliput kunjungan Presiden Soeharto ke Tapos. Sialnya dia terlambat! Mana harus menembus penjagaan ketat pula. Kalau wartawan cetak masih bisa mengandalkan press release. Wartawan radio mana bisa?"
Akal kancil harus dipakai agar atasan tidak menyembur memuntahkan kata-kata cacian. Si wartawan akhirnya menempuh strategi satu ini:ia memakai efek suara (sound effect) sapi. Dan ia menyuruh temannya -- para wartawan cetak -- berpura-pura melenguh bagai sekawanan sapi Tapos yang sedang menjalani proses inseminasi buatan. "Ia menyuruh temannya bilang,'Muooooo!!!'"
Sontak derai tawa membuat kaca-kaca restoran itu bergetar. Saya makin meriang sebab hembusan angin malam menerjang tubuh yang belum mengasup makanan sama sekali ini. Saya teguk lagi cairan serai dan jahe tadi sedikit. Saya tak mau nasi goreng itu tiba dan minuman ini habis sebelumnya.
Soal siasat untuk tetap terkesan meliput jika terlambat, ia masih punya amunisi kisah lagi. Alkisah wartawan televisi yang sudah sampai ke tempat yang dituju terengah-engah hendak menjumpai jenderal. Apa daya si jenderal sudah meninggalkan tempat itu. Tak mau menyerah begitu saja si wartawan televisi menyuruh seorang temannya menghidupkan mesin mobilnya dan dengan nada tenang dan mantap ia melaporkan pada pemirsanya,"Pemirsa, itulah mobil dari jenderal U yang baru saja akan meninggalkan Polda M setelah konferensi pers tentang..."
Tahulah saya sekarang kenapa ada laporan-laporan langsung yang terlihat berlatar belakang aneh sekarang. Dan betapa meyakinkannya pewarta-pewarta itu menutupi kegilaan-kegilaan ini. Tiba-tiba saya bersyukur tak punya televisi.
Satu kisah lagi tentang wartawan radio yang harus mewawancarai seorang menteri di suatu era Orde baru. Sebut saja menteri W, yang bersuku Jawa. Karena ia baru tiba dan menteri W sudah meninggalkan tempat perhelatan, ia tak kurang akal. Ia tarik lengan temannya yang wartawan tulis dan berkata seraya memohon,"Kamu kan orang Jawa, pura-pura jadi W ya?!" Ia pun wawancarai wartawan tulis itu dengan sebuah skrip yang ia telah tentukan sebelumnya.
Kembali pada tema banjir. Wartawan yang rupanya sering meninjau peristiwa banjir ini mengisahkan foto yang dimuat di sebuah harian ibukota. Untuk menggambarkan dahsyatnya banjir Jakarta, ia membidik seseorang yang sedang terperangkap banjir sampai selehernya tapi masih di foto yang sama, tertangkap juga pemandangan kontras. Kenapa kontras? Karena di sudut lain dalam foto, ada sebuah angkutan umum yang terendam banjir juga tapi ketinggiannya tak sampai melahap roda-rodanya. Bisa jadi kesan banjir seleher itu karena orang tadi terperosok masuk ke selokan yang cukup dalam. Sebuah kesalahan fatal namun menggelikan juga.
Soal narasumber juga. Hanya karena kita sudah akrab dengan banyak narasumber, tidak serta merta kita bisa menggunakan mereka sebagai antek dalam membuat pernyataan palsu. Seorang wartawan teman wartawan di depan saya ini pernah mengalami kejadian tidak terduga. Karena sudah merasa akrab dan tak perlu meminta persetujuan atas pernyataan yang ia karang dengan menggunakan namanya, si wartawan tinggal membubuhkan saja ke berita yang ia buat. Berita dimuat dan sampai dibaca keluarga si narasumber. Keluarga itu pun menghubungi sang wartawan yang ceroboh. "Begini mas, kami bukan mau protes isi beritanya. Kami cuma keberatan karena bapak Y ini sudah meninggal." Ah, siapa yang sempat memeriksa mati hidupnya narasumber? Kecuali orang-orang di sekitarnya. "Bener sih beritanya ada bantuan tapi bapak saya sudah meninggal lama, mas." Lalu harus bagaimana lagi, beritanya sudah telanjur dimuat.
Wartawan juga mesti secerdas kancil dalam mencari peluang. Dan jika peluang itu tidak ada, ciptakan! Alkisah seorang wartawan koresponden di sebuah kota di Pantura merana karena semua perhatian media tersedot ke peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Dan ini memengaruhi tingkat pemasukan mereka. berita-berita dari daerah mereka tak laku dijual dan banyak yang tidak dimuat redaktur pusat. Apakah ia akan mengarang ada kejadian tsunami di Laut Jawa? Tentu tidak sejauh itu. Yang ia lakukan hanyalah mengajak rekan-rekannya dari media televisi untuk iuran 10-20 ribuan untuk membeli tumpeng. Mereka sepakat membawanya ke sebuah pantai dan nelayan-nelayan lokal yang sebetulnya tidak memiliki tradisi sedekah laut itu disuruh mereka untuk mengadakan selamatan agar menolak bala tsunami yang mungkin bisa melanda daerah tersebut. Saya pikir inilah 'inovasi' dalam dunia jurnalistik. Journalists don't cover news only. They make (fake) news sometimes. Tapi tentu jangan terlalu sering.
Saat dinding usus-usus saya sudah lelah bergesekan, akhirnya tiba juga nasi goreng sayuran itu di depan muka. Dan stok pembicaraan ludes juga. (Juga dipublikasikan di blog pribadi akhlis.net/Foto: Wikimedia Commons)
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Gagal Tes CPNS Bukan Berarti Bodoh, Bisa Jadi Karena Langit-langit Bangunan Tempat Tesmu!
Jumat, 12 Juli 2024 08:11 WIB
Mozilla Indonesia Akan Gelar 'Firefox Support Sprint'
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0