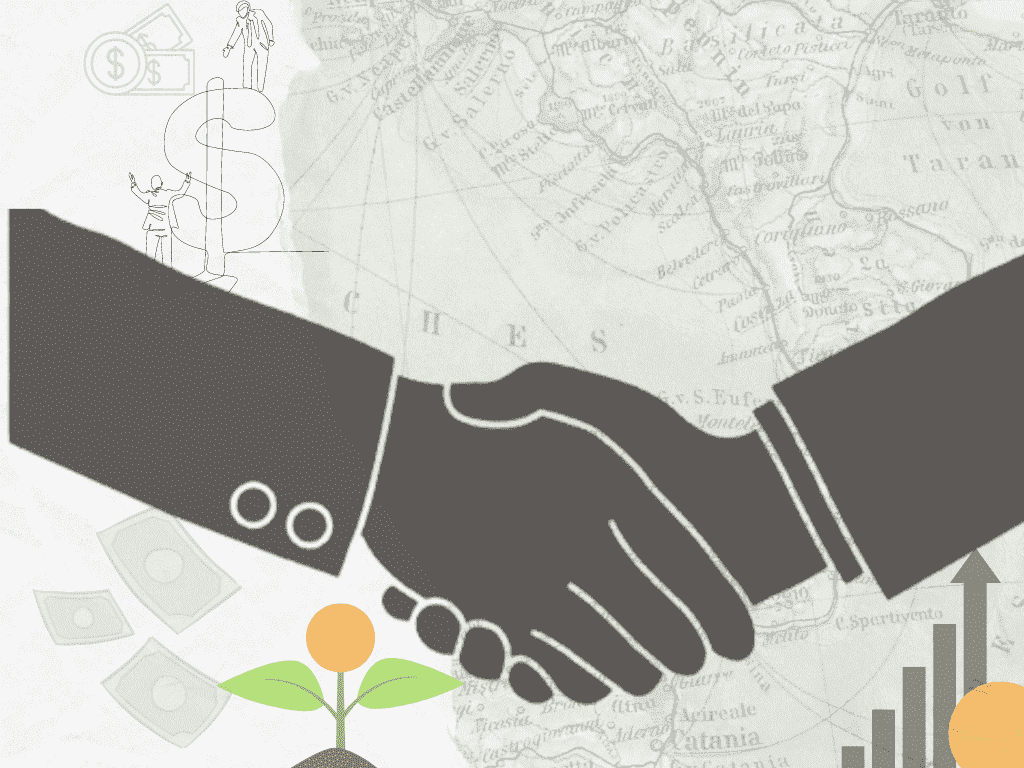JJ Rizal
Sejarawan
Sambil merongos dan berleleran air mata, sebanyak 75 keluarga berusaha menghadang 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja yang menggusur Kampung Rawajati, Jakarta Selatan. Di antara korban gusuran yang menghadang itu, termasuklah Ilyas Karim, yang pada 2011 namanya meroket lantaran mengaku-ngaku sebagai pengibar bendera saat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Karena itu, di sela-sela perdebatan tentang tidak insaf-insafnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur paksa yang, menurut Resolusi PBB Nomor 24 Tahun 2008, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, santer juga perdebatan apakah Ilyas Karim—meminjam istilah Bung Hatta—mitos atau realitas di sekitar proklamasi. Bagaimana memahami kedua hal itu?
Pertama, tidak ada Ilyas di halaman rumah Sukarno pada 17 Agustus 1945. Ia bukan pengerek bendera jahitan Fatmawati saat mengandung Guntur Sukarno itu ke tiang bambu yang dibuat dadakan Barisan Pelopor. Meskipun banyak tersebar mitos di sekitar peristiwa proklamasi, para sejarawan—berdasarkan berbagai sumber yang lulus kritik—telah sama sepakat bahwa Latief Hendraningrat dan Soeharsono dibantu Soehoed sebagai pengibar bendera saat proklamasi adalah sejarah yang sudah diterima kebenarannya (accepted history).
Kedua, justru Ilyas dengan kepalsuannya itu adalah sebuah peringatan ihwal perwujudan janji proklamasi yang belum kesampaian. Kadang-kadang peringatan memang turun tak disangka-sangka dan dengan cara yang ganjil. Tapi, cobalah percaya. Kepalsuan Ilyas lahir dari masalah kemiskinan. Ia mewakili wajah kaum miskin kota yang sakit karena dalam periode panjang Jakarta mereka sering dianggap bukan manusia, apalagi warga negara. Ia korban pembangunan Jakarta, yang dikatakan Susan Blackburn, dalam bukunya 400 Tahun Sejarah Jakarta, diorientasikan hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan politik.
Dalam konteks itulah Ilyas menemukan jalan keluar dari derita kemiskinan di dalam sejarah Proklamasi RI yang karut-marut serta lama dibiarkan kacau oleh negara. Negara yang abai terhadap kemiskinan dan sejarah itulah yang dimanfaatkan Ilyas untuk menarik simpati betapa kenyataan hidupnya sebagai veteran pejuang jauh dari harapan janji kemerdekaan.
Demikianlah, kepalsuan Ilyas sesungguhnya kepalsuan kerja nyata mewujudkan janji proklamasi. Bahkan, pengkhianatan janji itu sangat terasa di Jakarta, kota tempat proklamasi dibacakan dan janji-janji kemerdekaan disusun. Padahal, dalam upacara pengayunan cangkul pertama Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur Nomor 56 pada 1 Januari 1961, Jakarta, kata Sukarno, seharusnya menjadi kota "jang memberi inspirasi kepada kita semua sebagai kota penunaian janji-janji proklamasi".
Sukarno percaya bahwa kota harus dibangun sebagai bagian dari "jang diamanatkan rakjat Indonesia di dalam perjoangannya jang berpuluh-puluh tahun agar supaja masjarakat adil dan makmur sebagai mana termaktub di dalam Amanat Penderitaan Rakjat terlaksana; agar supaja kami bangsa Indonesia terlepas daripada segala penindasan, penghisapan, agar kebahagiaan jadi milik kita sekalian."
Jakarta merupakan medium pendidikan nilai kemerdekaan itu. Tidak berlebihan jika Jakarta disebut Sukarno sebagai kota juang. Sebab, memang Jakarta harus memperjuangkan wajahnya yang bersari wajah nilai proklamasi, yaitu merdeka dari ketidakadilan, ketidakberadaban, dan ketidakmanusiawian. Itulah seharusnya wajah Jakarta, yang dikatakan Sukarno sebagai wajah Indonesia, wajah orang Indonesia. Jakarta harus menjadi cerminan manusia Indonesia yang berdiri tegak, tidak menunduk, berwawasan luas, dinamis, inklusif, penuh solidaritas, tidak menindas, dan simpatik terhadap sesama manusia.
Pemerintah Jakarta harus menyadari bahwa mereka memimpin pembangunan kota untuk mengedepankan nilai-nilai tersebut di wajah kotanya. Sebagai Ibu Kota, Jakarta memimpin sambil mengaitkan dirinya dengan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia dalam menempuh kemerdekaan, yang disebut Sukarno sebagai jembatan emas yang di ujungnya pecah menjadi dua, satu jalan menuju sama rata sama rasa, satu lagi jalan sama ratap sama tangis. Jangan sampai Jakarta memimpin ke jalan tujuan yang salah.
Sebab itu, Sukarno harus tahu semua rencana pembangunan Jakarta dan memeriksanya seraya memberi "Acc Soek". Bukan ingin mengambil alih tugas gubernur, melainkan kesadaran bahwa presiden harus ikut bertanggung jawab atas nasib ibu kota negaranya. Ia harus terlibat agar ide Kota Proklamasi tetap berapi, tidak tinggal abu. Karena itu, Sukarno mentradisikan setiap ulang tahun Jakarta berpidato. "Kita bangun Djakarta dengan cara semegah-megahnya, megah bukan saja karena gedung-gedungnya pencakar langit, megah di dalam segala arti sampai di dalam rumah-rumah kecil dari pada marhaen di Djakarta harus ada rasa kemegahan," demikian Sukarno mengingatkan khitah Jakarta sebagai Kota Proklamasi pada ulang tahun Jakarta ke-435 tahun 1962.
Jakarta terus membangun semegah-megahnya. Tapi, untuk siapa kemegahan itu? Apakah pembangunan Jakarta kembali ke jalan sesat pembangunanisme otoriter yang sudah disepakati untuk ditinggalkan pada 1998? Jawabannya tersimpul dalam berita Gubernur Ahok mengundang para artis ke Balai Kota untuk menjelaskan bahwa tiada penggusuran di Jakarta, melainkan relokasi, serta berita Ilyas Karim yang mengaku-ngaku pengibar bendera saat proklamasi. Sungguh, Ilyas dan Ahok sama palsunya: satu memalsu sejarah pengibar bendera proklamasi, satunya lagi memalsu janji Kota Proklamasi.
Ikuti tulisan menarik JJ Rizal lainnya di sini.