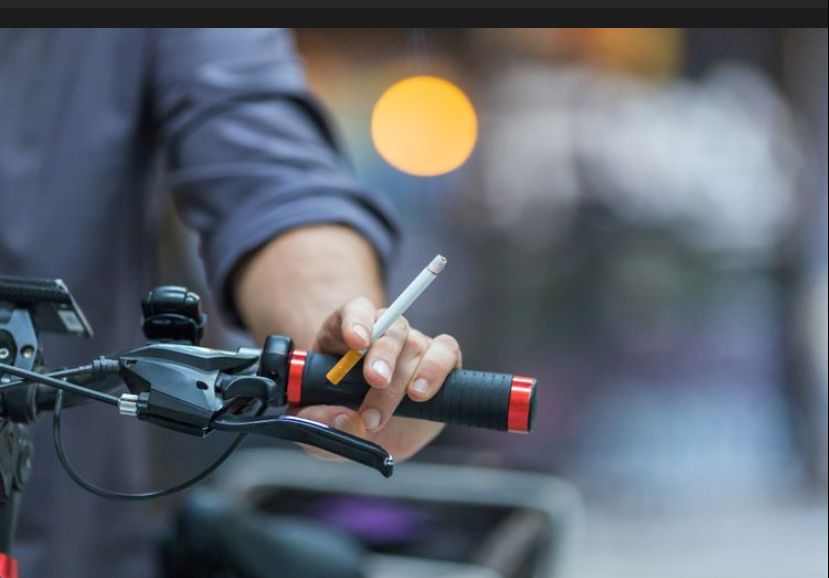Belakangan ini publik diramaikan oleh polemik pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Benarkah bahwa pembubaran HTI oleh pemerintah sudah tepat? Apakah dasar yang dipakai pemerintah untuk membubarkan HTI? Adakah ide khilafah yang didengungkan HTI bertentangan dengan ideologi negara? Padahal, wujud khilafah jika merujuk secara historis kepada model dan aksinya, apalagi dikaitkan dengan konteks kepemimpinan umat muslim pasca Nabi Muhammad, maka khilafah yang terjadi waktu itu jelas tidak didasarkan pada argumentasi hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Quran maupun Sunnah, tetapi lebih pada praktek pemilihan secara konsultatif, dimana para khalifah dipilih berdasarkan musyawarah dan legitimasinya ditegaskan melalui sebuah proses “bai’at” (kontrak sosial).
Dengan demikian, saya jelas menolak jika diasumsikan bahwa Khilafah merupakan sistem negara Islam apalagi jika disebut sebagai bentuk pemerintahan teokrasi, dimana seorang “khalifah” secara politik telah mendapatkan legitimasi dari Tuhan. Profesor Noorhaidi Hasan bahkan menyebut sistem khilafah yang digaungkan HT menganut asas teokrasi dengan melibatkan Tuhan dalam mengatur seluruh kehidupan sosial-politik. Asumsi ini jelas sangat mudah dibantah jika kita kembali merunut pada sejarah Islam awal, dimana pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad tidak sama sekali didasarkan pada asumsi-asumsi teokratik. Umar bin Khattab, misalnya, ketika mem-bai’at Abu Bakar bahkan menyatakan, “Demi Allah aku telah menyalahi Kitabullah dan ucapanku bukanlah ucapan yang diwasiatkan Rasulullah kepadaku” (Ibnu Hisyam: al-Sirah al-Nabawiyah).
Ungkapan Umar bin Khattab ketika bersama-sama umat muslim mem-bai’at Abu Bakar adalah penegasan dirinya atas sebuah proses politik kekhilafahan yang sekular, tanpa mendasarkan sama sekali kepada rujukan otoritatif manapun dalam hukum Islam, baik itu al-Quran maupun Sunnah. Seluruh proses politik kekhalifahan dari mulai pengajuan calon, pengujian kredibilitas, diskusi, musyawarah, dan bai’at merupakan cerminan dari ide pembangunan negara sekuler bukan wujud dari perwujudan negara agama. Jika seandainya khilafah menjadi cita-cita negara Islam, tentu hal itu sudah diproyeksikan oleh Nabi Muhammad bahkan dengan sangat mudah bisa diterapkan di negara Madinah. Tetapi, negara Madinah jelas dibangun Nabi tidak bercita-cita menjadi negara agama sebagaimana hal ini dapat dilihat secara utuh dalam poin-poin yang tertuang di Piagam Madinah.
Merujuk pada kesejarahan muslim awal pasca Nabi, jelas terlihat bahwa khalifah pertama, Abu Bakar Siddiq, adalah khalifah terpilih secara aklamasi dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sa’idah yang dipilih oleh umat muslim Mekkah dan Madinah. Proses-proses politiknya tidak dilalui berdasarkan perdebatan-perdebatan keagamaan secara argumentatif, tapi lebih banyak didorong oleh keinginan bersama membangun kondusifitas sosial pasaca wafatnya Nabi Muhammad. Dalam hal ini, saya sepakat dengan Ali Abd Raziq dalam sebuah karyanya yang kontroversial, al-Islam wa Ushul al-Hukm secara tegas menyebut, khilafah merupakan sistem sekular jika merujuk kepada historisitas pembentukan dan mekanisme pemilihannya, bukan sistem berdasarkan agama apalagi teokrasi. Ide khilafah justru salah kaprah ketika diasumsikan sebagai konsep pemerintahan berdasarkan agama (teokrasi) sebagaimana yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Ide khilafah jika dibangun berdasarkan peristiwa kekhalifahan awal pasca Nabi jelas memiliki konotasi makna yang cenderung sekular walaupun pada masa-masa kekhalifahan berikutnya, nuansa teokratis-absolut justru dipertontonkan oleh para penguasa muslim yang justru memanfaatkan legitimasi keagamaannya.
Sistem khilafah yang sekular justru secara nyata dapat dilihat pada praktek pemerintahan Islam generasi Khulafa al-Rasyidun (para Khalifah yang diberi petunjuk), yang dimulai periode Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Serangkaian proses politik yang dijalankan dalam pemilihan dan pergantian khalifah berada di luar koridor otoritas keagamaan. Fungsi kekhalifahan para Khulafa al-Rasyidun bukanlah “wakil Tuhan” tetapi mereka menggantikan fungsi kenabian dan melanjutkan otorisasi keagamaan yang sebelumnya melekat dalam diri Nabi Muhammad. Persoalan yang datang kemudian adalah ketika praktek kekhalifahan terus ditarik ke dalam wilayah keagamaan, mencari pembenaran-pembenaran otoritatif dari agama sekadar meneguhkan dan melegitimasi sistem negara Islam berdasarkan khilafah. Hal inilah yang tercermin dari model khilafah pasca Khulafa al-Rasyidun yang keseluruhannya bersifat monarki absolut, otoriter dan klaim tentang khalifah sebagai “wakil Tuhan” secara politik benar-benar diwujudkan.
Apa yang selalu digaungkan oleh HT mengenai prinsip kekhalifahan, jelas tidak merujuk pada konteks khilafah generasi muslim awal, tetapi lebih banyak mengadopsi pada praktek kekhilafahan setelahnya dan diperkuat oleh pembenaran-pembenaran secara agama yang sengaja dibuat oleh para ulama kerajaan. Karya-karya para ulama yang pro-khalifah jelas membangun dan menyusun teori-teori politik Islam secara sistematis demi bertujuan melegitimasi kekuasaan para khalifah. Benar, bahwa sistematika kepolitikan Islam beserta bentuk pemerintahannya dibangun berdasarkan rujukan otoritatif dari al-Quran dan Sunnah, tetapi tak jarang bahwa secara keseluruhan adalah upaya untuk sekadar melegitimasi kekuasaan para khalifah pasca Khulafa al-Rasyidun.
Oleh karena itu, upaya HT yang terus menggaungkan ide kekhilafahan sebenarnya lebih banyak dilatarbelakangi oleh kondisi frustrasi dimana sistem kekhalifahan yang dipaksa masuk menjadi wilayah keagamaan, padahal secara substantif khilafah adalah bentuk sekular dari sebuah bentuk sistem politik pemerintahan. Jelas kedua prinsip ini—sekular dan keagamaan—saling bertolak belakang dan pasti semakin menunjukkan banyak kelemahannya dalam berbagai sisi. Khilafah tidak hanya kehilangan momentum dalam setiap upaya penegakannya, karena ia bernuansa sekular, maka Khilafah tidak perlu mewujud dalam sebuah tatanan legal-formal yang dilegitimasi oleh agama. khilafah semestinya dipandang secara substantif, dimana proses-proses politik yang didasarkan atas pemilihan konsultatif, musyawarah, kontrak sosial dan legitimasi kekuasaan adalah benar-benar bersifat sekularistik dan keluar dari otoritas keagamaan.
Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.