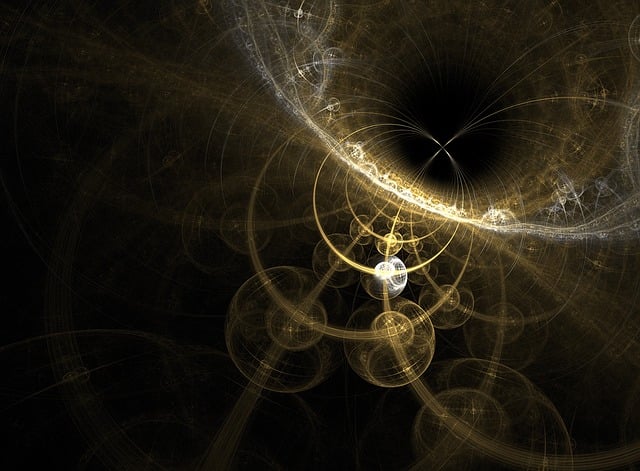Oleh : Ikhsan Yosarie
Memasukkan elite militer ke dalam sektor pemerintahan menjadi pola kepemimpinan di masa Orde Baru. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menjaga stabilitas nasional dan menstabilkan sistem politik yang diselenggarakan pemerintahan Orde Baru.
Secara tidak langsung, pola demikian membuat militer memiliki andil dalam menjaga kelanggengan Orde Baru. Militer menjadi pilar penopang pemerintahan, dan mengubah relasi antara militer dengan pemerintah yang semula alat negara, menjadi alat kekuasaan. Tidak heran jika mantan Pangkopkamtib Soemitro, mengatakan kondisi demikian mencerminkan militer (ABRI) mengalami proses down graded (penurunan derajat), dari alat negara menjadi alat kekuasaan politik (Salim Said, 2006).
Keikutsertaan militer dalam politik secara terbuka ditandai pada dua peristiwa penting. Pertama peristiwa 17 Oktober 1952, ketika militer berkonflik dengan parlemen. Peristiwa ini terjadi karena kepemimpinan sipil yang dianggap selfish, korup, dan tidak bertanggung jawab. Dengan sikap demikian, sipil tidak berhasil memerintah negara yang baru merdeka ini, dimana para perwira militer merasa memegang andil terbesar dalam mencapai dan menegakkan kemerdekaan pada masa 1945-1950. Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai peristiwa “Politico Military Simpton”. Kondisi demikian, membuat mereka (perwira militer) merasa terpanggil untuk turun tangan dalam rangka stabilisasi kondisi bangsa. .
Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1957, ditandai dengan berlakunya UU keadaan darurat perang. Setelah berlakunya UU tersebut, setapak demi setapak memungkinkan para perwira tentara mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi-fungsi politik, administrasi, dan ekonomi. Ketidakmampuan sipil menjaga stabilitas nasional, membuat para perwira militer bulat keyakinan bahwa mereka mempunyai tanggungjawab untuk melakukan campur tangan agar negara dan stabilitas nasional terjaga
Namun, konstelasi politik berubah di penghujung Orde Baru, dan awal Reformasi. Tekanan dari kekuatan-kekuatan pro-demokrasi untuk mereformasi berbagai elemen dan sistem kenegaraan terus digaungkan. Keterlibatan militer dalam politik dianggap menghambat konsolidasi demokrasi.
Dwi Fungsi ABRI di hapus dan fraksi ABRI di parlemen pun ditarik dari parlemen tahun 2004. Tindakan memangkas militer dari parlemen merupakan upaya yang dilakukan kelompok pro-reformasi untuk menjauhkan militer dari politik praktis. Keterlibatan militer dalam ranah politik dianggap sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan militer dikembalikan kepada ranah utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Abu-Abu
Mengacu kepada sejarah, keterlibatan militer dalam ranah politik bukanlah sesuatu yang baru. Militer (khususnya Angkatan Darat), tidak pernah menganggap dirinya sebagai suatu organisasi atau institusi yang tidak berpolitik. Yahya Muhaimin juga berpendapat bahwasanya militer sejak lahirnya sudah committed dengan urusan-urusan non-militer, termasuk dalam bidang politik. Terutama dengan adanya para tokoh militer yang berpengaruh dan berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Jenderal Sudirman, A.H. Nasution, TB Simatupang dan pewira lainnya.
Peranan ABRI dalam memberantas beragam peristiwa yang mengancam keamanan nasional, seperti pemberontakan PKI di Madiun, PRRI/Permesta, dan pemberontakan lainnya, bukan saja terdorong oleh fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, namun juga unsur keterlibatan secara politik (Yahya Muhaimin, 2005).
Keberadaan tokoh dan fenemona tugas militer tersebut membuktikan bahwasanya militer terlibat langsung dalam sejarah berdirinya republik ini. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, dilakukan militer dengan strategi atau kegiatan kesemestaan, maksudnya militer tidak hanya melakukan pertempuran secara fisik, tetapi juga terlibat dalam strategi penyusunan pendirian bangsa Indonesia
Secara lebih dalam, Harold Crouch mengatakan bahwa ambiguitas ini mulai ada sejak pemuda atau pejuang mulai mengangkat senjata. Para pemuda dan pejuang pada waktu melawan penjajah dahulu, mengangkat senjata tidak didorong oleh keinginan untuk membangun karier dibidang militer, tetapi didorong oleh semangat patriotik terhadap Republik Indonesia.
Perdebatan tentang keterlibatan militer di dalam politik juga mengarah kepada perbedaan pemahaman, sebagai bentuk perbedaan titik pijak pemikiran yang digunakan. Pemahaman dan kesadaran politik ini muncul karena selama perjuangan merebut kemerdekaan atau selama masa revolusi, kepemimpinan militer terlibat dalam permasalahan politik nasional.
Ambiguitas ini juga terjadi karena kesenjangan generasional dan kultural. Para perwira yang pernah mengenyam pendidikan militer dan akademis dari Belanda, terpengaruh doktrin dan paham Belanda bahwa militer harus netral dalam politik. Sementara, para perwira yang mengenyam pendidikan atau dilatih Jepang, menganggap militer tidak perlu enggan untuk terlibat dalam dunia politik.
Persoalan ini berbuntut panjang ketika para perwira yang terpengaruh doktrin bahwa militer terlibat dalam dunia politik, merasa memiliki hak yang sama seperti golongan politisi sipil dalam pemerintahan untuk menentukan bagaimana perjuangan dilakukan.
Pendalaman dan Perluasan
Keterlibatan militer dalam politik mengakar pada sejarahnya yang dapat dikatakan abu-abu dalam segi batasan politiknya. Dengan batasan yang abu-abu tersebut, pemahaman tentang keterlibatan militer dalam politik mengalami pendalaman dan perluasan. Pendalaman pemahaman tersebut kemudian dikonsepsikan oleh Jenderal A.H. Nasution dengan merumuskan konsep “Jalan Tengah”. Dalam konsep tersebut, para perwira Angkatan Darat aktif berperan serta dalam urusan pemerintahan, namun tidak berusaha merebut posisi dominan, militer juga menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan, dan administrasi.
Kemudian, perluasan pemahaman perihal keterlibatan militer dalam politik tampak setelahnya. Hal ini ditandai dengan diadakannya Seminar pertama Angkatan Darat pada bulan April 1965. Hasil dari seminar tersebut tercetusnya sebuah doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata di Indonesia merupakan suatu “kekuatan militer” dan “kekuatan sosial” sekaligus.
Kegiatan AD kemudian meluas meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan”. Kemudian, dengan adanya seminar kedua Angkatan Darat bulan Agustus 1966. Outputnya adalah peningkatan tekanan kepada Presiden Sukarno untuk menyerahkan diri sendiri kepada kenyataan dominasi militer atas pemerintahan, yang kemudian menjadi cikal bakal Orde Baru (Harorld Crouch, 1999).
Sejarah menjadi saksi bahwasanya keterlibatan militer dalam politik sudah mengakar dari era penjajahan Belanda, dalam bentuk perjuangan. Jika ditarik sampai ke Era Reformasi, dan disesuaikan dengan kondisi zaman, wajar jika terdapat ketidakcocokan. Akibatnya, militer didalam politik terjebak pada wilayah abu-abu (Grey Areas). Ambiguitas batas peran menjadi persoalannya, serta persoalan lain seperti profesionalisme militer. Sehingga, pembahasan mengenai hak politik militer menjadi sesuatu yang dianggap bertabrakan dengan semangat reformasi dan demokrasi masa sekarang.
sumber gambar : idiom.web.id
Ikuti tulisan menarik lainnya di sini.