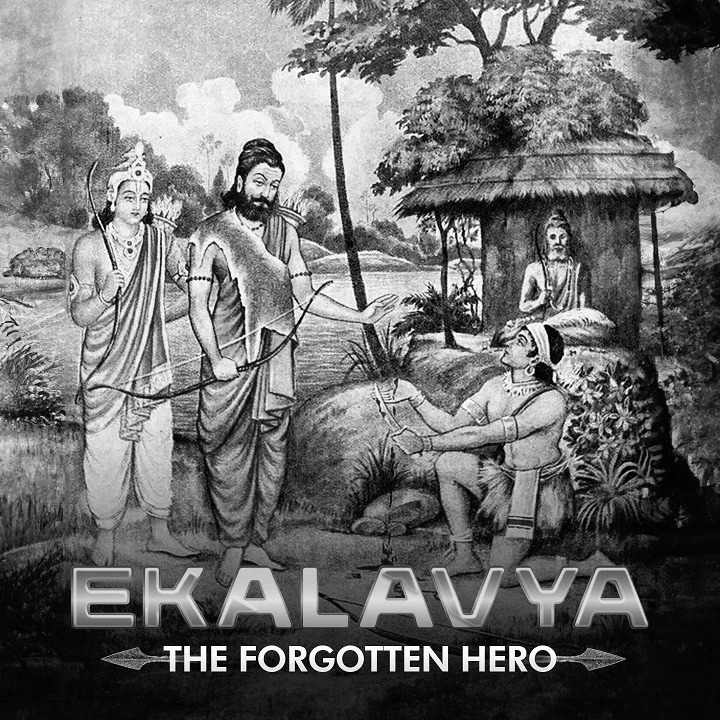Oleh : Ikhsan Yosarie
Keruntuhnya Orde Baru mengawali era baru dalam politik Indonesia, yaitu era Reformasi. Era itu tersebut ditandai dengan adanya “transfer kekuasaan” daru Presiden Suharto ke Wakilnya B.J Habibie pada 21 Mei 1998. Secara simbolis, peristiwa ini dimaknai adanya transfer dari pemerintah yang dikendalikan oleh pihak militer (disimbolkan dengan Suharto), kepada pemerintahan baru yang dikendalikan oleh sipil (disimbolkan oleh B.J Habibie).
Disisi lain, transfer ini sering dipandang sebagai transfer kekuasaan yang tidak menyeluruh, persoalannya adalah B.J Habibie juga merupakan bagian penting Orde Baru, dan salah satu orang yang dipercaya Suharto. Sehingga, pemerintahan Habibie dianggap sebagai copy-paste pemerintahan Suharto. Tetapi, yang perlu disadari adalah transfer dari Suharto ke Habibie tidak pelak lebih bermakna ketimbang skenario lain, misalnya transfer kekuasaan dari Suharto ke Wiranto (Panglima ABRI). Sekiranya, jika transfer ini terjadi dan disepakati, ini hanya menjadi transfer dari militer ke militer.
Peralihan tampuk kekuasaan, dari militer kepada sipil menjadi momentum dan titik balik perjuangan golongan pro-demokrasi. Peralihan kekuasaan ini dipandang sebagai kembalinya supremasi sipil dalam pemerintahan, setelah sebelumnya di dominasi oleh militer. Dengan supremasi sipil, semangat-semangat kebebasan dan anti-otoritanianisme kembali digaungkan. Semangat demokrasi yang lama terkubur, dan bergerak dibawah tanah sebagai akibat dari pengekangan rezim Orde Baru tampil kepermukaan.
Keruntuhan Orde Baru ternyata membawa implikasi yang besar terhadap posisi militer didalam kancah politik Indonesia. Tuntutan yang muncul salah satunya adalah pencabutan dwifungsi ABRI. Sehingga, posisi dan peran strategis militer ketika Orde Baru menjadi surut ketika reformasi, dan digantikan oleh supremasi sipil.
Terguncang
Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwasanya konsolidasi demokrasi mampu terwujud sebagai implikasi dari adanya perubahan relasi dan kekuatan politik antara negara dengan dengan masyarakat sipil. Semula, ketika Orde Baru berkuasa, negara memiliki kekuatan yang lebih kuat dari masyarakat, dan mampu mengatur serta mendikte masyarakat sesuai dengan kepentingan penguasa. Namun, perubahan yang terjadi adalah ketika masyarakat memiliki kekuatan yang mampu menandingi hegemoni negara, dan membuat perimbangan kekuataan dan posisi tawar.
Yang menjadi catatan pada hampir 2 dekade berikutnya (pasca-1998) –khususnya tahun 2016– adalah keterguncangan konsolidasi demokrasi kita. Keterguncangan ini disebabkan munculnya fenomena yang mengindikasikan bahwasanya kekuatan negara perlahan mulai melebihi kekuatan masyarakat sipil. Akibatnya, negara kembali memiliki kemampuan untuk mendikte bagaimana masyarakat sipil. Perkembangan kekuatan negara yang signifikan, dan tidak diimbangi dengan perkembangan kekuatan sipil (terlebih jika masyarakat sipil terpecah), hanya akan memunculkan kembali hegemoni negara dan mempersempit ruang publik masyarakat sipil.
Hal ini dapat kita lihat dalam 3 hal pokok, pertama perihal kemerdekaan pers. Dewasa kini, pers menjadi sarana masyarakat sipil untuk mengetahui tindak-tanduk pemerintah. Pers menjadi fasilitator informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, belakangan yang menjadi kemunduran konsolidasi demokrasi kita adalah ketika media-media konvensional beralih menjadi kaki tangan pemerintah, atau menjadi “corong” pemerintah. Sehingga, pemberitaan yang diberikan media tidak berimbang dan cenderung kurang fair untuk masyarakat. Akibatnya, media tersebut menjadi pilar keropos dalam demokrasi. Dan terakhir, siapa yang bertanggung jawab ketika bermunculan media-media daring yang menjadi antitesis dari media mainstream?
Kedua, kebebasan sipil dalam mengemukaan pendapat (lisan dan tulisan). Belakangan, kegiatan mengkritik, menghina, dan mencemarkan nama baik menjadi sesuatu yang semakin ambigu dan campur aduk ketika seseorang mengeluarkan pendapat lisan atau tulisannya. Sering kasus-kasus yang mempersoalkan opini masyarakat terjadi, dimana mengkritik dianggap menghina, mengkritik dianggap mencemarkan nama baik.
Dan semuanya include kedalam perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan, penangkapan terhadap mereka yang aktif dan vokal mengkritisi pemerintah juga dilakukan dengan anggapan “makar”. Sehingga, secara tidak langsung, fenomena ini menjadikan ruang masyarakat untuk mengkritisi pemerintah semakin kecil, lantaran takut dihadapkan kepada hukum.
Dan ketiga adalah perihal supremasi hukum. Persoalan ini klasik, ketika hukum tajam kebawah dan tumpul keatas, serta adanya mereka yang “kebal atau tidak tersentuh hukum”. Namun, yang menjadi catatan lain dan tidak kalah penting adalah perihal berlarut-larutnya suatu kasus hukum dan persidangannya. Hal ini kemudian menjadi dilema, baik dalam hal pemberitaan, maupun penanganannya.
Perihal pemberitaan, ketika beritanya menutupi kasus-kasus yang menyangkut masyarakat luas dan negara. Misalnya korupsi dan illegal logging. Dan perihal penanganan, ketika adanya perbedaan rentang waktu apabila yang terjerat dari kalangan elit pemerintah atau masyarakat biasa. Sehingga terkesan berbelit-belit dan indikasi politisasi.
Konsolidasi Demokrasi
Pada era Reformasi inilah semangat Demokratisasi hadir. Proses menuju demokrasi ini ditandai dengan perubahan kondisi hubungan antara negara dengan masyarakat (State-Civil). Ketika Orde Baru berkuasa, negara berada pada posisi lebih kuat dari masyarakat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk meredam, dan bahkan mengamputasi kebebasan dari masyarakat sipil. Kondisi ini biasa kita sebut otoritarianisme pemerintahan, atau relasi zero-sum.
Namun, relasi itu berubah ketika Orde Baru runtuh. Kondisi berbalik, perlahan masyarakat sipil memiliki kekuatan yang mampu menandingi dan mengimbangi hegemoni negara. Kemudian, ketika kekuatan seimbang, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah konsolidasi antara negara dengan masyarakat sipil, dan muncullah relasi Positif-sum. Konsolidasi dan pola hubungan seperti itu yang kemudian menjadi awal mula semangat demokratisasi pada era Reformasi, dan terciptanya check and balance antara masyarakat sipil dengan negara.
Era Reformasi menjadi awal implementasi supremasi sipil seutuhnya, dan kebebasan sebagai motor penggerak. Kebebasan menjadi sesuatu yang “langka” didapat ketika Orde Baru. Kebebasan ini didapat, dapat kita pahami sebagai konsekuensi dari perimbangan kekuatan antara masyarakat sipil dengan negara. Sehingga, negara tidak lagi memiliki kuasa sendiri untuk menghegemoni masyarakat dan mencengkeram kebebasan sipil. Kebebasan tersebut dapat kita lihat dari segi Pers, berpendapat, berkumpul dan berserikat, dan yang paling utama adalah mengkritisi pemerintah.
Dengan kebebasan inilah kemudian masyarakat sipil mampu mengawasi kinerja pemerintah, dan mengkritisi jika terdapat penyalahgunaan wewenang dan perihal tugas yang dijalankan aparat. Mengawasi dan mengkritisi pemerintah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam masa demokrasi. Fenomena ini menggambarkan bahwasanya check and balance antara pemerintah-masyarakat sipil itu memang ada, dan kekuatan politik sipil mampu mengimbangi negara.
Kebebasan dalam mengkritisi dan mengawasi pemerintah tersebut dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, namun tetap sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah diatur. Serta tak lupa peran pers yang senantiasa memberi informasi kepada masyarakat tentang pemerintahan. Kebebasan setiap warga negara ini tampak jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 28A-28J, dan perihal pers diatur dalam UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.
Yang perlu dicatat adalah, dalam negara demokrasi partisipasi, masyarakat dalam kehidupan bernegara merupakan sebuah keniscayaan, karena hal tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Di negara-negara demokrasi, umumnya muncul anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah-masalah politik, dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
Sumber gambar : Shaleh Kadzim - blogger
Ikuti tulisan menarik lainnya di sini.