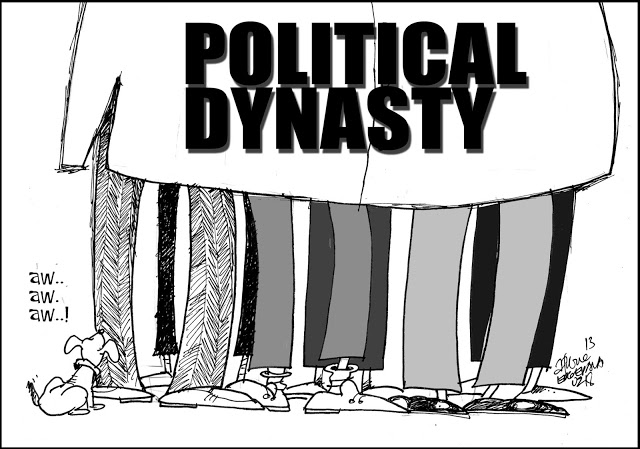Mencermati situasi demokrasi di tanah air, tak salah bila kita menilai ada gejala abuse of power (penyimpangan kekuasaan). Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain.
Sejarah mencatat terjadinya fenomena ini; dua kali malah: Orde Lama dan Orde Baru. Fenomena ini terjadi semasa demokrasi terpimpin. Namun, agar tidak salah kaprah, yakni menisbatkannya hanya dengan era pemerintahan Sukarno, sebaiknya kita pahami dahulu, apa yang disebut dengan demokrasi terpimpin.
Filsuf politik Sheldon Wolin menyebut demokrasi terpimpin sebagai pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Artinya, demokrasi dikelola agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berubah, statusquo.
Sehingga, meskipun menggunakan topeng pemerintahan demokrasi, dapat muncul penyimpangan ke arah otoritarianisme—pada titik otoritarianisme ini secara otomatis telah terjadi abuse of power. Ciri lainnya adalah masyarakat dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan.
Secara tegas, era demokrasi terpimpin berlangsung pada 1959-1966. Era itu ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, serta berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin diantaranya mengaburnya sistem kepartaian di mana pemimpin parpol yang bersilang pendapat dengan presiden banyak yang dipenjarakan.
Lalu peranan parlemen amat lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden, dan dibetuklah DPRGR. Jaminan HAM lemah, sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peran pers, lalu kebijakan politik bebas aktif dikangkangi dengan merapatnya Indonesia ke RRC (Blok Timur). Dan jatuhlah Orde Lama.
Ciri-ciri demokrasi terpimpin juga kental di era Orde Baru. Parpol dan legislatif menjadi omong kosong karena pemilu sudah dikangkangi untuk memenangkan satu peserta, yakni Golongan Karya.
Tindakan represif memuncak, di mana kalangan oposisi bukan hanya digiring ke penjara, tetapi digebuk, diculik bahkan ditembak. Pelanggaran HAM meruyak, sementara kebebasan berpendapat hanya mimpi di siang bolong karena segala informasi sudah disetir. Dan jatuhlah Orde Baru.
Bagaimana dengan era pemerintahan Jokowi? Sejatinya, gejala Demokrasi Terpimpin sudah mulai tampak. Ada lima indikatornya.
Pertama, pemusatan kekuatan terhadap presiden. Kabinet kerja nyata-nyata kelimpungan dalam menghadapi keriuhan demokrasi, sehingga sedikit-sedikit, mereka melakukan potong “kompas” dengan menjual nama Presiden.
Ambil contoh perkara pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri tempo hari yang diwacanakan Mendagri Tjahjo Kumulo. Bahkan Tjahjo mengajukan opsi penerbitan perppu untuk memutus kegagalannya dalam melobi agar presidential treshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Jangan lupakan pula perppu ormas yang dipakai untuk membubarkan HTI yang diusulkan Kajagung Prasetyo. Apa yang dilakukan Mendagri dan Kajagung nyata-nyata mendorong presiden agar mendominasi alam demokrasi di Indonesia.
Kedua, pembungkaman oposisi. Saya pikir fenomena ini amat jelas. Dalam tempo setahun saja, banyak kalangan nasionalis atau Islam-politik yang mengambil posisi oposisi, dihajar beragam kasus hukum. Mulai dari tudingan makar, dugaan chat mesum, dan pelanggaran UU ITE. Terlalu pandir rasanya membaca fenomena ini sebagai suatu kebetulan menimbang kejadiannya yang begitu cepat, hanya dalam tempo kurang dari setahun. Dan celakanya, meskipun penangkapan itu dilakukan dengan menggebu-gebu, sampai sekarang kasus makar dan chat mesum itu tidak kunjung tuntas. Padahal, sekiranya memang bukti-bukti sudah lengkap, seharusnya kasus-kasus ini sudah masuk persidangan.
Ketiga, teror bagi orang-orang “berbahaya”. Ini yang terbaru dan paling berbahaya karena mengancam fisik sampai keselamatan jiwa. Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, penyidik KPK, sungguh memprihatinkan. Sudah tiga bulan berlalu, dan belum jelas pula siapa yang bertanggungjawab. Belakangan, ada pembacokan Hermansyah, yang gandrung berteriak atas rekayasa di balik chat mesum Riziq Shihab. Tidak bisa tidak, hal ini tentu mempengaruhi psikologi massa, khususnya bagi mereka yang biasa mengritik kebijakan pemerintah.
Tetapi perlu pula dicatat bahwa sejatinya teror ini sudah lama ada. Jauh sebelum maraknya aksi-aksi perkusi, orang-orang biasa yang mengritik pemerintah pun sudah mengalami teror di media sosial. Kalau sekarang muncul Muslim Cyber Army (MCA), ini tak lebih dari aksi balasan atas terorisme medsos ala pendukung pemerintah.
Keempat, kebebasan bersuara. Ada trend seketika kebebasan bersuara di media sosial yang merosot di era pemerintahan Jokowi. Menurut data safenet, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah pelaporan kasus teknologi informasi tidak signifikan, yang totalnya pada periode 2008-2012 sejumlah 16 kasus.
Jumlah ini naik drastis pada 2013(20) dan 2014 (35) karena sudah memasuki dua tahun pemilu. Tetapi, pada 2015, mendadak pelaporan melonjak menjadi 63 pelaporan. Lalu pada 2016, naik lagi menjadi 91 pelaporan. Perlu dicatat bahwa pemerintah Jokowi melakukan revisi UU ITE pada tahun 2016.
Jangan lupakan pula, pada era Jokowi ini, warganet seolah-olah dilakukan seperti kaum dungu. Alih-alih membiarkan warganet mengelola dirinya sendiri, secara sepihak pemerintah malah memblokir situs-situs yang dituding SARA, provokasi, hate speech atau menyebarkan berita bohong.
Sama sekali tidak ada peluang. Belakangan pemerintah sudah masuk pula ke ranah jejaring sosial, dan akun-akun yang dianggap “berbahaya” pun “mati” mendadak. Keduanya berlangsung begitu cepat, tidak ada ruang dialog antara pemerintah dan pengelola situs-situs ini. Sehingga mereka yang dituduh merugikan publik ini tidak bisa melakukan pembelaan diri.
Kelima, rumor mengakali pemilu. Saya sengaja menulisnya dengan istilah ‘rumor’ karena memang tidak ada bukti nyata terkait hal ini. Mungkinkah seorang Presiden berpihak kepada seorang kandidat di ajang pilkada, dan mengerahkan kekuasaannya secara tersamar untuk memenangkan kandidat tersebut? Sulit dipercaya memang, tetapi jika kita merangkai kejadian demi kejadian yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta amat wajar bila banyak masyarakat yang mendapat bayangan seperti itu.
Kelima fenomena ini bisa menggambarkan betapa model kepemimpinan Jokowi secara sadar atau tak sadar telah bergerak menuju demokrasi terpimpin. Janji-janji kampanye Pilpres dahulu yang menggambarkan kemeriahan demokrasi akan mendapat ruang pada era pemerintahan Jokowi tidak terbukti.
Jokowi terkesan fokus untuk menuntaskan ambisi proyek-proyek mercusuarnya dan persiapan-persiapan menghadapi Pilpres 2019. Pembangunan demokrasi nyata-nyata sudah semakin mundur. Secara nalar tentu kita sama-sama sepakat bahwa sejarah kelam jangan sampai diulang apalagi hanya untuk melanggengkan kekuasaan.
Ikuti tulisan menarik Bagas Sanjaya lainnya di sini.