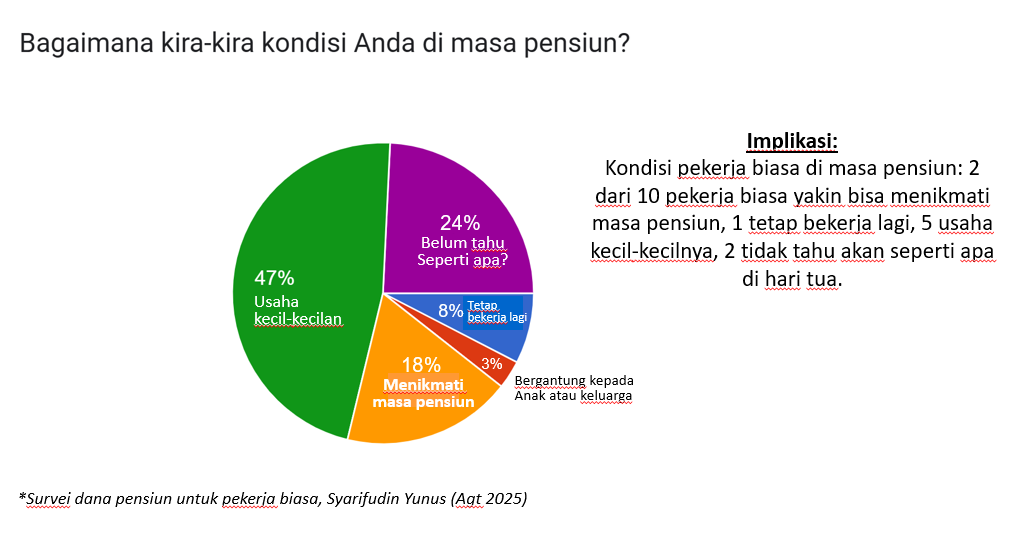Tambora 1815: Tragedi Kelam yang Mengubah Dunia
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Letusan dahsyat Tambora tahun 1815 memberikan dampak yang mengerikan bagi Indonesia (Hindia Belanda kala itu), tapi juga kepada dunia.
Foto : Kaldera Gunung Tambora
(Sumber : Tempo.co)
Sebagai negara yang berada pada lingkaran cincin api, Indonesia memiliki jumlah gunung api aktif yang tidak sedikit. Karunia alam ini memberikan anugerah kesuburan pada bumi pertiwi. Disisi lain berada di lingkaran cincin api membuat Indonesia rentan terhadap peristiwa erupsi gunung berapi yang bisa datang kapan saja tanpa bisa diduga. Bencana erupsi Merapi, Sinabung, Gunung Agung hanyalah segelintir bencana alam erupsi di masa kini. Tepat 203 tahun silam, erupsi dahsyat mengguncang nusantara dan menjadi sejarah kelam yang mengubah dunia. Tambora meletus tepat sesaat setelah Maghrib tanggal 10 April 1815.
Telah banyak tulisan yang mengulas tentang dampak dan kehebatan letusan gunung yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini. Salah satunya adalah Tempo yang menyajikan sebuah laporan khusus yang dibukukan saat peringatan 200 Tahun Tambora pada 2015 lalu. Tulisan ini adalah secuil nukilan dari buku tipis ‘Liputan Tempo: 200 Tahun Tambora’ namun tebal akan khazanah pengetahuan tragedi kelam tersebut. Terutama dampak yang ditimbulkan dan mengubah peta sejarah dunia.
Raffles Pun Terkejut
Letusan Tambora memang maha dahsyat. Kekuatannya setara dengan energi ledakan 171.500 unit bom atom. Memuntahkan 160 kilometer kubik material abu, gas, dan batuan yang membentuk tiga kolom asap setinggi 43 kilometer menembus lapisan stratosfer. Suaranya terdengar hingga Bengkulu, Makassar, dan Ternate. Saking kerasnya suara letusan, membuat Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa yang berada di Batavia Thomas Stamford Raffles terkejut. Dia mengira suara itu berasal dari meriam armada laut musuh, lalu mengerahkan semua armada dan pasukannya di Yogyakarta hingga Makassar untuk bersiap.
Raffles pun meminta pejabatnya untuk membuat laporan perihal ledakan tersebut. Owen Phillips, seorang pegawai Raffles sekaligus Perwira tinggi kapal Benares di Makassar-lah yang pertama kali memastikan Tambora meletus. Owen berangkat dari Makassar 13 April dan melego jangkar di pelabuhan Bima 19 April. Dari sana dia mendapat laporan warga Bima jika Tambora yang berada 32 kilometer barat Bima meletus.
Owen mengitari sekitaran lokasi letusan setelah dua hari kedatangannya. Dia melihat langsung kengerian yang terjadi disana dan melaporkannya kepada Raffles. Lima bulan kemudian, 28 September 1815 Raffles berdiri di atas mimbar forum ilmiah Masyarakat Ilmu dan Seni di Batavia untuk mempresentasikan kronologi letusan Tambora. Bahannya merupakan hasil pengamatan yang dilakukan Owen saat di Bima dan menyusuri sekitaran Tambora. Penggalan laporan ini juga disisipkan dalam buku mahakarya Raffles ‘The History of Java’.
Kegelapan Dunia dalam Sebuah Lukisan
Saat Tambora meletus, kala itu tidak ada teknologi foto ataupun video untuk mengabadikan suasana kelam di Eropa. Para seniman lukis menjadi saksi dan memvisualisasikan situasi lewat karya mereka yang kini tersimpan di National Gallery, London. Sebut saja seperti John Constable dengan lukisan ‘Weymouth Bay : Bowleaze Cove and Jordan Hill’ yang dibuat ketika dia menghabiskan masa bulan madunya di Pantai Weymouth, Inggris selatan pada musim gugur 1816. Tahun tersebut merupakan sebagai tahun tanpa musim panas atau ‘year of without a summer’ di Eropa.
Pelukis Eropa lainnya yang merekam ‘tahun kegelapan’ Tambora adalah seorang Jerman bernama Caspar David Friedrich. Caspar terkenal dengan karya lukisan berjudul ‘Ships in the Harbor at Night (After Sunset)’ dibuat pada 1816 dan ‘Woman in Front of the Setting Sun’ tahun 1818 yang menggambarkan siluet wanita dengan tangan terentang di bawah langit jingga erupsi Tambora.
Ada juga nama Joseph Mallord William Turner. Lewat lukisannya berjudul ‘Red Sky and Crescent Moon’ yang kini terpajang di Tate Museum of Modern Art, London dia mencoba menggambarkan kengerian gelap kala itu. Anggapan ini juga diperkuat oleh Gillen D’Arcy Wood dalam bukunya ‘Tambora : The Eruption that Changed the World’. Wood menjelaskan jika karya Turner melukiskan langit merah garang tersebut adalah gambaran sulfur pada debu vulkanis erupsi Tambora yang tertiup angin hingga Eropa, sehingga menghasilkan efek optik menakjubkan.
Kerusuhan London, Kekalahan Napoleon dan Kolera Benggala
Pasca Tambora meletus, suhu di London tercatat mencapai angka minus 16 derajat Celcius. Perubahan suhu dan iklim ini membuat orang tertekan dan kian tak terkendali. Kerusuhan pun tak bisa dihindari bagi mereka yang mengalami kelaparan. Penguasa lokal di Smoersetshire, Inggris sampai mengerahkan milisi untuk meredam para perusuh. Penjara di Inggris kebanjiran para perusuh.
Dalam Bab Ketiga Les Miserables, sastrawan Perancis Victor Hugo menyebut langit telah menentukan nasih Eropa. ‘Bila saja hujan tak jatuh pada malam 17 Juni 1815, masa depan Eropa pastilah berbeda. Hujanlah yang kurang lebih menumbangkan Napoleon’. Hujan yang dimaksud adalah ketika Napoleon melawan pasukan koalisi pimpinan The Duke of Wellington dan Gebhard von Blucher. Belakangan, hujan lebat itu menurut Hugo merupakan salah satu efek letusan Tambora yang berjarak sekitar 12 ribu kilometer dari lokasi kejadian di dataran Belgia. Namun, banyak pihak tidak sepenuhnya sependapat dengan anggapan ini dan hendaknya disikapi dengan hati-hati. Karena kekalahan Napoleon banyak dilihat dari banyak aspek.
Wabah penyakit adalah dampak kesekian dari letusan Tambora. Kolera Benggala awalnya adalah penyakit endemis di sekitaran tepi Sungai Gangga. Kuman kolera dibawa ke luar oleh prajurit Inggris di India saat berpindah tugas ke negara lain. Mulai dari Indonesia, menyebar ke Laut Kaspia hingga Moskow. Dari Eropa, kolera menyeberangi Samudra Atlantik dan mencapai New York. Dan tak mustahil letusan Tambora juga turut menyebarluaskan penyakit ini.
Dari Frankenstein sampai Terlahir Sepeda
Dari ranah kesusastraan, Tambora juga turut melahirkan novel klasik ‘Frankenstein’. Novel yang ditulis Mary Shelley ini pertama kali terbit pada 1 Januari 1818 dan diangkat ke layar lebar pada 1910. Dalam kata pengantar novelnya pada 1831, Mary Shelley menuliskan jika Frankenstein dia tulis ketika berlibur di Jenewa, Swiss bersama suaminya. Awalnya, mereka merencanakan untuk mengelilingi danau namun dibatalkan akibat cuaca buruk. Saat itulah dia berpikir untuk menuliskan kisah fiksi klasik itu.
Hal ini makin diperkuat oleh Bill Phillips, dalam tulisannya ‘Frankenstein and Mary Shelley’s Wet Ungenial Summer’ menerangkan ketika Frankenstein ditulis, belahan bumi bagian utara mengalami perubahan iklim tiba-tiba. Penyebabnya adalah letusan Tambora di Hindia Belanda (Indonesia) tahun 1815 dan menyebabkan perubahan cuaca hingga tiga tahun kedepan bagi Eropa.
Tak hanya Frankenstein, di daratan Eropa lainnya tepatnya di Jerman lahir inovasi baru yang bernama laufmaschine yang merupakan cikal bakal sepeda yang diciptakan Karl von Drais. Dikisahkan oleh Hans-Erhard Lessing kurator dari Technomuseum Manheim, seusai amuk Tambora, Eropa dilanda bencana gagal panen yang membuat stok pangan menipis. Tak hanya manusia, banyak hewan penting seperti kuda yang mati. Drais berpikir bagaimana menciptakan sebuah alat untuk menggantikan kuda-kuda yang mati. Maka lahirlah laufmaschine dan belakangan disebut velocipede, nenek moyang sepeda modern.
Dampak Lainnya
Dampak lain dari letusan dahsyat Tambora juga melanda Amerika Serikat. Di New England tahun 1816 dikenal sebagai ‘eighteen hundred and frozen to death’ yang membuat persediaan pakan ternak menjadi menurun, sehingga babi dan biri-biri pun diberi makan ikan makarel. Cuaca buruk di Pantai Timur memaksa para eksodus mengungsi ke arah barat. Selain itu juga lahir negara bagian baru seperti Alabama, Illinois, Kentucky dan Missouri. Tahun 1819 produksi panen semakin merosot dan memaksa 100 bank tutup, peristiwa ini dikenal dengan istilah Panic 1819.
Di bebrapa negara Eropa tak kalah peliknya. Irlandia dilanda wabah tifus yang menewaskan lebih dari 100 ribu orang dalam tiga tahun (1816-1819). Anomali cuaca terjadi di Italia, yakni turunnya salju berwarna cokelat dan merah karena tercemar abu vulkanis Tambora. Tahun-tahun awal meletusnya Tambora menjadi ‘tahun pengemis’ di Jerman. Krisis membuat makanan di negara ini langka, dan harga di pasaran mebumbung tinggi. Inilah yang memaksa sebagian besar orang turun ke jalan untuk meminta-minta.
Sementara itu di Cina kegagalan panen membuat ribuan orang mati kelaparan. Tanaman pangan kemudian diganti dengan opium yang kelak akan menjadi tren baru pasar candu dunia sehingga pecah Perang Opium tahun 1839. Sungai Yang Tze pun meluap akibat hujan terus menerus dan membanjiri kota. Total di Asia, Eropa dan Amerika lebih dari 200 ribu orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang dipicu cuaca buruk saat itu. Di Sumbawa sendiri bencana kelaparan melanda hingga tiga sampai empat tahun pasca erupsi akibat tanah tak bisa ditanami akibat tercemar abu vulkanik. Letusan Tambora juga membuat suhu bumi menurun tiga derajat Celcius.
Sumber :
- Tempo. 2015. ‘Liputan Tempo : 200 Tahun Tambora’. Jakarta : Penerbit KPG
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Cara Mengisi Kemerdekaan di Era Digital ala Pengusaha Muda Surabaya
Sabtu, 14 Agustus 2021 13:02 WIB
Menjaga Relasi dengan Klien? Begini Tips Efektifnya!
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0







 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 98
98 0
0