Partai-partai Berwatak Perusahaan
Selasa, 27 Agustus 2019 17:20 WIB
Dari segi tata kelola partai-partai politik Indonesia lebih mirip perusahaan daripada lembaga demokrasi yang sejatinya berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat. Melalu partai berwatak perusahaan ini, oligarki terus mencengkram politik Indonesia hingga hari ini dan menjadi salah satu penyebab demokrasi berhadapan dengan jalan buntu.
Diskusi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekarang ini hampir selalu menyertakan topik “ancaman oligarki” dalam pembahasan lebih lanjut. Keberadaan oligarki dinilai sebagai salah satu penyebab utama kebuntuan (sebagian malah menyebutnya kemunduran) demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat diperjelas melalui telaah singkat terhadap tata kelola partai politik di Indonesia.
Seandainya partai-partai politik Indonesia tidak melakukan aktivitas-aktivitas politik atau tidak ada embel-embel nama dan simbol partai politik di kantor dan alat-alat peraga mereka, kita akan menemukan kesulitan membedakan mereka dengan perusahaan biasa. Secara garis besar tata kelola parpol di Indonesia lebih menyerupai tata kelola perusahaan daripada tata kelola sebuah lembaga demokrasi yang sejatinya berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat.
Pemilik atau Pemegang Saham
Dalam analogi terhadap perusahaan, kita dapat membagi partai-partai politik di Indonesia ke dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok partai yang dikelola seperti perusahaan keluarga. Ke dalam kelompok ini bisa kita masukkan PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat dan berberapa partai lainnya. Sebagaimana lazimnya perusahaan keluarga di mana pusat kendali struktur dan operasional perusahaan berada di tangan keluarga konglomerat bisnis, demikian juga dengan partai-partai dalam kelompok pertama ini. Semua keputusan penting menyangkut jabatan-jabatan strategis dan pengambilan keputusan pokok dalam partai berada di tangan keluarga pemiliknya yang bisa kita sebut sebagai keluarga konglomerat politik.
Telah menjadi pengetahuan umum bahwa PDIP milik keluarga Megawati, Gerindra milik Prabowo, Nasdem milik Surya Paloh, Demokrat milik SBY dan demikian juga dengan beberapa partai lain yang layak dimasukkan dalam kelompok ini. Hampir mustahil figur baru bisa muncul dan menduduki posisi strategis dalam partai-partai kelompok pertama ini tanpa terlebih dahulu membuktikan diri sebagai pelayan yang baik terhadap kepentingan pemiliknya atau anggota keluarga dari pemiliknya.
Kelompok kedua adalah partai-partai yang dikelola seperti perusahaan publik di mana ada pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas. Saham mayoritas bisa dimiliki figur-figur berpengaruh, faksi, atau gabungan antara figur berpengaruh dengan faksi yang dipimpinnya. Ke dalam kelompok ini bisa kita masukkan Golkar, PKB, PKS, PAN, PPP dan beberapa partai lain.
Dalam partai-partai kelompok kedua, pusat kendali struktur dan keputusan partai hampir seluruhnya berada di tangan figur-figur berpengaruh atau elit-elit partai yang bisa diibaratkan sebagai pemilik saham mayoritas. Peluang untuk menjadi ketua umum atau pimpinan tertinggi partai praktis hanya ada di tangan para pemilik saham mayoritas. Penentuan struktur kepengurusan partai pertama-tama mesti mencerminkan kepentingan ketua umum dan faksinya, kemudian kepentingan elit-elit lain dan faksi-faksi mereka dalam partai tersebut. Prinsip yang sama berlaku dalam pengambilan pengambilan keputusan partai.
Tiadanya patron tunggal seperti Megawati di PDIP, Prabowo di Gerindra atau SBY di Demokrat membuat persaingan perebutan pucuk pimpinan dan perebutan posisi-posisi strategis relatif lebih terbuka dalam partai-partai kelompok kedua ini. Dalam arti tertentu, partai-partai kelompok kedua lebih terbuka terhadap mekanisme demokrasi terutama dalam proses suksesi kepemimpinan. Konsekuensinya, partai-partai kelompok kedua lebih rentan terhadap perpecahan dan konflik internal karena tiadanya figur pemersatu. Pertarungan antar faksi dalam partai-partai kelompok kedua relatif lebih menonjol dibanding partai-partai kelompok pertama. Namun, jika ditilik dari garis besar tata kelola semua partai ini yang telah dijelaskan melalui analogi terhadap perusahaan, tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok pertama dan kelompok kedua.
Wacana Pelembagaan
Berkaca pada tata kelola partai politik yang digambarkan di atas, wacana pelembagaan partai politik atau agenda indah bertema “institusionalisasi nilai-nilai demokrasi dalam Parpol” menjadi mimpi yang sulit ditemukan dalam kenyataan. Menjadi sangat sulit mengharapkan adanya mekanisme demokrasi yang terlembaga dan menjadi acuan wajib bagi semua kader partai (termasuk pimpinan) dalam melakukan aktivitas politik. Setiap saat pemilik atau para pemegang saham mayoritas partai dapat mengubah aturan agar selaras dengan kepentingan mereka; setiap saat mereka dapat bermanuver agar jabatan-jabatan strategis dalam partai diduduki oleh orang-orang yang bersedia melayani kepentingan mereka.
Absennya mekanisme yang terlembaga secara lebih gamblang terlihat dalam tata cara penentuan koalisi antar partai. Dalam hal ini kita dapat kembali menggunakan analogi perusahaan. Sebagaimana lazimnya perusahaan dalam membangun hubungan kerja sama dengan perusahaan lain berdasarkan kepentingan bersama atau prinsip saling menguntungkan, demikian juga partai-partai politik dalam membangun koalisi. Dalih kesamaan idiologi atau kesamaan platform partai yang sering digunakan politisi untuk menjelaskan latarbelakang terbentuknya sebuah koalisi, hanya basa-basi politik.
Kita tahu idiologi atau platform semua partai di Indonesia hampir sama tetapi dituangkan dalam rumusan-rumusan yang berbeda-beda. Dari sisi idiologi atau platform partai, hampir tidak ada perbedaan antara Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB dan partai-partai lainnya.
Di bidang ekonomi, misalnya, semua menggunakan retorika ekonomi kerakyatan tetapi tidak menutup diri pada perkembangan ekonomi global. Perbedaan kecil hanya bisa kita lihat dalam penegasan pandangan terhadap agama. Semuanya memang mengaku nasionalis-religius, tetapi beberapa partai seperti PKS menekankan perjuangan penegakan nilai-nilai agama.
Secara lebih konkrit, perbedaan kecil tersebut hanya kelihatan di musim Pemilu saat idiologi dan platform partai diterjemahkan menjadi program atau janji-janji kampanye. Segera setelah Pemilu berakhir, perbedaan-perbedaan kecil tersebut dengan mudah dilupakan karena konsentrasi partai akan terfokus pada upaya mendapatkan jabatan bagi kader-kader mereka sebanyak mungkin. Partai-partai dari koalisi yang kalah akan berusaha mendekatkan diri ke koalisi pemenang tanpa menghiraukan adanya perbedaan program atau janji-janji kampanye di masa Pemilu.
Koalisi antar partai manapun dapat dibangun selama memiliki kepentingan yang sama atau selama bisa memenuhi kriteria “saling menguntungkan”. Tidak ada mekanisme baku yang terlembaga sebagai acuan dalam menentukan koalisi. Ini tergambar dari perubahan-perubahan komposisi koalisi yang bisa terjadi setiap saat.
Cengkraman Oligarki
Selebar apapun jurang pemisah atau seberat apapun konflik yang pernah terjadi di antara para pemilik atau pemegang saham mayoritas partai, mereka dapat dengan mudah bersatu saat menemukan kepentingan bersama atau saat berhadapan dengan persoalan yang mengancam eksistensi kekuasaan mereka. Dalam kerangka inilah kita dapat memahami mengapa pelaksanaan agenda penguatan nilai-nilai demokrasi di berbagai sendi kenegaraan kita tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Kita menghadapi jalan buntu karena pelaksanaan demokrasi secara konsisten dan tuntas adalah ancaman bagi oligarki.
Kemunculan elit-elit baru berkat dukungan kuat dari masyarakat belum mampu memberi solusi efektif terhadap kebuntuan demokrasi tersebut. Mereka hanya mampu menunjukkan gejala-gejala perbaikan dan sama sekali tak menyentuh sumber persoalan. Mengingat posisi penting partai politik sebagai tangga untuk meraih dan mempertahankan kursi Presiden, Gubernur dan Walikota/Bupati, kita dapat memahami kesulitan kepala pemerintahan di pusat maupun di daerah untuk melepaskan diri dari cengkraman oligarki yang sepenuhnya memiliki kendali terhadap partai politik.
4 calon independen (jalur non-partai) yang berhasil meraih kursi Kepala Daerah pada Pilkada lalu sama sekali belum memadai sebagai bukti berkurangnya ketergantungan para calon-calon pemimpin eksekutif terhadap partai politik. Jumlah yang gagal melalui jalur independen jauh lebih banyak, termasuk yang gagal menjadi peserta Pilkada.
Ketergantungan pada partai juga diperkuat oleh sistem presidensial “setengah hati” pemerintahan kita. Dalam Konstitusi secara jelas memang tertulis kita menganut sistem Presidensial, tetapi di tataran praktis pemerintahan kita juga beraroma Parlementer sebagaimana terbukti dari banyaknya kewenangan yang dimiliki parlemen.
Dengan berbagai kewenangan tersebut, parlemen dapat menyandera pemerintah, misalnya dengan tidak menyetujui program-program unggulan tertentu. Karena itu dukungan kuat dari parlemen mutlak dimiliki oleh seorang presiden, gubernur, atau walikota/bupati dan karena alasan itu dia mesti melayani kepentingan para pemilik atau pemegang saham mayoritas partai politik yang berkuasa penuh mengatur anggota-anggotanya di parlemen.
Dengan kerangka berpikir di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa cita-cita mulia dan dukungan luas dari masyarakat tidak cukup sebagai modal bagi seorang pemimpin pemerintahan untuk menyukseskan agenda-agenda demokrasi di Indonesia. Kuatnya cengkraman oligarki terutama melalui partai politik, membuat pemimpin yang memiliki cita-cita paling mulia sekalipun, dengan mudah tunduk pada kepentingan oligarki. Dalam skala tertentu dia mesti menjadi perpanjangan tangan oligarki. Kita hanya berharap dia tidak melupakan cita-cita mulianya dan berubah menjadi bagian sah dari oligarki.
JPM Group Reporter
0 Pengikut

Ambulan Musolla All-Falah untuk Semua Masyarakat dari Semua Agama
Rabu, 30 Maret 2022 19:10 WIB
Cengkeraman PT TPL Membuat Masyarakat Tak Berdaya (Bagian 1)
Selasa, 22 Februari 2022 07:37 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





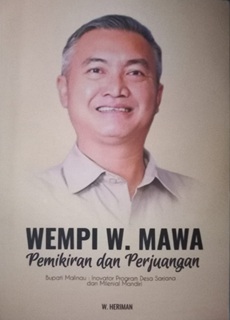

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 99
99 0
0














