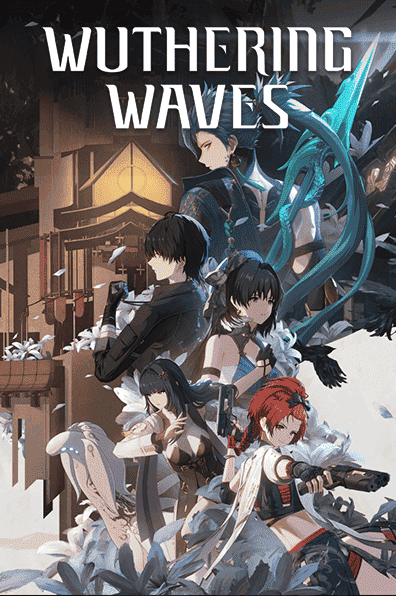Siapa Suruh Jadi Pakar Sastra
Rabu, 17 November 2021 05:44 WIB
Penyebutan pakar sastra ini menarik. Satu sisi dunia sastra butuh ahli yang berkecimpung di dunia sastra untuk membedah dan mengkaji karya, mendiskusikan nilai-nilai etisnya, membangun autokritik, dan sebagainya. Tapi di sisi lain pakar bisa berarti inklusif. Mengambil jarak dengan masyarakat pada umumnya. Kadang mereka membentuk pertemanan semu agar disebut pakar. Siapakah yang bisa disebut pakar sastra?
Sebagian dari kamu yang pernah membaca novel, kumpulan cerpen atau buku puisi, mungkin memiliki sejumlah pertanyaan. Seperti seorang teman yang pernah mengatakan, "Novel ini, loh, bagus, coba baca".
Apa ukuran bagus dari karya sastra? Cerita dengan plot yang rumit dan dengan bahasa yang rumit? Penulisnya sudah terkenal? Ataukah karya sastra yang sedang kamu baca itu adalah karya sastra yang sudah lama kamu tunggu. Dalam artian, dibenakmu kamu menjustifikasi bahwa karya yang kamu baca saat ini sudah bagus bahkan sebelum karya sastra itu terbit. Ukuran mana yang kamu pakai?
Dulu, dulu sekali ada seseorang yang khusus membahas kritik karya sastra. Beliau terkenal karena kritik sastranya bahkan melebihi karya sastra beliau sendiri. Pendeknya, kritiknya lebih besar ketimbang karya sastranya.
Di masyarakat kita selama ini, penulis biasanya memiliki pembaca sendiri. Seperti orang pemasaran yang bilang, lebih segmented. Dengan target market yang sudah diperkirakan sejak semula, seorang penulis bisa menentukan pembaca yang diinginkannya.
Ini berarti, berbicara tentang konten, konteks, desain sampul, gaya bahasa, medium apa yang cocok. Penulis menggunakan kemampuan mereka terutama hanya untuk perihal jangka pendeknya. Padahal karya sastra sebetulnya tidak hanya itu. Karya sastra yang sering kurang dipikirkan biasanya adalah karya sastra yang harus dipenuhi di kemudian hari.
Harus memupuk keindahan, harus membimbing peradaban dan keutuhan bangsa, harus menuntun ke arah pembangunan rohani bangsa, harus memberikan jawaban bagi persoala di masyarakat. Pendeknya, karya sastra harus menghibur dan memberi gagasan baru.
Untuk bisa menghasilkan karya sastra yang menghibur dan penuh gagasan baru, perlu lebih dulu tahu seluk beluk ilmu sastra, ilmu linguistik, ilmu semiotik, dan lain-lain.
Namun demikian, buku yang membahas ilmu sastra, biasanya tebal-tebal dan monoton. Orang-orang keburu malas untuk membacanya. Hanya mereka yang kuliah di jurusan sastra yang mendapat tugas kuliah yang akan membaca buku-buku tebal itu. Selebihnya, tak akan ada orang yang mau membaca bahkan untuk sekadar menyentuh.
Jalan pintasnya, dibutuhkan seorang pakar. Orang yang sehari-hari berkecimpung di dunia sastra. Pakar-pakar inilah yang memiliki pengetahuan tentang karya sastra yang bagus. Seseorang yang tugasnya mengulik karya sastra dan membangun auto kritik di masyarakat. Dimana apabila auto kritik itu dijalankan, maka terbangunlah iklim yang konstruktif di dunia sastra Indonesia.
Dalam ulikan seorang pakar, terdapat saran mengenai nilai-nilai etis karya sastra. Memperjelas lagi pemikiran-pemikiran manusia tentang dunia, termasuk keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan.
Di era media sosial saat ini, beterbaran karya-karya sastra di dunia maya. Dalam hal ini, kita sepatutnya bangga karena sastra semakin membumi. Siapa saja bisa menghasilkan karya sastra. Anak SD yang menulis catatan hariannya tentang guru dan teman sekolahnya bisa kita sebut itu karya sastra. Seorang jomlo yang menuangkan kegundahannya akibat dirundung di media sosial, itu juga karya sastra, dan masih banyak lagi contoh lainnya.
Siapa saja bisa menghasilkan karya sastra. Karena mediumnya jauh lebih mudah. Dan karya sastra tak harus berbentuk buku. Ia bisa berupa channel Youtube, Blog, fanspage facebook, dan media sosial lainnya. Dominasi buku mengecil pengaruhnya di era ini, meski peminatnya masih ada, masih banyak.
Tentu saja, disamping bermunculan karya sastra, bermunculan pula "pakar" sastra. Tanda kutip ini berarti, siapa saja bisa menilai sastra.
Ini menariknya, seorang selebritis yang ngetwit kata-kata di twitternya dihargai sama pentingnya dengan penulis yang sehari-harinya berkecimpung di dunia sastra.
Tidak jelas ukuran penilaian sastra. Tidak jelas pula siapa yang bisa disebut pakar sastra, yang boleh dan tidak menilai suatu karya sastra.
Penyebutan pakar sastra ini, menarik bagi saya. Satu sisi, dunia sastra butuh orang-orang ahli yang berkecimpung di dunia sastra setiap hari. Membedah karya sastra dalam kajian-kajian rutinnya, mendiskusikan kembali nilai-nilai etisnya, membangun autokritik, dan sebagainya.
Di sisi lain, pakar bisa berarti inklusif. Mengambil jarak dengan masyarakat pada umumnya, paling ahli, paling pintar, membentuk pertemanan-pertemanan semu yang di mana untuk menjadi pakar haruslah ikut tergabung dalam komunitas-komunitas tertentu.
Siapa yang bisa disebut pakar? Penulis yang pernah menang di perlombaan? Penulis yang sudah menelurkan banyak karya? Yang pada akhirnya tolok ukurnya seberapa banyak buku yang dihasilkan. Siapa yang bisa disebut paling mumpuni di bidang sastra?
Jangankan menjadi pakar sastra, untuk menjadi penulis sastra saja pun tak mudah. Istilah kerennya, nulis aja masih bolong-bolong kok pengen disebut pakar sastra.
Jika kamu punya akun twitter, cobalah menulis sajak di filesajak, yang senang menulis fiksi cobalah tulis fiksinya di fiksimini. Saya jamin, belum tentu akan diretweet. Bukan karena kontennya jelek, atau kamunya bukan penulis buku, tulisan kamu tidak diretweet. Bisa jadi admin di komunitas itu tidak mengenal akunmu. Itu kenapa tulisanmu tidak diretweet.
Retweet bisa berarti penilaian. Seberapa berharganya tulisanmu. Yang menarik akan di retweet, yang sering-sering kirim tulisan akan diretweet. Tentu saja itu hak preogratifnya si admin. Apakah si admin ini bisa disebut pakar?
Di era media sosial sekarang ini, banyak karya sastra yang saling berteriak di tengah masyarakat. Seperti menjejali, tak peduli mau apa tidak. Hukum alam berlaku, siapa yang jamaahnya paling banyak, karyanya yang akan kekal.
Mediumnya banyak, tak dominan buku. Semua penulis bisa mengaktualisasi kegelisahannya di banyak tempat. Menjangkau area yang lebih jauh dan luas daripada era yang sebelumnya.
Perlukah seorang pakar sastra di era ini? Saya tidak tahu. Tentu saja, yang eksis yang bisa menjawabnya.
Teks sastra yang menjadi rujukan
Kamu bisa melihat kitab Pararaton, kitab Raja-Raja. Berisikan naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Sejarah mencatat, penulisnya anonim. Tak diketahui siapa yang menulis kitab tersebut. Tak diketahui pula darahnya, apakah tergolong darah biru, merah atau bahkan tak berdarah (jin, red).
Yang tak dipungkiri, hingga detik ini, kitab Pararaton masih menjadi salahsatu rujukan membuka tabir nenek moyang.
Tak seorang pun yang mengkritik naskah sastra yang ada di dalamnya. Tak seorang pun kritikus sastra, hanya sedikit sejarahwan yang berani mengulik fakta-fakta sejarah yang terulas dalam naskah. Antara fakta dan fiksi saling berbaur.
Bahwa kemudian teks-teks dalam kitab Pararaton bersifat supranatural dengan tujuan menentukan kejadian-kejadian masa depan tak mengerdilkan kitab Pararaton sebagai sumber rujukan.
Ada tokoh dengan nama Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang yang notabene tidak ada dalam inskripsi-inskripsi lain, saat ini menjadi ikon sebuah kota. Sebuah peradaban lengkap dengan langgam budayanya.
Bisa jadi penulis kitab Pararaton hanya mengarang cerita-cerita drama. Mengambil kejadian-kejadian di masa lalu, memberi nama tokohnya, memberi konflik dan lengkap dengan puntiran konfliknya. Ya, bisa jadi penulis tak ubahnya seorang novelis yang membentuk dramanya sendiri di kepala. Lalu menuliskannya di medium saat itu yakni daun lontar. Kemudian, berabad-abad kemudian, sejarahwan menemukannya.
Karya sastra yang 'biasa' saat itu, bisa jadi sangat penting di kemudian hari. Tidak perlu 'bagus' seperti kata kritikus. Hanya perlu menjadi 'satu-satunya drama yang ditemukan sejarahwan'. Tentu saja, sejarahwan akan mengagung-agungkan penulisnya. Dari seorang yang berprofesi biasa menjadi keturunan ningrat dengan kecakapan yang luar biasa.
Tidak ada ukuran sastra yang sanggup menilai 'satu-satunya drama yang ditemukan sejarahwan'. Tidak ada yang sanggup mengkritisi naskah di dalamnya.
Berbeda dengan kakanwin Negarakretagama. Syair ini ditulis oleh sastrawan negara. Syair yang mengagung-agungkan Raja Majapahit, Hayamwuruk. Teks sastra ini juga menjadi rujukan membuka tabir nenek moyang.
Ditulis rapi oleh beberapa pujangga dengan nama pena Mpu Prapanca. Tiap syairnya ada empat baris (pada). Tiap baris terdiri dari delapan hingga dua puluh empat suku kata (matra).
Nah, di sinilah diperlukan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sastra. Yang sanggup menyusun pada dan matra yang begitu ketat. Seorang pujangga yang mampu menyampaikan langgam tulisnya dengan struktur yang bisa dimengerti oleh orang awam. Bahkan generasi berabad-abad kemudian.
Tidak hanya itu, dibutuhkan ketelitian dalam merangkum pujasastra. Sebab disusun keroyokan sesama pujangga. Setidaknya satu gagasan yang sama.
Bilamana kitab Pararaton menulis drama. Di situ ada lakon, tokoh, konflik. Beda dengan kakanwin Negarakretagama. Di sini lebih seperti dokumentasi perjalanan, instruksi negara, atau pedoman yang ditulis dengan kaidah sastra yang ketat. Memenuhi unsur keindahan, membimbing keutuhan negara, menuntun rohani masyarakatnya, dan sebagainya.
Sebagai teks sastra, keduanya hingga kini masih menjadi rujukan sejarah. Terlepas dari nama di baliknya yang menjadi tolok ukur karya sastra yang 'bagus' saat ini.
Penulis Sastra
Siapa yang bisa disebut penulis sastra? Dia yang menulis prosa? Menulis puisi? Bisa jadi. Bisa juga mereka yang menulis instruksi atau ajaran. Sebab sastra diserap dari bahasa Sanskerta, Shastra. Yang berarti teks yang mengandung instruksi atau ajaran. Pendeknya, menurut saya, tolok ukurnya adalah karya. Mereka yang bekerja menghasilkan tulisan atau karya yang memiliki arti atau keindahan tertentu.
Kamu sudah mempunyai penulis sastra favorit? Atau kamu sendiri juga seorang penulis sastra? Siapkah kamu menilai sendiri hasil karyamu?
Salahsatu faktor penentu hasil karya sastra adalah penulisnya. Dan yang namanya hasil karya sastra, ujung-ujungnya dinilai dari angka. Berapa angka sudah hasil karya sastramu? Berapa angka rupiah yang dihasilkan? Berapa angka jamaahmu? Berapa angka kamu diundang sebagai panelis? Dan sebagainya.
Angka ini yang diterjemahkan sebagai jarak. Ada penulis mayoritas dan ada penulis minoritas. Tentu saja, ini tentang pengaruh. Hal ini juga yang memberi jalan kepada penulis untuk tetap eksis, sekaligus secara tidak langsung mewajibkan seorang penulis untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas tertentu. Dan untuk memuluskan jalan sebagai penulis sastra.
Penulis selalu dekat dengan kata. Harus bisa berdiri sendiri menentukan nasibnya sendiri. Keharusan untuk melepaskan diri dari ketergantungan yang ada di luar dirinya sendiri.
Apa maksudnya berdiri sendiri? Penulis itu bebas berekspresi dan berbicara dalam tulisannya, jangan sampai penulis, seperti ucapan Chairil, mendurhakakan kata. Kata tidak dibentuk oleh kesadaran berpikir tapi oleh aku (penulis) yang ada di dunia. Hidup dari masa ke masa, terisi padu dengan penghargaan mimpi, harapan, cinta dan dendam. Kata adalah analog dengan kehidupan. Tak bisa dikotak-kotakkan, tak bisa disatukan dalam kategori, tidak bisa dimatikan dalam kamus. Selalu mengalir dari pembakuan bahasa komunikasi sehari-hari.
Penulis sastra harus deteritoralisasi. Lepasnya sastra dari kekangan penguasa. Mendobrak batasan yang diciptakan penguasa berupa arah sastra, agenda isme apapun juga nasionalisme.
Masyarakat Sastra
Sastra melibatkan dirinya ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui sastra, pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat dapat terpengaruh.
Era kemerdekaan Indonesia, sastra mengambil perannya. Menyebarkan informasi, arah dan nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Kita bisa mengingat slogan-slogan yang hingga kini kita kenal, "Merdeka atau Mati".
Sastra seperti memaksa masyarakat mengubah pola pikir, mendobrak tatanan, serta komunikasi sehari-hari. Bila di era sebelum kemerdekaan ada kata paduka , di era kemerdekaan kata itu berubah menjadi bung. Seperti bung Karno, bung Hatta, dan sebagainya.
Lain lagi di era sekarang ini, di mana media sosial merajalalela dan sangat berpengaruh. Sastra mengambil perannya. Sebagai contoh, kamu bisa melihat di jalanan ibukota, di punggung bus trans jakarta kamu bisa melihat slogan yang ditulis besar-besar Merdeka atau Macet. Menurut Goenawan Mohamad ini bentuk kedewasaan yang menarik dalam sastra.
Sastra juga sering digunakan dalam produk-produk komersil yang lain yang berperan menjelaskan kelebihan produk secara singkat. Kata demi kata disusun dengan isi dan kandungan tertentu sehingga menarik konsumen untuk membeli.
Cuci tanganmu sebelum makan
Sederhana bukan? Apa yang menarik dari kata-kata tersebut? Yang pasti kata itu dikemas sedemikian rupa agar mudah kamu ingat. Dan yang paling penting mengubah pola pikirmu, mengubah perilakumu.
Sastra juga punya punya fungsi membangun kesadaran masyarakat terhadap sesuatu, memberi informasi, imbauan juga motivasi. Di berbagai kesempatan sastra kerap digunakan terutama yang berhubungan dengan informasi publik. Sastra semakin membumi di masyarakat, digunakan di segala tempat. Tentu ada saja yang tidak senang.
Dewasa ini banyak yang mempertentangkan sastra. Bagaimanakah kiranya sastra bisa disebut sastra? Para penulis ingin menulis sastra yang bener-bener sastra. Tak mau menjadi dewasa atau menolak tua. Bahwa sastra seperti barang komoditi yang diperjualbelikan, tak ada arti. Ketika masuk ke dunia iklan, orang-orang sastra akan menolak, bahwa tulisan atau kata-kata yang ada di produk komersil itu bukan sastra.
Ketika masuk di dunia politik, orang-orang sastra cenderung enggan mengakui bahwa slogan-slogan identitas yang ada di partai politik beserta kegiatan politiknya adalah bagian dari sastra.
Orang-orang sastra ingin memurnikan ajaran. Para penulis ingin menulis sastra yang bener-bener sastra. Para pembaca ingin membaca tulisan yang bener-bener sastra. Sastra yang baru, bukan sastra yang mengulang-ulang para pendahulu. Sebab jika terjadi adalah pengulangan karya maka bisa dikatakan sastra Indonesia tidak maju, atau jalan di tempat.
Untuk mengetahui adanya kemajuan dalam sastra, di sinilah peran kritikus sastra sebagai pengingat. Juga tak kalah pentingnya peran apresiasi sastra.
Apa itu apresiasi sastra?
Yakni penghargaan atau penilaian terhadap karya sastra. Menilai sesuatu yang berharga di karya sastra. Ada sesuatu yang berharga apabila kamu membaca karya sastra.
Untuk bisa mengapresiasi karya sastra, jalan satu-satunya ialah membaca karya sastra.
Membaca itu kegiatan senggang. Bukan waktu inti manusia. Bekerja, makan, tidur, itu inti waktu manusia. Tapi membaca dibutuhkan waktu diantara inti tersebut.
Kamu tak akan pernah bisa menyukai sastra bila waktu untuk membaca tidak ada. Tak kenal maka tak sayang. Maka untuk menyenangi sastra ialah menyiapkan waktu senggang untuk membaca.
Sedikit demi sedikit waktu senggang disediakan. Mula-mula 10 menit. Kemudian lanjut 30 menit sehari, dan seterusnya. Dengan sendirinya, pengetahuan akan sastra akan meningkat. Rasa senang, cinta dan ilmu sastra akan diperbaharui dengan membaca.
Membaca bukan kegiatan menyenangkan. Membaca menjadi begitu menantang untuk sebagian orang. Tentu saja, alasannya, menghabiskan waktu berjam-jam dengan membaca karya sastra bisa sangat membosankan.
Hal ini menjadi penyebab mengapa banyak buku sastra yang terabaikan, si pemiliknya sibuk bekerja. Banyak orang tidak tahu, menghabiskan waktu di sela-sela kesibukan dengan membaca buku sastra akan menjaga empati di pelbagai hal. Mengetahui apa yang tidak banyak diketahui orang lain, dan juga membantu mengolah rasa, mengasah seni yang ada dalam diri. Karena pada dasarnya setiap manusia dibekali kecakapan soal seni. Seni dalam diri itu bisa muncul lebih bagus bila terus disugesti dengan bacaan-bacaan sastra yang berkualitas.
Berbanding lurus dengan kegiatan membaca, tentu yang dibutuhkan selanjutnya adalah karya sastra. Semakin banyak karya, semakin banyak ragam semakin banyak pula pilihan untuk membaca. Semakin banyak pilihan untuk mengapresiasi atau mengkritisi. Karya sastra semakin dewasa, semakin berkualitas.
Selalu ada perdebatan tentang sastra yang berkualitas. Perdebatan ini tidak pernah selesai. Ada yang cenderung menengok ke masa lalu. Bahwa sastra itu tak lepas dari langgam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk. Tolak ukurnya tentu saja karya sastra yang sudah-sudah.
Tapi ada juga yang cenderung berontak. Mendobrak kukungan zaman. Lebih melihat masa depan. Bahwa sastra yang berkualitas itu tak harus sesuai langgam budaya Indonesia. Ia bisa datang darimana saja, bisa dalam negeri maupun luar negeri. Tak harus sesuai kaidah kebakuan. Karena mereka cenderung bebas dari kotak batasan.
Selain itu, sastra yang berkualitas mustahil dapat menghindar dari segala tetek bengek kehidupan. Karena pada umumnya problematika sehari-hari dijadikan ilham bagi penulis. Mustahil menghindari proses kreatif semacam itu. Memghayati setiap problematika, merenungkannya, kemudian mengendapkannya sampai muncul suatu gagasan yang nantinya disalurkan dalam wujud karya sastra.
Seorang penulis biasanya memiliki penalaran yang tinggi, mata batin yang tajam, sekaligus memiliki daya intuitif yang peka sekali yang jarang ditemukan dalam diri orang kebanyakan. Tentu saja, ini semua hasil akumulatif dari kegiatan membacanya.
Maka dibutuhkan karya-karya sastra baru, yang tidak membosankan, yang menawarkan hal baru, menggugah selera untuk membaca, menjaring lebih banyak pembaca.
Dewasa ini orang-orang berbondong-bondong nulis di media sosial. Entah nulis puisi, prosa, atau kritik sastra. Semua tulisan saling berteriak, mencari pembaca. Seorang penulis yang ajeg dalam menulis akan semakin dikenal. Akan semakin banyak pula jamaahnya.
Muncullah era selebritis sastra, yang di mana mengagungkan jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah, semakin terkenal, semakin pula berpengaruh apa yang ditulisnya.
Suatu kenyataan yang ironi. Mengenai dunia sastra yang absurd, yang dibangun oleh beragam permasalahan intuisi yang membentuk perilaku dan budaya masyarakat. Sastra dianggap sebagai gambaran realitas yang normal dan biasa-biasa saja.
Selebritis sastra dianggap memenuhi kebutuhan komunikasi dan eksistensi pembaca. Tentang perasaan sedih, muram, putus asa, dan tertekan serta merasa tak berdaya mulai membanjiri sastra di media sosial. Belum ada kajian yang bisa menghubungkan selebritis sastra dengan rasa kehilangan, kecemasan, depresi dan kesepian yang menjamur ini. Bagaimana selebritis sastra bisa menimbulkan kesepian? Apa kaitannya? Tentu saya tak bisa menjawabnya. Yang saya tahu, begitu banyak, begitu massive 'sastra yang sedih' ini. Dan diperluas jangkauannya oleh selebritis sastra.
Terkadang ada kesan bahwa setiap orang lebih keren bila depresi, bila kesepian, bila tertekan dan tak berdaya. Celakanya banyak penulis justru ikut-ikutan 'membenamkan diri' karena hanya itu yang mereka kenali sebagai karya sastra.
Aksi rame-rame, 'membenamkan diri' bukan melankoli namun sudah menjadi realitas yang normal dan biasa-biasa saja. Kenyataan ini menggambarkan masyarakat kita enggan membiasakan diri melakukan pembacaan secara berulang dan menyeluruh serta menelaah secara serius karya sastra yang dibaca.
Sastra pada hakikatnya religius. Selalu ada ruang untuk sastra diantara mahluk dan tuhannya. Kata demi kata dalam karya sastra seperti kitab suci. Butuh penaswiran lebih dalam untuk mengungkap makna terkandungnya.
Proses kreatifnya disebut ibadah. Tak jarang butuh berulang-ulang kepekaan serta ketajaman penghayatan realitas untuk menghasilkan satu karya sastra. Tidak sekadar teks, melainkan ada abstraksi dan nuansa puitis yang tinggi.
Pergeseran nilai juga terjadi pada motif disusunnya karya sastra. Bila dulu sebagai pujasastra. Sastra yang menyanjung dan mengagungkan raja, juga sebagai dharmabakti sang pujangga kepada raja.
Hari ini motif sastra mengarah ke barang komoditi. Ditulis dan disebarluaskan agar mendapat pengakuan dan kekayaan. Tak berkarya tak dapat cuan, tak berkarya tak dapat makan.
Minimal masih kental dengan urusan dapur. Tema sastra apa yang lagi digandrungi? Kapan menulisnya? Target marketnya siapa? Judul apa yang dengan segera menggugah selera pembaca?
Kata penulis pun kini di bagian depannya diberi tambahan kata, menjadi profesi penulis.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Siapa Suruh Jadi Pakar Sastra
Rabu, 17 November 2021 05:44 WIB
Pencarian Isabel
Minggu, 14 November 2021 16:24 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0