Pilihan Bentuk Estetik Sastra Posmoderen
Selasa, 30 November 2021 14:10 WIB
Setelah sastra modern, sastra posmodern semakin semarak. Di Koran Tempo atau beberapa media lain sering kita dapatkan fiksi model itu. Biasanya kaum milenial lebih tertarik dengan mode posmodern ini karena dianggap baru dan sesuai karakternya. Tapi sastra posmodern, meskipun relatif baru di Indonesia, tapi tidak di lanskap sastra dunia, terutama Amerika Serikat. Kalau Amerika Latin realisme magis. Sastra posmodern, terutama dicirikan oleh penggunaan teknik pastiche, metafiksi, mitos,fantasi,intertekstual. Dalam artikel ini, saya mencoba membahas tiga mode dalam sastra posmodern. Semoga bermanfaat.
Pada tahun 1937, Jorge Luis Borges menulis kolom pendek berjudul “William Faulkner, Absalom! Absalom!” Tulisan pendek itu menyinggung tentang pilihan seorang pengarang memilih cara bagaimana mereka menulis. Ada dua jenis penulis yang saya kenal, tulis Borges. Pertama, mereka yang fokus utamanya adalah teknik verbal, dan mereka yang berfokus pada tindakan dan hasrat manusia. Satu mewakili seniman murni yang cenderung ‘Binzantium’ dan satunya lagi mendapat pujian karena kemampuannya mengangkat hal-hal yang manusiawi. Di antara para penulis lain yang disebutkan seperti novelis hebat Josep Conrad, Borges lebih memilih William Faulkner sebagai penulis yang memiliki kombinasi teknik dan isi yang layak dipuji setinggi langit.
Dalam novelnya “Absalom! Absalom! dan Sound and the Fury, Faulkner tidak saja mampu menguraikan masalah manusia yang dihancurkan oleh sebab rasa iri hati, alkolhol, rasa benci, dan juga rasa sepi, tetapi juga kemampuannya secara teknis menguraikan karakternya dengan pelbagai sudut pandang dan suara. Pilihan Borges ini tentu saja berangkat dari pemahaman bahwa dalam sastra, apa yang teknis dan filosofis selalu mendukung isi untuk membawa konsekuensi dari apa yang kita sebut tulisan yang hidup. Sesuatu yang membawa pada kesenangan dalam membaca sekaligus memikirkan nilai-nilai yang ditawarkan.
Dua hal ini, pilihan membangun bentuk secara teknis verbal, atau pilihan membangun isi (bobot rmakna) juga seringkali menjadi perhatian banyak penulis masa kini (baca:posmodern) saat ini dengan ragam kualitasnya. Pada banyak cerpen yang ditulis di pelbagai media massa saat ini, kita seringkali mendapatkan bentuk yang oleh kalangan awam disebut aneh. Aneh tentu saja karena dari judul hingga isinya jauh dari apa yang dipahami sebagian pembaca yang konvensional dan tak terlalu melihat pergerakan sastra modern ke posmodern. Beberapa cerpen yang disebut aneh tersebut banyak kita temui dan ditulis dengan mode metafiksi, fantasi, dan pastiche.
Tiga Mode
William. H. Gass adalah pencetus pertama istilah metafiksi dalam bukunya Fiction and the Figures Life (1970). Metafiksi adalah metode di mana cerita dibangun atas dasar kesadaran bahwa apa yang dibaca merupakan realitas fiksi. Ilusi yang ada di dalam fiksi dialihkan sebagai kesadaran realitas bahwa apa yang tengah dibaca merupakan fiksi semata. Gass menyebut metode ini sebagai kesadaran penulis terhadap medium.
Di Indonesia kita bisa menyebut beberapa cerpen Sungging Raga, Kiki Sulistyo, dan A.S. Laksana sering menggunakan teknik ini. Namun, metafiksi jelas sudah dipratikkan pada beberapa abad lalu dengan intensitas yang rendah. Don Quixote karya Carventes (1605) dan The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentlement karya Laurence Sterne (1759) adalah contoh dari mode metafiksi yang dimaksud Gass.
Namun, jika kita membaca karya John Barth, misalnya Lost in the Funhouse (1968), penggunaan teknis metafiksi menjadi lebih intensif dan terasa mengganggu ilusi fiksi yang ada. Melalui penggunaan tringualasi dengan tiga perspektif: protagonis, narator, dan penulis, pembaca akan sangat merasakan gangguan ilusi itu. Kita terlibat dalam diskusi yang tengah memperkarakan posisi Ambrose sebagai protagonis remaja yang tengah berkembang dan jatuh cinta, dan narator serta penulis yang membahas teknis dan plot dalam cerpen itu. Pada mode ini, pada prinsipnya pembaca sadar bahwa ia tengah membaca fiksi.
Sedangkan dalam mode pastiche, pengarang biasanya menirukan gaya penulis-penulis lain yang sudah ada. Semacam parodi, namun bukan sebagai kritikan, hanya sebagai merayakan karya pengarang lain. Di Indonesia, karya Franz Kafka berjudul “Metamorfis” seringkali dicatut beberapa pengarang cerpen dengan pelbagai judul baru. Pastiche, seperti halnya perangkat lain dalam sastra posmodern menurut Fredic Jameson hanyalah parodi yang hampa makna dan kehilangan kekritisannya. Pastiche semacam gado-gado instan demi memenuhi hasrat citra pop semata. (Linda Hucheon agak berbeda dengan Fredic Jameson tentang ini)
Meskipun demikian, ada jenis pastiche yang banyak dipuji, seperti dalam novel The British Museum Is Falling Down (1965) karya David John Lodge. Dalam novel itu, kita mendapatkan beberapa karya milik James Joyce, Viginia Woolf, dan Franz Kafka menjadi sebuah karya yang unik dan menarik. Cerpen saya berjudul “Gadis Penjaga dan Pria Berjanggut” (Tribun Jabar, 2021) dan “Tiada Tuhan Selain Keinginan” (MI, 2018) juga menggunakan pendekatan intertekstual.
Italo Calvino, mungkin adalah sastrawan posmodern yang paling dipuji oleh John Barth dalam esainya The Literature of Replenishment (1983) dari banyak karya sastra posmodern yang ada. Beberapa karyanya seperti kumpulan cerita pendek Cosmicomics (1965) mengunakan pendekatan fantasi dan mitologi. Salah satu cerpennya dalam Cosmicomics, The Distace of the Moon, misalnya, Calvino membangun imajinasi pembaca melalui gambaran bulan yang hanya berjarak beberapa meter dari permukaan laut, sehingga bisa dipanjat dengan menggunakan tangga. Di Indonesia, kita bisa membaca karya Seno Gumira Ajidarma seperti “Sepotong Senja untuk Pacarku” (Kompas, 1991) dan “Simudistopikoronakra” (Kompas, 2020) menggunakan teknik fantasi seperti Italo Calvino.
Ketiga mode itu tentu saja menjadi semacam pilihan para penulis karena pertimbangan kebutuhan mencari bentuk baru, dan sebagian karena tak sengaja karena kebutuhan tren masa kini. Dua kondisi itu tentu saja akan menghasilkan mutu karya yang berbeda. Satu merancangnya sepenuh hati dengan sebuah kesadaran teks dan makna, dan satu lagi menulis karena ingin menjadi seperti tulisan siapa. Namun, sesungguhnya sastra, dalam bentuk apapun, seperti kata John Barth:
“Karya yang bagus akan tetap bagus dan selalu membawa sikap kritis, bahwa spesimen yang benar-benar indah dalam mode estetika apa pun akan menarik ideologi kritis di belakangnya.” []
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Kalimat Pendek dan Panjang dalam Sastra
Selasa, 18 Juli 2023 12:24 WIB
Setan Rumah B2A
Rabu, 1 Desember 2021 13:40 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 99
99 0
0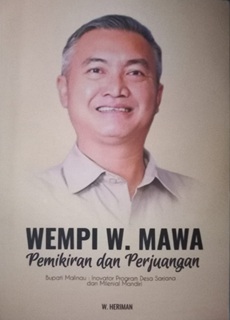



 Berita Pilihan
Berita Pilihan









