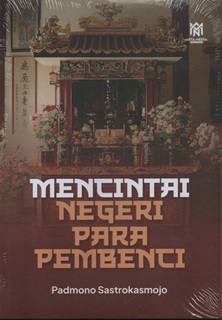Terkait tulisan saya bisa klik pada link https://linktr.ee/firmandads
Perkembangan Sejarah Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan Indonesia
Minggu, 9 April 2023 09:07 WIB
Menulis atau mengkaji kota bisa jadi selama ini kurang diperhatikan karena kurangnya kepercayaan terhadap kekayaan dan kemungkinannya. Padahal sejak abad ke-20 kota-kota di Indonesia telah mengambil banyak kegiatan dari pedesaan. Pergeseran dari desa ke kota terjadi bersamaan dengan perubahan sosial dalam masyarakat.
Awal Kedatangan Para Pendatang ke Jakarta
Seiring kembalinya Pemerintah Republik Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta pada 1949, pertambahan penduduk di Jakarta mengalami kenaikan pesat. Kecenderungan ini berulang mengarah kepada kenaikan jumlah penduduk secara cepat. Angka resmi memperlihatkan berlipat gandanya populasi dari 823.000 jiwa pada 1948 menjadi 1.782.000 jiwa pada 1952.
Angka-angka ini sebenarnya juga melebih-lebihkan tingkat pertumbuhan awal jumlah penduduk kota Jakarta karena batas kota mengalami perubahan pada tahun 1950, Kotapraja Jakarta Raya yang baru telah bertambah luasnya menjadi tiga kali lipat dari batas kota yang lama (sebelumnya). Perluasan wilayah ini adalah tanggapan terhadap pertumbuhan penduduk yang membawa kesadaran bahwa populasi perkotaan telah jauh melewati batas-batas lama kota dan sebagain besar daerah-daerah baru tersebut masih relatif jarang penduduknya.
Sebagian besar populasi masih terkonsentrasi dalam batas kota yang lama. Selain perubahan batas kota, penyebab utama pertumbuhan populasi adalah besarnya migrasi masuk (in-migration) penduduk. Pada tahun 1948 dan 1949, jumlah penduduk Jakarta terus mengalami penambahan yang drastis yaitu 823.356 dan pada tahun 1949 yaitu menjadi 1.340.625. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk ini sebagai akibat dari masuknya arus migrasi pertama yang terbesar dalam periode setelah kemerdekaan.
Pada awal periode tahun 50an menurut Nordholdt, nasionalisme sedang berada di puncak kejayaannya. Hal ini dilihat sebagai sebuah proyek budaya dengan pesan utama, “menjadi Indonesia berarti menjadi moderen.” Di masa itu, modernitas bersinonim dengan nasionalisme. Pembangunan bangsa (nation-building) itu diantaranya terwujud dari diadakannya pembangunan yang didasarkan untuk mendekonstruksikan simbol-simbol warisan kolonial. Imaji-imaji kolonial dihapuskan dari ingatan, untuk kemudian dibangun imaji-imaji baru yang bersifat “nasionalis”. Monumen Van Heutz , Patung Jan Pieterszoon Coen, Patung Dewi Kebenaran di Taman Wilhemnia adalah contoh-contoh diantara monumen peninggalan kolonial yang dihancurkan pada masa itu untuk pembangunan Jakarta sebagai simbol nasionalisme bangsa Indonesia.
Sebagian lain orang datang ke Jakarta karena untuk menghindari kerusuhan di pedesaan yang terus berlanjut pasca awal kemerdekaan bahkan setelah perang dengan pihak Belanda berakhir. Di sejumlah wilayah di Jawa, para pemberontak mencoba melawan wewenang Pemerintah Republik. Di Jawa Barat misalnya, Darul Islam dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap keteraturan dan ketertiban. Angkatan perang pemberontak muslim yang dipipmpin oleh Kartosuwiryo ini berperang demi mewujudkan sebuah Negara Islam dan menentang Republik Indonesia yang dianggap sekuler.
Jakarta sebagai sebuah Masyarakat Campuran
Jakarta atau dulu dikenal sebagai Batavia, sejak berabad-abad ditempati oleh beragam etnis dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Mereka datang, tinggal dan kemudian menetap karena berbagai alasan dan tujuan. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar pada 1949, orang Eropa diberi waktu dua tahun untuk memutuskan apakah ingin menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Mayoritas orang Eropa tersebut memilih menjadi warga negara Belanda, kemudian meninggalkan Indonesia dengan bantuan permerintah Belanda. Rasa takut akan kehilangan status dan pendapatan dalam Republik Indonesia, ditambah insentif finansial dari Belanda sepertinya telah menentukan nasib orang-orang Eropa ini. Pada tahun 1956, jumlah orang Belanda di Jakarta kurang dari 17.000 jiwa. Setelah gerakan anti-Belanda terus menerus diteriakkan oleh pemerintah Indonesia, ditambah penolakan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat, hanya tinggal 530 jiwa orang Belanda di Jakarta pada tahun 1961.
Lalu ada juga warga yang memiliki keturunan Cina diharuskan untuk memilih kewarganegaran ketika terjadi sinisme terhadap warga asing. Etnis non pribumi terbanyak yang tinggal di Jakarta pada 1950-an adalah masih tetap keturunan Cina. Sudah sejak lama mereka merupakan penduduk minoritas terbesar di Jakarta. Menurut sensus tahun 1961, jumlah penduduk keturunan Cina sebesar 294.000 jiwa atau 10,1 persen dari seluruh penduduk Jakarta.
Jumlah yang cukup besar ini dikarenakan seluruh penduduk keturunan Cina di Indonesia tidak lebih dari tiga persen. Di Jakarta sendiri mereka mudah sekali ditemukan di pemukiman lama kota tua Jakarta seperti di daerah Glodok, Pinangsia dan sekitarnya yang merupakan daerah pecinan di Jakarta. Sebagian besar lagi bisa ditemui di Pasar Senen, Pasar Jatinegara, Pasar Tanah Abang dan beberapa daerah pertokoan lainnya yang masih bisa dilihat keberadaannya hingga sekarang. Karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang atau pengusaha yang membuka toko dan usaha maka tidak heran ketika mereka biasa dijumpai di wilayah pertokoan maupun pasar.
Pada saat itu tidak ada kelompok etnis yang mendominasi di Jakarta, sehingga semua harus belajar berkompromi untuk kepentingan hidup bersama. Tjalie Robinson menyebutnya sebagai kebudayaan gado-gado Jakarta, makanan yang dapat dipersiapkan dengan segala macam sayuran dicampur dengan saus kacang pedas. Bagi sejumlah pendatang baru, kelonggaran budaya yang sepertinya tanpa akar di Jakarta nampak tidak dapat dicerna. Namun bagi sebagian besar orang, toleransi ini sepertinya tumbuh dari keyakinan terhadap kemampuan Jakarta untuk menghadapi keberagaman. Ini tentu saja ciri kebudayaan yang penting dalam kehidupan di kota metropolitan. Hubungan penduduk Jakarta antara satu suku dengan suku lainnya relatif cukup rukun.
Konflik kesukuan jarang terjadi di Jakarta meski beragam suku tinggal bersama di kota ini. Sedikit gesekan tentu tidak bisa dihindarkan ketika para pendatang mulai membuat pertahanan diri di kota yang keras ini dengan membuat ikatan dari sesama suku. Ikatan antar suku menguat lantaran para pendatang mesti bertahan hidup karena tidak masuk kedalam angkatan kerja dibidang formal. Banyak dari pendatang ini yang akhirnya harus saling sikut demi sebuah pekerjaan informal seperti pedagang kecil, sopir, buruh musiman, tukang bensin eceran, tukang becak, pemulung dll.
Content Writer
1 Pengikut

Wujudkan Dunia Kerja yang Lebih Manusiawi
1 hari laluBaca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0









 99
99 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan