Ikhwal Penerimaan Kemiskinan Sebagai Kewajaran
Selasa, 3 September 2024 15:22 WIB
Menyelenggarakan kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum yang tidak memberi keyakinan bahwa dengan proses tersebut kerberlangsungan sebuah negara dapat dipertahankan adalah sebuah kekeliruan.
Oleh: Dr. Muhammad Afif, S.H.,M.H.
“Empty are the words of the philosopher who does not heal the suffering of man.” – Epicurus dalam Howard Jones, The Epicurean Tradition (1989)
Sebagai sebuah fenomena, kemiskinan mungkin sudah ada sejak manusia mulai menyejarah di era agrikultural, di masa holosen.
Manusia sebagai pemburu dan peramu boleh jadi hanya mengenal penderitaan (suffering) dan bukan kemiskinan.
Saat manusia mulai tinggal di tempat yang sama dan bercocok tanam, masyarakat mulai terbagi ke dalam berbagai stratum yang mengeksplisitkan perihal memiliki (to have) dan tidak memiliki (to have not).
Kemiskinan mulai menyembul terpisah dari rumpun besar penderitaan.
Kemiskinan saat ini secara hakikat adalah sebuah konsep yang mengambang, oleh karenanya, respons negara terhadap fenomenon ini beragam. Namun demikian, apakah pemerintah sebenarnya bebas bersikap di dalam ambiguitas kemiskinan?
Secara empirik, kemiskinan dapat dilihat sebagai persoalan angka yang riil dan diukur dengan penghasilan yang diterima.
Data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik per Maret 2023 mencatat bahwa untuk dapat dikategorikan miskin, pendapatan seseorang per bulan adalah sekitar 550 ribu rupiah atau kurang.
Apabila dikaitkan dengan pendapatan rumah tangga dengan anggota keluarga sekitar hampir lima orang, pendapatan total untuk masuk kategori miskin berada di kisaran dua setengah juta rupiah.
Bila berpatokan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), maka seseorang yang bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan penghasilan sesuai UMP sekitar dua juta rupiah per bulan dan harus menghidupi empat anggota keluarga lainnya dikategorikan hidup dalam kemiskinan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi bahwa pada tahun 2030 jumlah orang miskin di dunia masih berjumlah 575 juta orang, dengan dampak negatif terbesarnya memengaruhi orang-orang lanjut usia (23,2%).
Angka ini tidak kecil karena bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia sekarang yang berjumlah delapan milyar manusia, prediksi kemiskinan global masih berada di angka tujuh persen.
Masalahnya, angka ini didasarkan pada besaran pendapat per bulan atau per hari.
Yang tidak dicakup oleh pendekatan kuantitatif semacam ini adalah kualitas hidup seseorang yang ada dalam konsep kebahagiaan.
World Happiness Report 2024 (WHR 2024) mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 80, di bawah negara tetangganya Malaysia di urutan 59 untuk enam hal yang sangat esensial, termasuk harapan hidup.
Parameter kebahagiaan dapat dimasukkan ke koridor argumentasi yang sama dengan kemiskinan, bila kita ingin membedah ambiguitasnya.
Risiko terbesar dari ambiguitas kemiskinan pada hakikatnya adalah penerimaan kondisi miskin sebagai sebuah kewajaran yang membahagiakan.
Sikap pasrah menerima dari mereka yang masuk ke dalam kategori miskin mengakar secara budaya dari berbagai aliran pemikiran, dan salah satunya adalah pemikiran Epikurus, seorang pemikir Yunani yang hidup di abad keempat sebelum masehi.
Epikurus adalah seorang pengikut Aristoteles yang memberi penekanan tentang panca indra sebagai sumber pengetahuan.
Sebagai filsuf Helenis (pasca Aristotelian), Epikurus merevisi pemikiran pendahulunya dengan mengatakan bahwa kesenangan (atau istilah lebih tepatnya kebahagiaan) memiliki empat dimensi dari yang paling rendah hingga paling luhur, yaitu fisik-dinamis, fisik-statis, mental-dinamis, dan mental-statis.
Mewajarkan Kemiskinan Ala Epikurean
Menurut Epikurus, untuk mencapai titik pembebasan yang ia sebut ataraksia, seseorang harus berdamai dengan pikirannya.
Epikurus mengatakan dalam ketenangan pikiran yang melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan yang sifatnya jangka pendek adalah inti dari kebahagiaan. Mengejar kesenangan sesaat adalah akar dari penderitaan.
Penstudi pemikiran Epikurus John Sellars dalam The Pocket Epicurean mencatat: “It’s the inner working of our mental lives that ought to be the main focus of our attention, not the superficial physical pleasures that people associate with hedonism today.”
Berpikir untuk sebuah kondisi ideal yang jauh dari jangkauan, seperti berpikir untuk mengalami kepuasan fisik, akan menghasilkan penderitaan.
Sederhananya, kebahagiaan sejati adalah menerima kondisi saat ini, atau dalam bahasa Epikurus, kemampuan untuk menerima kebahagiaan mental-statis.
Tidak ada yang salah dengan sikap mental semacam itu.
Menerima kondisi apa adanya adalah sebuah kedewasaan dan kepuasan rohani tanpa terjebak dalam kesenangan sesaat.
Dalam catatan ensiklopedik Tim O’Keefe berjudul Epicurus, “Everything we do, claims Epicurus, we do for the sake ultimately of gaining pleasure for ourselves”.
Penerimaan kondisi marjinal sekalipun adalah bentuk kesenangan yang paling dalam.
Persoalannya, sikap semacam ini secara makro terkadang dinilai sebagai sebuah kesempatan untuk menunda berbagai pendekatan yang sifatnya terukur untuk memperbaiki kualitas hidup warga negara.
Sebagai contoh, sikap pasrah terhadap tingginya harga bahan pokok dibandingkan dengan negara-negara lain yang sejenis, kualitas infrastruktur yang rendah (misalnya keterbatasan akses jalan dan angkutan umum), atau pendidikan yang terlalu mekanis yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang menuntut kreativitas tinggi dapat dianggap oleh penyelenggara pemerintahan sebagai sebuah kesempatan untuk menunda perbaikan dan pemerataan kualitas hidup.
Dengan kata lain, dalam cara pandang Epikurus, kemiskinan bersifat sangat relatif. Kebahagiaan seseorang untuk makan kenyang sekali sehari dengan tempe dan tahu bacem dapat dilihat sebagai sebuah cara untuk mempertanyakan seberapa akurat angka-angka yang mengukur tingkat kemiskinan hanya berdasarkan pada pendapatan.
Sementara di sisi lain, angka kecukupan gizi seseorang menurut World Health Organization (WHO) untuk jumlah kalori protein adalah optimum 175 gram per orang. Besarnya ketimpangan antara persepsi personal yang berdasarkan sikap penerimaan pasrah dengan perhitungan berbasis keilmuan menunjukkan seberapa besar kesempatan pemerintah untuk menunda peningkatan tingkat pendapatan seseorang yang berakibat pada pola konsumsinya.
Menuju Negara yang Bersikap Epikurean
Semestinya, pola pikir para penyelenggara pemerintahan juga bersifat Epikurean.
Perbaikan hal-hal yang sangat mendasar bagi peningkatan kualitas hidup warga negara perlu dilihat sebagai kebahagiaan jangka panjang.
Berbagai program jangka pendek yang berdampak kecil bagi, misalnya, angka kecukupan gizi masyarakat dipertimbangkan kembali.
Secara sederhana, sikap menerima dan berdamai dengan kondisi sekarang tidak hanya cukup dimiliki oleh warga negara, tetapi juga oleh pemerintah yang tercermin dalam program-program dan kebijakan-kebijakannya.
Kebahagiaan sejati atau ataraksia seseorang dapat ditarik ke tingkat nasional, dan berujung menjadi kebahagiaan sejati sebuah negara.
Kembali ke WHR 2024, keenam kriteria yang menjadi dasar penilaian adalah seberapa suram masa depan negara dilihat oleh warganya, tingkat korupsi, seberapa dermawan orang di suatu negara, seberapa bebas orang bisa memilih jalan hidupnya, baik tidaknya indikator kesehatan secara umum, dan seberapa kuat dukungan negara untuk jaminan sosial.
Parameter ini bisa menjadi dasar untuk mengkritik kebijakan keliru yang dilakukan berbagai negara terhadap pengentasan atau bahkan penghapusan kemiskinan.
Mungkin bagi sebagian orang, menjadi miskin adalah sesuatu yang bisa diterima.
Namun negara wajib menyediakan pilihan hidup yang secara umum lebih baik kepada warganya.
Kita dapat menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan menjadi pelik saat konsep menjadi miskin disandingkan dengan seberapa bahagia pihak yang mengalaminya, terutama berbahagia karena pasrah.
Persoalan semakin kompleks saat masyarakat dibiasakan untuk menerima dalam standar-standar kehidupan di bawah standar global.
Akibatnya, kualitas hidup yang bersifat standar di seluruh dunia serta terukur ditunda pelaksanaannya.
Menautkan jumlah kalori minimum tanpa melihat komposisinya (seperti protein) tidak cukup.
Menyelenggarakan kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum yang tidak memberi keyakinan bahwa dengan proses tersebut kerberlangsungan sebuah negara dapat dipertahankan adalah sebuah kekeliruan.
Menaikkan angka harapan hidup tanpa memberi jaminan daya beli warga negara pasca pensiun tidaklah relevan.
Transparansi semua kegiatan yang diselenggarakan pemerintah bukan untuk semata-mata mengamankan fondasi keuangan sebuah negara, tetapi sebagai bentuk pembuktian kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Menyiapkan lapangan kerja yang tidak sejalan dengan dinamika tuntutan dunia kerja pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah pengangguran.
Dengan kata lain, negara yang mengamankan warganya dari sisi primer terbatas (jumlah pemenuhan minimum kebutuhan pangan, sandang, papan) tanpa melihat parameter kebahagiaan yang lebih luas, akan selalu menjadi negara miskin.
Penulis Indonesiana
1 Pengikut

Ikhwal Penerimaan Kemiskinan Sebagai Kewajaran
Selasa, 3 September 2024 15:22 WIB
Industri Tekstil Indonesia dalam Krisis: Tantangan dan Solusi yang Diperlukan
Sabtu, 6 Juli 2024 11:40 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





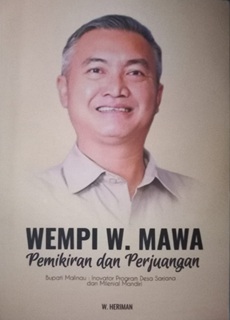

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 99
99 0
0
















