Pidato Politik Kontemporer sebagai Alat Kekuasaan:
Selasa, 27 Mei 2025 09:32 WIB
Bahasa politik tidak pernah netral. Ia menyuarakan pihak tertentu dan, pada saat yang sama, berpotensi membungkam pihak lain.
Oleh: Hasan Mustofa
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa bukan hanya sarana komunikasi—ia adalah alat pembentuk kekuasaan. Pidato politik, yang sering dianggap sebagai seremoni retoris belaka, sejatinya merupakan ladang subur bagi operasi kuasa melalui simbol, narasi, dan framing yang halus tapi efektif.
Michel Foucault pernah mengatakan bahwa kuasa tidak hanya hadir melalui struktur institusional, tetapi juga melalui bahasa yang membentuk kebenaran. Di sinilah pidato politik berperan: menciptakan realitas, membingkai persepsi publik, dan menyusun peta ideologis bangsa.
Bahasa dan Produksi Realitas Politik
Setiap pidato politik adalah upaya menciptakan dunia. Lewat pilihan kata, intonasi, dan susunan logika yang dipaparkan, seorang politisi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi. Frasa seperti “pemulihan ekonomi inklusif”, “transformasi digital nasional”, atau “kita adalah bangsa tangguh” bukan hanya retorika; ia mengandung makna ideologis, membentuk rasa kolektif, dan memberikan legitimasi kepada kekuasaan yang sedang berjalan.
Dalam pidato-pidato Presiden Indonesia, terutama dalam forum resmi seperti Sidang Tahunan MPR, dapat ditemukan pola wacana yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif dan performatif. Bahasa digunakan untuk menyatukan, menenangkan, namun kadang juga untuk menyembunyikan kompleksitas dan konflik yang nyata.
Narasi dan Eksklusi: Siapa yang Bicara, Siapa yang Terwakili
Bahasa politik tidak pernah netral. Ia menyuarakan pihak tertentu dan, pada saat yang sama, berpotensi membungkam pihak lain. Dalam banyak pidato politik kontemporer, terdapat kecenderungan untuk membangun narasi besar tentang “kemajuan”, “persatuan”, atau “stabilitas”—tetapi sering kali tanpa mengikutsertakan suara kelompok marginal seperti petani kecil, masyarakat adat, atau buruh informal.
Misalnya, penggunaan istilah “revolusi industri 4.0” sering diangkat tanpa menjelaskan bagaimana ketimpangan akses teknologi tetap menghantui masyarakat kelas bawah. Narasi besar ini menimbulkan kesan kemajuan universal, padahal yang terjadi bisa jadi adalah pelapisan baru dari ketidaksetaraan.
Retorika Populis dan Pengaruh Emosi
Politik kontemporer juga sarat dengan gaya populis, di mana bahasa digunakan untuk menciptakan kedekatan emosional. Penggunaan bahasa sehari-hari, sapaan akrab, hingga pengulangan frasa seperti “rakyat kecil” atau “kita semua pejuang” menjadi alat membangun simpati. Namun, strategi ini bisa menjadi bentuk manipulasi halus, di mana kedekatan semu menggantikan diskusi substansial tentang kebijakan.
Fenomena ini semakin menonjol di era media sosial, ketika pidato tidak lagi dinilai dari kedalaman isi, melainkan seberapa viral atau menggetarkan. Bahasa politik pun bergeser: dari yang semula bersifat deliberatif menjadi sekadar performatif.
Pentingnya Literasi Wacana dalam Demokrasi
Dalam masyarakat demokratis, publik seharusnya tidak menjadi konsumen pasif dari pidato politik. Diperlukan literasi kritis untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membingkai realitas dan mengarahkan opini.
Kesadaran ini penting agar kita tidak terjebak dalam retorika semu atau dikendalikan oleh narasi tunggal yang meninabobokan. Dengan kemampuan membaca wacana secara kritis, masyarakat bisa membongkar lapisan-lapisan makna dalam pidato politik dan menuntut bentuk komunikasi yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Penutup: Bahasa Adalah Kekuasaan
Pidato politik bukan sekadar kata-kata. Ia adalah manifestasi dari struktur kuasa yang ingin membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan masyarakat. Memahami bahasa politik berarti memahami cara kerja kekuasaan itu sendiri.
Dalam menghadapi tahun-tahun politik yang penuh dengan janji dan jargon, kita dihadapkan pada pilihan: menjadi pendengar pasif atau pembaca aktif. Karena di dalam bahasa, tersembunyi niat, visi, dan sering kali—agenda.
Catatan untuk Redaksi: Artikel ini ditulis sebagai refleksi atas pentingnya studi wacana dalam membaca dinamika politik kontemporer, dan bagaimana publik perlu dilibatkan secara kritis dalam membongkar narasi-narasi kekuasaan yang dikemas dalam pidato politik.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Peran Humaniora dalam Membangun Peradaban
Selasa, 27 Mei 2025 20:44 WIB
Kearifan Lokal dan Perubahan Sosial: Dinamika Nilai Komunal diTengah Globalisasi
Selasa, 27 Mei 2025 09:36 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

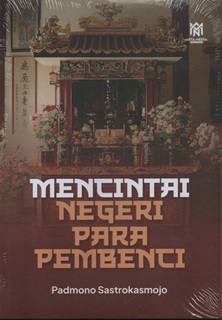







 98
98 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan














