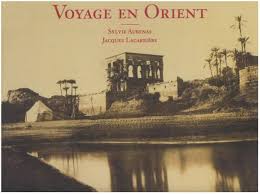SAYA MAHASISWA SEMESTER 6 DARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI MANAJEMEN UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
Target Naik, Etika Turun: Dilema Dunia Kerja Modern
Jumat, 11 Juli 2025 18:24 WIB
Target penjualan, target produksi, target pertumbuhan
penulis:
1.Desy Astriani Saragih merupakan mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Prodi Manajemen, di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2.Helena Sihotang, S.E., M.M merupakan dosen tetap, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Prodi Manajemen, di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
Dunia kerja saat ini semakin cepat, ambisius, dan penuh tekanan. Dalam banyak rapat evaluasi, kata “target” menjadi mantra utama. Target penjualan, target produksi, target pertumbuhan. Semua harus naik. Namun di tengah hiruk-pikuk pencapaian itu, ada yang kian jarang dibahas: nilai-nilai etika. Kenyataannya, banyak pekerja kini merasa terjebak dalam sistem yang lebih mengagungkan hasil dibandingkan proses. Ukuran keberhasilan seringkali hanya berdasarkan angka. Semakin tinggi angka itu, semakin besar pula penghargaannya. Padahal, jika angka-angka itu dihasilkan dari proses yang tidak etis—seperti manipulasi laporan, kompetisi tidak sehat, bahkan menimbulkan terhadap rekan kerja—apakah itu masih bisa disebut keberhasilan?
Menurut laporan Gallup State of the Global Workplace (2023), hampir separuh karyawan di dunia, tepatnya 44%, mengalami stres tinggi akibat pekerjaan. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan berlebihan untuk mencapai target yang dianggap mustahil atau tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam 10 negara besar dengan tingkat stres kerja tertinggi. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak sehat dalam sistem yang sedang kita jalani bersama.Di sektor publik, tekanan ini mendorong munculnya berbagai penyimpangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, rekayasa laporan kegiatan proyek masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran paling umum di banyak instansi pemerintah. Kegiatan yang belum selesai dilaporkan telah rampung, bahkan dalam beberapa kasus, kegiatan fiktif pun “dijustifikasi” dengan dokumen palsu. Salah satu narasumber anonim menyatakan, “Kami sering diminta menyesuaikan data agar terlihat berhasil. Kalau tidak, bisa dianggap tidak kompeten.”
Yang paling terserap adalah ketika orang-orang yang berusaha menjaga integritas justru terpinggirkan. Mereka dianggap terlalu lambat, terlalu kaku, atau terlalu idealis. Akibatnya, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas pelan-pelan kehilangan tempat. Mereka digeser oleh strategi “asal hasil jadi”, yang penting bos senang dan naik grafik. Padahal, menurut studi Harvard Business Review (2022), perusahaan dengan budaya kerja yang sehat, kolaboratif, dan berbasis nilai justru lebih unggul dalam hal produktivitas dan loyalitas karyawan. Produktivitas mereka meningkat hingga 20%, dan tingkat pergantian pegawai lebih rendah. Ini membuktikan bahwa etika bukanlah menghambat kinerja. Justru ia menjadi fondasi dari kinerja yang berkelanjutan.
Namun, mengembalikan etika ke dalam dunia kerja bukanlah hal yang mudah. Diperlukan perubahan paradigma, terutama dari para pemimpin. Budaya kerja adalah cerminan dari pemimpinnya. Jika pemimpin hanya menilai dari hasil akhir tanpa proses, maka budaya instan dan tak etis akan terus hidup. Namun jika pemimpin mencontohkan transparansi, konsistensi, dan penghargaan terhadap proses, maka perlahan nilai-nilai itu akan menular ke seluruh tim.
Pentingnya reformulasi sistem penilaian kinerja. Jangan hanya menilai apakah target tercapai atau tidak. Ukur juga bagaimana target itu tercapai. Apakah kolaboratif? Apakah transparan? Apakah jujur? Apakah menginspirasi orang lain? Penghargaan dan promosi harus diberikan bukan hanya kepada yang “terbaik di angka”, tetapi juga kepada mereka yang menjaga nilai dan membawa energi positif dalam waktu.
Langkah lain yang tak kalah pentingnya adalah membangun budaya “speak-up”—budaya di mana karyawan merasa aman untuk menyampaikan kritik atau melaporkan penyimpangan. Banyak pelanggaran etika yang terus terjadi hanya karena tak ada yang berani bersuara. Perusahaan harus memiliki sistem pelaporan yang independen dan melindungi identitas pelapor. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar slogan, tapi harus diwujudkan dalam mekanisme nyata.
Selain itu, perusahaan dan institusi perlu menyeimbangkan antara pencapaian dan kesejahteraan mental. Budaya kerja “selalu sibuk” dan mengagungkan lembur sudah seharusnya ditinggalkan. Kita membutuhkan sistem yang manusiawi yang memberi ruang untuk istirahat, refleksi, dan pertumbuhan pribadi. Tanpa ini, pekerja akan cepat kelelahan dan lebih rentan melakukan pelanggaran etika karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri.
Pendidikan etika di dunia kerja juga seharusnya menjadi bagian dari pelatihan wajib, bukan pelengkap. Banyak perusahaan fokus pada pelatihan teknis, padahal soft skill seperti integritas, komunikasi jujur, dan kepemimpinan yang etis sangat krusial. Nilai-nilai ini bukan bawaan lahir, tapi bisa dibentuk melalui kebiasaan dan pemahaman.
Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa dunia kerja yang sehat bukan sekadar tempat untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga tempat untuk membangun karakter. Karena pekerjaan bukan hanya soal pencapaian, tapi juga proses menjadi pribadi yang lebih baik. Kita membutuhkan lebih banyak tempat kerja yang menghidupkan semangat berbuat benar, bukan sekadar “berhasil”.
Target boleh naik, bahkan harus. Tapi jangan sampai demi mengejar angka, kita mengorbankan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena jika etika terus-menerus ditekan ke pinggir, maka yang tersisa hanyalah sistem kerja yang bising tapi kosong penuh pencapaian, tapi minim makna.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Target Naik, Etika Turun: Dilema Dunia Kerja Modern
Jumat, 11 Juli 2025 18:24 WIB
Ketika Jasa Tak Dihargai: Potret Buram Perlakuan terhadap Kurir di Indonesia
Jumat, 11 Juli 2025 09:12 WIBArtikel Terpopuler

 0
0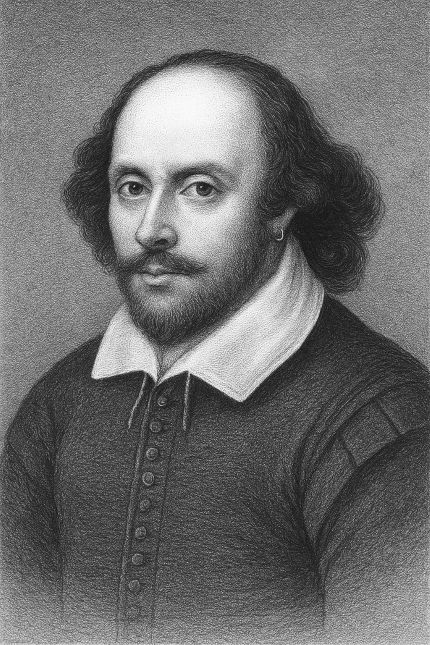


 Berita Pilihan
Berita Pilihan






 99
99 0
0