Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Pemberhentian 57 Pegawai KPK: Retaknya Nurani Hukum dan Akal Sehat Demokrasi
2 jam lalu
Pemberhentian 57 pegawai KPK melalui TWK mencerminkan pelanggaran HAM, maladministrasi, dan upaya sistematis melemahkan KPK.
***
Kasus pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukan hanya persoalan administratif. Hal ini adalah bentuk kemunduran moral dan demokrasi yang terang-benderang. Ketika negara menggunakan mekanisme birokrasi untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas, maka hukum telah berubah fungsi dari alat keadilan menjadi alat kekuasaan.
TWK sejatinya dirancang sebagai sarana alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun dalam praktiknya, TWK menjelma menjadi ajang seleksi ideologis yang sarat muatan politis. Dari ratusan pegawai yang mengikuti, 57 orang dinyatakan tidak lolos dan mayoritas di antaranya merupakan penyelidik dan penyidik senior yang tengah menangani kasus besar, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Di sinilah kejanggalan mulai tampak. Mereka yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru dianggap tidak cukup pancasilais. Padahal, mereka telah membuktikan loyalitasnya pada konstitusi dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika ukuran kebangsaan ditentukan oleh selembar hasil tes yang tidak transparan, maka nasionalisme telah direduksi menjadi alat ukur kesetiaan pada penguasa, bukan pada kebenaran.
Keputusan untuk memberhentikan mereka menandai pergeseran nilai dalam tubuh KPK. Lembaga yang dahulu independen kini tunduk di bawah kekuasaan eksekutif. Sejak revisi undang-undang KPK tahun 2019, lembaga ini kehilangan otonomi dan dikontrol ketat oleh pemerintah. TWK menjadi salah satu konsekuensi nyata dari perubahan itu dan 57 pegawai yang didepak adalah korban pertamanya.
Pelanggaran HAM dan Maladministrasi: Dua Luka dalam Satu Keputusan
Dua lembaga negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia, telah melakukan investigasi mendalam atas proses TWK. Hasilnya jelas pelanggaran hak asasi manusia dan maladministrasi terjadi bersamaan dalam satu kebijakan.
Komnas HAM menyatakan bahwa TWK telah melanggar hak atas keadilan, hak untuk bekerja, dan hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum. Proses seleksi yang digunakan tidak menjunjung asas nondiskriminatif karena banyak pertanyaan yang menyinggung ranah pribadi dan keyakinan seseorang. Beberapa peserta bahkan mengaku mendapatkan pertanyaan terkait pandangan politik dan praktik ibadah, yang jelas tidak relevan dengan tugas seorang pegawai KPK. Ini bukan lagi tes wawasan, melainkan penghakiman moral.
Sementara itu, Ombudsman menemukan bahwa TWK sarat dengan unsur maladministrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai kriteria kelulusan, tidak ada mekanisme banding bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos, dan tidak ada transparansi hasil tes. Pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam proses tersebut.
Kedua lembaga negara itu telah mengeluarkan rekomendasi resmi agar pimpinan KPK memperbaiki keputusan dan memulihkan hak 57 pegawai. Namun, hingga kini rekomendasi tersebut diabaikan. Ketiadaan tindak lanjut dari institusi negara terhadap rekomendasi lembaga independen menunjukkan betapa lemahnya komitmen pemerintah terhadap prinsip rule of law. Negara seakan menutup mata terhadap fakta bahwa keadilan sedang dilanggar atas nama prosedur.
Pelanggaran HAM dan maladministrasi ini bukanlah kesalahan teknis, melainkan kesalahan struktural yang lahir dari kehendak politik. Proses TWK menjadi cermin bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi hukum dan administrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Di sinilah letak bahayanya, ketika hukum menjadi instrumen politik, maka keadilan berubah menjadi alat pembenaran.
Upaya Sistematis Melemahkan KPK dan Krisis Kepercayaan Publik
Kasus ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas pelemahan sistematis terhadap KPK yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Revisi undang-undang tahun 2019 menjadi titik balik yang mengubah karakter lembaga ini. KPK yang dahulu berdiri sebagai lembaga independen kini berada di bawah kendali pemerintah. Wewenang penyadapan, penuntutan, hingga rekrutmen pegawai kini harus melalui mekanisme birokrasi negara.
Dalam konteks ini, pemberhentian 57 pegawai KPK dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mensterilkan lembaga dari figur-figur kritis. Banyak di antara pegawai yang dipecat dikenal vokal dalam menentang kebijakan internal yang dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Ada di antara mereka yang menangani kasus besar, termasuk korupsi di kementerian, lembaga hukum, dan BUMN strategis. Tidak mengherankan jika publik menilai bahwa TWK hanyalah dalih administratif untuk menyingkirkan mereka yang tidak bisa dikendalikan.
Akibatnya, kepercayaan publik terhadap KPK merosot tajam. Lembaga yang dulu dianggap simbol integritas kini dipandang sebagai alat politik yang kehilangan taring. Survei berbagai lembaga menunjukkan tren menurunnya persepsi publik terhadap efektivitas KPK dalam menegakkan keadilan. Dalam situasi ini, pelemahan KPK bukan hanya masalah kelembagaan, tetapi juga ancaman terhadap demokrasi.
Ketika lembaga pengawas kehilangan kepercayaan rakyat, maka tidak ada lagi yang mampu mengimbangi kekuasaan. Hukum kehilangan daya korektifnya, dan keadilan berubah menjadi formalitas. Kasus 57 pegawai KPK menunjukkan bahwa pelemahan terhadap lembaga antikorupsi tidak selalu dilakukan dengan kekerasan; ia bisa dilakukan dengan kebijakan yang tampak legal, tapi sejatinya tidak bermoral.
Kasus 57 pegawai KPK adalah cermin buram dari wajah penegakan hukum di Indonesia. Ketika mereka yang berintegritas disingkirkan atas dasar tes yang tidak jelas, maka yang sesungguhnya diuji bukanlah wawasan kebangsaan, melainkan moralitas penguasa. Komnas HAM telah berbicara, Ombudsman telah menegur, tetapi suara nurani itu dibiarkan tenggelam oleh kepentingan politik.
Pelemahan KPK bukan hanya ancaman bagi lembaga itu sendiri, melainkan ancaman bagi seluruh sistem keadilan. Sebab tanpa lembaga independen yang berani melawan korupsi, negara akan kembali dikuasai oleh para pemangsa kekuasaan. Sudah saatnya publik bersuara lebih keras—karena diam dalam ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 96
96 0
0
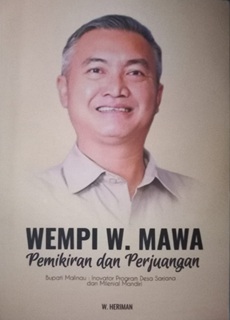


 Berita Pilihan
Berita Pilihan









