Sejarah Uang
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Dunia ini telah dijarah oleh uang, yang tidak berfungsi sebagai alat tukar yang efektif dalam kendali rasionalitas manusia, tapi sebaliknya telah mengendalikan rasionalitas manusia. Uang menjadi pengendali kehidupan, tanpa dapat ditentang.
Konon, setelah praktik barter dalam kehidupan tradisional dianggap tidak efektif, disebabkan sering tumpang-tindihnya nilai komoditas yang diinginkan oleh kedua pihak yang bertransaksi, maka di berbagai willayah dikembangkan media tukar yang bertujuan sebagai standarisasi nilai, hingga akhirnya dikenallah media transaksi berbentuk uang sebagai yang paling efektif (www.wikipedia.org). Demikian pengetahuan tentang uang yang dipopulerkan oleh dunia modern, yang konon didasarkan pada rasionalitas manusia. Namun, tulisan ini bukan ditujukan untuk menelusuri sejarah uang dari berbagai kajian ilmiah, tetapi lebih ditujukan sebagai refleksi terhadap pengalaman penulis dalam mengenal uang, yang nampak membingungkan, semakin tidak rasional; uang yang menyejarah dan menjarah kesadaran.
Dahulu, dalam ingatan penulis, anak kecil tidak perlu memegang uang; kalau perlu sesuatu, tinggal bilang pada orang tua yang menentukan apakah boleh dibeli atau tidak; atau lebih tepatnya, menunggu diberi uang karena orang tua yang menentukan kebutuhan anak kecil. Pertama kali aku memegang uang adalah ketika bersekolah di madrasah ibtidaiyah (setingkat SD): sejak kelas satu, setiap berangkat sekolah, Ibu memberiku 50 rupiah untuk jajan empat kerupuk dan sambal pada jam istirahat; setelah kelas 4, uang jajanku ditambah menjadi 100 rupiah yang juga seharga empat kerupuk dan sambal; setelah bersekolah di madrasah tsanawiyah (setingkat SMP), aku jarang jajan, tapi biasanya aku membawa 500 rupiah yang masih saja seharga empat kerupuk dan sambal. Aku pun heran, kenapa empat kerupuk itu semakin meningkat nilai pertukarannya; mungkin kupikir perjalanan kehidupan ini memang terus berkembang, tidak perlu dipertanyakan, hanya perlu diikuti alurnya. Maklum, begitulah seorang anak kecil yang “tidak rasional”; terlalu banyak yang tidak diketahui, sehingga lebih mudah mengikuti arus kehidupan saja.
Selain uang jajan, yang kuketahui tentang fungsi uang saat itu adalah sebagai bayaran sekolah. Kepala sekolah sering menagih bayaran sekolah, tapi aku tidak perlu bingung, toh Ibu pasti memberikannya. Bayaran sekolah ini memberikan pehamanan tersendiri: semakin tinggi jenjang pendidikan, dibutuhkan pula bayaran yang lebih mahal. Seperti halnya barang dagangan, pencapaian pengetahuan pun semakin mahal. Namun, itu tidak masalah, karena memang “dibutuhkan” dan “diimpikan” oleh orang tuaku bagi anak-anaknya. Aku pun membawa impian itu: menempuh jenjang pendidikan tinggi, tanpa menghiraukan sejauh mana bayaran yang mampu ditanggung.
Setelah lulus dari sebuah pesantren modern, berdasarkan aturan pesantren itu, aku harus mengabdikan diri sebagai pengajar di sana; pengalaman pertamaku mendapatkan uang, tanpa terencana. Setiap bulan, aku digaji 35 ribu plus perlengkapan mandi dan cuci. Lumayan buat ditabung, toh asrama dan makan juga ditanggung oleh pesantren. Tugasku hanya belajar dan mengajar, tidak perlu ribet memikirkan persoalan keuangan. Mengikuti alur, sebagaimana yang selalu kulakukan sejak kecil.
Namun, selama pengabdian di pesantren, impian kecilku muncul: rasanya tidak cukup hanya belajar keagamaan. Aku perlu memperluas wawasan. Tekadku untuk keluar dari lingkungan pesantren semakin menguat setelah berjumpa dengan teman-teman yang sedang melanjutkan studi ke luar wilayah. Mereka membicarakan berbagai persoalan sosial yang tidak kuketahui. Kesadaran baru tumbuh: begitu sempit wawasanku, jauh tertinggal dari yang lain. Untuk memperluas wawasan, aku harus melanjutkan studi ke luar kota. Dan, melalui berbagai pertimbangan, tujuan studiku adalah Jakarta sebagai pusat beragam macam aktivitas dan sirkulasi wawasan. Seorang teman berkata, “Di Jakarta, kau bisa kuliah sambil bekerja untuk membiayai kehidupanmu.” Tekadku pun bertambah bulat: berpetualang untuk menambah wawasan seraya membiayai hidup sendiri, tanpa mengetahui seperti apa dinamika Jakarta. Sosiologi kuanggap paling tepat sebagai program studi yang dapat memperluas wawasanku.
“Aku” yang mengikuti arus pun berubah menjadi “aku” yang bermain dengan arus; awal penggunaan rasionalitas terbatas. Namun, arus itu terlalu kencang, tidak tertebak, di luar pemahamanku. Semester pertama kulalui tanpa menghasilkan uang; semua biaya hidupku ditanggung orang tua; melenceng dari tekadku untuk mandiri. Di semester dua, ada tawaran untuk mengajar privat ngaji. Apa boleh buat, itu satu-satunya cara untuk mendapat bayaran. Terasa aneh, sebelum ke Jakarta aku menjadi pengajar gramatika bahasa arab tingkat aliyah (setingkat SMA), tapi masa awal di Jakarta justru mengajar bacaan huruf hijaiyyah bagi anak TK dengan bayaran dua ratus ribu per bulan. Namun, mana cukup; bukan hanya karena biaya makan dan kontrakan semakin tinggi, tetapi kebutuhan pun bertambah banyak: aku butuh beli buku, pakaian, HP, laptop, motor dan sebagainya. Semua itu kubutuhkan supaya tidaktenggelam dalam arus Jakarta. Sehingga aku sering bergonta-ganti beragam macam pekerjaan sampingan berbentuk survey, terjemah, layout, editing, tulisan dan sebagainya, baik yang legal maupun yang kurang legal—untuk tidak menyebutnya illegal. Menjual jasa, begitulah profesiku, yang dibutuhkan oleh orang lain, untuk membuatku survive, sesuai dengan tuntutan dunia dan dinamika modern (Li 2014).
Kebutuhan atas uang telah menggeser kesadaranku. Upaya memperoleh uang demi menopang pengembangan wawasan telah lenyap. Yang terjadi justru sebaliknya, “aku” yang mengembangkan wawasan untuk memudahkan memperoleh uang. Sehingga, semua kemampuan, keterampilan, pengetahuan, waktu dan tenaga yang kumiliki terus diarahkan dan dikembangkan untuk mengamankan dan mempermudah akses terhadap sirkulasi uang, sebagai penopang jalan hidupku. Terlebih, kesuksesan butuh biaya mahal. Segalanya dari dan demi uang, yang tak pernah cukup, selalu berkembang biak dalam pikiran dan realita. Ini dinamika manusia modern; yang kualami juga dialami teman-temanku. Dunia ini telah dijarah oleh uang, yang tidak berfungsi sebagai alat tukar yang efektif dalam kendali rasionalitas manusia, tapi sebaliknya telah mengendalikan rasionalitas manusia. Uang menjadi pengendali kehidupan, tanpa dapat ditentang.
Beruntung, aku cukup mampu membaca arus; mengembangkan keahlian yang dibutuhkan orang lain. Dan, yang lebih penting untuk mengembangkan peran dalam dinamika ekonomi, diperlukan keterampilan kewiraswastaan, sebuah keterampilan untuk menyulap yang awalnya dianggap sepele menjadi penting dan dibutuhkan orang lain. Memang manusia modern mengejar kualitas, namun kualitas merupakan perpaduan antara citra dan kegunaan. Tidak hanya citra, kegunaan pun dapat diciptakan oleh wiraswasta profesional. Apa pun dapat dijadikan uang, sebagaimana uang dapat menjadi apa pun. Banyak manusia modern menyadari itu, mengembangkan, dan berlomba-lomba menjadi wiraswasta profesional, demi memudahkan akses terhadap uang, membangun kemakmuran, dan mengejar kesuksesan. Berbagai kontestasi kewiraswastaan itulah yang mewarnai dinamika kehidupan modern (Tsing 2005).
Namun, tidak semua menjadi pemenang; hanya sebagian kecil orang kaya yang berhasil menguasai dan memelihara sirkulasi uang atas nama pengejaran kesuksesan, sementara sebagian besar lainnya tersingkir menjadi pengangguran tanpa uang, tanpa modal yang dapat dikembangkan. Aku pun hanya mampu menyelinap memanfaatkan celah sirkulasi uang, yang rentan tertutup dan terpaksa mencari celah lainnya. Sirkulasi uang mengambil peran berbeda bagi beragam aktor dengan latar yang berbeda, misalnya berbentuk monopoli, kolaborasi, persaingan, perebutan, penyingkiran, dan sebagainya. Begitu pula fungsi uang bermutasi dalam kesadaran dengan caranya yang unik, misalnya sebagai sarana mencukupi makan sehari-hari, sarana bersosialisasi, sarana mengejar kesuksesan, sarana membangun kehidupan, sarana mengembangkan gaya hidup, sarana memamerkan kemewahan, dan sebagainya. Uang telah mengendalikan segalanya, sementara “aku” hanya menggeser kesadaran tanpa memiliki kuasa mengubah arus sejarah; sejak kecil hingga saat ini, “aku” hanya mengikuti dan membangun kesadaran atas tuntutan arus sejarah di sekitarku. Begitulah dinamika budaya modern terbentuk: rasionalitas yang menyejarah dan dijarah oleh uang.
Pustaka:
Li, Tania Murray. 2014. Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. London: Duke University Press.
Tsing, Anna. 2005. Friction: an Ethnography of Global Connection. Princeton: Princeton University Press.
Sumber foto: www.teropongbisnis.com
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Definisi Optimisme: Seri Motivasi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Sejarah Uang
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
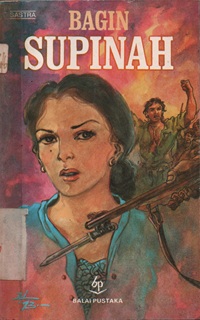






 99
99 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan













