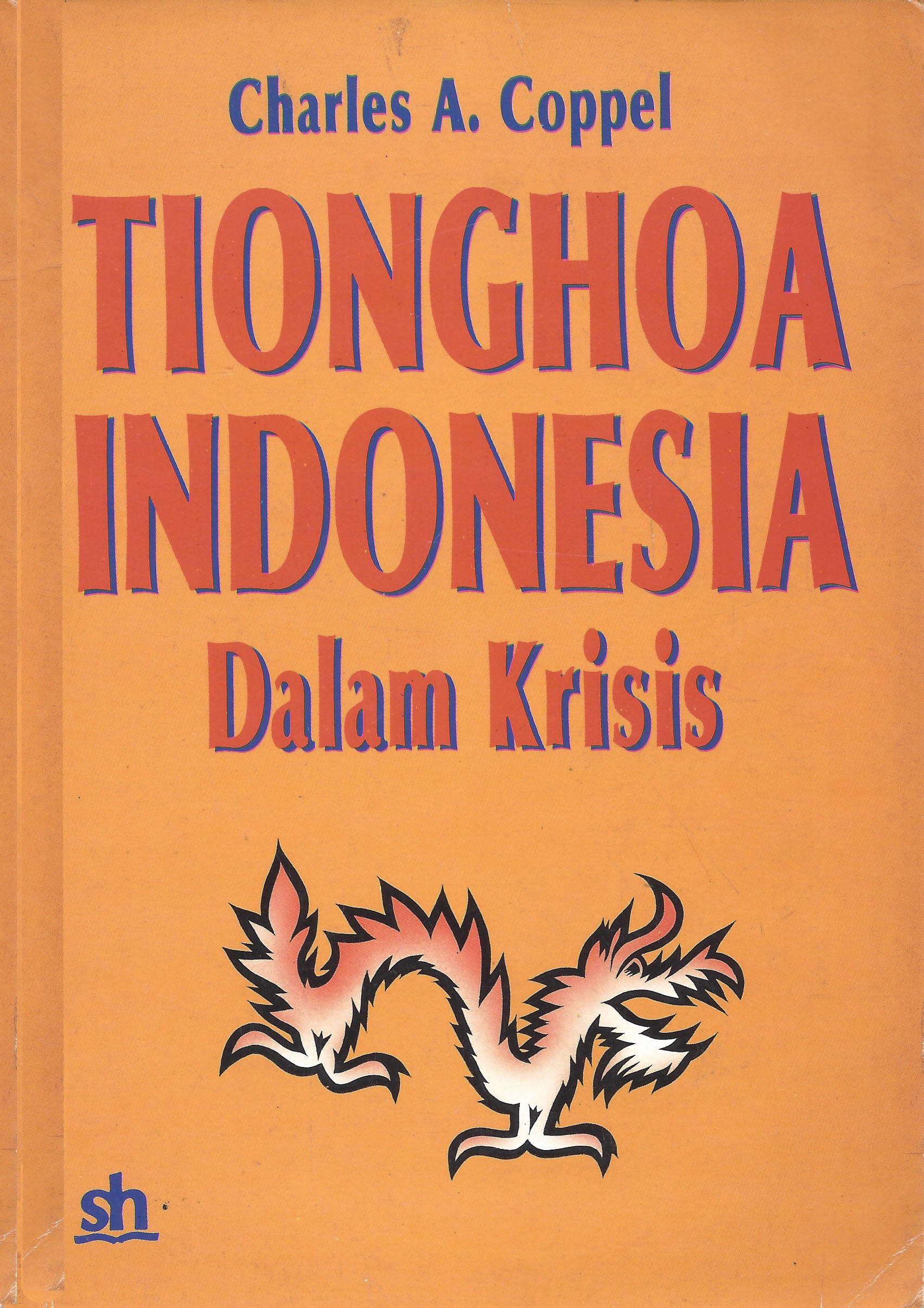Judul: Tionghoa Indonesia Dalam Krisis
Penulis: Charles A. Coppel
Tahun Terbit: 1994
Penerbit: Pustaka Sinar Harapan
Tebal: 360
ISBN: 979-416-177-2
Siapa sesungguhnya Tionghoa Indonesia selalu menjadi bahasan yang menarik. Berbagai peneliti, pemerhati dan di kalangan Tionghoa sendiri pendapatnya berbeda-beda. Beragamnya asal-usul, pandangan politik dan perilaku sosial Tionghoa Indonesia menjadi penyebab sulitnya mendefinisikan siapa mereka. Coppel (hal. 26) mendefinisikan Tinghoa Indonesia sebagai orang keturunan Tionghoa yang berfungsi sebagai warga atau berpihak pada masyarakat Tionghoa atau yang dianggap sebagai orang Tionghoa oleh orang Indonesia pribumi (paling tidak dalam beberapa keadaan) dan mendapatkan perlakuan tertentu sebagai akibatnya. Definisi ini setidaknya membantu kita untuk memahami cara pandang Coppel dalam menguraikan pendapatnya tentang posisi Tionghoa di Indonesia.
Coppel menguraikan bahwa dominasi ekonomi orang Tionghoa dan pendapat bahwa orang Tionghoa tidak mau masuk Islam karena tidak mau berkorban nikmatnya makan babi tidaklah didasarkan kepada sebuah penelitian yang baik. Coppel mengemukakan bahwa orang Tionghoa terlibat dalam perdagangan dan industry tidaklah berarti bahwa sebagian terbesar dari mereka yang bekerja di bidang ini adalah orang Tiongha. Dalam pengertian mutlak, orang Indonesia di bidang pekerjaan tersebut jumlahnya jauh melebihi orang Tionghoa (hal. 47). Argumen bantahan Coppel tentang Tionghoa yang tidak mau masuk Islam dikemukakan dengan menyampaikan fakta bahwa pendatang Tionghoa di abad-abad awal kebanyakan beragama Islam (hal. 35). Coppel juga menyitir hasil penelitian Mely Giok-lan Tan di Sukabumi yang menunjukkan bahwa orang Tionghoa sedikit sekali makan babi karena lingkungannya mengharamkan babi (hal. 36). Argumen lain adalah orang Tionghoa bisa beralkulturasi dengan orang Jawa yang Islamnya kebanyakan abangan (37). Namun Coppel juga menyampaikan bahwa ada faktor-faktor penghalang dari dalam masyarakat Tionghoa sendiri yang menyebabkan akulturasi ini mengalami kegagalan (hal. 37). Pendapat Coppel semakin menguatkan bahwa prasangkalah yang menyebabkan Tionghoa belum diterima secara utuh sebagai Bangsa Indonesia. Prasangka tersebut berasal dari dua pihak. Di pihak orang-orang Tionghoa sendiri dan prasangka di pihak “pribumi”.
Dua faktor di atas, yaitu beragamnya Tionghoa di Indonesia dan prasangka yang sangat kuat, serta tidak adanya kebijakan yang holistic dalam memecahkan masalah Tionghoa menjadi penyebab belum utuhnya warga Tionghoa diterima sebagai Bangsa Indonesia secara utuh. Coppel menunjukkan bahwa kebijakan negara sejak dari jaman Hindia Belanda dan kemudian Orde Lama selalu bersifat reaksioner dan ad hoc. Kebijakan penyelesaian dwi kewarganegaraan (hal. 80) yang terkatung-katung, kebijakan diskriminasi Assaat (hal. 81), kebijakan pelarangan bisnis di pedesaan (hal 82) adalah beberapa contoh kebijakan reaktif dan ad hoc untuk mengangani masalah Tionghoa di Indonesia menjelang era Orde Baru. Baru pada awal Orde Baru ada upaya yang lebih menyeluruh dalam memecahkan persoalan Tionghoa di Indonesia (hal. 60).
Salah satu contoh beragamnya orang Tionghoa adalah dalam hal pandangan politik. Di awal kemerdekaan setidaknya ada tiga kelompok pandangan politik orang Tionghoa. Pertama adalah mereka yang mendukung penuh NKRI, kedua adalah yang berupaya mempertahankan sebagai warga negara Belanda dan yang ketiga adalah yang berorientasi tetap sebagai warga negara Tiongkok. Bagi mereka yang mendukung NKRI-pun terpecah menjadi mereka yang memperjuangkan integrasi, dimana warga Tionghoa harus diserap menjadi warga negara Indonesia dengan budayanya dan kelompok yang menganjurkan asimilasi. Kedua kelompok pendukung NKRI ini tercermin dengan organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) dan Lembaga Pembida Kesatuan Bangsa (LPKB). Baperki adalah organisasi yang memperjuangkan integrasi masyarakat Tionghoa ke dalam Bangsa Indonesia, sedangkan LPKB adalah organisasi yang mengupayakan asimilasi.
Di era awal tahun 1950-an dan masa Demokrasi Terpimpin, partisipasi politik warga Tionghoa sangatlah besar. Keberagaman arah politik warga Tionghoa ini menyebabkan partisipasi politik bukan menjadi sarana untuk penyelesaian masalah Tionghoa, melainkan justru menjadi penyebab semakin tingginya pandangan rasial anti Tionghoa. Pengalaman persaingan Baperki dan LPKB menjadi dasar bagi Coppel untuk tidak setuju dengan pendapat Lea Williams yang mengatakan bahwa masalah minoritas Tionghoa di Asia Tenggara dapat dipecahkan dengan mengikutsertakan mereka dalam pemerintahan dan politik (hal. 9). Setidaknya dalam kasus Indonesia, pendapat Lea Williams ini tidak cocok.
Di akhir pemerintahan Sukarno dan dilanjutkan di awal Pemerintah Orde Baru upaya memecahkan persoalan Tionghoa dilakukan dengan lebih holistic, yaitu dengan memformalkan kewarganegaraan mereka. Meski upaya untuk menerima warga Tionghoa ini secara formal telah diupayakan, namun hasilnya masih belum juga memuaskan. Prasangka masih sangat mewarnai hubungan Tionghoa dengan warga negara lainya di Indonesia. Integrasi, asimilasi dan partisipasi politik yang secara teoritis bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi masalah Cina perantauan, ternyata di era Orde Baru justru menjadi penyebab warga Tionghoa mengalami krisis.
Prasangka menyebabkan orang Tionghoa dengan mudah dijadikan menjadi kambing hitam dalam konflik politik. Dalam kasus G 30 S, dimana pada awal Oktober 1965 situasi tidak terlalu jelas, sementara persaingan antara PKI dan Angakat Darat begitu hebat, orang Tionghoa menjadi sasaran kerusuhan. Orang Tionghoa cocok sekali untuk keperluan ini. Mereka dengan mudah dapat dipercaya sebagai wakil ancaman komunis, kolone kelima dan penyabot ekonomi. Lagi pula ada keuntungn tambahan bahwa mereka merupakan sasaran yang relative tidak punya pertahanan (hal. 132). Dalam kasus ini jelas sekali bahwa prasangka menjadi faktor utama pemicu kerusuhan anti Cina.
Kerusuhan anti Cina sebagai ikutan peristiwa G 30 S menyebabkan pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah Tionghoa. Pada tahun 1967 dibentuk komisi negara yang bertugas memberi rekomendasi kepada presidium kabinet dalam memecahkan masalah Tionghoa. Komisi ini merekomendasikan pembentukan dua badan di tingkat presidium cabinet yang bertugas untuk melaksanakan semua kebijakan pemerintah mengenai “masalah Tionghoa”. Satu badan berbentuk lembaga khusus yang menangani penelitian dan pengembangan, dan satu badan lagi yang bertugas untuk mengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi (hal. 249). Komisi ini juga tidak merekomendasikan pengusiran 3,5 juta warga Tionghoa karena mereka memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia (hal. 249). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan di awal era Orde Baru tentang masalah Tionghoa masih sangat diwarnai dengan urusan ekonomi.
Di era Orde Baru, upaya untuk asimilasi masyarakat Tionghoa lebih menonjol. Anjuran untuk berganti nama, pelarangan budaya Tionghoa di muka umum, pelarangan surat kabar berbahasa Cina adalah kebijakan-kebijakan Orde Baru yang mendorong asimilasi. Di sisi ekonomi, Orde Baru memberi akomodasi yang sangat besar kepada warga Tionghoa. Coppel secara jelas mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru telah memberikan kepada pengusaha Tionghoa apa yang mungkin sekali adalah zaman keemasan mereka (hal. 290).
Meskipun permasalahan formal kewarganegaraan warga Tionghoa sudah bisa diselesaikan pada masa Orde Baru, namun masalah Tionghoa belum sepenuhnya selesai. Akomodasi berlebihan kepada para pengusaha Tionghoa di era Orde Baru justru membuat prasangka anti Cina kembali marak.
Buku yang ditulis berdasarkan thesis Coppel tahun 1975 ini memang hanya memotret masalah Tionghoa pada era awal kemerdekaan sampai dengan masa awal Orde Baru. Coppel berkesimpulan bahwa masalah Tionghoa belumlah selesai. Sebagai minoritas etnis yang kecil, golongan Tionghoa Indonesia mempunyai sedikit pilihan kecuali berusaha mencapai kesepakatan dengan pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi selama prasangka anti Tionghoa dan kepentingan yang bertentangan terus ada, maka terdapat dilemma abadi bahwa suatu identifikasi yang terlalu besar dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada suatu saat dapat mendatangkan malapetaka bagi minoritas itu secara keseluruhan kalau kekuatan-kekuatan itu dijatuhkan (hal. 324). Hal ini terbukti di akhir era Orde Baru, sekali lagi masyarakat Tionghoa menjadi korban.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.