Melipir ke Edensor
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Edensor adalah desa kecil di Derbyshire, Inggris, merupakan destinasi impian para pembaca novel tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
Di bawah gerimis senja dalam suhu 7 derajat yang menggigit, saya berdiri sendirian di tepi jalan sunyi, menanti bus. Petang itu tinggal dua trayek bus ke kota Sheffield, yaitu bus pukul 17.49 dan 18.03. Jika saya tak setia berdiri di halte tanpa atap ini, hanya berupa tiang dengan papan kecil berisi jadwal bus, bisa-bisa terlewat dan harus bermalam entah di mana. Tak ada hostel di sini, hanya ada cottage yang tarifnya tidak masuk dalam budget backpacker berkantong rupiah seperti saya.
Desa ini sungguh sunyi, tapi juga sangat cantik. Di hadapan saya membentang padang rumput hijau dengan pohon-pohon yang daunnya masih malu-malu bersemi, meski sudah memasuki musim semi pertengahan bulan April. Di balik hamparan bukit hijau dan pepohonan itu, tersembunyi rumah bangsawan Inggris, Duke of Devonshire. Itulah Chatsworth House, salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Inggris. Rumah di tepi sungai Derwent yang dibangun pada abad 15 itu mengundang banyak pengunjung karena keindahan tempatnya. Rumah itu juga pernah digunakan untuk syuting film Pride and Prejudice (2005), yang diangkat dari novel klasik dengan judul sama karya Jane Austen.
Tapi, langkah kaki saya tak terayun ke sana menyusuri pedestrian yang meliuk di punggung bukit hijau. Meski saya begitu ingin. Hanya 15 menitan berjalan, tapi saya juga harus membuat pilihan. Dalam keterbatasan waktu, saya memilih menjelajahi desa kecil di seberangnya, yang bukan merupakan destinasi wisata lokal, tapi menjadi impian para pembaca novel Andrea Hirata. Ya, itulah desa Edensor (dibaca Ensor).
Gara-gara Andrea Hirata, desa mungil di kawasan Derbyshire yang semula sama sekali nggak pernah didengar oleh telinga orang Indonesia, mendadak menjadi destinasi impian para pembaca novel tetralogi Laskar Pelangi. Setelah mengunjungi Belitong tak ada salahnya punya mimpi napak tilas jejak Andrea di Edensor kan?
Padahal Andrea nyaris tak banyak bercerita tentang Edensor itu sendiri. Tak ada deskripsi yang detil mengenai di mana persisnya letak Edensor. Hanya dikisahkan, Si Ikal, tokoh dalam novel tersebut, harus menemui profesornya yang tinggal di pinggiran Inggris. Dalam perjalanannya dengan bus dari Sheffield, Ikal mengalami de javu melihat keindahan sebuah desa yang membawanya terbang ke masa lalu. Gambaran desa yang pernah dibacanya dalam sebuah buku dan hidup dalam khayalannya selama belasan tahun. Lalu ia turun dari bus dan bertanya pada seorang nenek yang ditemuinya di jalan, ”Madam, would you please tell me the name of this place?” Nenek itu menjawabnya, “Sure lof, it’s Edensor….” Novel berakhir. Sekian, the end. Edensor ditulis hanya dua kali dalam novelnya, sebagai judul dan penutup. (Tapi semoga saya yang kurang teliti membacanya).
Ajaibnya, setelah nama Andrea Hirata makin melejit, setelah Belitong diserbu turis domestik, giliran Edensor diburu pembacanya. Cerita dan foto-foto desa Edensor mulai bermunculan di blog dan sosmed penggemarnya. Dari manakah mereka bisa menemukan Edensor, sementara di novelnya nyaris tak ada gambaran detil mengenai Edensor?
Di era internet, tidak sulit menemukan tempat di ujung dunia manapun. Tinggal ketik sederet kata di mesin pencari Google dan kita akan dengan mudah menemukannya. Kebetulan Edensor bukan nama rekaan, tapi nama desa yang nyata ada di wilayah Derbyshire, nggak jauh-jauh amat dari Sheffield, tempat Andrea menuntut ilmu. Selain itu sampul novelnya (cetakan pertama) juga menampilkan gambar gereja St. Peter yang menjadi landmark desa Edensor.
Memang sih, pembaca Andrea yang mengunjungi Edensor masih bisa dihitung jari, nggak sederas arus turis domestik yang memadati Belitong. Mayoritas dari mereka pun mahasiswa yang berkesempatan mendapat beasiswa studi di Inggris. Atau warga Indonesia yang tinggal di Eropa dan negara-negara lain yang lebih dekat penerbangannya daripada langsung dari Indonesia. Hanya satu dua blog yang ditulis oleh pelancong Indonesia yang sengaja singgah ke Edensor dalam perjalanan wisatanya ke Britania Raya. Mungkin saya yang ketiga. Hehe…!
Saya sendiri sebenarnya termasuk pelancong yang telat mengunjungi Edensor, meski sudah beberapa kali traveling ke Inggris. Bahkan, ketika novel Edensor baru terbit pada bulan Mei 2007, saya membawanya dalam perjalanan ke Inggris sebagai buah tangan untuk teman yang sedang kuliah di Leeds. Tak ketinggalan dua novel sebelumnya, yaitu Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi, ikutan saya ajak bertualang dari Jogja, Jakarta, London, Manchester, dan akhirnya Leeds. Manchester dan Leeds sudah lumayan dekat dengan Sheffield dan Edensor. Tapi saat itu saya memilih ke York lalu ke Edinburgh, Skotlandia.
Ada banyak hal yang membuat saya tidak membelokkan langkah ke Edensor dan memilih destinasi blusukan lainnya. Alasan pertama, Edensor bukan destinasi wisata, hanya populer di Indonesia. Itupun hanya yang membaca novel Andrea Hirata yang mengenalnya. Saat saya melakukan pencarian di internet pada awal novel Edensor terbit, nyaris tak menemukan informasi wisata yang worthy untuk dibela-belain. Destinasi di sekitar Edensor yang populer adalah Chatsworth House, dengan rumah bangsawan Dukes of Devonshire di pinggir kali Derwent yang dikepung perbukitan hijau. Kawasan lain yang lebih populer adalah Peak District National Park, yang banyak dikunjungi turis terutama saat summer.
Alasan kedua, jika punya waktu jelajah desa, rasanya saya akan terlebih dulu mengunjungi Cotswold, dekat Birmingham. Kecantikan desa-desa di Cotswold sudah dikenal dunia, menyedot jutaan turis setiap bulannya. Sebagai turis yang hanya punya waktu dalam hitungan hari menjelajah Britania Raya, rasanya wajar jika saya memilih mengagendakan Cotswold sebelum ke Edensor. Alasan ketiga, jika ingin mengunjungi pedesaan Edensor dan sekitarnya, musim panas (summer) adalah waktu yang tepat. Langit biru, perbukitan hijau, dan sinar matahari yang hangat adalah suguhan paling indah di pedesaan. Masalahnya, tidak setiap summer saya punya kesempatan ke Inggris kan.
Sembilan tahun kemudian, setelah merasakan blusukan ke Cotswold dan desa-desa lain, barulah saya tergerak melangkahkan kaki menuju stasiun Manchester, membeli tiket kereta ke Sheffield, lalu menanti bus nomer 218 di halte Moorhead. Saat itupun tanpa rencana matang, juga nggak yakin akan lanjut ke Edensor mengingat cuaca awal musim semi di Inggris bukanlah waktu yang tepat untuk jelajah desa. Enaknya sih urban adventure saja, blusukan dari satu kota ke kota lain. Kalau hujan bisa berteduh di mall. Tapi kebetulan, saya juga sudah beberapa kali ke Manchester, kota-kota di sekitarnya sudah saya singgahi pula. Enaknya ke mana lagi ya? Tak ada rencana khusus, saya membeli tiket lewat mesin, memilih tiket “any time day return” agar bisa lebih fleksibel kembali ke Manchester jam berapapun.
Setiba di Sheffield, setelah berkereta kurang lebih 1 jam, hari sudah siang. Saya memilih jalan-jalan dulu ke Moors Market sembari mencari makan siang yang hemat. Sempat juga motret sana-sini dan windows shopping. Tau-tau sudah jam tiga lewat. Saya jadi gamang lagi. Lanjut ke Edensor nggak ya? Jika lanjut, artinya sudah sore saya tiba di sana. Perjalanan dengan bus sekitar 40 menit. Ah, setidaknya masih bisa menikmati secangkir teh tradisi Midland di Edensor Tea Room, sambil menulis kartu pos untuk anak wedok, putri saya.
Bayangan secangkir teh yang menghangatkan di sore yang gerimis membuat saya bergegas melangkah ke halte Moorhead MH2, menunggu bus 218 dengan rute Sheffield - Bakewell. Nomer bus dan halte itu saya temukan dari aplikasi Google Map saat mencari halte terdekat dari posisi saya saat itu.
Halte Moorhead berada di seberang kampus Sheffield Hallam University, tempat kuliah Andrea Hirata. Sekitar 300 meter jaraknya, hanya 5 menit jalan kaki. Mungkin ia pun dulu berdiri di sini, menanti bus yang sama. Aha, saya jadi mulai baper nih. Padahal belum tentu juga, karena di seberang kampus sisi yang berbeda adalah terminal bus Sheffield. Mungkin ia naik bus dari terminal. Tapi namanya juga baper, boleh saja kan? Dan makin terhanyut suasana ketika bus 218 mulai bergerak meninggalkan kepadatan kota, menyusur jalan berkelok dengan bukit-bukit dan lembah kehijauan di kanan kirinya.
Setelah 40 menit perjalanan bus dan memantaunya lewat Google Map, saya memencet bel memberi kode pada sopir bus, seorang perempuan paruh baya, untuk berhenti. Sopir menghentikan bus persis di sisi pohon besar. Di sekitarnya hanya terlihat pemandangan hijau perbukitan dan pohon-pohon besar. Beneran ini Edensor? Sebelum turun dari bus, saya memastikan bertanya pada driver perempuan itu. “Madam, is it Edensor?” Saya berharap dia menjawab seperti dalam novel Andrea, “Sure lof, it’s Edensor…”. Tapi ia hanya mengangguk dan menjawab singkat, “Yes…”. Saya segera melompat turun sambil mengucapkan terima kasih padanya. “Thank you. Byee!”
Ketika bus bergerak, barulah saya bisa melihat bangunan gereja St. Peter seperti pada kaver novel Edensor. Bangunan gereja itu terletak di seberang jalan, di balik pagar besi rendah berwarna biru tosca. Semula saya mengira pagar tersebut adalah pagar halaman gereja, bukan gerbang memasuki desa. Namun ternyata di sisi kanan kirinya ada jalan, meski tak begitu lebar, yang menghubungkan ke rumah-rumah kediaman warga.
Dari seberang jalan, desa Edensor tampak mungil dan tertata rapi. Edensor memang merupakan desa yang dibangun oleh bangsawan penguasa wilayah Chatsworth, yaitu Duke of Devonshire VI pada tahun 1838 - 1842. Duke ke-6 itu memindahkan pemukiman yang semula di pinggir sungai Derwent ke kawasan lain di sebelah barat sejauh kurang lebih 1 mil. Konon, pemidahan pemukiman tersebut karena Sang Duke ingin menikmati pemandangan hijau tanpa gangguan dari kediamannya di Chatsworth House. Jadilah Chatsworth House seperti yang dapat dilihat hingga kini, menjadi istana di lembah hijau dikelilingi perbukitan dan pepohonan.
Untuk menata desa Edensor, Duke ke-6 memerintahkan arsitek dan gardener Joseph Paxton yang juga menangani penataan Chatsworth House. Paxton membangun 33 rumah yang saat ini sebagian besar ditempati para staf dan pegawai pensiunan Chatsworth House. Arsitektur bangunan rumah-rumah di Edensor sangat unik, campur aduk mengadaptasi berbagai gaya. Konon, saat Paxton menyodorkan sejumlah rancangan yang digambar arsitek John Robertson, Duke ke-6 malah terpesona pada semua rancangannya. Bukannya memilih salah satu, tapi malah memerintahkan Paxton untuk membangun semua gaya tersebut. Alhasil, dari 33 rumah yang dibangun, bisa ditemui beragam gaya: ada gaya Tudor, bangunan lengkung Norman style, atap bergaya Swiss, juga jendela gaya Italia. Meski bergaya campur aduk, tapi hasil penataan Paxton ini membuat saya terpesona. Memberikan kesan klasik yang unik dan berbeda dengan bangunan pedesaan Inggris di Cotswold.
Di mata saya, Edensor ini jadi mirip kompleks perumahan, bukan sebuah desa. Tak hanya jumlah rumahnya yang sedikit, tapi penghuninya juga beberapa gelintir. Menurut data yang saya baca di Wikipedia, jumlah penghuninya tak lebih dari 145 orang (tahun 2011). Kurang lebih sama dengan jumlah siswa sekolah dasar di Indonesia. Saya bisa merasakan kemungilan dan kesunyian desa ini ketika menjelajah pada sore yang gerimis saat itu. Sama sekali nggak berpapasan dengan warga setempat saat blusukan menyusur jalan-jalan di belakang gereja. Sampai membuat saya merasa sedikit was-was. Takut dianggap sebagai orang asing yang nyelonong tanpa tujuan. Mana saya jalan sendirian pula.
Gerimis sore itu belum juga reda membuat saya tak bisa leluasa menyusur lorong-lorong Edensor. Salah saya juga sih, sudah tahu kalau blusukan ke desa itu paling nyaman saat summer, tapi kok ya nekat melipir ke Edensor di awal musim semi. Basah dan dingin juga membuat saya merasakan ada desakan di kandung kemih.
Aduh, di mana ya mencari toilet? Ah, mungkin sudah saatnya minum teh di Tea Room sambil numpang pipis. Saya melangkahkan kaki ke jalan di depan gereja, kemudian mengikuti petunjuk arah: Tea Rooms 50 metres on left.
Di depan bangunan klasik dengan teras berisi sejumlah meja dan kursi kafe, langkah saya terhenti. Lega menemukan tulisan Edensor Tea Cottage tergantung di dinding, namun juga kecewa karena pintu biru tosca di bawahnya tertutup rapat. Yaa, kok sudah tutup. Saya lihat jam di ponsel, sudah lewat pukul lima sore. Kedai ini tutup pukul 16.30 dan 17.00 saat weekend.
Saya mendekat ke arah pintu yang tertutup dan digantungi tulisan Closed. Kedai sudah tutup beneran. Tapi saya tetap mendekat, mengintip ke dalam dari kaca pintu, terlihat dua pegawai kedai yang tengah sibuk berberes. Sirna sudah kehangatan secangkir teh yang sudah saya bayangkan sejak menanti bus di Sheffield. Sekarang yang tersisa hanya dingin gerimis dan desakan kandung kemih yang makin tak tertahankan. Sungguh perpaduan yang sama sekali tak nikmat.
Saya tinggalkan kedai dengan langkah gontai menuju halte bus di depan gerbang desa. Sudah pukul 17.20, sekitar 20 menit lagi ada bus menuju Sheffield. Lebih baik saya berdiri di sana.
Sambil menanti bus dan menahan kebelet pipis, diam-diam saya bermimpi untuk kembali ke Edensor suatu hari ini, saat summer. Bukankah perbukitan hijau yang menyembunyikan rumah keluarga bangsawan Duke of Devonshire belum sempat saya jelajahi? Semoga Tuhan memeluk mimpi-mimpi saya.
(Foto: Matatita)
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Melipir ke Edensor
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Adakah Dampak Brexit bagi Turis Indonesia?
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





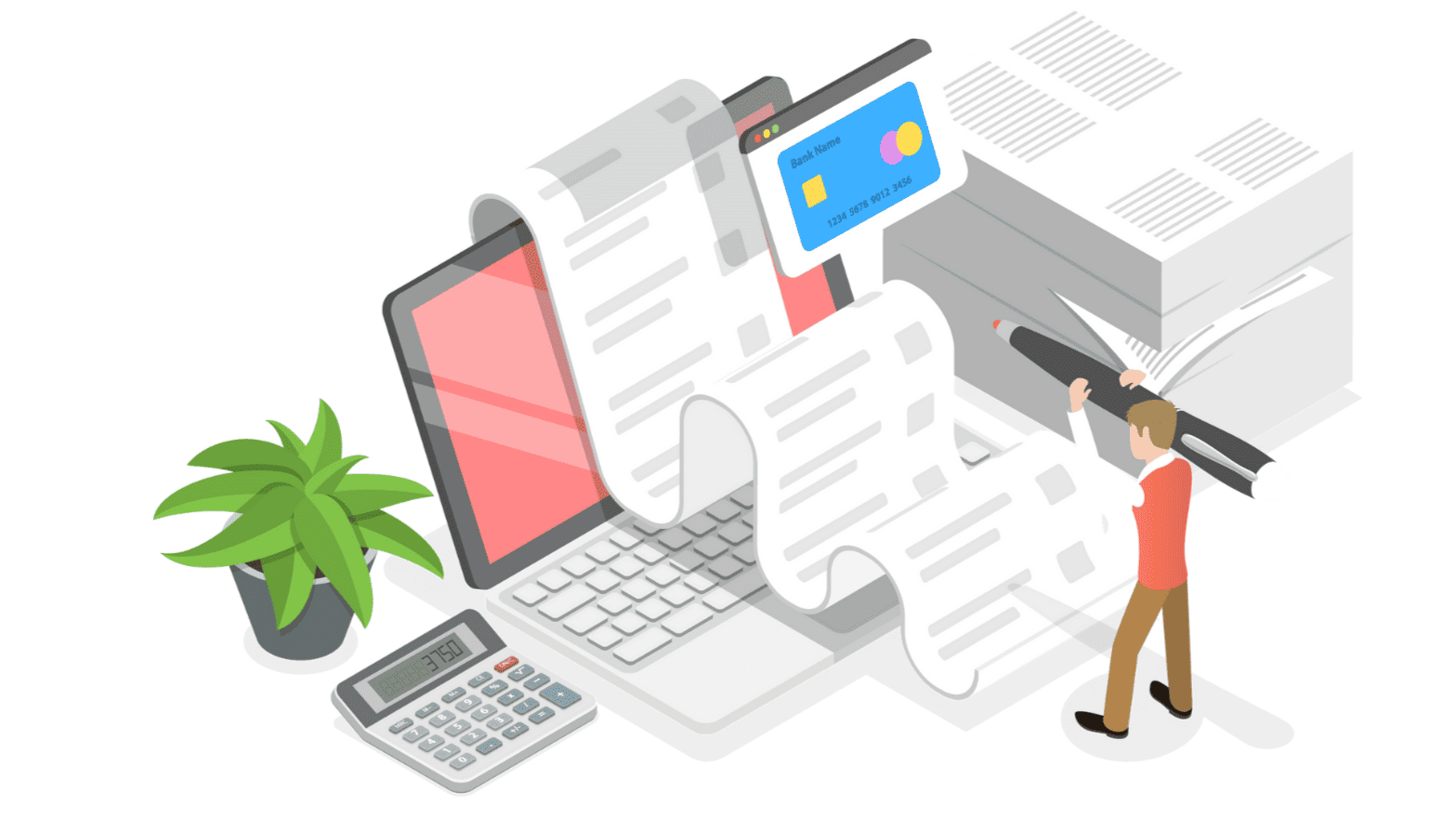

 98
98 0
0















