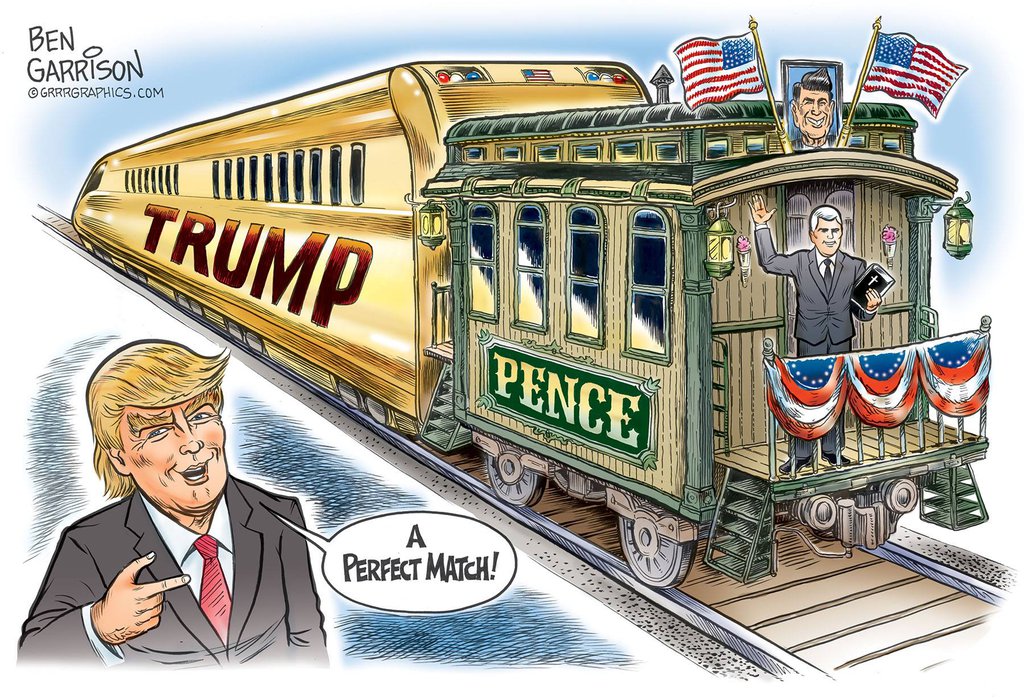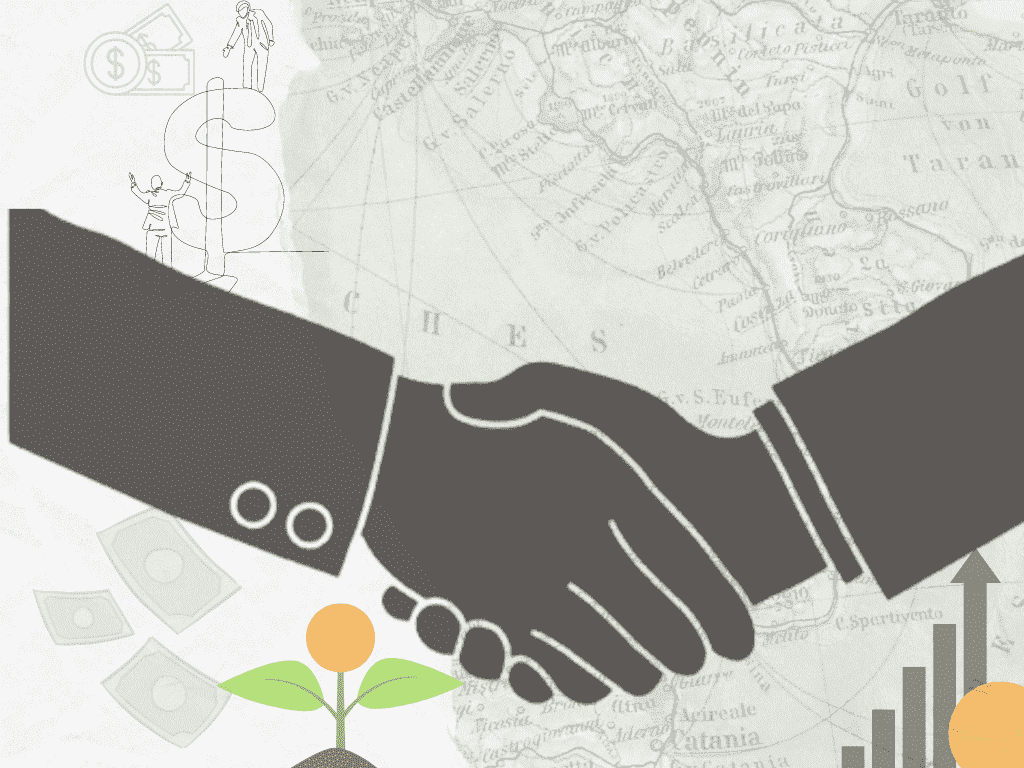Sebuah kisah fiksi memiliki keunggulan untuk menembus ruang dan waktu. Itulah yang terjadi pada serial The Simpson musim ke-11 yang berjudul Bart to The Future. Bart, anak sulung Homer, yang berwisata ke masa depan.
Di masa depan, Bart menemukan sang adik, Lisa, 38 tahun, menjadi presiden Amerika Serikat perempuan pertama. Tahukah siapa yang diganti oleh Lisa? Ya, Donald Trump! Jadi, 16 tahun lalu, ramalan itu telah dibuat oleh serial animasi karya Matt Groening tersebut. Lalu, apa yang ditinggalkan Trump dalam kisah itu? Sebuah negara yang nyaris bangkrut karena bengkaknya anggaran belanja.
Bukan kali itu saja sindiran pada aktor politik itu terjadi melalui medium tontonan populer. Yuk, kita kembali ke masa lalu, bukan, masa depan....
Reagan dan Arnold sebagai Pesohor Politik
Robert Zemeckis, sineas ternama Hollywood, dalam film besutannya berjudul Back to the Future (diproduksi 1985) menampilkan sebuah adegan menarik. Si tokoh utama film itu, Marty McFly yang hidup di tahun 1985, kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1955. Ia menggunakan mesin waktu yang ditemukan oleh sahabatnya, ilmuwan eksentrik, Doc Emmett Brown.
Kedua sahabat itu kembali bertemu di tahun 1955. Terang saja Emmet muda di masa lalu tak mengenal Marty yang datang dari masa depan. Dalam keadaan penuh curiga, Emmett bertanya sekaligus menguji Marty, “Siapa Presiden Amerika Serikat tahun 1985?” Marty spontan menjawab, “Ronald Reagan.” Emmet pun membalas sinis, “Lalu siapa wakil presidennya? Jerry Lewis? Aku tebak pasti ibu negaranya Jane Wyman.” Jerry Lewis adalah aktor yang kerap beradu akting dengan Reagan. Sedangkan Jane Wyman adalah aktris ternama yang memang menjadi istri pertama Reagan sebelum bercerai pada 1949.
Respons Emmet yang hidup di tahun 1955 sungguh menarik disimak. Ia tak membayangkan jika kelak negaranya dipimpin oleh seorang aktor Hollywood. Sejarah panjang Amerika Serikat hingga dekade 1960-an menunjukkan bahwa negeri yang merdeka pada 4 Juli 1776 tersebut selalu dipimpin oleh figur-figur pahlawan perang hingga tokoh politik kenamaan. Ronald Reagan memang menjadi seorang politisi di kemudian hari, lalu menjadi Gubernur California hingga benar-benar menjadi orang nomor satu di Negeri Abang Sam itu pada tahun 1981. Tapi, reputasi Reagan sebagai pesohor dan bintang film koboi terus melekat padanya.
Tentu, membayangkan Reagan sebagai Presiden bagi warga AS di tahun 1955, seperti halnya Emmet muda, adalah hal mustahil. Di masa-masa ketika Amerika Serikat sedang adu kuat dengan Uni Soviet, popularitas seorang pahlawan perang dunia kedua seperti Dwight Eisenhower, politisi muda cemerlang seperti John F. Kennedy, hingga Richard Nixon, sedang melesat-melesatnya.
Setelah Reagan, terpilihnya pesohor dalam jagat perpolitikan Amerika berulang lagi pada tahun 2003. Arnold Alois Schwarzenegger, aktor yang dikenal melalui film The Terminator (1984) , Commando (1985), hingga Predator (1987), terpilih sebagai Gubernur Negara Bagian California ke-38 pada 2003. Ia menggantikan politisi Demokrat Gray Davis yang terjungkal karena defisit anggaran, tingginya pengangguran, hingga kondisi pendidikan yang buruk.
Tak main-main, Sang Terminator meraih suara 48,7 persen. Ia melesat mendahului rival-rivalnya seperti Cruz Bustamante, Tom McClintock, juga Gubernur pertahana Gray Davis. Cibiran soal minimnya pengalaman politik Arnold serta tuduhan skandal seksual di masa lalu tak memperngaruhi sebagian besar pemilih. Karpet merah pun digelar untuk sang pesohor Hollywood masuk ke dunia politik.
Stanley Bing, dalam bukunya Sun Tzu: Was a Sissy, menyebut beberapa faktor yang menyokong kemenangan Arnold, tentunya dengan nada sinis. Kemenangan itu tidak didasarkan pada visi-visinya yang memukau publik, melainkan gaya murka (penuh keyakinan) Arnold untuk melakukan apa yang ia inginkan –dalam film-filmnya. Seperti, lanjut Bing, ucapan, “I’ll be back,” dalam film The Terminator.
Faktanya, publik punya selera masing-masing. Di sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki akses luas untuk memilih pemimpinnya. Menariknya, pilihan itu tak serta-merta hadir. Peristiwa politik tertentu hingga rekayasa sosial yang rapi dan sistematis, bisa memunculkan figur tertentu yang disukai publik. Salah satu rekayasa sosial yang rapi dan sistematis, salah satunya, dapat dilakukan media dan propaganda yang intens.
Arus informasi yang mengetuk setiap pintu rumah turut memberikan andil bagi terbentuknya opini publik itu sendiri. Bukankah sudah lama publik mengenal Arnold sebagai Kolonel John Matrix, tentara tangguh dalam film Commando, atau Mayor Alan "Dutch" Schaefer yang gagah berani berduel dengan alien di Predator , hingga Android canggih dari masa depan dalam The Terminator.
Hitler, Faktor Media, dan Propaganda
Media, terutama berkategori arus utama (mainstream) dan berjaringan luas, jelas mampu membentuk opini publik. Jika tingkat kekritisan rendah, masyarakat akan dengan mudah mengunyah mentah-mentah setiap infomasi yang diproduksi oleh sebuah media. Mereka cenderung malas untuk melakukan verifikasi terhadap berita yang sudah dipublikasikan tersebut. Sehingga, tak heran jika berita sumir, gosip, dan bohong begitu mudah tersebar.
Model yang nyaris paripurna dalam aksi propagandanya dapat dilihat dari cara kerja partai ultranasionalis Jerman, NAZI. Tak hanya popularitas partai yang terdongkrak, NAZI juga sukses melambungkan figur Adolf Hitler sebagai mesias bagi supremasi Deutschland Uber Alles.
Setelah November 1923, saat kudeta NAZI gagal, bisa dikatakan Hitler kehilangan posisinya dalam politik praktis Jerman kala itu. Momentum kembalinya Hitler dimulai ketika Jerman dilanda krisis hebat pada 1929. Dimulai dari jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat, Jerman pun dihantam badai PHK dan kebangkrutan sejumlah bank. Hitler pun berjanji untuk memulihkan kondisi ekonomi dan melepaskan diri dari Perjanjian Versailles –yang dianggap merugikan Jerman pascakekalahan Perang Dunia I.
Tiga motor propaganda NAZI adalah buku Mein Kampf yang ditulis oleh Hitler sendiri, lalu dua koran, Völkischer Beobachter dan Der Angriff. Koran terakhir disokong oleh Joseph Goebbels, Menteri Penerangan dan Propaganda NAZI yang juga salah satu kepercayaan Hitler.
Dalam Mein Kampf, misalnya, Hitler membuat rumusan jelas tentang makna propaganda. Ia menulis, “Propaganda tidak harus menyelidiki kebenaran obyektif dan, sejauh itu, menguntungkan ke sisi lain, hadir sesuai aturan teoretis keadilan; namun (propaganda) harus hadir hanya pada aspek kebenaran yang menguntungkan untuk sisi sendiri.” Dari rumusan itu, dapat dibaca bahwa propaganda bukan berdiri pada ranah obyektif. Satu-satunya nilai yang tersirat jelas bahwa propaganda adalah alat demi tercapainya sebuah tujuan. Rumusan di atas seperti menjadi pegangan seluruh kanal propaganda NAZI. Salah satu kampanye mereka adalah gerakan anti-Yahudi, melalui poster, kartun, film, hingga selebaran. Film Der Ewige Jude, atauThe Eternal Jew karya Fritz Hippler pada 1940, merupakan produk propaganda paling muram tentang diskriminasi terhadap Yahudi. Film berformat gambar hitam-putih dan bernarasi bahasa Jerman itu adalah bahan bakar yang bisa menyulut kebencian pada komunitas Yahudi.
Alhasil, Hitler kembali meraih popularitasnya. Menariknya, ia tetap konsisten untuk meraih kekuasaan melalui jalur demokratis: pemilihan umum. Perolehan suara partai NAZI yang dipimpinnya terus menanjak. NAZI meraih perolehan suara hingga 44 persen pada Maret 1933, setelah perolehan keterpurukan suara partai di angka 3 persen pada Desember 1924. Kuncinya, Hitler sukses meramu dua hal: nasionalisme bangsa Jerman di satu sisi, dan kebencian pada kaum Yahudi di sisi lain. Rakyat Jerman telah memilihnya (secara demokratis) lalu dunia pun terjebak pada konflik bernama Perang Dunia ke-2 yang berakhir dengan kematian 62 juta jiwa.
Membaca Ulang “Vox Populi Vox Dei”
Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), demikian bunyi kalimat yang diperkenalkan Alcuin, pujangga dan tokoh pendidik yang hidup abad ke-7. Slogan ini lalu dipopulerkan oleh William of Malmesbury pada abad ke-8. Seiring perjalanan sejarah, kalimat itu menjadi penting untuk disigi kembali kebenarannya. Dari uraian sebelumnya, sejarah Jerman era Hitler adalah bukti sahih betapa “Suara Rakyat” tak selamanya sejalan dengan “Suara Tuhan”.
Kita lupa, bahwa banyak orang mengutip kalimat ‘vox populi vox dei’ sepotong-sepotong. Sejatinya, Alcuin menulis kalimat itu lebih panjang dari yang selama ini terlanjur populer. Uraian latinnya:‘Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit. ' Dalam terjemahan Inggrisnya: And do not listen to those who keep saying, 'The voice of the people is the voice of God.' because the tumult of the crowd is always close to madness’.' Dan jangan dengarkan mereka yang senantiasa berujar, “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, karena kekacauan sebuah kerumuman sungguh dekat dengan kegilaan.”
Terpilihnya Reagan, Arnold, dan Hitler bisa jadi menegaskan bahwa suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, melainkan suara populer semata. Jadi, tak usah terlalu kaget jika Donald Trump menjadi presiden hari ini. Bahkan, The Simpson pun bisa meramalnya....
Sumber gambar:
The Trump/Pence Train by superguy2036
Ikuti tulisan menarik Yugha Erlangga lainnya di sini.