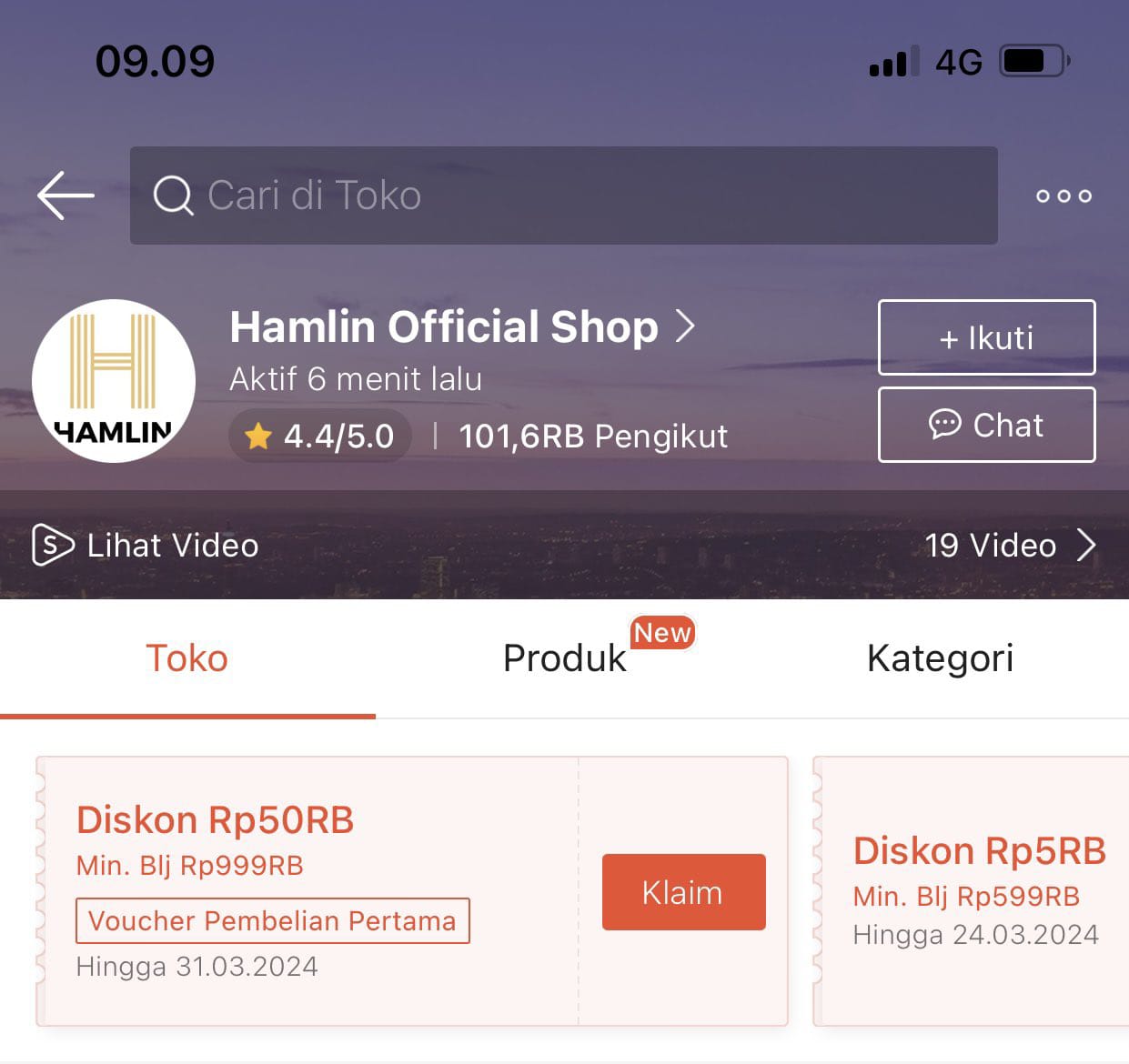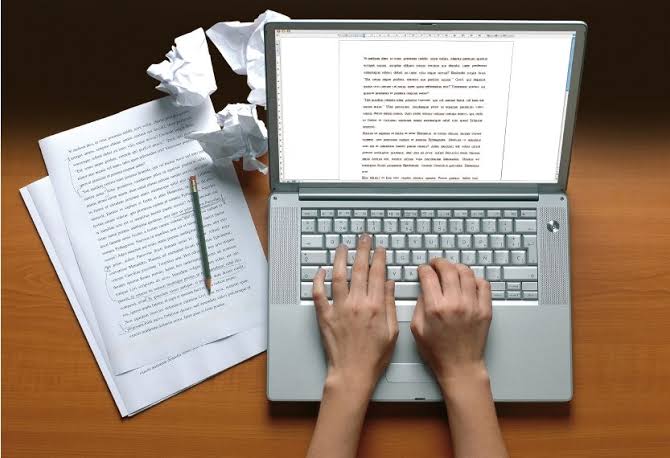“Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore”. Sepotong bait lagu “Libur telah Tiba” yang dinyanyikan oleh Tasya kecil terasa cocok sekali dengan semangat berlibur masyarakat Indonesia setiap kali menyambut momen-momen hari libur.
Dari segi kata, libur sendiri turunan dari kosakata Perancis, libre. Dalam kamus Micro Robert poche (2011), salah satu arti libre adalah “qui n’est pas privé de sa liberté” (yang tidak dirampas kebebasannya). Namun, lema libur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya menjadilain, yaitu “bebas dari bekerja atau masuk sekolah”. Adapun berlibur diartikan “pergi (bersenang-senang, bersantai-santai dsb) menghabiskan waktu libur”.
Antara kata asal dan derivasinya terasa memiliki makna yang berbeda. Libur dalam konteks (bahasa) Indonesia cenderung hanya menekankan relasi bebas dari aktivitas bekerja dan sekolah saja. Tujuannya pun lebih sebatas ke konteks berpergian untuk bersenang-senang dan bersantai-santai. Nah, jika dikaitkan dengan konteks libre, maka pekerjaan dan sekolah dalam konteks libur justru terkesan sebagai “perampas kebebasan”. Dus, bekerja dan belajar jadinya hanya dianggap beban belaka (maka itu ada istilah “beban kerja” dan “beban belajar”). Meski dianggap wajib dijalani, tapi bekerja dan belajar tersirat bukan aktivitas yang menyenangkan karena dianggap telah “membunuh” waktu luang (leisure) bagi jiwa dan pikiran. Maka, jangan heran jika selepas libur panjang (seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru), banyak didapati pekerja membolos kerja dan siswa membolos sekolah. Seakan ini menandakan, kebebasan selama liburan “kembali dirampas” oleh kantor dan sekolah. Apakah masyarakat Indonesia merasa “kurang piknik” dikarenakan hidupnya yang minim leisure itu?
Jelas ini berbeda dengan konsep leisure di negara seperti Jerman sebagaimana diulas dalam artikel Eryn Paul, Why Germans Work Fewer Hours but Produce More?: a Study in Culture, yang dirilis www.knote.com. Di Jerman, rata-rata orang bekerja 7 jam sehari atau 35 jam per minggu. Kualitas produktivitas kerja lebih diprioritaskan daripada mengukur kerja berdasarkan kuantitas lama jam kerja, lembur, dan banyaknya rapat. Pemerintah Jerman bahkan memandatkan libur dan cuti berminggu-minggu bagi para pekerja tanpa dipotong gaji. Tentu saja, maksud dari kebijakan pemerintah Jerman yang murah-hati ini adalah agar warga negaranya bisa terbebas dari stress. Jadi, ketika kembali dari masa liburannya, para pekerja kembali bersemangat bekerja. Tentu, kultur itu kontras dengan di Indonesia. Merujuk data Decent Work Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum rata-rata minimum jam kerja di Indonesia adalah 40 jam per minggu atau 8 jam sehari. Dan setiap tahunnya, lamanya jam kerja pekerja di Indonesia terus meningkat lebih dari 48 jam per minggu. Jadi, jangan bermimpi bisa seperti halnya para pekerja di Jerman yang mendapat mandat libur dan cuti selama berminggu-minggu. Dan jangan heran, jika selepas menjalani liburan, hawa malas serasa menyergap ketika memulai aktivitas kerja (dan sekolah).
Makna Leisure
Dalam bukunya Man and Leisure: a Philosophy of Recreation (1962), Charles K. Brightbill menegaskan bahwa manusia mutlak perlu leisure. Leisure sendiri turunan dari kosakata Latin Licere yang memiliki arti “freedom from occupation, employment, and engagemet”. Konteks kebebasan dalam kata leisure itu sendiri menurut Brightbill (dengan mendukung pemikiran Max Kaplan yang menulis buku Leisure and Life [1957]), bukanlah merujuk ke banyak atau lama-nya waktu luang. Melainkan, seperti apa kondisi kebebasan itu, kesempatan untuk merasakannya, pengetahuan yang didapat darinya dan kontrol sosial sebagai instrumennya.
Apa yang dipikirkan Brightbill dan Kaplan terasa maknanya untuk memahami pemahaman libur masyarakat Indonesia. Jika menelaah kembali makna “bebas” dalam libur, justru yang terjadi di Indonesia adalah tersanderanya kebebasan itu sendiri. Tujuan untuk tetirah demi menghilangkan kepenatan dari rutinitas kerja dan belajar, malah tersandera oleh kemacetan parah akibat tumpah ruahnya penggunaan kendaraan pribadi. Padahal dalam industri pariwisata, kemacetan adalah hal yang tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat. Bukan hanya bagi para pelaku wisata, tapi juga bagi banyak pihak non-pelaku wisata yang merasa dirugikan akibat tidak efisiennya waktu tempuh perjalanan.Ketika kemacetan parah terjadi, akhirnya liburan bukan lagi untuk membebaskan kepenatan, tapi justru penumpukankepenatan. Kepenatan yang menumpuk itu sepintas terasa terobati ketika berwisata. Tapi dalam banyak kasus, hal itu nyatanya tidak diimbangi kesadaran para wisatawan untuk sadar kebersihan. Jangan kaget jika keindahan lokasi wisata (seperti Pantai Kuta) menjadi rusak,tak nyaman dilihat karena begitu banyak sampah dibuang sembarangan oleh pengunjung.
Dari kasus itu, miskinnya leisure mungkin sekali terhubung dengan masih rendahnya budaya pariwisata di kalangan masyarakat Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan dari masih banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang moda transportasi publik. Akhirnya, kemacetan parah akibat menumpuknya kendaraan pribadi menjadi sulit terurai. Terbatasnya kantong-kantong parkir di lokasi wisata kian menambah tidak eloknya pemandangan.
Jika itu semua terjadi, maka apa yang dicemaskan oleh pengamat pariwisata James J. Spillane dalam bukunya Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan (1994) menjadi terbukti, bahwa industri pariwisata hanya menjadi sesuatu yang rapuh. Satu sisi masa libur panjang memberi efek rembesan (trickle down effect) ekonomi bagi industri wisata. Tapi sisi lain, juga memberi efek rembesan yang tidak elok berupa kemacetan, polusi, pengotoran, dan vandalisme di lokasi-lokasi wisata. Kontrol sosial sebagai instrumen untuk meredam kesengkarutan itu pun nyaris absen. Setidaknya ini menunjukkan, di Indonesia, kesadaran dalam memahamipraktik berwisata sebagai sarana leisuremasih begitu rendah.
Maka kiranya, edukasi budaya pariwisata perlu ditanamkan sebaik-baiknya bagi masyarakat agar bisa lebih memahami bagaimana proses menuju dan ketika berada di lokasi wisata. Selain itu, regulasi waktu kerja dan sekolah yang lebih manusiawi dalam menanamkan makna leisure sedianya dipikirkan secara seksama oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan agar diterapkan oleh lembaga-lembaga (kerja dan sekolah) terkait. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi merasa hidupnya “kekurangan piknik”.
Fadly Rahman
Ikuti tulisan menarik Fadly Rahman lainnya di sini.