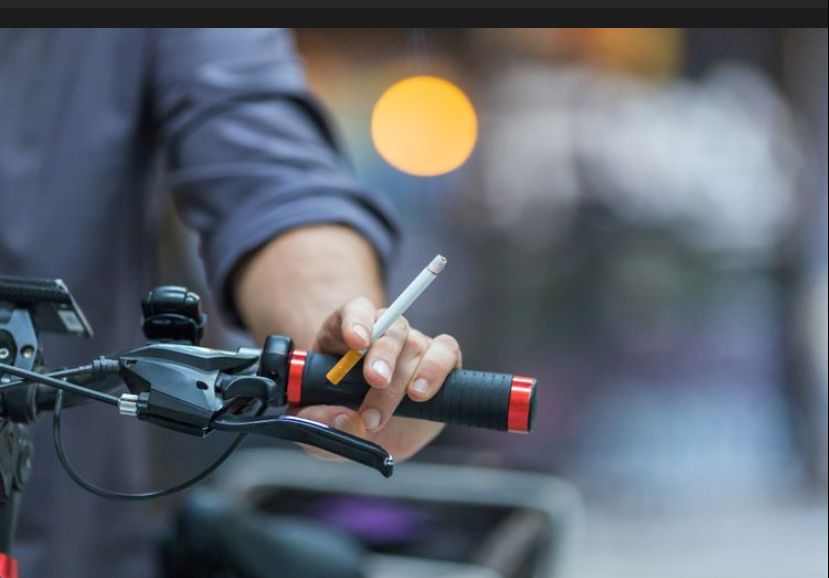Bulan Oktober selain diperingati sebagai hari lahir TNI, sejak 2015 dikukuhkan sebagai Hari Santri Nasional (HSN) yang selalu diperingati setiap tanggal 22 yang tinggal beberapa minggu lagi, para santri di penjuru Indonesia bersuka cita memperingatinya. Peringatan HSN sekilas mempunyai kaitan sejarah dengan TNI, karena bertepatan dengan ultimatum para ulama soal “Resolusi Jihad” agar rakyat bersama TNI berjuang bersama-sama menghalau Belanda yang melakukan agresi militernya di Pulau Jawa. Sejarah menyebutkan, bahwa hampir seluruh pesantren di penjuru Nusantara menyatakan dirinya setia kepada NKRI dan berhak berjihad merebut kembali kemerdekaan yang pada waktu itu justru dicederai oleh Belanda yang menjadi penumpang gelap dalam pasukan sekutu.
Refleksi sejarah mengenai kedudukan santri sebagai bagian dari semangat perjuangan menegakkan NKRI memang sulit terbantahkan. Fenomena ini bahkan digambarkan oleh seorang ilmuwan Jepang Mitsuo Nakamura, yang menyebut mereka yang berjihad melawan penjajah sebagai gerakan “tradisionalisme radikal”. Tradisionalis merupakan ciri santri yang memang hidup secara “rural” di pelosok-pelosok Nusantara, belajar keagamaan secara tradisional dalam lingkungan pesantren secara “patriarki” karena ikatan solidaritas kiai dan santri yang begitu kuat. Para santri disebut “radikal” karena semangat juang mereka besar terhadap hal yang bertentangan dengan dirinya, terutama soal penjajahan yang harus dihapuskan. Sebutan “tradisionalisme radikal” kurang lebih memiliki konotasi “jihadis” sekaligus “fundamentalis” yang kala itu semestinya tak mungkin ditemukan pada sebuah kultur masyarakat tradisional.
Sejauh ini, keberadaan santri yang tinggal di berbagai pesantren memiliki watak khas tradisionalisme dimana sistem patriarki antara kiai dan santri jelas memiliki ikatan kuat yang terstruktur dalam lingkup budaya pesantren. Ikatan-ikatan solidaritas ini tidak hanya sebatas ketika seseorang masih “nyantren” tetapi, setelah tidak menjadi santri-pun ikatan solidaritas itu masih kuat terjalin. Tradsisi keilmuan dalam dunia pesantren tidak saja membuktikan kekuatan ikatan solidaritas tersebut, baik melalui pembukaan pondok pesantren baru yang diinisiasi oleh para santri yang telah lulus, tetapi akan diperkuat melalui tradisi perkawinan antara seorang santri senior dengan keluarga kiai, sehingga budaya pesantren tetap melembaga dan kuat hingga saat ini.
Keterikatan solidaritas kiai-santri belakangan semakin memudar, karena dampak globalisasi yang mengharuskan watak tradisionalis pesantren berubah mengikuti irama perkembangan zaman. Berbagai lembaga pendidikan pesantren mau tidak mau harus mengikuti berbagai metode pendidikan modern, baik dari sisi penggunaan kurikulum pendidikan maupun cara pengajaran yang dilakukan dalam pola kelas-kelas. Berbeda dengan pola pengajaran santri terdahulu, yang bersifat tradisional dan berhasil membangun kedekatan serta ikatan kuat kiai-santri, era milenial seperti saat ini, jelas hampir tak pernah ditemukan kekuatan solidaritas sosial yang terbangun secara kuat melalui pola kiai-santri seperti era terdahulu.
Fenomena pesantren belakangan lebih banyak diisi oleh para “santri milenial” yang memiliki kecenderungan inklusif, tidak peduli terhadap pola ikatan solidaritas kiai-santri bahkan tak pernah mengenal ulama-ulama lain yang memiliki keterkaitan tradisi keilmuan di pesantrennya sendiri. Barangkali, tidak hanya itu, santri milenial dengan pola pikir yang serba “medsos” akan lebih banyak berinteraksi dengan dunia maya dan terkadang malah terasing di dunia pesantren yang sedang digelutinya. Lihat saja, perayaan HSN pada akhirnya akan lebih semarak di medsos, melalui berbagai unggahan, tautan atau swafoto jauh dari sekadar nilai-nilai solidaritas yang semestinya tetap terjaga dalam ikatan-ikatan kiai-santri.
Gambaran santri era milenial saat ini, barangkali sangat jauh berbeda ketika saya pernah nyantri dulu. Nuansa kedekatan emosional yang begitu terjaga dalam pola kiai-santri memperkuat watak tradisionalisme pesantren yang ekslusif. Keterbukaan, toleransi dan ikatan-ikatan solidaritas tampak kuat, baik dalam kebersamaan ketika masih di pesantren maupun setelahnya. Sulit ditemukan nuansa kebersamaan para santri era terdahulu yang cenderung prihatin, terutama dalam menjalani hidup sebagai santri sehari-hari di era santri milenial saat ini. Inklusifitas santri milenial mudah ditemukan dari cara bergaul mereka dengan santri-santri lainnya dan pola hubungan yang berubah antara kiai-santri. Terlebih, dunia pesantren belakangan lebih banyak mendahulukan nilai-nilai keekonomian dan bisnis dan cenderung “materialistik” dibanding tetap mempertahankan watak tradisionalismenya.
Para santri akan diarahkan untuk memilih “fasilitas” bukan “kualitas”, sehingga jika keberadaan pesantren itu tidak memenuhi kriteria “modern” jelas enggan dipilih oleh mereka yang berniat belajar di pondok pesantren. Pondok pesantren belakangan semakin kehilangan ruh-nya sebagai perekat ikatan solidaritas sosial—baik antara kiai-santri atau santri-masyarakat—dan penjaga tradisi mata rantai keilmuan (sanad) yang dahulu justru populer dan senantiasa hidup menjadi bagian dari budaya masyarakat. Wajar, jika saat ini pesantren bukan lagi menjadi “subkultur”—meminjam bahasa Gus Dur—tetapi memisahkan diri dari watak kekulturannya, mengikuti arus globalisasi yang sulit dibendung. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa santri milenial merupakan “generasi baru” pesantren yang tak lagi menganut pakem tradisionalisme dan watak subkultur sebagai satu-satunya model paling origin dari pendidikan bangsa Indonesia.
Pemenuhan pemerintah soal HSN pada akhirnya hanya dapat dilihat sebagai sebuah “oleh-oleh” yang sekadar bentuk “akomodatif” bagi pengakuan atas pesantren di Indonesia, tanpa melihat watak subkultur dalam sejarahnya. Pesantren justru lebih banyak dipergunakan sebagai “komoditas politik” oleh berbagai pihak dalam membangun pencitraan sebagai jalan menuju panggung kekuasaan. Tak heran, jika kemudian pesantren justru semakin ramai dikunjungi oleh para penguasa, bukan karena alasan kebanggaan atas “produk asli” pendidikan Indonesia, tetapi karena memang semakin banyak alasan-alasan politis yang membuat seseorang kemudian berkunjung dan mengapresiasi pondok-pondok pesantren. Para santri milenial pada akhirnya akan cenderung instan dalam banyak hal, termasuk gairahnya yang terlampau akomodatif terhadap berbagai afiliasi politik.
Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.