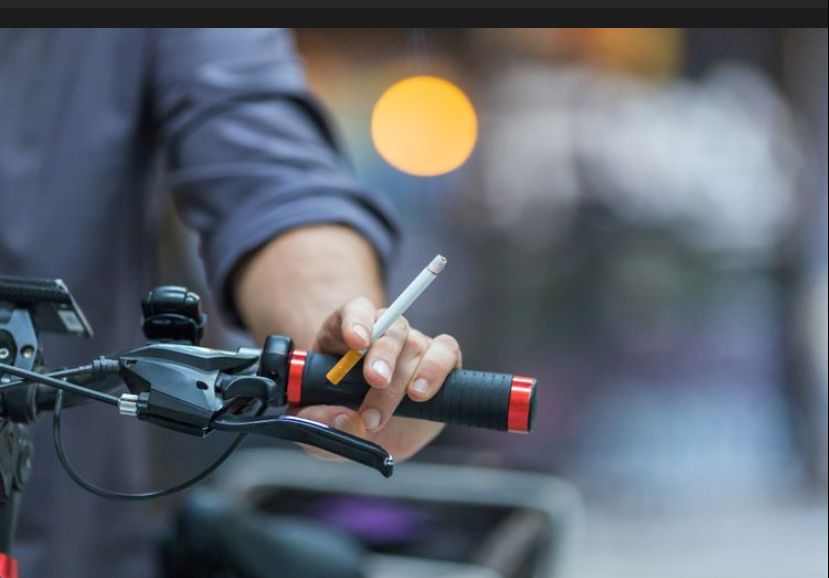Oleh: Satriwan Salim*
Perihal Persekusi
Sebagai seorang pendidik, rasa-rasanya penggunaan istilah dan persoalan mengenai “persekusi” intensitasnya makin marak di era pemerintahan sekarang. Berasal dari terminologi asing, diambil dari kata “persecution”, diserap menjadi Bahasa Indonesia menjadi persekusi, yang berarti; “pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas” (KBBI daring).
Pola persekusi yang terjadi akhir-akhir ini meliputi; 1) menelusuri orang-orang di media sosial yang dianggap melakukan penghinaan, 2) menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto dan alamat, 3) mendatangi rumah atau kantor, melakukan intimidasi, dan dalam beberapa kasus dipukul, dipaksa menandatangani surat permohonanan maaf bermaterai, ada pula yang didesak agar ia dipecat (diolah dari https://kamushukum.web.id/arti-kata/persekusi/)
Persekusi di masa Orde Lama misalnya dilakukan oleh Pemuda Rakyat underbow PKI, kepada para kyai dan santri Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kediri, pada 13 Januari 1965. Kyai Jauhari yang juga merupakan adik ipar KH. Mahrus Ali (seorang kyai NU kharismatik pemimpin Ponpes Lirboyo) diseret-seret dan ditendang oleh gerombolan PKI tersebut di pagi buta.
Persekusi yang di zaman itu lazim dikenal dengan sebutan “aksi sepihak”, dilakukan PKI mulai pertengahan 1961. Misalnya peristiwa Kendeng Lembu, Genteng, Banyuwangi (13 Juli 1961), peristiwa Dampar, Mojang, Jember (15 Juli 1961), peristiwa Rajap, Kalibaru, dan Dampit (15 Juli 1961), peristiwa Jengkol, Kediri (3 November 1961), peristiwa GAS di kampung Peneleh, Surabaya (8 November 1962), sampai peristiwa pembunuhan KH. Djufri Marzuqi, dari Larangan, Pamekasan, Madura (28 Juli 1965) (lebih lanjut baca buku: “Benturan NU-PKI 1948-1965”, oleh Abdul Mun’im DZ, 2013).
Kita boleh berbeda pendapat, persekusi yang tak kalah menakutkan juga dilakukan oleh massa bersama organisasi masyarakat dan diperkuat oleh tentara, melakukan persekusi terhadap eks anggota, simpatisan PKI dan yang dituduh PKI. Akibatnya, ratusan ribu orang tewas (lebih lanjut baca buku; “The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966”, oleh Robert Cribb, 2003).
Tapi baiklah, kita langsung “move on” saja dari peristiwa sejarah berdarah tersebut. Era demokrasi yang sudah dinikmati warga negara sekarang ini, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, semestinya membuka ruang lebar bagi kebebasan warga negara yang sesungguhnya. Sebagai seorang pendidik tentang warga negara dan kewarganegaraan (civic education), penulis mengutip pemikiran John Locke (1632-1704) tentang hak-hak kodrati seorang manusia, yang kemudian melahirkan konsepsi universal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi; hak kebebasan, hak hidup dan hak kepemilikan, begitu pula sebaliknya tidak merusak kebebasan, hak hidup dan hak kepemilikan orang lain. Dan hak-hak tersebut lebih tua usianya ketimbang usia negara ini.
Adalah hak seorang warga negara, untuk diperlakukan secara adil, hak memeroleh rasa aman, hak untuk tidak disakiti dan kebebasan untuk tidak dipersekusi oleh siapapun. Karena semua warga negara itu statusnya setara di depan hukum. Hak-hak dasar inilah yang baru saja dirampas, menimpa Ustad Abdul Somad (selanjutnya ditulis UAS), ketika melakukan dakwah di komunitas muslim di Bali.
Tulisan ini tak bermaksud memperkeruh suasana yang sudah kembali “tenang”, setelah UAS menuntaskan dakwah dan kembali ke kampungya, Pekanbaru. Tapi sekedar memberikan catatan korektif dan reflektif atas kejadian yang menimpa “dai sejuta jamaah online” tersebut (istilah ini penulis pakai karena aktivitas dakwah UAS menjadi fenomena keummatan yang unik saat ini, dengan pendengar yang sangat banyak, baik langsung dan streaming di media sosial).
Para pelaku persekusi yang merupakan oknum masyarakat dan ormas, diduga telah melakukan teror psikologis dan fisik (karena di video yang beredar di media ada yang membawa senjata tajam) terhadap pribadi UAS dan termasuk jamaah. Penulis haqul yaqin, sesungguhnya karakter asli masyarakat Bali jauh dari kata intoleran dan kasar seperti itu.
Alasan para peneror melakukan persekusi terhadap UAS adalah karena UAS dinilai tidak setia terhadap Pancasila dan anti NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sehingga dia dipaksa menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia dengan cara: mencium bendera merah putih, menyanyikan “Indonesia Raya” dan bersumpah di bawah Alquran menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia. Inilah informasi yang sudah beredar luas, bisa dibaca di berbagai media online.
Bagi penulis gaya-gaya seperti di atas adalah khas model kelompok vigilante. Kelompok massa yang suka main hakim sendiri, memonopoli kebenaran dan mengabaikan pluralitas dan hak-hak kewargaan, bahkan merasa sebagai warga negara kelas pertama. Tudingan palsu ditambah mungkin sedang berhalusinasi tentang keindonesiaan UAS.
Ustad Abdul Somad dan NKRI
Faktnya, UAS justru “bergerilya” masuk ke pedalaman hutan Sumatera (Riau) sembari menjunjung bendera merah putih, masuk hutan belantara menemui saudara sebangsa yang juga warga negara Indonesia yang dilupakan negara, yang belum kenal Pancasila dan NKRI yang dibangga-banggakan itu. Tanpa menuding masyarakat suku Talang Mamak tidak pancasilais. Tanpa juga mendaku bahwa dirinya atau orang-orang Melayulah yang paling cinta Indonesia. Semua dilakukan untuk menjaga NKRI, bukan untuk periuk nasi. Cukuplah foto-foto dan video yang diunggah di akun FB beliau sebagai bukti nyata aksi bersejarah tersebut. UAS berpancasila dalam perbuatan, bukan sekedar slogan dan teriakan.
Gerilya UAS bersama timnya itu justru demi tegak dan tertanamnya Pancasila, UUD 1945 dan merah putih di dalam dada masyarakat suku Talang Mamak. Mengajari dan mengenalkan anak-anak Talang Mamak tentang Pancasila dan warna merah putih. Bendera itu dipikul serta, ditempelkan, membariskan anak-anak dalam upacara bendera. Tak lupa melantunkan nyanyian kebangsaan “Indonesia Raya”, yang berkumandang di tengah belantara rimba raya Sumatera. Suara merdu anak-anak Talang Mamak menyanyi bersama suara jangkrik dan nyamuk-nyamuk hutan. Jauh dari tudingan mem-bid’ah-kan dan menyalahkan perihal hormat kepada bendera, seperti yang acap kali dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mengklaim “salafi” dan “hizbi” itu.
Nyanyian ibu pertiwi yang secara seksama, mungkin juga disaksikan para “Inyiak Balang” alias harimau Sumatera di antara semak-semak dan rindangnya pohon surian dan andalas. Dalam perspektif normatif ideologis, UAS telah melakukan sebuah tindakan “bela negara”. Kemudian juga dalam perspektif kewargaan, dia telah memberikan teladan dan aktulisasi nyata dengan apa yang disebut oleh Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2011) sebagai civic engagement (suatu keterlibatan kewargaan).
Persekusi atas nama Pancasila dan NKRI
Pola tudingan dan vonis semacam di atas tadilah yang marak terjadi di era pemerintahan sekarang, khususnya yang dilakukan oleh massa atau mengatasnamakan ormas tertentu. Setelah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kontroversial itu dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian disahkan oleh DPR. Rangkaian peristiwa persekusi ini makin marak terjadi. Persekusi yang dilakukan massa atas nama undang-undang negara.
Secara psikologis dan sosial, massa merasa sebagai kelompok yang paling pancasilais, paling cinta NKRI, paling toleran dan paling terdepan membela negara ini. Di sisi lain dengan serampangan mereka memvonis individu atau kelompok lain sebagai musuh, menuding dengan sebutan anti Pancasila, anti NKRI, intoleran dan radikal. Model seperti inilah yang akan mengoyak-ngoyak kebhinekaan kita.
Pada era Orde Baru, persekusi terjadi oleh tentara dan negara, karena tentaralah yang digunakan untuk menakut-nakuti rakyatnya. Ini sangat lazim terjadi di pemerintahan otoriter dimanapun di dunia. Tapi di era demokrasi yang seharusnya mengedepankan hak asasi manusia -kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa terancam, diperlakukan tidak adil dan perlindungan dari kekerasan apapun bentuknya- justru tidak terjadi. Aparatur negara justru tidak melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku persekusi.
Padahal sebagai pendidik, kami acap kali mengungkapkan di depan kelas, tentang hak asasi manusia yang secara eksplisit dalam Pasal 28 UUD 1945. Bahwa siapapun dia, termasuk warga negara Indonesia adalah berhak mendapatklan perlindungan dari kekerasan. Negara wajib menghadirkan perlindungan mutlak kepada warganya. Bukan berkompromi bahkan mensponsori pelaku kekerasan tersebut.
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Pasal 28G ayat 1).
Pembelahan sosial yang saat ini terjadi di masyarakat, seolah mengulang sejarah masa Orde Baru. Ada kelompok masyarakat yang dituding anti Pancasila (kemudian dikenal dengan sebutan “ekstrem kiri” dan “ekstrem kanan”) dan ada yang pancasilais. Pemilahan semacam ini tak lain merupakan watak asli dari pemerintahan yang otoriter. Rakyatnya sengaja dipecah-belah, agar lemah. Mungkin saja terinspirasi dari teori kekuasaan negara klasik ala Lord Shang Yang (Abad ke-3 SM) dan Niccolo Machiavelli (1469-1527). Bahwa pemerintah boleh berbuat apa saja demi kepentingan negara. Kemudian, agar negara dan pemerintahnya kuat, maka rakyatnya haruslah (di) lemah (kan).
Penulis tidak bermaksud menyamakan sepenuhnya pemerintahan saat ini dengan Orde Baru dulu. Karena di era Soeharto, tentu menyampaikan gagasan seperti ini saja adalah suatu hal yang sangat mustahil. Sekarang, terhadap gagasan sudah diberikan ruang yang lebar. Tapi fakta bahwa masyarakat kita saat ini sedang terbelah, adalah suatu realita empiris yang tak terbantahkan.
Menuding sesama saudara sebangsa sebagai yang tidak pancasilais, anti NKRI, radikal dan anti toleransi plus bertindak dengan persekusi. Justru tindakan semacam inilah yang mengotori Pancasila itu sendiri. Apakah masih laik disebut tindakan toleran? Apakah pantas dan tepat mengaku sebagai penjaga keutuhan NKRI, jika suka membelah dan memvonis saudara sebangsanya dengan posisi diametral “kami pancasilais” dan “mereka anti Pancasila?”.
Tentu kita tidak mengharapkan pembelahan sosial ini semakin larut. Sebuah konsekuensi logis dari politik murahan para politisi demi elektoral di Pemilu nanti. Persekusi adalah sebuah tindakan teror dan wujud radikalisme & intoleransi yang berbahaya. Tetapi akan jauh lebih berbahaya lagi, jika tindakan persekusi ini justru diproduksi dan difasilitasi oleh politisi atau penguasa dan aparat negara, untuk kepentingan politik elektoral semata. Yang ada dan bertahan bukan lagi diskusi, melainkan persekusi. Miris!
Mestinya bangunlah dialog yang setara, seperti yang ditirukan oleh M. Natsir dan IJ Kasimo dulu. Lahirkan musyawarah dan mufakat seperti yang dicontohkan Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo. Hidupkan kembali nilai-nilai luhur, “duduk sama rendah, tegak sama tinggi”, yang sering disebut-sebut Moh. Hatta dan Syahrir. Inilah yang penulis khawatirkan saat ini, yakni radikalisme, intoleransi dan premanisme yang berbaju Pancasila dan NKRI! Juga sama bahayanya dengan premanisme berjubah agama! Inilah ancaman terhadap Pancasila, NKRI dan kebhinekaan kita sesungguhnya.
Janganlah dengan jumawa kita mendaku sebagai yang paling Indonesia, yang paling nasionalis, paling pancasilais dan paling toleran. Mendaku dan merasa “yang paling” itu tidaklah elok. Agama apapun tidak membenarkannya. Sama halnya dengan merasa bahwa kelompoknya yang paling suci, merasa paling benar atau paling baik. Mengutip Alquran, Surat An-Najm ayat 32 yang artinya: “Maka janganlah kamu menganggap dirimu paling suci, Dia Allah mengetahui orang yang paling bertakwa.”
Semoga ke depannya, persekusi atas nama apapun; atas nama toleransi & kebhinekaan, atas nama agama, dan atas nama Pancasila & NKRI sudah sepatutnya dihentikan. Sebagai penegak hukum, bukanlah tugasnya organisasi masyarakat, tapi itu urusan para penegak hukum. Bagi penegak hukum, ingatlah ucapan klasik Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM); “Fiat justitia ruat coelum” yang berarti hendaklah tegakkan hukum, walaupun langit akan runtuh.
*Penulis adalah Pengajar Labschool Jakarta-UNJ/Wasekjen FSGI dan Pengurus AP3KnI
Ikuti tulisan menarik Satriwan Salim lainnya di sini.