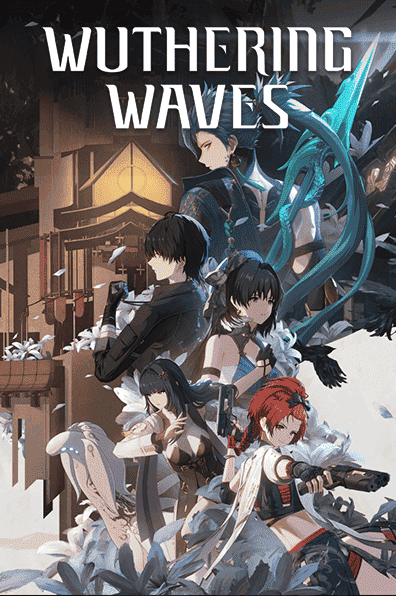Bandung Kota HAM itu, (in)toleransi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Hari HAM internasional ditetapkan setiap tanggal 10 desember dan menjadi tonggak bagaimana HAM diperingati, dilaksanakan termasuk oleh warga kota.
Foto oleh Frans Ari Prasetyo (Sept 2017-Flyover Pasopati Bandung)
Hari HAM internasional ditetapkan setiap tanggal 10 desember dan itu menjadi tonggak bagaimana HAM diperingati dan dilaksanakan dalam keseharian warga, termasuk warga kota Bandung. Nyatanya, Bandung telah menunjukan sebagai kota yang tidak ramah HAM dan menjadi lansekap intoleransi yang nyata. Berbeda sekali dengan jargon sebagai kota Juara dan kota Ramah HAM yang digembar-gemborkan selama ini, lalu dimana bukti indeks kebahagiaan itu?. Pemerintah Kota Bandung terkesan terburu-buru mengumbar klaim sebagai kota ramah HAM yang dimulai pada Konferensi Asia Afrika tahun 2015 lalu. Klaim ini jadi komoditas politik untuk mendapat simpati warga dengan menjejalkan citra kota yang baik, cerdas dan kreatif disertai oleh promosi figuratif sosok kepala daerahnya ke muka nasional dan dunia internasional. Nyatanya ini hanya politik artifisial, bukan politik substansial yang menyelesaikan perkara HAM ditataran keseharian warga sipilnya. Bandung menjadi kota (juara) yang memalukan peradaban kota. Ibaratnya ingin berdandan cantik tapi salah menggunakan kosmetik yang akhirnya mengakibatkan kanker ganas yang menggerogoti narasi kewargaan (kota) yang berbhineka dan berdemokrasi.
Peristiwa KKR pada desember tahun 2016 lalu, merupakan satu dari sekian peristiwa intoleransi yang terjadi dikota Bandung selama ini, menjadi bukti kemunduran demokrasi, kebhinekaan dan toleransi dari peradaban kota. Kita melihat bagaimana perlakukan diskiriminatif terhadap Syiah dalam setiap momen peringatan Hari Asyura dan juga terhadap Ahmadiyah yang terjadi hampir setiap waktu dalam moment-moment tertentu pulak. Apakah mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak boleh mempergunakan ruang publik yang notabene sebagai ruang yang demokratis dan egaliter. Tapi disisi lain ada sekelompok lainnya yang tentu saja mayoritas yang bisa dan dengan leluasa menggunakan ruang publik untuk hal yang serupa bahkan difasilitasi pemerintah.
Pelanggaran-pelanggaran ini menyasar kaum minoritas keyakinan seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen, dan minoritas agama lain. Bentuk-bentuknya termasuk pembatasan atau pelarangan atau perusakan tempat ibadah, pembatasan atau pelarangan ibadah dan kegiatan keagamaan, ancaman atau intimidasi kelompok keagamaan, pembatasan keyakinan, kriminalisasi lewat pasal penodaan agama, diskriminasi, dan pembiaran oleh aparat negara. Salah satu aturan yang kerap menjadi senjata dalam pelarangan ibadah adalah SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat yang menyebutkan untuk "melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam". Walau ini peraturan provinsi jawabarat datpi Bandung sebagai ibukotanya turut “mengamini” dan terkena dampak dari regulasi yang diskriminatif ini. Apakah ini adil, apakah ini toleran dan apakah ini yang disebut demokrasi?
Ada beberapa indikator yang menjadi parameter dalam melihat apakah sebuah daerah provinsi dan kota itu ramah HAM atau tidak dengan cara melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMD) Kota, Peraturan Daerah, pernyataan pemerintah, tindakan pemerintah terkait peristiwa intoleransi, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, dan demografi penduduk berdasarkan agama. Hal ini dapat merujuk kepada regulasi sosial yang kemudian dibentuknya dan dapat dilihat dari seberapa banyak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di suatu kota. Nyatanya sekarang ini, hampir di seluruh Indonesia, minoritas beragama termasuk muslim Syiah, beberapa gereja Kristen, dan Ahmadiyah, adalah target dari pelecehan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan.
Tidak hanya ancaman terhadap KBB yang tinggi di Jawabarat dan Bandung, tapi ancaman terhadap demokrasi pun menunjukan linearitas yang serupa dengan menggunakan topeng agama. Misalnya pementasan monolog Tan Malaka di Auditorium pusat kebudayaan Prancis, IFI, Bandung pada tahun 2016 lalu dimana sekelompok anggota ormas Islam datang dan membubarkan pertunjukan ini. Hal yang sangat disayangkan hal ini terjadi diruang publik, bahkan ruang yang steril secara politik karena adanya otoritas diplomasi sebagai perwakilan diplomatik suatu negara dalam hal ini diplomatik kebudayaan karena tempat berlangsungnya acara ini di sebuah tempat yang notabene merupakan representasi kedutaan negara Perancis di Indonesia yang kebetulan berada di kota Bandung. Anehnya pemerintah kota melalui walikotanya Ridwan Kamil yang mencetuskan Bandung sebagai kota ramah HAM dalam konferensi asia Afrika 2015 lalu tidak berbuat apa-apa pada waktu kejadian, malah setelah menjadi ramai pemberitaan menjadikannya sebagai arena politik kosmetika yang seolah menjadi kota tuan rumah yang ramah HAM. Lalu, dimana ramah HAMnya ketika kejadian, dimana demokrasi negara Indonesia ini mewujud nyata dalam keseharian, dimana tindakan tegas aparat atas sebuah tindakan yang merugikan orang lain apalagi ini diruang milik negara lain.
Hal ini dibuktikan jika merujuk kepada survei Wahid Foundation tahun 2016 yang menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk berpandangan dan berperilaku intoleran terus meningkat yang ditandai dengan provinsi Jawa Barat memasuki urutan pertama kasus intoleransi di Indonesia. Maka dari itu, apa yang terjadi di Bandung sebagai ibukota provinsi JawaBarat telah banyak menunjukannya. Selain itu dalam hasil riset Setara Institute tahun 2015, menunjukan bahwa tujuh kota di Provinsi Jawa Barat masuk dalam 10 besar kota yang dinilai intoleran dan Bandung termasuk didalamnya. Hal ini jelas menunjukan bahwa kota Bandung mengalami darurat toleransi walau tidak sepanjang waktu tapi potensi kemunculannya besar, sulit diprediksi dan hanya pada moment-moment tertentu.
Sedangkan menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jawa Barat masih memiliki 46 kebijakan yang diduga melanggar KBB dan diskriminatif. Data ini menunjukkan pemerintah kota di Jawa Barat produktif dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB. Pemerintah provinsi Jawabarat termasuk Bandung sebagai legitimasi ibukotanya nyatanya masih terjebak dalam budaya sektarian. Salah satu penyebab utama lahirnya kebijakan yang melanggar KBB adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama. Kelompok-kelompok ini dapat berupa organisasi keagamaan maupun himpunan massa yang mengatasnamakan agama tertentu.Tidak hanya itu, The Islah Center (TIC) Mujahidin Nur pun menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi di Indonesia sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute pada 2015 yang menunjukan kepada tingginya kejadian intoleransi di Jawabarat termasuk kota Bandung.
Sebagai contoh saja bagaimana peristiwa-peristiwa diatas dapat terjadi dan kita bisa mengambil contoh nyata dalam peristiwa KKR tahun 2016 lalu. Jika melihat keterkaitannya dengan berbagai peristiwa intoleransi yang terjadi di Bandung selama ini termasuk peristiwa pada acara KKR, antara pihak kota dan provinsi kemudian saling lempar tanggung jawab, Ridwan Kamil menyebut acara KKR berada dalam level Pemprov Jawa Barat, sementara Ahmad Heryawan menyebut Wali Kota Bandung lebih tahu terkait persoalan tersebut. Padahal acara tersebut telah mendapatkan ijin dari Kepolisian dan dalam website Sabuga sebagai tempat berlangsungnya acara tersebut menyebutkan bahwa fasilitas Sabuga sebagai fasilitas komersial umum yang bisa digunakan untuk beragam acara termasuk acara keagamaan. Jadi ini bukan perkara sebagai sebuah kesalahan prosedur administrasi perijinan dan penyalahgunaan fungsi penggunaan tempat atau ruang publik semata, tetapi terdapat gerakan intoleransi yang sebenarnya merupakan fasisme sekelompok orang yang mengatasnamakan mayoritas dan agama.
Merespon kejadian intoleransi tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan 10 poin pernyataannya melalui media sosial padahal sebagai otoritas kota mampu memberikan satu penekanan melalui peran negara dengan cara membuat surat resmi pernyataan sikap negara/kota melalui sikap politik sebagai pemimpin daerah yang mewakili negara, bukannya melalui media sosial pribadi saja yang hanya menunjukan sikap pribadi. Selain itu yang disesalkan kemudian adalah pernyataan Gubernur JawaBarat yang bilang bahwa peristiwa tersebut sebagai perkara kecil. Jika hal ini terus terjadi, Kota ramah HAM cuma utopia dan kosmetika semata. Klaim kota ramah HAM menjadi gemerlap euforia politik kota dengan menggunakan simbolisme kekuasaan yang bekerja untuk mendapatkan simpati publik dalam penentrasi simbolik seremonial semata.
Pada waktu itu, publik kota Bandung yang tergabung dalam Forum Demokrasi Bandung merespon cepat menyatakan sikap terkait kejadian diatas dengan memaparkan kronologis peristiwa dan membuat 7 point pernyataan yang disepakati bersama hingga mendapatkan dukungan publik dengan terkumpulnya 303 tandatangan dukungan perseorangan dan 73 dukungan organisasi dan simpul komunitas. Dukungan publik sudah tergalang, tapi tetap diperlukan kehadiran negara, sehingga peristiwa intoleransi dalam format dan bentuk apapun tidak boleh terjadi dikota, provinsi dan di negara ini. Ini menjadi contoh menarik bagaimana warga kota Bandung masih tetap memegang teguh narasi kewargaan yang berbhineka.
Hal diatas merupakan contoh saja dan apa yang terjadi di Bandung merupakan representasi bahwa negara yang terwakili oleh pemimpinnya yang alpa dan abai bahwa negara perlu hadir dalam ruang-ruang (publik) sipil sebagai wakil masyarakat sipil dan otoritas kehidupan publik yang memiliki legitimasi hukum negara untuk menegakan toleransi. Kita harus melihatnya bukan hanya persoalan keagamaan semata, tapi ini persoalan narasi kebangsaan dan demokrasi bahwa ada persoalan fasisme tengah terjadi disekeliling kita. Jika berbeda, Fasisme siap membungkam. Betapa mengerikannya hidup diruang (kota) seperti itu ?.
Selain itu, ketidakpahaman pemerintah kota dan ketidakmampuan pemimpin lokal memberikan arahan yang benar sesuai perundangan adalah alasan utama tren pelaku pelanggaran tersebut. Masih banyak birokrat dan politikus di pemerintahan yang tidak paham perlindungan dan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi termasuk aparatur negara yang lebih tunduk pada fatwa mayoritas dengan menafikan UU yang berlaku di negara ini. Penerapan hukum yang tajam pada minoritas dan tumpul pada mayoritas, solidaritas negatif, serta saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kota dan provinsi menjadi langgam sinetron politik dari sebuah toleransi yang seharusnya berlaku nyata.
Pemanfaatan ruang publik bagi kegiatan keagamaan tidak mengganggu netralitas ruang publik itu sendiri, karenanya penggunaan dan pemanfaatan ruang publik sebagai ruang bersama secara bergiliran dalam konteks ini dapat dilakukan sebagai bagian dari kerja HAM yang melekat pada publiknya. Ruang publik yang digunakan bersama menjadi arena bergaul, toleran dan saling menawarkan nilai baik bukannya memjadi arena pertentangan. Upaya sterilitas ruang publik dengan legitimasi tertentu, dalam konteks ini melalui agama justru mengingkari hakekat dari ruang publik itu sendiri dan menjadi tidak netral. Keadaban publik dan HAM diuji dalam ruang publik dimana masyaraka mempraktikan kebajikan dan nilai tawarnya sebagai mahluk sosial yang toleran.
Jika kota ramah HAM hendak terwujud, sepatutnya negara melalui pemerintah kota Bandung melihat poros gerakan HAM dalam kacamata internasional walaupun kota akan bekerja dalam aras lokal melalui skema desentralisasi. Piagam Dunia tentang Hak atas Kota tahun 2005 yang berlanjut kepada agenda piagam global tentang HAM di kota pada tahun 2010 menjadi landasan utama pembentukan kota ramah HAM dalam skala internasional. Dalam skala regional , piagam ASEAN melalui pembentukan AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) menjadi pijakan kerjasama antar negara Asia Tenggara untuk mendorong upaya penajuan HAM dikawasan ini. Jauh panggang dari api, nyatanya untuk perwujudan Bandung sebagai kota ramah HAM tidak ditopang oleh skema regulasi yang mendorong upaya ke arah sana. Tidak adanya peraturan daerah yang menaungi payung hukum dari klaim kota ramah HAM tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa utopia kota HAM dalam sudut pandang ini sedang terjadi. Kalau pun terdapat payung hukumnya, tetapi tidak akan menjamin bahwa pelanggaran HAM dikota ini akan mendapatkan keadilan HAM yang memadai sebagai bagian dari Hak atas kota walaupun menggunakan preferensi dari piagam Dunia tentang Hak Atas Kota. Padahal dalam laporan perkembangan komite penasehat tentang peran pemerintah daerah dalam memajukan dan melindungi HAM, termasuk pengarusutamaan HAM dalam pemerintah lokal dan layanan publik yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2014 menjelaskan pentingnya kerangka hukum dalam implementasi HAM (dalam hal ini skala pemerintah daerah-kota).
Anehnya, sekian banyak rentetan peristiwa intoleransi di Bandung sebagai ibukota Jawabarat, kota Bandung malah mendapatkan penghargaan sebagai kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2016 dari Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 10 desember 2017 lalu tepat di hari peringatan hari Hari HAM internasional. Bukankah ini menjadi anomali sedangkan kenyataan dilapangan kota Bandung ini jauh dari ramah HAM bahkan kesan peduli HAM pun sangat minor terasa. Sebenarnya jika merujuk kepada KUHP pasal 175 dan 176, termaktub jelas bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh diancam dengan pidana penjara. Jika melihat pasal ini, mestinya negara bisa hadir melalui pemerintah dan pihak kepolisian agar adanya proses hukum yang berlaku di negara ini dan jika itu terjadi tidak mustahil bahwa negara menjadi payung legitimasi atas berlakunya HAM yang kongkrit. Kota Bandung bisa memulai pranata hukum dan kehadiran perannya yang kongkrit untuk memberikan hak atas kota kepada warganya melalui HAM yang juga selaras dengan kearifan dan toleransi yang tebal dari warganya, maka jika itu terjadi kosmetik kota HAM itu tidak akan luntur dan tetap terpelihara dan kota ramah HAM bukan sekedar utopia di Bandung.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Arsitektur Masjid Al Jabbar Plagiat?
Senin, 14 Agustus 2023 15:35 WIB
Dari World Bank ke Global Land Forum: dari Setan Kredit ke Setan Tanah
Sabtu, 15 April 2023 07:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0