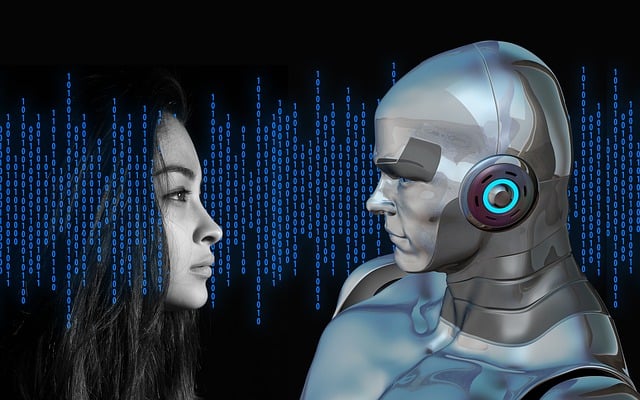“People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don't know is what what they do does.”
Pemikiran bernas-cerdas Michel Foucault dalam Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason ini seakan menjadi salah satu pilihan kerangka pikir dalam menghadapi virus yang menguras otak dan benak kita.
Orang Tahu Apa yang Mereka Lakukan
Secara alami —sejak tinggal di gua sampai tinggal di dunia maya— manusia secara naluri tahu apa yang dikerjakan untuk menjaga diri tetap aman. Teori Darwin pun kembali mendapatkan tempatnya. Di saat pandemi, kita otomatis tahu apa yang kita lakukan, yaitu menjaga diri tetap sehat dan menghindarkan diri dari bahaya. Namun, saat perut melilit dan sembako tinggal selilit, tubuh dipaksa untuk melejit.
Himbauan, larangan sampai ancaman tetap kita sampingkan agar tubuh tidak semakin kurus kering. “Aku lebih takut anak istri kelaparan ketimbang virus korona!” Tulisan sindiran ini menyiratkan ‘tekad’ di tengah bahaya yang kelewat batas. Bukankah semut pun akan menggigit saat terinjak?
Kenekadan ini, oleh beberapa orang, bahkan dilakukan jauh lebih gila lagi. Entah karena merasa sok jagoan, atau menantang agar orang tidak takut melawan Covid-19, ada orang yang berani menyedot dahak seseorang! Sebelum dinyatakan secara resmi bahwa virus ini bisa menyebar dan ditularkan lewat udara (aerosol), bukankah droplet yang paling kita takuti?
Bahkan di dalam karya Plato, Timaeus, pun penderita epilepsi dikaitkan dengan keberadaan dahak dan empedu hitam dalam jiwa rasional. Bukankah otak dan kepala seseorang bisa saja dipenuhi ‘dahak’ dan ‘empedu hitam’ sehingga tidak lagi berpikir rasional?
Seringkali Orang Tahu Mengapa Mereka Melakukan Apa yang Mereka Tahu
Menghindari kerumunan, menyemprotkan desinfektan, mengoleskan hand sanitizer, sering mencuci tangan pakai sabun, bahkan mandi dan ganti pakaian sesegera mungkin setelah menghabiskan waktu di luar merupakan protokol kesehatan yang nempel di benak kita. Rasanya sampai bosan mendengar kalimat itu diulang-ulang baik oleh pemerintah maupun keluarga.
Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu memang baik bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak lagi tersinggung seperti pada awal pandemi jika ada orang yang menolak salaman dengan kita. Siapa tahu bukan ‘dia’ yang OTG, eh, suspect, eh ganti istilah apa lagi? Bisa jadi justru kita yang pembawa bencana tak kasat mata.
Namun, Apa Kita Benar-Benar Tahu Apa Dampak dari Apa yang Kita Lakukan?
Dampaknya sungguh multifaset dan multidimensi. Bagi diri kita sendiri, misalnya, jika kita menjaga diri sedemikian rupa, bisa jadi kita memang terhindar dari virus yang tak gampang tergerus ini. Namun, jika kita tidak beraktivitas maksimal, perekonomian baik mikro maupun makro akan terganggu. Negara tetangga seperkasa Singapura pun terancam resesi. Pengusaha raksasa di bidang migas di sana pun sudah lebih dulu terpapar dan terkapar.
Sahabat yang yang bergerak di bidang horeka (hotel, restoran, kafe) bukan hanya harus menutup beberapa outlet bisnisnya, melainkan beralih profesi menjadi dan mengerjakan ‘apa saja’ yang hasilnya masih tidak menentu. Sektor ekonomi yang anjlok bahkan sampai lebih dari 90% membuat semut di dalam diri kita bukan hanya menggeliat, melainkan meloncat. Dalam sebuah webinar yang saya pimpin, saya memakai istilah ‘Bounce Back’.
Saat bicara via daring, saya pun gamang, benarkah kita bisa benar-benar memantul tanpa takut terpukul KO? Seperti jungkat-jungkit, saat ekonomi kita beri kesempatan untuk naik, risiko penurunan kesehatan bisa terjadi. Bukankah pelonggaran PSBB di mana-mana membuat virus kembali kluyuran ke mana-mana? “Keramahan kitalah yang membuat korona merasa betah!” Sebuah tulisan yang saya dapatkan di sebuah media cetak tampaknya hendak menyindir pilihan sikap ini.
Lalu, Bagaimana?
Saat mengajukan pertanyaan itu kepada diri sendiri, perkataan filsuf Perancis itu kembali menyeruak hebat. “Death as the destruction of all things no longer had meaning when life was revealed to be a fatuous sequence of empty words, the hollow jingle of a jester’s cap and bells,” ujar Foucault.
Kita perlu keluar dari diskursus ke direksi khusus, dari wacana ke wajib terlaksana. Penanganan pandemi yang terlalu berhati-hati, pengumbaran rapat internal ke ruang publik dan tindakan lanjutan yang setengah hati justru membuat masyarakat gerah. Jika kematian yang menurut Foucault bisa meluluhlantakkan semua sendi kehidupan tidak lagi memiliki makna yang menyengat membuat kehidupan terasa seperti retorika dan kata-kata hampa. Persis isi topi dan terompet badut saja. Lagu yang keluar pun terdengar basa basi.
Ketimbang ditarik dari dua sisis ekstrem yang sama-sama mematikan —optimisme hampa yang bisa jadi PHP dan paranoid yang membuat kita sakit dan terhimpit— lebih baik kita mengambil langkah pragmatis dengan senyum dan tawa di sana-sini. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang mujarab? Ucapan Joyce Meyer ini terasa pas di hati: “If you can't learn to enjoy your life when you have problems, you may never enjoy it because we'll always have problems.”
Sebuah meme menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Ian Malcom dalam film legendaris Jurassic Park “Life will find a way”. Meme yang membuat saya tersenyum itu bertulisan: “Eventually, everyone will be quatantined to their houses with no sports to watch… and in 9 months from now a boom of babies will be born… and we will call them Coronials.”
- Xavier Quentin Pranata, pelukis kehidupan di kanvas jiwa.
Ikuti tulisan menarik Xavier Quentin Pranata lainnya di sini.