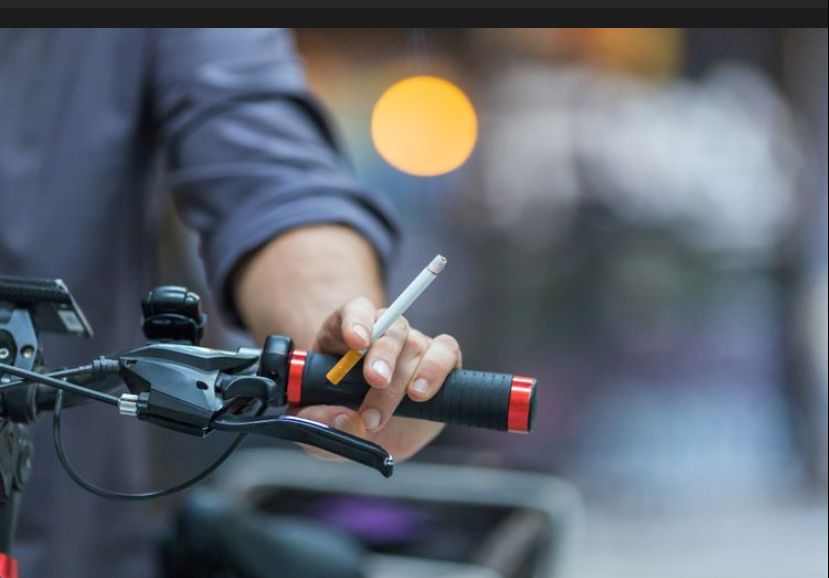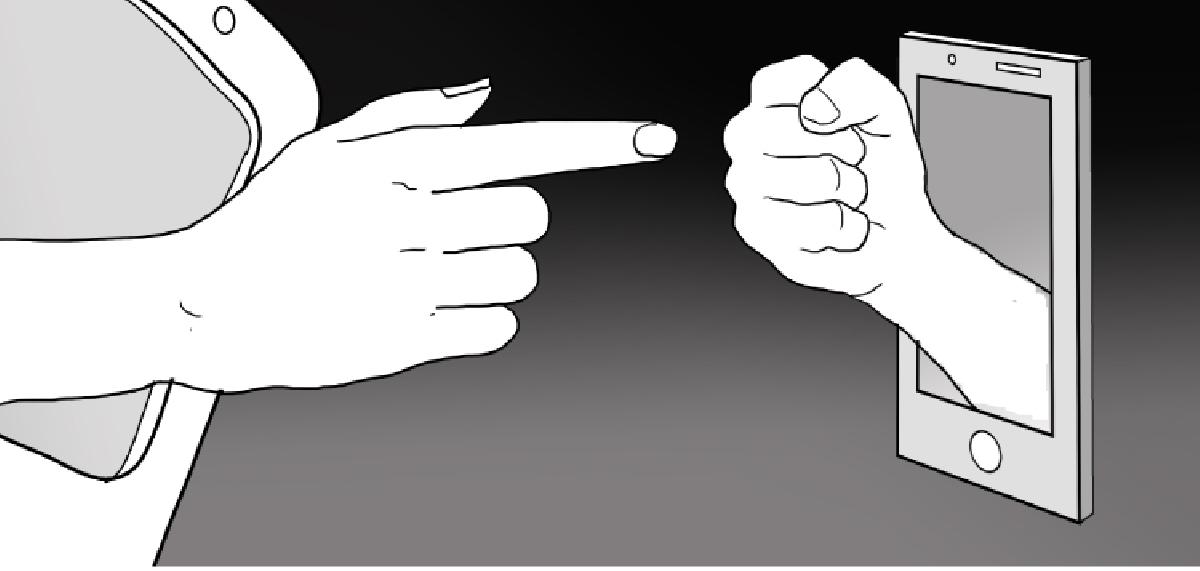al quran
Bukan karena saya tidak butuh, atau sok kaya, dan tidak butuh duit. Sebab di dunia ini siapa yang tidak butuh duit. Semua kita butuh, termasuk saya. Bagi saya : duit memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Mungkin kalimat ini Ada setuju. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Sebab Anda punya hak penuh untuk tidak sepakat.
Kalau saya katakan alergi terhadap bantuan pemerintah, bukan kemudian saya menolak bila dikemudian hari diberi bantuan. Tetapi, yang membuat saya risih dan gerah, sejarah perjalanan saya mulai mahasiswa di era 90-an, bahkan sampai di era 2000-an, tradisi potongan dari uang proposal seolah sudah menjadi kewajiban, bagi siapapapun ketika kita mencairkan anggaran.
Sebagian orang mengatakan, itu adalah etika kepada aparat negara yang sudah membantu melakukan pencairan duit. Atau kalau bahasa Palembang-nya: Kalu ado wong yang mbantu caierke duit, kito harus ado caro. "Ado caro" itu istilah Wongkito yang berarti etika atau adab. Meskipun dua kata ini maknanya sangat berbeda.
Melihat itu, kadang saya memberotak. Bukan dengan demo ke jalan, atau bunuh diri, bukan. Tetapi bisa melalui tulisan, baik cerpen, puisi, opini atau apapun yang bisa saya lakukan, termasuk mungkin saya harus menulis berita, yang harus saya muat di media saya.
Pertanyaannya, kalau harus memberi duit dan memotong yuang proposal, memang itu duit siapa? Itu kan duit kita? Duit pajak dari rakyat, kenapa harus dibagi lagi pada pemerintah? Lalu orang bilang, itu kan oknum. Bukan lembaga. Saya katakan benar, itu oknum. Tapi okum itu pakai seragam pemerintah. Kata pepatah: Gara-gara Nila setitik rusakl susu sebelanga. Hanya karena ulah oknum yang sedikit, dan terbiar. Akhirnya nama baik pemeirntahan, saya tidak mengatakan nama baik presiden, gubernur dan bupati, rusak semua, oleh karena gara-gara ulah oknum yang berbaju pemerintah.
Oleh karena risih dan alergi ini, sampai akhirnya ketika saya melihat sejumlah ustadz-ustadz yang berjuang di lembaga pendidikan agama non pemerintah, satu diantaranya Rumah Tahfidz, saya kemudian bertanya-tanya: Ini ratusan ustadz, guru ngaji bersusah payah mengajari santri-santri, calon pengganti generasi bangsa, tapi kok nasibnya miris. Lantas saya bertanya, kemana peran negara?
Diantara mereka ada yang beralasan sama dengan saya. Katanya. malas mengajukan bantuan ke pemerintah, sebab selalu ada potongan. Saya bilang, itu hak kita, itu hak para guru ngaji, hak para ustadz, harus diambil. Sekali lagi, ustadz itu berkata."Saya tidak mau ada potongan, saya takut dengan pertangngjawaban di akhirat."
Masya Allah! Kata-kata itu membuat saya merinding. Jantung saya berdetak kencang. Kisah itu, mengingatkan Saya pada kisah yang lain yang juga membuat saya marah, membuat darah saya hampir mendidih, karena ada ustadz yang berksiah, tentang sikapnya yang juga menolak bantuan pesantren sebesar 100 juta dari untuk pesantrennya karena harus dipotong 50 persen.
Tentu masih banyak kisah lain yang juga dialami para ustadz, kiai dan guru ngaji yang serupa dengan gaya yang berbeda, termasuk nasib rumah tahfidz se-antero jagad Indonesia.
Kelau kemudian melihat kenyataan ini, saya kian miris pada nasib guru para kiai, ustadz, dan para guru ngaji di dusun-dusun, yang tetap konsisten mengajari santri-santrinya membaca Al-quran. Mereka mengajari ilmu dunia dan akhirat. Sebab Al-quran pedoman hidup untuk bekal kematian bagi setiap nyawa manusia. Tapi harganya lebih murah dari pada seutas kangkung di Pasar 16, upahnya lebih rendah dari mandor dan kuli bangunan.
Saya tidak menuduh siapa yang salah. Tapi inilah potret buram, betapa empatik negara terhadap kiai, ustadz, guru mengaji, demikian rendah. Bukan hanya negara, tetapi mungkin sebagian kita juga tidak atau kurang memahami dan nyaris tidak menghargai mahalnya ilmu Al-quran yang selama ini diajarkan oleh para kiai, ustadz dan guru mengaji, baik secara personal atau kelembagaan.**
Palembang, Agustus 2020
Ikuti tulisan menarik Imron Supriyadi lainnya di sini.