Kecemasan Politisi Kehilangan Eksistensinya
Jumat, 24 September 2021 21:15 WIB
Apakah kekuasaan ditujukan untuk membuat orang lain berdiri tak nyaman, duduk tak enak, makan tak kenyang, hingga tidur tak nyenyak? Juga berbicara dengan bibir bergetar dan keringat dingin merayapi tubuh? Bukankah sebaliknya yang semestinya terjadi?
Kekuasaan telah jadi bagian penting dalam politik, bila bukan yang terpenting bagi para politisi. Entah berapa banyak politisi yang berusaha duduk di kursi kekuasaan dengan melakukan apa saja. Hasrat kuat pada kekuasaan ini berpotensi membuat politisi kehilangan pegangan: apakah kekuasaan menjadi tujuan atau sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat lahir batin?
Ketika kekuasaan jadi tujuan, setelah menang dalam kompetisi politisi akan cenderung menjadikan dirinya pusat segala sesuatu [self-centring]. Dari kursi kekuasaan, politisi sejenis ini memandangi dunia sekelilingnya: rakyat, wilayah, sumberdaya, lawan dan sekutu, wewenang, dan seterusnya—segala sesuatu yang membuat dirinya merasa lebih penting dibandingkan lainnya.
Kekuasaan perlahan mengubah dirinya sebagai manusia baru yang di tangannya tergenggam wewenang untuk melakukan banyak hal—termasuk yang sebelumnya tak mampu ia lakukan. “Oo, alangkah besar kuasa dalam genggamanku,” barangkali begitu ia berujar. Minuman hangat dan kudapan tersedia di mejanya tanpa ia perlu memintanya. Sarapan lengkap tertata rapi di meja makan. “Apakah Tuan menginginkan menu khusus untuk makan siang?” tanya pelayan takzim.
Banyak orang datang kepadanya dan bertanya dengan bibir gemetar: “Kami telah mengerjakan sejumlah hal, mohon petunjuk bagaimana langkah selanjutnya.” Apa yang membuat kursinya berbeda ialah pengaruh yang ditimbulkan, yang membuat manusia lain mengikutinya—sukarela ataupun terpaksa. Ia kini dalam posisi dimintai petunjuk, saran, perintah; dan ia menikmati ketika orang-orang mengajukan permintaan itu. “Ini rupanya perbedaannya,” gumamnya sembari menatap orang-orang yang tak berani melepaskan pandangan dari dirinya.
Kekuasaan telah mengubah relasi di antara dirinya dan orang-orang sekelilingnya, padahal mereka orang-orang yang sama secara lahiriah. Ia menikmati keheningan tiba-tiba manakala ia memasuki ruangan. Percakapan terhenti seketika. Tak ada yang bersuara sebelum ia berbicara dan tak ada yang bersuara sebelum ia mengizinkan yang hadir berbicara.
Tapi apakah kekuasaan ditujukan untuk membuat orang lain berdiri tak nyaman, duduk tak enak, makan tak kenyang, hingga tidur tak nyenyak? Juga berbicara dengan bibir bergetar dan keringat dingin merayapi tubuh? Bukankah sebaliknya yang semestinya terjadi?
Bukankah kekuasaan semestinya membuat yang menggenggamnya merasa khawatir ada kewajiban yang belum ia tunaikan, ada janji yang belum ia penuhi, dan ada amanah yang tak mampu ia jaga. Bukankah kekuasaan semestinya membuat hatinya gelisah karena cemas tergoda untuk menyalahgunakannya demi dirinya sendiri, keluarganya, kerabatnya, hingga kawan-kawannya.
Bukankah kekuasaan mestinya membuat penggenggamnya khawatir tak mampu mempertanggungjawabkannya—bukan kepada manusia semata, tapi yang lebih penting kepada Sang Pemberi Kuasa, yang perhitungannya demikian detail dan dahsyat. Tak ada satu zarahpun yang luput dari pengamatannya—termasuk satu zarah penyimpangan kekuasaan. Tak ada satu zarahpun yang luput dari permintaan pertanggungjawaban. Tapi, tak setiap orang mengerti, terlebih ketika ia tengah berkuasa.
Lihatlah bagaimana banyak orang datang kepadanya dengan kegalauan: terombang-ambing di antara cemas dan gembira. Sebagian orang keluar dari istananya dengan wajah tegang dan tertunduk, sebagian lainnya terlihat riang sembari melambai-lambaikan tangan. Lihatlah, betapa orang-orang berebut menjadi juru bicara dan juru tafsir baginya. Ia pun bergumam: “Betapa menyenangkan kekuasaan, orang-orang berebut ingin jadi penyambung lidahku.”
Tidak mengherankan bila kehilangan kekuasaan adalah persoalan eksistensial, sebab mereka tahu, begitu turun dari kursi kekuasaan, mereka tidak lagi diistimewakan oleh manusia lainnya layaknya orang yang sedang berkuasa. Perintahnya tidak lagi berlaku, ucapannya tidak lagi sangat diperhatikan. Itulah yang terjadi manakala manusia bergantung kepada kekuasaan. Mereka cemas setiap kali waktu berjalan semakin mendekati masa akhir kekuasaannya. Karena itu, ia tak ingin melepasnya. Ia tidak ingin kehilangan eksistensinya. >>
Penulis Indonesiana
2 Pengikut

Di Balik Dugaan Manipulasi Angka Statistik ala Rezim Prabowo
Rabu, 27 Agustus 2025 18:54 WIB
Di Balik Amnesti Hasto: Prabowo dan Megawati Sepakat Mengubah Permainan
Sabtu, 2 Agustus 2025 08:59 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
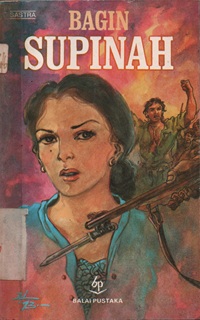






 98
98 0
0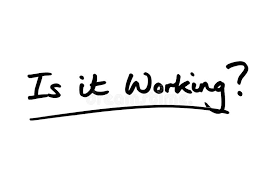





 Berita Pilihan
Berita Pilihan













