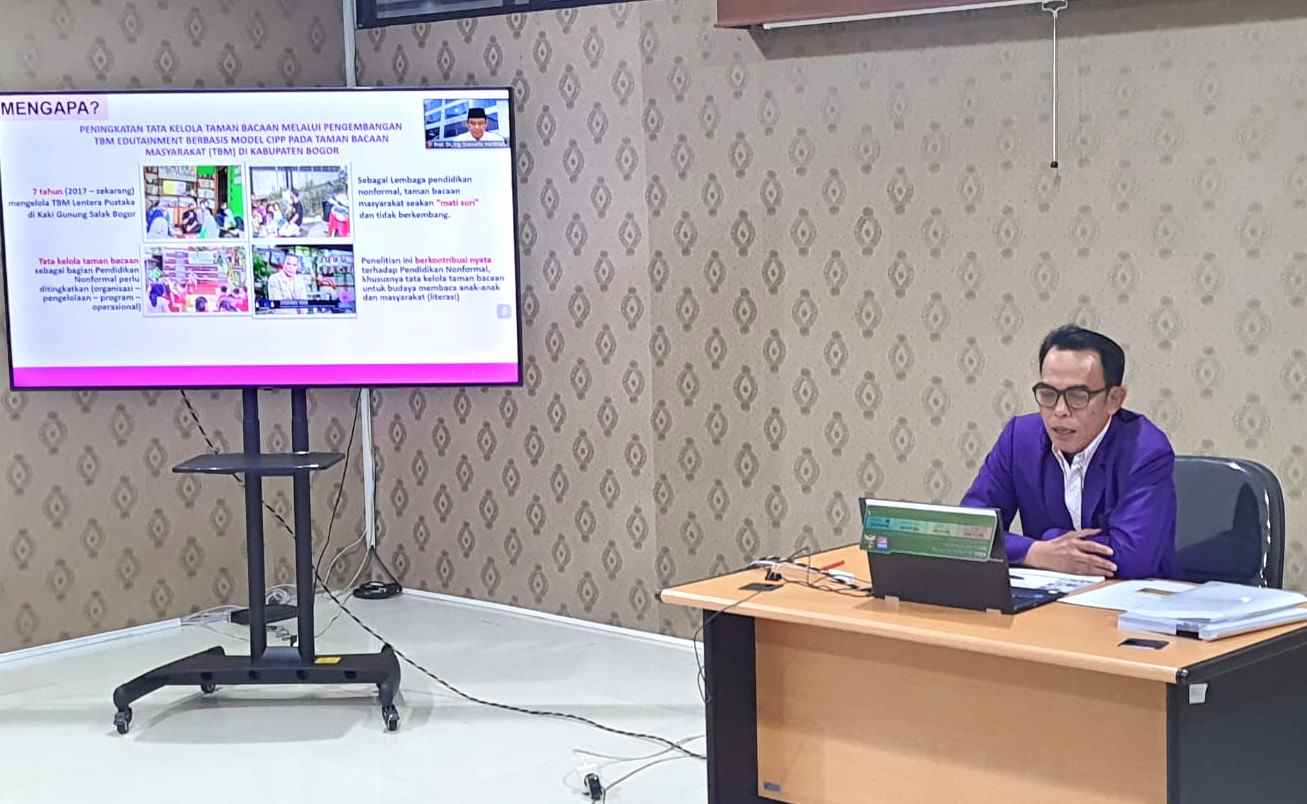Anita Lie, Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unika Widya Mandala Surabaya
Menjadi guru--dengan segala inflasi makna dalam berbagai jargon yang terkait mulai dari pahlawan tanpa tanda jasa, digugu lan ditiru, panutan, orang tua kedua, dan sebagainya adalah suatu penjelajahan dan perjalanan emosional, intelektual, dan spiritual. Kita beruntung dalam bahasa Indonesia kata guru tidak diterjemahkan seperti dalam bahasa Inggris menjadi teacher. Guru mengandung makna yang lebih luas dan dalam dibandingkan teacher (seseorang yang mengajar). Dalam bahasa Inggris, ketika seseorang mau mengungkapkan makna yang lebih dalam terkait dengan profesi pendidik, dia mesti beralih dari teacher dan menggunakan kata educator, pendidik.
Secara etimologis, kata educator ini berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, educare yang berarti membentuk atau melatih dan educere yang berarti menarik keluar. Dua makna berbeda ini juga mewarnai paradigma berbeda dalam teori, aliran, dan praktik pendidikan. Pada paradigma yang dibungkus dalam kata yang pertama educare, pendidikan dipandang sebagai proses pelestarian nilai-nilai luhur dan penyampaian ilmu pengetahun serta pembentukan orang-orang muda dalam model orang tua mereka. Sebaliknya, paradigma educere diterjemahkan sebagai persiapan generasi muda untuk menghadapi perubahan dan menciptakan solusi untuk permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya. Paradigma pertama membutuhkan ketaatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan menjadi pekerja yang baik sementara paradigma kedua membutuhkan kemampuan menanya, berpikir, dan mencipta (Bass & Good, 2004). Sampai saat ini pun, perdebatan antara dua kubu paradigma ini masih berlanjut.
Bagaimana dengan makna guru dan penerapan makna ini dalam profesi guru di Indonesia? Sementara itu dalam bahasa Inggris, kata guru masih digunakan hanya untuk menyebut seseorang dengan tingkat kepakaran dan kearifan yang luar biasa (seperti misalnya, Amartya Sen is the guru of economics who was awarded the 1998 Nobel Prize in Economic Sciences), dalam bahasa Indonesia, kata guru digunakan secara umum untuk semua orang yang mengajar dan mendidik mulai dari Guru Besar, guru sekolah, sampai dengan guru les.
Dalam bahasa Sansekerta, guru ( गुरू ) lebih dari seorang pengajar. Seorang guru adalah juga seorang ahli, konselor, saga, sahabat, pendamping dan pemimpin spiritual. Kata guru kemudian diadopsi ke dalam bahasa Hindi, Marathi, Bengali, Gujarati, dan banyak bahasa lainnya termasuk bahasa Indonesia. Sebagai kata benda, guru berarti tempat sakral ilmu pengetahuan. Sebagai kata sifat, guru berarti berbobot karena ilmu pengetahuan dan kearifan spiritual. Etimologi esoterik dari istilah guru menggambarkan suatu metafora peralihan dari kegelapan menjadi terang. Suku kata gu (गु) berarti kegelapan dan ru (रू) berarti terang. Jadi guru bermakna seseorang yang membebaskan orang lain dari kegelapan karena ketidak-tahuan dan ketidak-sadaran (Lie, 2008).
Cahaya Bangsa
Makna pembebasan dari kegelapan melalui profesi guru menjadi bagian penting ingatan kolektif bangsa Indonesia. Cahaya para guru bangsa sejak pra-kemerdekaan sampai dengan masa kontemporer terus menerangi perjalanan anak-anak Indonesia dalam perjuangan menjadikan negara dan bangsa yang beradab, tangguh, maju, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Dalam dunia fiksi, Andrea Hirata menulis dalam ”Laskar Pelangi”, ”Guru yang pertama kali membuka mata kita akan huruf dan angka-angka sehingga kita pandai membaca dan menghitung tak ’kan putus-putus pahalanya hingga akhir hayatnya. . . . Dan tak hanya itu yang dilakukan seorang guru. Ia juga membuka hati kita yang gelap gulita.” Pengalaman Hirata mengingatkan kita pada kerja mulia seorang Anne Sullivan yang berhasil membebaskan Helen Keller dari kegelapan dan keterasingan karena keterbatasan mata dan pendengarannya.
Dalam dunia nyata, sejarah pendidikan di Bumi Nusantara mencatat bangsa Indonesia mempunyai model para guru bangsa, di antaranya Raden Ajeng Kartini, Ki Hadjar Dewantara, yang dikenang sebagai pahlawan yang menumbuhkan dan menyebarkan kode kebangsaan di kalangan para perintis bangsa. Selain itu, pada masa persemaian kode kebangsaa ini, ada peran serta para tokoh yang menjadi bagian dari komunitas guru.
Ketokohan Kartini dalam sejarah pendidikan di Tanah Air tertulis dalam buku ”Dari Kegelapan Menuju Cahaya ” (Door Duisternis tot Licht) yang kemudian pada 1922, diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan judul ”Habis Gelap Terbitlah Terang” yang memuat kumpulan surat Kartini kepada J.H. Abendanon, seorang sahabat Kartini berkebangsaan Belanda. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan kegelisahannya terhadap isu-isu ketidaksetaraan yang ada di Tanah Jawa pada masa kolonial dan harapannya untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan pendidikan di Bumi Nusantara. Kartini bukan hanya menulis, namun secara nyata juga berjuang untuk mendirikan sekolah untuk para perempuan.
Satu dekade setelah kelahiran Kartini, lahirlah seorang Raden Mas Soewardi Soerjaningrat pada 2 Mei 1889 dari keluarga Kadipaten Pakulaman di Yogyakarta. Bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ernest Douwes Dekker, Soewardi muda pernah diasingkan ke Belanda mulai 1913 hingga 1919. Sepulangnya ke Tanah Air, Soewardi menulis kritik-kritik tajam kepada kolonial dan harus berurusan dengan aparat pemerintah dan keluar-masuk penjara. Kemudian, Soewardi memutuskan mengubah strategi perjuangannya dengan jalan lain, yakni lewat pendidikan. Pada 3 Juli 1922, Soewardi mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Cita-cita Taman Siswa adalah untuk membahagiakan bangsa dan manusia serta merupakan panggilan nurani untuk ikut memajukan kehidupan bangsa. Soewardi menawarkan gagasan untuk pendidikan nasional. Jadilah Taman Siswa sebagai tonggak awal kebangkitan masyarakat terpelajar Bumiputera yang mempelopori kebangkitan rakyat melawan kolonialisme. Pada 3 Februari 1928, Soewardi mendeklarasikan darma baktinya dalam dunia pendidikan melalui perubahan namanya menjadi Ki Hajar Dewantara.
Kartini dan Ki Hajar Dewantara tidak berjuang sendiri. Pada masa itu, ada simpul-simpul perjumpaan pikiran dan hati di antara para pemikir dan pejuang. Dalam buku “Pendidikan yang Berkebudayaan”, Yudi Latif mencatat bahwa hingga akhir abad ke-19 kaum gurulah yang pertama kali mempromosikan gerakan kemajuan: kaum guru pula yang memelopori pembentukan ruang-ruang publik modern. Sebagai intelektual baru, guru mengemukakan konsep ‘kemajuan’ sebagai tolok ukur baru dalam menentukan privilese sosial. Gagasan kemajuan dan kritik kaum guru diartikulasikan dalam ruang publik melalui media cetak dan berbagai perkumpulan yang mereka dirikan, seperti Soeloeh Pengadjar (sejak 1887) dan Taman Pengadjar (sejak 1899), beserta perkumpulan guru yang paling berpengaruh, Mufakat Guru. “Pada tingkat embrional, pergerakan kaum gurulah yang membuka jalan bagi kebangkitan nasional yang mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia” (hal. 122).
Kode kebangsaan terus mengristal dan menyatukan para perintis bangsa sehingga ikrar bersatu dalam Tanah Air, Bangsa dan Bahasa mengumandang dan membentuk ke-Indonesia-an pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, atau 17 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga bulan setelah kemerdekaan tepatnya pada 24-25 November 1945, Kongres Guru Indonesia yang diadakan pertama kali di Surakarta menandai hari kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan diperingati sebagai Hari Guru Nasional (HGN) setiap tanggal 25 November.
Perjalanan Profesi Guru
Lahirnya PGRI menandai geliat perjalanan profesi guru. Seorang pakar pendidikan guru Andy Hargreaves (2000) menawarkan kerangka tahapan pengembangan profesi guru dalam empat fase: pra-profesional, profesional mandiri, profesional kolegial, dan pasca-profesional.
Pada fase pra-profesional, menurut Hargreaves, siapapun yang mempunyai pengetahuan sedikit saja tentang suatu bidang dianggap bisa mengajar. Pada era pra Kemerdekaan 1945, situasi ini terjadi karena kebutuhan mendesak, Berasal dari keluarga ningrat, Bupati Jepara R.M. Sosroningrat, ayah Kartini menyekolahkan putrinya di ELS (Europese Lagere School). Di sekolah inilah ia kemudian belajar bahasa Belanda, namun hanya sampai berusia 12 tahun.
Menurut tradisi pada masa itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk ‘dipingit' sebelum menikah. Sebenarnya, Kartini sudah memeroleh beasiswa untuk melanjutkan studi di Belanda atas dukungan Abendanon. Namun sekali lagi, tradisi pada saat itu bagaikan tembok tebal yang menghentikan langkah Kartini mengejar mimpinya. Adat istiadat memaksa Kartini mempersiapkan diri memasuki dunia pernikahan.
Karena latar belakang keluarga ningrat, Soewardi pun bisa menikmati pendidikan di ELS dan bahkan melanjutkan ke STOVIA (sekolah dokter). Namun, pendidikan sekolah dokter tidak diselesaikan karena kondisi kesehatan yang menghalangi. Selanjutnya, Soewardi berkarir sebagai jurnalis dan terlibat aktif dalam pergerakan melawan kolonial melalui tulisan-tulisannya.
Setelah kembali dari pengasingan, Soewardi bergabung di dalam sekolah binaan dari saudaranya sendiri, sehingga kemudian ia memiliki pengalaman dan akta untuk mengajar. Berbekal pengalamannya di dalam mengajar kemudian Soewardi mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikannya sendiri. Pada 3 Juli 1922, sekolah ini diberi nama National Onderwijs Institut Tamansiswa atau yang lebih dikenal sebagai Perguruan Nasional Tamansiswa,
Berbeda dengan Soewardi, Kartini tanpa pendidikan formal yang memadai bisa mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan dan menjadi guru. Baik bekal pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi maupun tanpa bekal formal, Soewardi dan Kartini bisa menjadi pendidik. Kedua tokoh ini bersama dengan para perintis lainnya, sudah termasuk kategori elite masyarakat yang pengetahuan. Kecerdasan mereka di atas rata-rata masyarakat sekitar. Menurut Hargraves, pada fase pra-profesional, menjadi guru dianggap mudah. Tentunya, pernyataan ini bersifat relatif. Dianggap mudah karena secara juridis formal, tidak ada yang menghalangi Kartini dan Soewardi untuk menjadi guru.
Dengan bekal pengetahuan yang mereka peroleh dari bacaan dan interaksi mereka dengan teman-teman termasuk orang asing yang berwawasan luas, mereka bisa menjadi mendidik. Kartini bersahabat dengan pejabat berkebangsaan Belanda Abendanon dan Soewardi berkomunikasi dan berjumpa dengan sejumlah tokoh pendidikan Barat, di antaranya adalah Montessori dan juga Froebel, serta bersahabat dengan tokoh pendidikan bangsa India.
Soewardi dan Rabindranath Tagore memiliki latar sejarah yang sama, yakni dalam situasi masyarakat yang terjajah. Kondisi kolonialisme tersebut mendorong lahirnya perjuangan melalui pendidikan (Supardi, 2013 dalam news.okezone.com). Dari pengaruh-pengaruh tersebutlah kemudian membuat kedua tokoh guru ini mengembangkan sistem pendidikan sendiri.
Langkah Kartini dan Soewardi tentunya sangat tidak mudah karena membutuhkan keberanian dan pengorbanan luar biasa. Mereka berdua berani meninggalkan zona nyaman sebagai anggota keluarga ningrat dan menjangkau dunia yang lebih luas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kartini berani bernegosiasi dengan calon suami Bupati Rembang Raden Adipati Joyodiningrat dan meminta persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak perempuan di daerah mereka. Soewardi berani menanggalkan atribut keningratannya dan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Secara total dia mengabdikan diri sebagai guru.
Pada fase kedua dalam kerangka Hargreaves (2000), guru dianggap sebagai profesional mandiri yang bisa menyiapkan dan menyampaikan materi dan metode di kelas. Pada fase ini, guru bekerja sebagai individu terampil namun tidak terhubung secara profesional dengan rekan guru lainnya. Dalam hal ke-terisolasi-an, di banyak daerah di Indonesia saat inipun, situasi guru masih pada fase ini. Fungsi supervisi dari dinas pendidikan setempat tidak menjangkau banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Bahkan, di unit sekolahpun termasuk di kota, banyak guru tidak disupervisi oleh pimpinan sekolah dan tidak terhubung dengan guru lainnya secara kolegial. Interaksi mereka terbatas pada berkantor bersama di ruang guru dan bercakap-cakap tentang topik yang tidak terkait dengan pengajaran dan profesi mereka. Dalam hal otonomi, sulit menilai kemandirian guru karena kebijakan kurikulum yang tidak konsisten dan berkesinambungan (Lie, 2018)
Fase profesional kolegial ditandai dengan upaya kolektif para guru untuk membangun budaya dalam profesi guru. Penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada 24-25 November 1945 dan kelahiran PGRI bisa dianggap sebagai upaya untuk memasuki fase profesional kolegial ini. Kolaborasi merupakan salah satu prasyarat untuk berkembang secara profesional. Pada fase ini, guru bertumbuh dan saling membantu dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta berorganisasi bersama rekan sejawat.
Pada fase itu pula, organisasi guru ingin ikut berperan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Sebagai organisasi guru paling besar, PGRI berupaya melakukan peran mitra kritis terhadap kebijakan terkait dengan guru. Selain PGRI, dewasa ini bertumbuh pula organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan masih banyak organisasi/asosiasi guru yang lain. Berbagai organisasi guru senantiasa diharapkan bisa membantu guru mengembangkan keterampilan dan wawasan, dan tidak menyita waktu guru yang sudah sangat terbebani berbagai tugas mengajar dan administratif.
Terakhir, pada fase pasca profesional, guru membangun jejaring strategis dengan komunitas yang lebih luas. Misalnya, para pemangku kepentingan pendidikan untuk merespons tantangan dunia di luar sekolah. Beberapa literatur menyuarakan peringatan kemungkingan disrupsi terhadap lembaga-lembaga pendidikan formal (OECD, 2020; Flemming, 2021). Fase ini membutuhkan keberagaman dan kelenturan individu guru dan organisasi profesi untuk secara kolektif meningkatkan mutu pendidikan agar lebih bisa bertahan menghadapi disrupsi. Sudah ada guru Indonesia yang mencapai fase ini, walaupun jumlahnya baru segelintir. Mereka mampu menggalang dukungan dan memanfaatkan sumber daya di luar sekolah dalam model pembelajaran berbasis permasalahan aktual dunia. Guru seperti ini menjadi jembatan antara sekolah dengan dunia luar (Lie, 2018).
Ikuti tulisan menarik Anita Lie lainnya di sini.