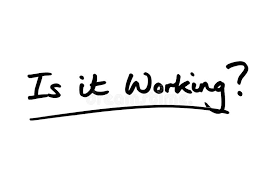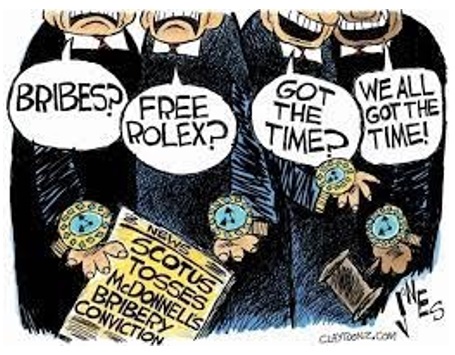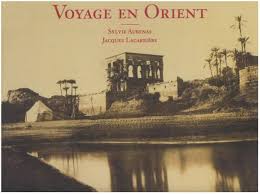Pertentangan Konsep Sastra Para Seniman Lekra dan Manikebu.
Selasa, 19 April 2022 18:12 WIB
Artikel ini mengulas tentang Para seniman Manikebu yang melancarkan kritik satra terhadap para seniman Lekra dan begitu pula sebaliknya.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa latar belakang karya sastra merupakan hasil konstruksi atas cerminan dari konteks (ruang dan waktu) penulisnya, latar belakang sastrawan, lingkungan dan masyarakat mempengaruhi bentuk pemikiran dan ekspresi sastrawan. Sekitar masa pertengahan tahun 1950 sampai 1965, Terjadi pertentangan politik yang berimbas pada dunia sastra Indonesia. Ini dibuktikan dari hadirnya beberapa kelompok sastra di tahun 1950-an akhir sampai 1965 yang secara massif berdebat dan bertengkar soal sastra. Konflik itu, memperluas panasnya sosial politik di dunia kesusastraan.
Pada saat itu, para Seniman harus memiliki pandang politik dan ikut serta dalam sebuah organisasi politik. Pernyataan tersebut didukung dengan pendirian lembaga kebudayaan dalam partai-partai politik untuk menarik massa dan dukungan terhadap pandangan politik partainya sehingga partai tersebut memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Seperti: Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) milik Partai Nasional Indonesia (PNI), Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdlatul Ulama, Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi) milik Partai Indonesia (Partindo), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) milik Partai Komunis Indonesia (PKI) (Moeljanto & Ismail, 1995, hlm. 9-10)
Selain itu, suasana pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin masih berfokus dalam upaya menjalankan revolusi yang belum selesai, semua aspek kehidupan dituntut untuk mendukung upaya tersebut, termasuk dalam aspek kebudayaan. Hingga muncullah slogan “Politik sebagai Panglima” yang dipopulerkan oleh Lekra untuk menyuarakan semangat seniman Indonesia agar selalu berupaya mendukung upaya pemerintah. Slogan tersebut dijadikan pedoman oleh mayoritas seniman saat itu.
Berbeda dengan seniman pada umumnya, seniman sastra cenderung tidak setuju dengan slogan tersebut karena mengisyaratkan bahwa politik dijadikan aspek utama dari segala aspek yang ada di Indonesia. Pernyataan sikap sastrawan mengenai situasi politik yang sedang berlangsung juga ditegaskannya dalam kata pengantar penerbitan tahun keduanya yang berjudul “Satu Tahun Sastra Pernyataan Sikap dan Pertanggungan jawab”, tim redaksi sastra (Jassin, dkk, 1962) menjelaskan bahwa:
“Dalam menentukan haluan kami mengambil kebijaksanaan tidak membenteng apa yang disebut dalam istilah sehari-hari kiri dan kanan, tapi sesuai dengan sila-sila nasional, bertolak dari kepribadian sendiri yang bebas memilih dan menentukan untuk pertumbuhan kepribadian diri, berpedoman pada sila-sila pancasila. Dan kalau kami tidak masuk partai kiri atau kanan, itu bukan berarti bahwa kami tidak punya pendirian, tapi karena baik partai kiri maupun kanan ada kekurangan-kekurangannya yang harus tetap kami hadapi dengan kritis. Landasan kami adalah perikemanusiaan, kemudi kami akal budi” (hlm.3)
Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa majalah sastra tidak berpihak pada kekuatan politik manapun, karena pada dasarnya setiap kekuatan politik memiliki kelemahannya sendiri, dan sikap itulah yang dipegang oleh sastrawan yang aktif di dalamnya. Dalam suasana Demokrasi Terpimpin yang sudah dijelaskan di atas, muncul sebuah kecenderungan di lingkungan seniman Indonesia, yaitu untuk mendukung jalannya revolusi yang belum selesai itu maka seniman Indonesia harus menyatakan dirinya masuk ke dalam organisasi sebagai pendirian politiknya. Hal tersebut juga dianjurkan oleh Pramoedya Ananta Toer (dalam Moeljanto & Ismail, 1995, hlm. 120) bahwa “organisasi adalah penting untuk pendekatan pada objektivitas. Sastrawan membaja diri dalam gerakan masa”. Sastrawan yang enggan terlibat politik praktis berusaha menggalang kesatuan dengan suatu gerakan bernama Manifes Kebudayaan pada pertengahan tahun 1963.
Pandangan yang dipegang oleh sastra dan para sastrawan yang aktif di dalamnya pada akhirnya menimbulkan reaksi terutama dari seniman Lekra karena dianggap tidak mengikuti jalannya revolusi yang belum selesai. Pramoedya Ananta Toer dalam tulisannya yang diterbitkan Lentera menyebutkan bahwa Seniman yang tidak menunjukkan pendiriannya dalam berpolitik adalah Seniman gelandangan, lebih lanjut Toer (dalam Mohamad, 1993, hlm. 21) menyebutkan bahwa “ketidaktegasan politik, yang menyebabkan timbulnya seni dan pemikiran gelandangan, harus disapu, harus dibabat, tidak perlu diberikan luang Sekecil-kecilnya pun. Sedikit pun tak boleh dibiarkan berkembang dan berlarut unsur-unsur penyakit ini, yang ternyata masih dapat mengembangkan sayapnya sampai dewasa ini.”
Selain tudingan di atas, Pada tahun 1963, sejumlah pengarang yang seharusnya berhak menerima hadiah menyatakan menolak hadiah tersebut dengan alasan-alasan Politik. Hal tersebut tidak lain karena Konsep Humanisme Universal yang dibawa Manikebu adalah wadah dari kebebasan manusia serta kebebasan berkarya. Mereka menentang “politik sebagai panglima” dan “tujuan menghalalkan segala cara” Realisme Sosialis yang dibawa Lekra dianggap merupakan dehumanisasi manusia untuk mengabdi pada politik yang hanya menghasilkan karya-karya yang bersifat propaganda semata.
Jadi, dapat saya simpulkan bahwa munculnya Manifes Kebudayaan karena adanya suatu kejenuhan akan suasana yang membawa masyarakat pada satu tujuan, yaitu revolusi yang belum selesai, sehingga terjadi pertentangan dan cap kontra-revolusi.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Pertentangan Konsep Sastra Para Seniman Lekra dan Manikebu.
Selasa, 19 April 2022 18:12 WIB
Meningkatkan Pembelajaran Sastra Pada Generasi Milenial Melalui Sastra Digital
Senin, 11 April 2022 20:42 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0



 Berita Pilihan
Berita Pilihan


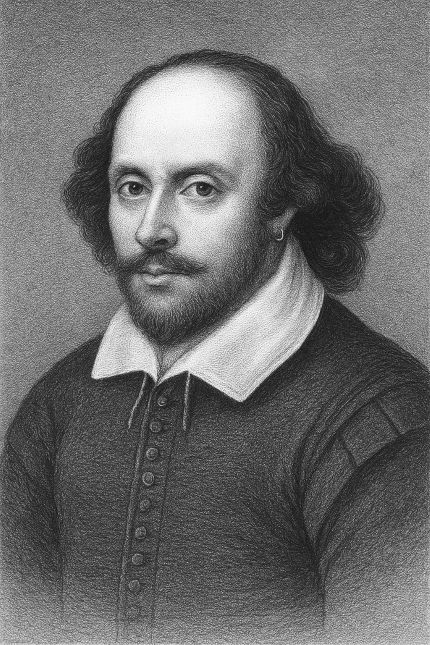


 97
97 0
0