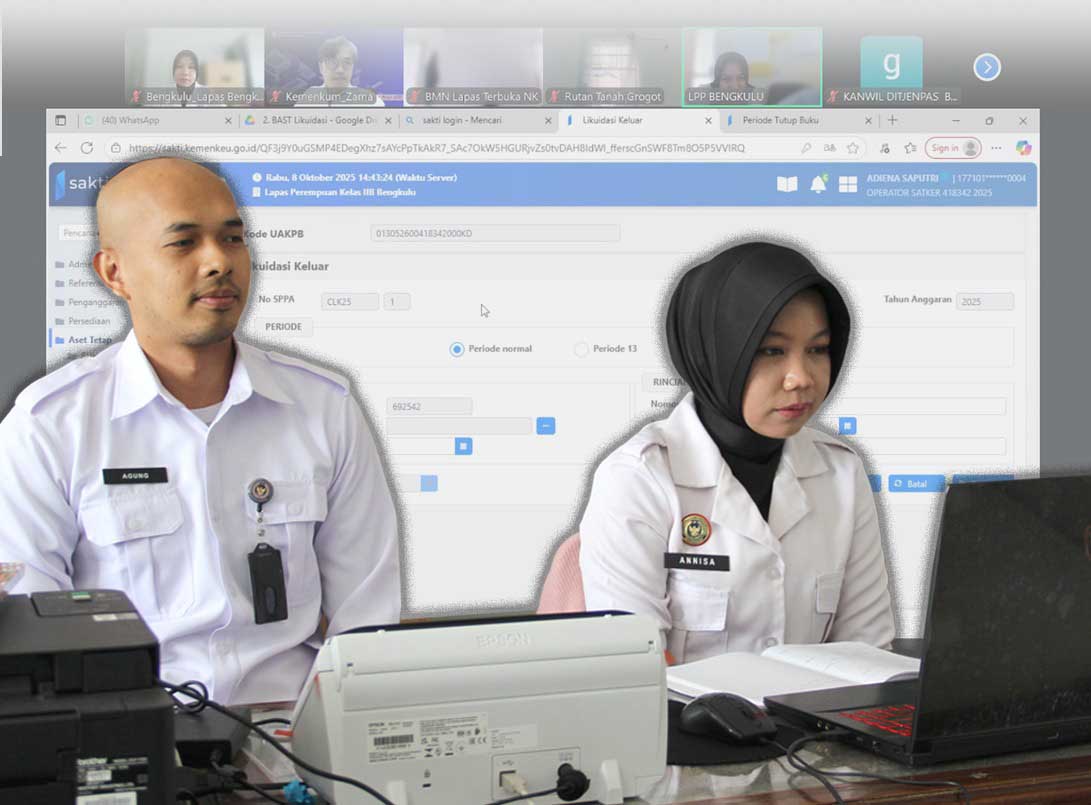Drama Arifin C. Noer: Sumur Tanpa Dasar
Senin, 25 Juli 2022 12:11 WIB
Drama ini menyuguhkan pergumulan eksistensial tokoh utamanya. Ia sukses secara materi, beristri cantik dan muda, namun selalu curiga dan merasa terasing. Hidupnya ibarat sumur tanpa dasar: kelam dan tak berujung.
Dapat dipastikan bahwa para pencinta seni, seniman atau budayawan, pernah mengenal nama Arifin C. Noer. Dia adalah dramawan, penulis skenario, dan kemudian sutradara film. Anak kedua dari sembilan bersaduara ini lahir di Cirebon pada 10 Maret 1941. Ketika masih SMP (1957) ia sudah menulis sekaligus menyutradari pementasan drama Dunia Jang Retak. Lalu, ketika pindah ke Solo (1960), ia bergabung dalam Himpunan Peminat Sastra Surakarta (HPPS). Selanjutnya ia pindah ke Jogjakarta. Di kota ini Arifin bergabung dalam Lingkaran Drama Jogja yang dimotori oleh WS Rendra dan Teater Muslim yang dipimpin Moh. Diponegoro. Akhirnya ia pindah ke Jakarta dan mendirikan Teater Ketjil.
Selain aktif di dunia drama, Si Ipin – demikian panggilan akrabnya-- juga banyak menulis skenario film, antara lain, Pemberang (1972, Rio Anakku (1973), Senyum di Pagi Bulan Desember (1974), Kugapai Cintamu (1976), dan Kembang-Kembang Plastik (1977). Sedangkan film pertamanya adalah Suci Sang Primadona (Akhir 1977). Lalu, pada 1982 ia menggarap film Serangan Fajar dan dilanjutkan dengan Pengkhianatan G 30 S PKI, keduanya diproduksi oleh Perusahaan Film Negara (PFN).
Salah satu drama yang ditulis dan disutradari Arifin yang selalu dikenang hingga kini adalah Sumur Tanpa Dasar. Konon lakon ini ditulis, disutradari, dan dipentaskan pertama kali oleh Arifin pada 1963-1964 di Yogyakarta di bawah bendera Teater Muslim. Lalu pada 1971, drama ini dipentaskan kembali di Taman Ismail (TIM) Jakatta, bersama Teater Ketjil yang didirikannya.
Tokoh utama drama ini adalah Jumena Martawangsa, seorang pengusaha pabrik yang berhasil menimbun kekayaan di akhir kehidupannya. Di samping berhasil menimbun harta, ia juga berhasil mempersunting Euis, seorang gadis muda yang cantik. Namun, kenyataannya, ia mengalami kekosongan batin dan menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanya untaian kesia-siaan. Tragedi kehidupan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya itu justru muncul ketika sukses telah diraihnya. Kekayaannya membuat ia bentrok dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, yang mengincar kekayaannya. Bahkan istri mudanya sendiri mulai menyeleweng ketika ia ingin benar-benar menyintai dan mengharapkan cintanya. Kebahagiaan makin jauh dari angan-angannya tatkala menyadari bahwa kematian akan datang, dan ia tidak berhasil memiliki seorang anak untuk melanjutkan usaha dan mewarisi kekayaannya. Jumena selalu bercuriga pada orang, merasa tersaingi, tapi juga tidak berdaya.
Ada yang menyebut Sumur Tanpa Dasar adalah drama eksperimental dan ada pula yang menyebutnya sebagai drama surealistis. Tetapi, yang pasti, Arifin berupaya memasukkan unsur teater tradisional, khususnya lenong Betawi dan tarling Cirebon, sehingga drama ini merupakan perpaduan antara dramaturgi Barat dan Timur. Hasil persenyawaan ini menghasilkan karya yang penuh simbol dan suasana yang kontemplatif tentang konflik kejiwaan tokoh utamanya. Konflik batin ini, oleh Arifin sendiri disebutnya sebagai konflik mengenai iman dan eksistensi diri. Hidup Jumena ibarat sumur tanpa dasar, gelap dan tak berujung.
Sebagai orang awam, ketika membaca sekilas “director statement” yang mengatakan bahwa drama ini mengenai konflik antara “iman” dan “eksistensi”, saya agak bingung. Apa maksudnya? Apakah orang “beriman” tidak memiliki “eksistensi diri”? Tidakkah lebih enak dan jelas jika disebut konflik antara “orang beriman” dan “orang “tidak beriman” alias ateis? Ataukah Arifin hanya ingin “memperhalus” kata “ateis” dengan “eksistensi” untuk menghindari kontroversial pada zaman itu? Ah, mungkin juga Arifin sebenarnya ingin menceritakan bahwa sang tokoh – Jumena Martawangsa— sebenarnya orang yang beriman, tapi ia sedang mempertanyakan keimanannya itu. Atau, apakah Arifin punya maksud lain lagi?
***
Drama ini dimulai dengan suara detak lonceng yang menggema memenuhi ruangan. Aneka suara ini menimbukan bermacam-macam asosiasi. Sesekali di sela-sela suara itu terdengar sayup-sayup lolong anjing atau serigala.
Lonceng itu antik, tua, agung, dan kukuh penuh rahasia. Dari rongga lonceng muncul “kabut-kabut” atau para pemain yang melukiskan kabut-kabut. Mereka melangkah mengendap-endap untuk selanjutnya secara penuh rahasia menyebar ke segenap arah dan segera gaib-sirna. Di panggung itu juga ada pigura tanpa gambar atau foto alias kosong, yang tergantung sunyi dan penuh rahasia.
Di atas kursi goyang, Jumena Martawangsa bergoyang dalam sunyi. Tampak sesak pernafasannya. Sekalipun begitu, kedua matanya masih menyorotkan pandangan yang tajam, amat tajam. Jumena kelihatan seperti sedang menghitung-hitung detak-detak lonceng.
Sejak tadi, seonggok “kabut” berdiri di sampingnya, memainkan sehelai tali yang siap untuk menggantung leher. Agak beberapa saat Jumena menimbang-nimbang tali itu. Kemudian Kabut itu mendekatkan tali gantungan dan Jumena mencoba memasangnya pada lehernya. Dia tertawa.
JUMENA: Kalau saya bunuh diri, sandiwara ini tidak akan pernah ada.
Sambil tertawa ia memberikan isyarat agar kabut pembawa tali pergi. Dan pada saat itu detak-detak lonceng semakin lantang. Dari rongga lonceng muncul SANG KALA alias PEMBURU yang siap dengan senapannya. Ketika senapan itu meletus, terkumpullah seluruh amarah dan kekagetan JUMENA.
JUMENA: Bangsat!
Tatkala SANG KALA raib, berdetanganlah lonceng itu. Kemudian berdetang jugalah berjuta-juta dan weker. Sedemikian rupa suara itu menteror sehingga menyebabkan JUMENA bangkit. Dan pada saat JUMENA berdiri, hening menggantikan suasana. Lalu JUMENA duduk kembali.
PEREMPUAN TUA muncul mengganti tempolong ludah di kaki kursi goyang dengan tempolong yang lain.
PEREMPUAN TUA: (sambil pergi). Terlalu bernafsu. Pucat sekali wajahnya.
Entah dari sebhelah mana, EUIS muncul.
JUMENA: Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya
tenang. Kalau saya percaya dan tidak bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi
saya tidak bisa percaya dan tidak bisa tidak percaya, jadi saya tidak
tenang. Tapi juga kalau saya tenang, tak akan pernah ada sandiwara ini.
EUIS : Akang
JUMENA: Euis
EUIS : Apa yang Akang lihat?
JUMENA: Kau.
EUIS : Kenapa?
JUMENA: Ingin tahu apa kau betul-betul cantik.
Euis merangkul dan menciumi leher Jumena, telinga Jumena, dan lain-lain sehingga Jumena kegelian. Keduanya tertawa-tawa. Sekonyong-konyong Jumena mematung murung.
EUIS: Kenapa, Akang?
Jumena memainkan bulu-bulu matanya sendiri.
EUIS : Kenapa tiba-tiba muram, Akang?
JUMENA (manja). Umur Euis berapa?
EUIS : Dua enam
JUMENA: Itulah sebabnya!
EUIS : Percayalah Akang, Euis akan tetap mencintai Akang sekalipun umur
Akang delapan puluh tiga tahun,
JUMENA: Betul?
EUIS ; Sumpah.
JUMENA: Seratus tujuh?
EUIS : Euis akan tetap menciumi leher Akang.
Kembali Euis merangkul dan menciumi leher Jumena dan lain-lain. Keduanya tertawa-tawa.
JUMENA: Kalau saja saya tahu kau betul-betul mencitai saya.
EUIS : Euis sangat cinta pada Akang.
JUMENA: Menyenangkan sekali kalau itu benar
EUIS : Betul, Euis mencintai Akang.
JUMENA: Mungkin. Sayang akang tidak tahu persis.
EUIS : Tidak perlu.
JUMENA: Perlu. Bahkan akang juga ingin tahu apa betul akang bahagia.
Terus mereka berciuman dan tertawa-tawa.
JUMENA: Sesekali enak juga berlibur seperti ini.
Terus mereka berciuman dan tertawa-tawa.
***
Dialog Jumena (“Kalau saya bisa percya, saya tenang.. dst) itu memancing saya untuk berhenti sejenak. Apa kira-kira maksud Jumena? Apakah sekadar soal keraguan cinta Euis kepadanya? Atau sesungguhnya ada yang lain? Drama ini memang menceritakan pergumulan eksistensial Jumena yang dikejar-kejar oleh kegalauan dirinya sendiri.
Bisa juga soal ketenangan batin, soal percaya dan tidak, itu diteruskan lebih jauh seperti yang dilakukan oleh Bambang Subandrijo dalam orasi Dies Natalis ke-79 Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta. Orasi Bambang itu memang mendapat inspirasi setelah menonton drama Arifin. Katanya, ketika kita percaya (entah kita mengerti atau tidak mengerti tentang subjek yang kita percayai), maka hati dan jiwa kita tenang. Demikian halnya ketika kita tidak percaya, kita pun tenang. Atau kalau kita percaya sesuatu dan sekaligus dapat tidak percaya kepada sesuatu yang lain, kita juga tenang. Kita akan menjadi tidak tenang, jika kita tidak dapat percaya, namun tidak dapat untuk tidak percaya. Kadang-kadang kita terjebak dalam kegalauan dan keraguan tentang apa yang kita percayai (baik yang kita mengerti maupun yang tidak kita mengerti), tetapi pada saat yang sama kita terpaksa (atau “dipaksa” untuk percaya. Dalam situasi seperti ini, hati dan jiwa kita tidak merasa tenang, seperti teraduk-aduk, bahkan terpilin dalam pusaran badai. Bambang yang beriman dan percaya Tuhan itu memang sedang berbicara mengenai ziarah teologis menggapai Allah.
***
Ada macam-macam pendapat orang tentang drama ini. Menurut Abdul Hadi WM (1987), misalnya, "Sumur Tanpa Dasar adalah sebuah judul yang simbolik, surealistik dan puitik, sesuai dengan bentuk penulisan dan kandungan lakon ini secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sumur adalah tempat mengambil air untuk memasak, mandi, mencuci dan minum. Jadi ia adalah tempat untuk mengambil sesuatu yang vital bagi kehidupan. Namun, sumur yang dimiliki oleh tokoh utama lakon ini, sangat kelam, tidak punya dasar, tak berujung pangkal, sehingga sia-sialah ia untuk mengambil "air" jawaban dari dalamnya.
Masih kata Abdul Hadi WM: "... kekosongan dan kesia-siaan hidup inilah yang ingin disorot oleh Arifin C. Noer, dalam lakon ini. Kekosongan dan kesia-sian ini merupakan bagian utuh dari kehidupan modern, sebagai suatu sisi tragis di balik keberhasilannya dalam mengatasi masalah-masalah kebendaan dan keduniawian. Ketragisan ini semakin mencuat manakala sang tokoh menyadari bahwa ia telah kehilangan akar kerohanian dan tercerabut dari kefitriannya sebagai manusia, tak kenal lagi akan kampung halamannya, sehingga menjadi asing dari dirinya, Tuhan, dan dunia sekitarnya. Ia tidak lagi merupakan makhluk historis dan spiritual yang bersilsilah pada Adam di hadapan kesia-siannya.
Lalu Jakob Sumardjo (1992) berpendapat: "Kesalahan yang diperbuat manusia hanyalah bahwa ia dilahirkan ke dunia. Menjadi manusia adalah sebab utama rangkaian masalah ini. Dan akhirnya Arifin menunjuk agama sebagai satu-satunya pemecahan, obat mujarab semua bentuk kemiskinan luar-dalam itu. Jumena tidak mempercayai Hari Nanti, Tuhan, tidak mempercayai ajarannya untuk berbuat amal, untuk bahagia dengan melihat hartanya".
Masih kata Jakob Sumardjo: "Sumur Tanpa Dasar menyoroti tabiat rakus, kerja keras, takut jatuh miskin, tetapi juga pencuriga, tidak percaya kepada manusia. Semua sifat itu timbul karena sang tokoh, Jumena, mempunyai latar belakang kemiskinan yang traumatis. Karakter yang demikian itu (kehilangan kepercayaan kepada sesama manusia) hanya dapat disembuhkan oleh agama, begitu kesimpulan drama ini."
***
Sementara saya sendiri melihat bahwa situasi yang dialami atau dihadapi Jumena ini mirip dengan “situasi batas” yang pernah digambarkan oleh Karl Jaspers, filosof kelahiran Oldenburg (Jerman Utara). Menurut Jaspers, setiap orang hidup dalam situasi-situasi tertentu. Manusia tidak pernah lepas dari situasi-situasi tertentu. Manusia hidup dan bertindak berarti juga mengubah dan menciptakan situasi-situasi. Dan seseorang bisa berada dalam situasi yang tidak bisa ditiadakan, yakni “situasi batas” (grenzsituation). Situasi batas ini tidak bisa dihindari. Misalnya, kematian, kesengsaraan, perjuangan, pengalaman pahit, ancaman maut, kebersalahan, ketergantungan pada nasib, dan lain-lain. Di sinilah eksistensi menemui batas yang tidak bisa dilewati. Dengan mengalami situasi-situasi batas ini seseorng justru mulai bereksistensi secara sungguh-sungguh. Dengan mengalami situasi batas itu eksitensi dapat menghayati dirinya sendiri sebagai eksistensi. Jadi, situasi batas ini begitu hakiki. Orang yang tidak hidup dengan cara eksistensial, akan menghilangkan situasi batas itu atau menutup mata, sehingga ia tidak tahu menahu tentangnya. Ia hanya memperhatikan situasi-situasi konkret yang dapat ditangani dan dikuasai.
Di antara sekian banyak situasi batas, kematian adalah yang paling dramatis. Jangan salah. Dengan mengetahui kematian pada umumnya (karena semuan orang juga akan mati), seseorang belum mengalami situasi batas. Situasi batas kematian akan dialami secara eksitensial dan konkret ketika kita menyaksikan kematian orang yang kita cintai atau bahkan kematian kita sendiri, yang makin lama makin dekat. Kematiaon ini bisa menimbulkan rasa takut, tetapi sekaligus menyempurnakan eksitensi. Sebab dengan keinsyafan adanya kematian, akan mendesak kita untuk hidup otentik. Keinsyafan terhadap kematian yang tak terelakkan akan memberi keberanian dan integritas. Oleh karenanya, manusia akan memperoleh suatu pandangan otentik tentang hal-hal yang paling penting dalam hidup.
Menurut Jaspes, seperti diterangkan K. Bertens, kesengsaraan yang terdapat dalam banyak bentuk, dapat juga dialami sebagai situasi batas. Dalam penderitaan dan kemalangan, lebih besar kemungkinan manusia akan mencapai eksistensi otentik daripada dalam kemakmuran dan kebahagiaan yang tak terancam. Dalam keadaan makmur yang berlimpah, arti eksistensi sering kali tersembunyi. Sementara kesengsaraan tak jarang menjadi jalan menuju pengalaman tentang transendensi. Apakah Jumena benar-benar sedang berada atau mengalami “situasi batas” itu?
***
Di akhir babak, sejuta senapan meletus bersama, lalu sejuta lonceng berdetang bersama.
PEMBURU: Kau tahu kau sudah mati?
JUMENA: Apa?
PEMBURU: Kau sudah mati
JUMENA : Gila! Saya sendiri tidak tahu (seyum pahit). Apa boleh buat.
PEMBURU: Tidak perlu tahu. Seperti halnya tentang hidup.
JUMENA : Tapi saya selalu ingin tahu.
PEMBURU: Hampir semua orang juga ingin tahu, tapi umumnya orang lebih hemat
dalam segala hal dan lebih sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk
menuju sorga. Kau telah memakan buah khuldi, sementara umumnya
orang lebih suka menelan air liurnya, lantaran mereka tak mau
kehilangan sorganya.
JUMENA: Kau ini sebenarnya siapa?
PEMBURU: Yang kaiu cari, Yang kau rindui. Ayahmu alias Tanya.
Jumena terpesona. Pemburu tersenyum, agung sekali.
JUMENA: Bajingan.
PEMBURU: Mulutmu kotor seperti otakmu.
Jumena terseenyum.
JUMENA: Kalau begitu, betul saya sudah mati.
PEMBURU: Begitu kata orang.
JIUMENA: Lalu bagaimana? Apakah ini berarti saya harus mulai lagi?
PEMBURU: Tidak, anakku. Lebih baik kau lanjutkan. Ikutlah saya.
Jumena mengikutin langkah Pemburu menuju lonceng raksasa itu.
JUMENA: Dari sini kita mulai?
PEMBURU: Ya.
Semua masuk ke dalam lonceng raksasa itu, sementara sebelumnya ia sudah memperdengarkan bunyinya yang menggema tepat pukul dua belas.
Ketika muncul Perempuan Tua mengambil tempolong ludah di kaki kursi goyang, dan tepat selangkah ketika dia masuk ke dalam, semua lampu surut cahayanya dan layar turun perlahan. Selesai.
***
Arifin C. Noer memang salah seorang seniman besar yang pernah kita miliki. Pengetahuannya luas dan enak diajak bicara apa saja. Saya beruntung pada pertengahan 1992, misalnya, berkesempatan untuk wawancara dengan Arifin tentang berbagai hal, dari yang agak serius sampai yang remeh-temeh. Maka, untuk menambah informasi tentang Arifin, terutama bagi generasi muda, berikut saya kutipkan beberapa saja dari obrolan panjang masa lalu itu. Saat itu Arifin baru saja menyelesaikan film bertajuk Bibir Mer.
Adakah sesuatu yang Anda anggap baru atau kemajuan buat Anda ketika menggarap film Bibir Mer ini?
Setiap kali saya berkarya, saya selalu berusaha tulus menelusuri misteri dari ide yang saya dapat. Dan saya termasuk yang percaya bahwa ide dan bentuk merupakan satu kesatuan organik. Jadi proses suatu penciptaan seni selalu merupakan petualangan baru.
Setiap kali saya berkarya, saya hanya setia kepada diri saya sendiri. Dan saya hanya bisa bekerja dalam keadaan saya betul-betiul merasa bebas.
Ada yang bilang bahwa penonton film kita masih rendah intelektualitasnya. Lalu mereka membuat film yang gampang-gampang saja agar mudah dicerna dan menghibur. Padahal dalam kenyataaan tidak selalu begitu yang terjadi. Komentar Anda?
Bukan saja dalam bidang film dan bukan saja produser yang berkata begitu. Tapi banyak orang dalam masyarakat seni suka beranggapan masyarakat penonton itu rendah apresiasinya, rendah intelektualitasnya. Pada mulanya mereka yang merasa di atas, merasa intelek, yang suka sekali menyatakan bahwa masyarakat penonton rendah dan seterusnya, sehinbgga lambat-laun hampir seluruh masyarakat percaya bahwa penonton di sini memang rendah. Ini skandal lama yang belum seluruhnya terungkjap dan sangat berbahaya.
Tapi saya tidak pernah terlibat dalam skandal ini karena saya tidak pernah merendahkan penonton. Bagi saya, masyarakat penonton memiliki suatu kearifan yang khas dalam mengapresiasi suatu karya seni. Saya bukan orang yang sombong, yang dengan gegabah menganggap orang lain bodoh!
Menurut Anda, apa problem atau hambatan utama perfilman Indonesia?
Film Indonesia persoalan dasarnya hampir sama dengan seni masa kini pada umumnya, baik sosiologis maupun kultural. Secara teknis masih terlalu sedikit kita memiliki penulis-penulis film yang baik, dan secara bisnis umumnya para pedagang film di Indonesia lebih banyak berperilaku sebagai penjudi.
Dalam teknik, komposisi penguasaan atas subyek adalah yang pertama kali harus dimiliki oleh penulis. Tapi justru kelemahan kita umumnya mulai dari pangkal ini. Persoalan bidang inilah yang kemudian menyebabkan lakon-lakon kita tidak tumbuh dan berkembang secara normal, sehingga mengesankan kita tidak pandai bertutur atau bercerita. Kelemahan naskah film ini selanjutnya mengakibatkan hambatan-hambatan pada perkembangan sektor-sektor lain, seni peran sendat perkembangannya, demikian juga seni penyutradaraaan.
Ada yang bilang bahwa satuan terkecil dalam film cerita kita itu bukanlah individu yang bebas, tapi keluarga. Anda setuju?
Boleh jadi begitu karena di negeri ini peluang untuk individu tumbuh secara mandiri hampir setengah ditolak. Buktinya: Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Kalau menurut saya, semboyan itu harus diganti menjadi: Bersatu Kita Teguh, Sendirian Kita Jitu!
Siapa tokoh drama yang sangat memengaruhi Anda?
Pada waktu SMP saya banyak mempelajari lakon-lakon Utuy Tatang Sontani, dan media 1960-an saya belajar pada Garcia Lorca, tapi saya merasa cocok dengan Ionesco.
Kalau tokoh perfilman siapa?
Dalam film, pertama kali saya – diam-diam—belajar pada Peransi. Saya suka solusi yang ditawarkan oleh Francis Truffaut. Tapi guru saya adalah seni rakyat.
Selera humor Anda kan cukup tinggi. Bisakah Anda ceritakan satu saja joke atau anekdot kepada saya?
Pada suatu hari saya dan Jajang makan bakso di Senayan. Sedang asyik-asyiknya melahap bakso, saya dan Jajang dikejutkan suara anak-anak sekolah. ‘He, bakso makan bakso’, teriak salah seorang di antara mereka. Begitu saya menyadari bahwa kepala saya sama bulatnya seperti bakso yang saya makan, langsung saya tertawa. Juga Jajang terbahak sampai keselak. Seketika anak-anak SMA itu tersipu, tapi kemudian mereka juga serentak tertawa. Dan semua tertawa. Termasuk yang jual bakso dan yang makan bakso!
- Atmojo adalah penulis yang meminati bidang filsafat, hukum, dan seni.
###
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Drama Nano Riantiarno: Kejujuran dan Penyesalan
Sabtu, 28 Januari 2023 06:50 WIB
Aum Teater Mandiri: Imajinasi yang Meneror
Senin, 9 Januari 2023 18:24 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0