Menilik Pelecehan Verbal sebagai Kekerasan yang Perlu Perhatian
Jumat, 20 Januari 2023 13:09 WIB
Nabillah Nagayi, Politisi Uganda yang diserang dalam narasi disinformasi di media sosial. Nabillah dianggap sebagai seorang mata-mata untuk partai lain. Ajakan untuk tidak memilihnya dalam Pemilihan Walikota Karpala pun viral di media sosial. Di Indonesia, dunia politik selalu dikaitkan dengan istilah “kadal gurun” atau “kadrun” yang ditujukan untuk pendukung salah satu tokoh politik. Serta berbagai macam istilah-istilah lainnya yang merendahkan seseorang berdasarkan pandangan politiknya dan ekspresinya di media sosial. Bentuk perendahan tersebut bersifat melecehkan, hingga mengajak seseorang untuk melakukan pelecehan kembali, baik secara tertulis ataupun ucapan. Hal ini mengindikasikan bahwa internet tidak aman untuk orang yang punya pendapat yang berbeda.
Komnas Perempuan pada 2021 melaporkan, terdapat 1721 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ruang media sosial (online). Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, kekerasan yang berada di ranah online tersebut diklasifikasikan pada terma Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) yang mengarah ke banyak bentuk. Salah satu bentuk nya adalah cyber harassment. Cyber harassment (secara harafiah diterjemahkan Pelecehan Online) didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu atau mempermalukan korban. Bentuk kekerasan ini yang banyak dilaporkan pada Komnas Perempuan melalui Unit Pengada Layanan (UPL) dengan korban yang mengalami kerugian psikis hingga mengisolasi diri.
Pada 24 April 2018, KJD, seorang sutradara yang pernah membuat film mengenai tokoh politik Basuki Tjahaja Purnama mengalami kekerasan yang difasilitasi teknologi melalui ranah online. Nomor ponsel pribadinya dicatut oleh pelaku tidak dikenal. Pencatutan tersebut dialamatkan sebagai nomor ponsel dalam akun-akun prostitusi online yang terdaftar di beberapa aplikasi kencan online. Akibatnya, KJD mendapatkan terror dan pelecehan bersifat verbal dari telepon, video call, dan pesan-pesan WhatsApp. Pesan-pesan tersebut dilakukan pelaku berdasarkan nomor telpon yang danggap sebagai nomor yang bisa membuka jasa prostitusi online. Hal ini membuat kehidupan pribadi dan profesionalnya terganggu. KJD pun melaporkan kasusnya kepada Mabes Polri dengan didampingi LBH Jakarta. Namun KJD harus mengalami pil pahit. Kasus yang dialami KJD dianggap belum ada dasar hukumnya, dan UU ITE belum menjawab kebutuhan kasus tersebut.
Pelecehan verbal terjadi ketika sebuah tindakan yang menyerang non fisik dengan menyasar kepada bagian tubuh seseorang atau seksualitasnya. Bentuk verbal dapat terjadi dengan ujaran dan kata-kata, serta ungkapan dan komentar baik tertulis ataupun lisan. Anastasia Powell, Adrian J Scott, dan Nicola Henry dalam penelitiannya yang berjudul “Digital Harassment and Abuse: Experiences of Sexuality and Gender Minority Adults” menerangkan bahwa beberapa subtype yang dapat ditelaah dalam pelecehan online dan kekerasan, yaitu meliputi menyerang dalam bentuk komentar dan/atau pelecehan nama panggilan (offensive comments and name-calling), komentar berbasis seksual dan/atau permintaan seksual (unwanted sexual comments and/or sexual requests), membuat, mendistribusikan, atau mengancam pendistribusian konten keterlanjangan atau seksual (creating, distributing or threatening to distribute a nude or sexual image), ancaman seksual atau tidakan seksual (sexual threats, and forced sex acts), dan komentar menghina, menyerang atau bentuk pelecehan lain yang mengarah pada gender atau identitas seksual seseorang (offensive comments, threats, or other harassment directed at an individual’s gender or sexuality identity). Tindakan ini dapat menyebabkan terenggutnya hak-hak fundamental seseorang seperti hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, hak atas kebebasan dan keamanan, hak kesetaraan atas perlindungan hukum, hingga hak atas akses pekerjaan yang adil dan menguntungkan.
Pada 2022, Never Okay Project dan International Labor Organization mengeluarkan hasil riset mengenai pelecehan seksual di tempat kerja yang berjudul “Semua Bisa Kena! : Laporan Hasil Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” menyatakan bahwa sebesar 42,70 persen atau 275 responden mendapatkan makian, teriakan, dan gangguan verbal lainnya. Kebijakan pemerintah seyogyanya dapat memberikan perlindungan kepada setiap pekerja untuk jauh dari pelecehan. Meskipun Konvensi ILO No.190 (KILO190) tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja tela ada pada 2019, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO. Namun hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa pelecehan seksual, termasuk pelecehan verbal itu ada.
Invasi Internet terus berkembang dan mengandalkannya dalam semua lingkup pekerjaan. Penggunaan Zoom sebagai ruang pertemuan virtual, dan berbagai platform lain sangat membantu dalam kepengurusan kebijakan dan kesepakatan. Terutama pada pandemi COVID-19, penggunaan media pertemuan virtual semakin meningkat. Meningkatnya penggunaan teknologi tak diiringi dengan perlindunga kepada penggunanya. Pelecehan verbal dapat terjadi dalam ruang online. Hal ini seperti mendistibusikan sticker dan emoji bernuansa seksual di dalam grup Whatsapp, menerima candaan yang bersifat mengajak untuk melakukan hubungan seksual melalui pesan teks atau telpon, hingga berkomentar terhadap konten seksual tertentu yang dikirimkan pada grup tertutup pada banyak platform, seperti Whatsapp, Telegram hingga facebook.
Lalu, mengapa bentuk kekerasan ini tidak mendapatkan ruang khusus untuk penanganannya? Hal ini terjadi karena ketidak seimbangan posisi tawar. Dalam budaya Jawa, gender yang sifatnya feminim, harus dapat berlaku dan bertutur kata baik kepada keluarga, pasangan dan masyarakat. Maskulinitas yang terjadi menimbulkan sifat seksis (anggapan bahwa satu gender lebih berkuasa) dan misoginis (paham yang merendahkan salah satu gender berdasarkan perannya), sehingga posisi tawar yang terjadi adalah superioritas. Seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan lebih berkuasa dibandingkan yang lain.
Pelaku pelecehan akan menganggap bahwa dirinya lebih tangguh secara kekuatan ataupun tingkat intelektual. Hal ini menjadikan ia masuk ke dalam superioritas. Sedangkan, seseorang yang memiliki sifat yang berbeda atas ideologi ataupun pendapat politik, menjadi target serangan superioritas. Di dalam internet, serangan buzzer yang bersifat anonimitas menyerang individu dengan mhadirnya misinformasi dan disinformasi terhadap individu yang aktif kontra terhadap pandangan politik tertentu. Serangan Muslim Cyber Army pada 2018 mengindikasikan seoerang yang mendukung politisi non-muslim seperti Basuki Tjahaja Purnama akan diteror, bahkan akunnya dibuat palsu dan diancam untuk membuat surat permintaan maaf. Hal ini juga dialami oleh perempuan yang membuat status di media sosial terkait dengan tokoh politik tersebut. Termasuk kejadian yang dialami oleh KJD.
Perempuan dan gender perempuan kerapkali mendapatkan perendahan terhadap bentuk tubuh. Hal ini dinamakan trolling. Trolling adalah perbuatan merendahkan dengan melakukan komentar yang menghina di media online. Bentuk trolling seakan-akan menjadi wajar katika seseorang di media sosial terlalu vocal dengan kata-kata, “Pantas saja gak laku. Sukanya bikin sensasi, sih!” bahkan melakukan perundungan dengan mengatakan, “Badan lu gak menarik, pantes galak!” Perilaku trolling ini menjadi sebuah pewajaran yang mengerikan. Selain budaya seksis dan misoginis terus berkembang, narasi media sosial yang dibangun dalam post truth dapat menggiring populis, memperparah budaya kita dalam mengakses internet.
National Democratic Institute (NDI) dalam laporannya yang berjudul “Amplified Abused : Report on Online Violence Against Women in the 2021 Uganda General Election” menerangkan bahwa perempuan yang terlibat dalam dunia politik, akan mengalami kekerasan dan disinformasi gender. Disinformasi gender mengedepankan stereotip politik, dan difubrikasi dalam bentuk narasi yang menyudutkan kelompok gender tertentu. Disinformasi gender mengindikasi latar belakang individu seperti status pernikahan, seksualitas dan identitas seksual individu yang terlibat dalam narasi politik, menjadi kekuatan dan keuntungan untuk menarasikan dan mendiskreditkan individu. Jenis disimfomasi yang sering ditemukan pada Pemilihan Umum Uganda 2021 lalu paling banyak yaitu trolling yang dialami oleh politisi perempuan sebanyak 50 persen dan laki-laki sebanyak 41 persen. Selain trolling, tindakan lainnya dengan presentasi dibawah 50 persen , yaitu kekerasan seksual, perundungan atas bentuk tubuh seseorang (body-shaming), menghasut dan ujaran kebencian (insult and hate speech), dan bentuk penghalusan bernuansa merendahkan (satire). Hal ini mengisiasikan bahwa motif politik memberikan dampak pelecehan yang masif.
Indonesia sendiri memiliki pengaturan yang secarai implisit mengenai pelecehan verbal sebagai kekerasan yang merugikan secara psikis. Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur mengenai kekerasan psikis. Kekerasan Psikis pada pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pengaturan dalam bidang domestic sudah lebih dahulu mengatur kekerasan psikis ini. Perilaku gaslighting, tindakan merendahkan melalui ujaran, dan ancaman atas ketidakseimbangan posisi tawar, seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga. Namun hal ini belum menjadi aspek penting di dalam pengaturannya. Perlu peran pemerintah melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) disertai pendamping dan konselor sebaya untuk lebih menerka atas kekerasan yang terjadi.
Selain UU PKDRT yang lebih sempit mengatur lingkup rumah tangga, Undang-Undang lainnya yang cukup komprehensif mengatur pelecehan verbal online ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam undang-undang terbaru, pelecehan verbal online dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan non-fisik pada Pasal 5. Pelecehan non-fisik menginisiasikan pada bentuk pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Bentuk pernyataan bias diartikan juga dengan sebuah ujaran atau bentuk penyerangan verbal kepada seseorang sehingga orang tersebut dirugikan. Undang-Undang ini perlu diturunkan dalam bentuk peraturan turunannya untuk memastikan mekanisme serta batasan-batasan pelecehan non-fisik ini ditangani.
Akan tetapi, UU ITE yang menjadi pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sering kali menjadi “daya Tarik tersendiri” bagi Aparat Penegak Hukum dan akhirnya mengkriminasi seseorang yang tidak memiliki kekuasaan. SAFEnet mencatat, terdapat 38 aduan kasus pada 2021 yang dikriminalisasi atas dasar UU ITE. Beberapa diproses dengan motif politik, seperti yang dialami oleh 10 aktifis HAM. Pelapor kasus ITE sebagian besar merupakan politisi, pejabat negara dan lainnya yang tidak ingin namanya dicemarkan hingga anti-kritik. Penuntutan pelaku pelecehan yang dialami oleh KDJ dengan dituntut Pasal 27 Ayat (1) tentang mendistribusikan muatan kesusilaan tidak mengakomodir tuntutan dengan kerugian yang lebih parah dari itu.
Kita sering mendengar bahwa “jejak digital itu abadi”. Nyatanya benar. Konten pelecehan verbal yang viral, akan terus dipublikasi, dipost ulang, diretweet dan lainnya sehingga masuk ke dalam mesin pencari yang susah untuk dihilangkan. Hal ini akan memberikan trauma baru bagi korban pelecehan yang dpaat menemukan kasusnya di internet. Trauma terus berlanjut ketika kejadian yang dialami korban dilihat oleh orang yang ia kenali, seperti pasangan, keluarga atau tetangga, sehingga menimbulkan stigma baru bagi korban.
Pelecehan verbal ini perlu perhatian khusus bagi pemerintah. Dukungan terhadap UU PKDRT dan UU TPKS untuk dapat melindungi korban dan mengusut pelaku pelecehan juga harus disegerakan. Kita dapat menciptakan ruang-ruang anti pelecehan verbal ini dengan membangun literasi digital yang baik. Karena kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan pesta politik, Pemilihan Umum Serentak 2024, penanganan khusus untuk tidak melakukan pelecehan verbal dengan motif politik harus ditegakkan. Pembelajaran dari Uganda, kita dapat menegakan ruang aman bagi sindividu yang mempunya pandangan politik yang berbeda, dan menghasilkan pesta politik yang sehat dengan narasi yang dapat memajukan Indonesia.
Part-Time Jobles. Tertarik pada Dunia Internet, Perempuan dan Gender Minoritas
0 Pengikut

Menilik Pelecehan Verbal sebagai Kekerasan yang Perlu Perhatian
Jumat, 20 Januari 2023 13:09 WIB
KBGO, Medium Baru Kekerasan Berbasis Gender
Jumat, 13 Januari 2023 13:07 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 99
99 0
0
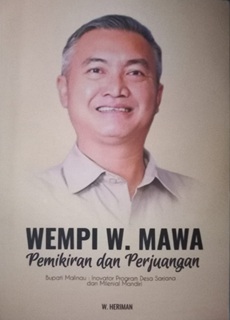

 Berita Pilihan
Berita Pilihan










