Hukuman Mati, Demi Tegaknya Keadilan atau Hanya Pembalasan?
Sabtu, 18 Februari 2023 14:12 WIB
Di bukit Palatium, Romulus membunuh saudara kembarnya, Remus, dan konon sejak saat itu tata tertib dunia untuk pertama kalinya lahir di Kota Roma. Tapi apakah setelah tata tertib dunia lahir masih diperlukan pembunuhan?
Di bukit Palatium, Romulus membunuh saudara kembarnya, Remus, dan konon sejak saat itu tata tertib dunia untuk pertama kalinya lahir di Kota Roma. Tapi apakah setelah tata tertib dunia lahir masih diperlukan pembunuhan? Tentu tidak, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman ketika dunia mulai mendewasakan diri.
Pembunuhan tetap saja sebuah pembunuhan, baik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, ataupun yang dilakukan oleh regu tembak. Undang-undang tidak seharusnya menjadi moncong senapan yang ditodongkan. Palu hakim tidaklah sama dengan peluru meriam yang siap ditembakkan. Dengan segala hormat terhadap konstitusi, saya tidak setuju hukuman mati.
Terdengar suara riuh ketika majelis hakim memutuskan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Suara sorak-sorai yang menggema di ruang sidang pagi itu bernada kepuasan terhadap keputusan majelis hakim yang melegakan. Akhirnya setelah serangkaian sidang yang pelik, keputusan final ditetapkan. Namun, suara kepuasan tidak sama dengan suara keadilan. Seringkali, demi kepuasan yang melegakan, keadilan dikorbankan.
Ada yang tak sama lagi, untuk Ferdy Sambo dan untuk majelis hakim. Butuh jiwa yang retak untuk membunuh sesama manusia, entah itu dengan pembunuhan berencana atau dengan sebuah putusan. Saya meyakini bahwa hukuman mati, tidak boleh menjadi ultimatum remidium, bahkan tidak boleh ada dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya 160 negara yang menghapuskan hukuman mati dalam berbagai bentuk, mengindikasikan hukuman tersebut sudah kuno dan perlu ditiadakan.
Sistem peradilan modern tercermin dalam adanya alternatif hukuman pada RKUHP baru –terlepas dari adanya konflik yang menyertainya. Yang mengedepankan aspek restorative justice daripada retributive justice yaitu keadilan yang lebih memfokuskan pada pemulihan kondisi korban (termasuk keluarga beserta kondisi sosialnya) daripada fokus terhadap penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.
Hukuman mati memang menimbulkan efek jera. Bagaimana tidak, jika pelaku sudah mati bagaimana dia dapat mengulangi kejahatannya? Efek jera tentu harus dipahami tidak hanya untuk pelaku melainkan juga untuk orang lain. Dengan adanya hukuman mati, diharapkan orang lain takut jika mereka melakukan tindak kejahatan serupa. Sayangnya, data statistik tidak berkata demikian.
Statistik dari banyak negara menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki dampak terhadap penurunan kejahatan. Bukan hukuman mati yang akan mencegah kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban, tetapi kepastian pelaku dihukum setelah pengadilan yang adil dan transparan (legal certainity of a fair trial).
Lagi pula, jika memang untuk menakut-nakuti mengapa eksekusi tidak dilakukan di tempat umum? Karena itu adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat sebagai manusia untuk dipertontonkan. Dan saya setuju, bukan terhadap hukuman mati yang tidak dipertontonkan, tetapi terhadap kenyataan bahwa hukuman mati itu kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat sebagai manusia.
Sadarkah kita bahwa dengan menghukum mati satu orang pembunuh, jumlah pembunuh tidaklah berkurang. Malah bisa jadi bertambah. Karena untuk mengakhiri nyawa satu pembunuh, diperlukan tiga peluru tajam dari tiga senapan yang ditarik pelatuknya oleh tiga diantara dua belas orang anggota regu tembak.
Lalu di mana letak keadilan jika tidak menerapkan eye for an eye, tooth for a tooth? Sekali lagi itu bukanlah keadilan tetapi pembalasan. Yang harusnya negara tegakkan adalah keadilan, bukan pembalasan –meskipun seringkali melegakan. Jika hukuman negara adalah pembalasan, maka seharusnya hukuman orang yang terpidana karena kasus perampokan adalah dirampok, hukuman untuk kasus penyiksaan adalah disiksa, dan hukuman untuk kasus pemerkosaan adalah diperkosa. Nyatanya tidak seperti itu.
Karena kita sebenarnya tahu bahwa memperjuangkan keadilan tidak semata-mata mengambil kembali sesuatu yang telah pelaku ambil, yang telah hilang dari kita—termasuk nyawa.
Di beberapa kasus, keluarga korban akhirnya memaafkan pelaku untuk menyelamatkannya dari hukuman mati. Karena toh hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa korban.
Jika putusan untuk menjatuhkan hukuman mati semata-mata diberikan dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, maka putusan semacam itu hanya didasarkan pada pertimbangan perasaan. Hukuman negara tidak boleh bertautan dengan perasaan, karena akan menghasilkan hasil yang subjektif dan meningkatkan risiko kesewenang-wenangan.
Selain itu, tidak pernah ada sebuah putusan yang benar-benar final di tangan manusia dengan segala keterbatasannya. Sifat alami manusia adalah tempatnya salah. Meskipun sudah sangat berhati-hati, majelis hakim masih tetaplah manusia. Segala putusan bisa jadi salah, dan kesalahan bisa dikoreksi. Namun bagaimana cara mengoreksi sebuah putusan yang sudah terlanjur menghilangkan nyawa?
Ini terbukti di beberapa kasus putusan hukuman mati, yang beberapa minggu setelah eksekusi dilakukan, diperoleh bukti bahwa sebenarnya pelaku tidak bersalah. Di Amerika Serikat contohnya, terdapat 190 kasus semacam itu sejak tahun 1973.
Jika telah demikian, apakah keadilan (baca: pembalasan) melalui putusan hukuman mati semacam itu dapat menghidupkan kembali orang tak bersalah tersebut? Tentu tidak. Jika kita menganggap hukuman mati adalah bentuk keadilan, keadilan macam apa yang didapatkan keluarga korban, keluarga orang tak bersalah itu, dan pelaku sebenarnya?
Beberapa pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati telah diatur dalam KUHP sehingga menjadi hukum positif di Indonesia. Sesuai asas positivisme hukum, segala keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum sedapat mungkin diatur berdasarakan hukum yang tertulis.
Konsekuensinya adalah hukum yang tertulis tidak akan bertentangan dengan hukum yang seharusnya, karena hukum yang seharusnya adalah hukum yang tertulis tersebut. Jika hukum tertulis mengatur harus hukuman mati maka putusan majelis hakim juga menyatakan demikian.
Tetapi tahukah, bahwa negara Belanda –negara yang mewariskan KUHP ke Indonesia itu—telah menghapuskan hukuman mati dari seluruh hukum Belanda sejak tahun 1991 dan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup.
Perkara-perkara yang sedang disengketakan di muka peradilan sudah saatnya menganut tidak hanya asas positivisme hukum namun juga asas progresivisme hukum. Yaitu penegakan hukum dilakukan dengan penuh determinasi, dedikasi, komitmen terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum dengan disertai keberanian untuk mencari jalan berupa terobosan daripada yang biasanya dilakukan oleh para penegak hukum selama ini.
Sehingga fungsi hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai rechtsvinder dalam rangka rechtsvinding –pencari yang tepat dalam menemukan hukum. Karena hukum mempunyai lingkup pengertian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan undang-undang.
Hukuman mati tidak lain hanyalah pembunuhan yang di legalkan oleh negara atas nama keadilan. Jika kita berpikir bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan yang kejam, sehingga pelakunya harus dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi mati yang dilakukan oleh regu tembak dengan menembakkan tiga peluru tajam ke jantung seseorang untuk mengakhiri nyawa adalah hal yang –meskipun legal– sama kejamnya.
Menolak hukuman mati tidak sama dengan mendukung adanya kejahatan –dalam hal ini pembunuhan. Masih ada jalan lain untuk menghukum pelaku kejahatan misalnya dengan hukuman seumur hidup seperti yang diadopsi oleh negara Belanda yang secara statistik terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan hukuman mati yang menciderai kehormatan sebagai manusia.
Paling tidak negara tidak menghapus kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk menyesal, bertobat dan berubah walaupun menghapus haknya dalam memperoleh kebebasan. Toh ujungnya nanti, setiap manusia pasti akan mati juga. Namun mati di jalan pertobatan –diambil atau tidak– saya kira mempunyai arti yang lebih dalam dibandingkan dengan mati dieksekusi regu tembak.
Karena hidup adalah suatu anugerah yang tidak boleh dicabut oleh tangan manusia dengan cara apa pun, se-legal apa pun. Demi melindungi kehormatan rakyatnya, negara harus tegas dalam menindak setiap pelaku kejahatan. Dan negara yang terhormat akan memahami bahwa kejahatan adalah sebuah anomali yang perlu dihukum –bukan dibalas– dengan seadil-adilnya, sehormat-hormatnya.
Penulis Indonesiana | Author of Rakunulis.com
1 Pengikut
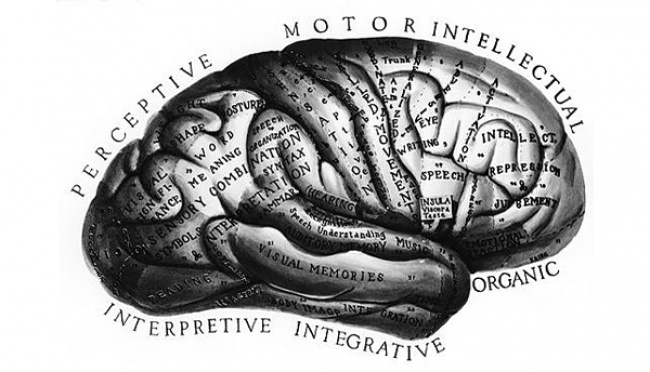
Hukum-hukum Akal dan Pertanyaan-pertanyaan Aneh yang Menyertainya
Sabtu, 7 Juni 2025 12:20 WIB
Menyoal Lampu Motor Siang Hari, Sertifikasi Halal dan PPN 12%
Selasa, 15 April 2025 21:18 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 99
99 0
0














