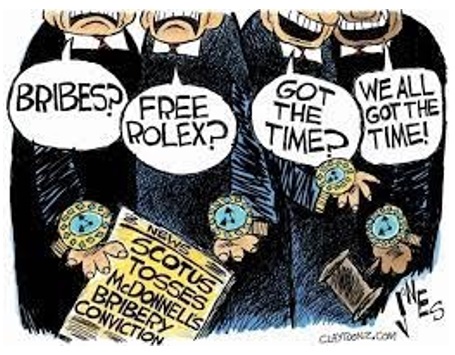Menakar Logika Presidential Threshold
Senin, 10 April 2023 14:28 WIB
Apakah presidential threshold memang diperlukan? Proses presidential threshold yang saat ini berlaku perlu diperbiki. Presiden yang butuh dukungan politik dari parlemen tidak mungkin mendapatkan kekuatan yang sama ketika suara parpol yang digunakan berasal dari Pemilu sebelumnya.
Pilpres 2024 akan berlangsung dalam beberapa bulan lagi. Namun, isu penolakan terhadap mekanisme presidential threshold masih terus disuarakan. Sejumlah pihak ingin ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dihapuskan menjadi 0 persen karena dinilai membatasi demokrasi, meski di satu sisi tidak sedikit pula yang mendukung keberadaan sistem tersebut.
Dalam sejarahnya, besaran ambang batas presidential threshold di setiap Pemilu senantiasa berubah-ubah. Namun, satu hal yang pasti, dari perubahan angka ambang batas tersebut menyebabkan jumlah peserta capres-cawapres menjadi terbatas. Partai politik (parpol) sampai Pemilu 2019 kemarin juga menciptakan koalisi agar bisa mencapai ambang batas yang sudah ditentukan.
Apakah presidential threshold memang diperlukan? Menurut hemat saya, ambang batas capres-cawapres saat Pemilu sangat diperlukan. Alasan pertama, karena siapa yang kelak menduduki kursi kepresidenan haruslah sosok yang mempunyai legitimasi dan dukungan politik dari parlemen. Perlu diingat bahwa fraksi parpol dalam parlemen merupakan buah dari demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Sederhananya, parpol yang lolos ambang batas parlemen merupakan representasi kehendak rakyat karena melalui mekanisme Pemilu.
Selain itu, perlu diingat pula dalam merumuskan serta memproduksi berbagai undang-undang yang menunjang program kerja strategis, eksekutif mesti berkolaborasi dan mendapat restu dari mayoritas legislatif. Dari sinilah kenapa mesti ada konsep koalisi politik.
Artinya, jika tidak mempunyai modalitas dukungan politik yang kuat di parlemen, justru akan menghambat kinerja eksekutif itu sendiri. Memang, sebagian orang menilai bahwa ini juga berpotensi menimbulkan oligarki. Akan tetapi, terlalu naif jika menilai oligarki seolah hanya terbentuk karena sistem ambang batas, terlebih politik itu bersifat cair dan dinamis. Tidak ada koalisi yang abadi, bahkan presiden yang terpilih dengan persentase ambang batas yang tinggi sekalipun tetap harus bekerja ekstra agar terus mendapatkan dukungan dari rakyat maupun parpol di parlemen.
Kedua, kendaraan dalam konstetasi demokrasi di Indonesia adalah parpol. Jika tidak ada ambang batas, maka parpol yang sebenarnya tidak mendapat dukungan dari masyarakat untuk duduk di kursi parlemen pun, tanpa harus bekerja keras atau menunjukkan dedikasi terhadap masyarakat bisa mengusung capres-cawapres. Tentu saja hal tersebut menjadi anomali, bagaimana mungkin rakyat selaku pemegang kedaulatan diberi opsi untuk memilih calon dari parpol yang sejatinya tidak lolos dalam ambang batas parlemen.
Dengan kata lain, adanya ambang batas yang didasarkan pada perolehan suara untuk parpol saat Pemilu akan mendorong parpol terus berkerja dan berinovasi guna mendapatkan legitimasi dukungan dari rakyat untuk mengusung capres-cawapres. Parpol tidak hanya sebatas menjadi kendaraan diam yang punya hak istimewa mencalonkan capres-cawapres, tapi harus menyalakan mesinnya setiap waktu tanpa harus menunggu tahun Pemilu untuk pencitraan.
Bagian yang Perlu Direvisi
Meskipun demikian, proses presidential threshold yang saat ini tengah berlaku perlu mendapatkan perbaikan agar semakin lebih baik. Pada Pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil Pileg yang dilaksanakan sebelumnya. Pada ketiga gelaran Pilpres itu, Pileg dilaksanakan beberapa bulan sebelum Pilpres. Sementara pada Pilpres 2019 menggunakan acuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur pasangan calon diusulkan oleh partai politk atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, yakni tahun 2014.
Tentu saja proses tersebut sangat tidak ideal. Mengingat, presiden yang butuh dukungan politik dari parlemen, tidak mungkin mendapatkan kekuatan yang sama ketika suara parpol yang digunakan berasal dari Pemilu sebelumnya. Karena suara yang didapat parpol saat Pemilu sendiri bersifat dinamis, tidak pernah di angka yang sama persis. Bahkan, bisa saja di Pemilu sebelumnya partai tersebut lolos ke Senayan tapi di Pemilu yang baru tidak lolos padahal capres-cawapres yang diusung menang Pilpres. Konsep yang saat ini berlaku telah menghilangkan manfaat ambang batas yang seharusnya dapat menjadi legitimasi kontekstual dan relevan. Konsep yang ideal adalah memisahkan tahun untuk Pileg dan Pilpres. Pileg diadakan sebelum Pilpres sehingga pemetaan koalisi menjadi jauh lebih konkret.
Selain itu, ambang batas presidential threshold juga harus dikurangi sekian persen (proporsional). Ambang batas yang berlaku sekarang cukup tinggi sehingga menyebabkan suatu koalisi menjadi sangat gemuk. Akibatnya, komposisi kekuatan menjadi sangat tidak seimbang dan otomatis juga menjadi tidak sehat. Ambang batas baiknya memberikan kemungkinan bagi munculnya poros tengah yang bisa menjadi penyeimbang pasca Pemilu.
Pegiat Gerakan Digital Jangkar Nusantara
0 Pengikut

Menakar Logika Presidential Threshold
Senin, 10 April 2023 14:28 WIB
Ragam Narasi Peristiwa 1965 Pasca Reformasi
Senin, 26 September 2022 17:24 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 97
97 0
0