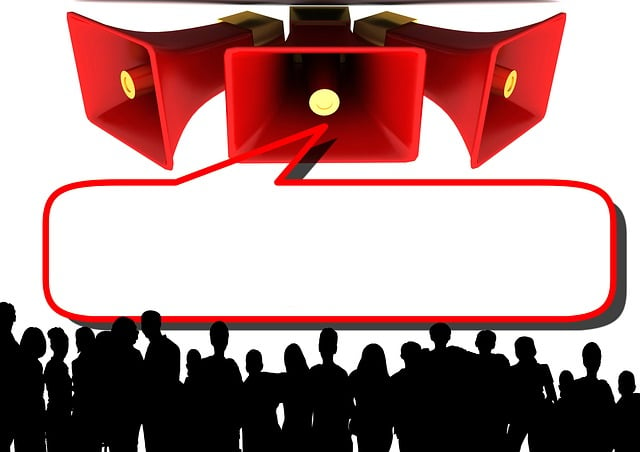Meski dianggap masih menyisakan problematika moral, akhirnya proses kandidasi Pilpres 2024 selesai. Tiga paslon capres-cawapres telah resmi ditetapkan KPU RI dengan nomor urut masing-masing.
Ketiga pasang kontestan juga telah menyiapkan tim pemenangan/tim kampanye yang melibatkan tokoh-tokoh populer di masing-masing kubu. Mulai dari elit-elit partai, menteri yang masih aktif, mantan pejabat negara, intelektual kampus, kalangan profesional, tokoh masyarakat, aktifis LSM, dan pentolan-pentolan relawan.
Di akar rumput, para pendukung ketiga paslon kian ramai dan masif saling mengonsolidasikan diri. Mereka bersiap mengerahkan segala sumberdaya dan kemampuan untuk mengantarkan capres-cawapresnya ke puncak kemenangan.
Dalam kerangka ikhtiar pemenangan yang pastinya akan sangat kompetitif itu kontestasi biasanya akan diwarnai oleh perilaku pendukung super-fanatik dan militan. Mereka adalah para pemuja yang di kepalanya hanya ada satu frasa juang : “Anies-Cak Imin harga mati?” atau “Prabowo-Gibran haga mati!”, atau”Ganjar-Mahfudz harga mati!”. Atau frasa juang lain yang setara dan senafas dengan itu.
Karakter khas para Pemuja
Kehadiran para pemuja capres-cawapres dalam kontestasi Pemilu tentu merupakan hal yang lumrah, bisa difahami. Bahkan sampai batas tertentu, mungkin “diperlukan”, setidaknya karena dua alasan.
Pertama, bagi masing-masing kubu paslon, keberadaan mereka menjadi anak panah elektoral yang dilesatkan atau melesatkan dirinya ke berbagai ruang publik sebagai pembawa semangat pemenangan sekaligus penular pesan-pesan politik.
Kedua, keberadaan para pemuja super-fanatik dan militan itu juga positif dilihat dari sudut pandang partisipasi, terlepas dari karakteristik perilakunya yang cenderung lebih mengedepankan emosi dan sentimen-sentimen psikopolitik. Tanpa kehadiran mereka hajat demokrasi mungkin akan sepi, kurang gairah, minus dinamika.
Lalu siapa para pemuja capres-cawapres? Mereka, tentu saja bagian dari kita, bahkan mungkin kita. Yakni para pemilih yang, oleh sebab satu dan lain alasan memantapkan dirinya untuk mendukung satu paslon secara fanatik yang --disadari atau tidak—fanatismenya itu menegasikan sikap kritis dari dirinya sendiri.
Bagi para pemuja, paslon yang didukungnya itu adalah segalanya, sosok yang sempurna, salah satu atau keduanya. Karena itu mereka merupakan pilihan wajib yang tidak bisa tergantikan kecuali oleh nihilisme. Jagoannya atau tidak sama sekali. Harga mati seperti disinggung di depan tadi.
Mereka tidak mengenal, atau lebih tepanya tidak membutuhkan nalar kritis bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Bahkan seorang yang memiliki rekam jejak bersih sekalipun. Dilengkapi dengan capaian-capaian perstatif entah di posisi apa sebelum ia menjadi Capres-Cawapres. Lalu dikomplitkan dengan gelar akademik berderet-deret di depan-belakang namanya, mereka tetaplah manusia yang pasti memiliki sisi kurang di samping kelebihan-kelebihannya.
Puja-puji dan Sindrome Megalomaniak
Di sisi kebutuhan akan keberadaanya sebagaimana dimaksud di atas tadi, dalam kerangka kontestasi kepemimpinan, dimana salah satu dari ketiga paslon itu akan menerima mandat dan amanah rakyat untuk memimpin negara-bangsa ini, fanatisme buta dan ketiadaan nalar kritis para pemuja juga mengandung bahaya. Terutama bagi paslon yang didukung dan dipujanya sendiri.
Cara-cara memberikan dukungan dengan fanatik, mengglorifikasi sosok-sosok jagoannya demikian rupa secara membabi-buta, dan mengesampingkan sikap kritis dari piranti akal sehat potensial bisa membuat figur-figur yang didukungnya lupa diri, terhipnotis oleh pesona ragam pujian dan rupa-rupa apresiasi.
Disadari atau tidak, figur-figur capres-cawapres pujaan itu bisa mengidap sindrom megalomaniak. Merasa diri paling unggul, cerdas, hebat dan paling kuasa. Ringkasnya, merasa paling sempurna dilihat dari sisi manapun. Nah, yang mengerikan jika paslon yang dipuja-puji secara fanatik oleh para pemuja nir-nalar kritis itu kemudian terpilih jadi presiden dan wakil presiden.
Keyakinan yang ditumbuhkan oleh dukungan dan pujian-pujian fanatik para pemujanya bahwa dirinya serba unggul akan sempurna ketika kekuasaan dan otoritas sebagai pemimpin berada dalam genggamannya setelah resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pemimpin yang mengidap sindrome megalomaniak kelak potensial akan mengoperasikan pemerintahan negara secara ugal-ugalan dan memimpin rakyat berdasarkan selera pribadi dan (sangat mungkin) selera para pemujanya. Tradisi berdemokras; membuka ruang terbuka untuk berdiskusi, menghormati keragaman pandangan dan perbedaan pendapat, serta menyerap aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan yang akan diambilnya, akan sulit tumbuh dengan baik.
Maka di tengah dinamika tahapan pilpres yang akan segera memasuki fase paling krusial dilihat dari sisi kontetasi, yakni kampanye, para paslon capres-cawapres sesungguhnya juga membutuhkan kehadiran para pendukung kritis di masing-masing kubu.
Keberadaan mereka, baik di dalam lingkungan internal tim pemenangan, di luar organ tim pemenangan, atau para pendukung yang berada di tengah-tengah masyarakat, dengan sikap kritisnya yang terukur dan proporsional tentu saja akan menjadi alat kontrol yang konstruktif bagi masing-masing paslon di samping menjadi barisan yang akan berjuang mewujudkan kemenangan.
Dengan nalar kritisnya, mereka akan mengingatkan ketika jagoannya nyerempet-nyerempet bahaya, apalagi menabrak rambu-rambu elektoral. Dengan nalar kritisnya pula mereka akan memberikan masukan-masukan strategis yang obyektif, jernih dan on the track di atas piranti hukum dan asas-asas demokrasi elektoral untuk memenangi kompetisi.
Jika ketiga kubu paslon memiliki para pendukung kritis serta masing-masing berani memerankan dirinya secara efektif, maka kita bisa berharap bahwa paslon manapun yang memenangi kontestasi, mereka telah memenanginya dengan cara yang fair, bermartabat dan berkeadaban.
Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.